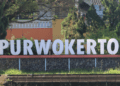Sebagai orang asli Sragen yang sedang kuliah di Solo, hidup saya terbagi dua ritme. Pagi saya jadi anak kota yang harus cepat bergerak, malam berubah jadi anak desa yang ritmenya jauh lebih pelan.
Sragen dan Solo itu sebenarnya dekat, tapi rasanya seperti hidup di dua dunia berbeda. Banyak mahasiswa dari daerah sekitar Solo pasti paham kondisi ini.
Sejak hari pertama kuliah, perbedaan dua kota ini langsung terasa. Solo memaksa saya berubah mode setiap turun dari bus, sementara Sragen menjadi tempat untuk menarik napas. Tanpa saya sadari, dua kota ini membangun keseimbangan yang unik dalam hidup saya.
Sragen damai, Solo ramai tanpa ampun
Sragen punya tempo hidup yang pelan dan stabil. Jalanan di sana lengang, suara nggak pernah benar-benar bising, dan hampir semua warung tutup sebelum malam benar-benar turun. Kita bisa menebak polanya. Ritme hidup di sana itu lembut dan suasananya menenangkan kepala tanpa perlu usaha.
Solo adalah kebalikannya. Dari pagi sampai malam, semuanya bergerak cepat. Jalanan ramai, mahasiswa ada di mana-mana menenteng tugas dan warung buka sampai larut. Kota ini menuntut kecepatan dan fleksibilitas. Suka atau tidak, kamu harus ikut ritmenya.
Ini bukan cerita unik dari saya yang asal Sragen saja. Teman-teman saya yang tinggal di daerah sekitar Solo pun mengalami hal serupa. Perubahan ritme ini memaksa kami cepat dewasa, karena kota tidak memberikan waktu jeda untuk beradaptasi.
Ritme berubah, saya ikut menyesuaikan
Sragen memberi ketenangan yang Solo tidak punya. Aktivitas terasa ringan, tidak ada tekanan mobilitas, dan hari berjalan stabil. Ketenangan itu membantu saya menjaga mental tetap waras setelah seminggu menghadapi kegiatan kampus.
Sebaliknya, Solo adalah tempat segala hal terjadi tanpa peringatan. Tugas datang tiba-tiba, rencana mendadak berubah, teman ngajak keluar tanpa aba-aba, dan dosen kadang membatalkan kelas secara tiba-tiba. Kota ini seperti memaksa kita belajar fleksibel setiap hari.
Pernah tetangga saya bilang, “Wong yo cedhak, ngopo ngekos?” Banyak orang menganggap PP Sragen-Solo lebih efisien. Tapi bagi saya, ngekos adalah latihan mandiri yang tidak bisa digantikan. Rumah memang dekat, tapi ruang berkembang butuh jarak.
Kos, nyasar, dan Google Maps yang sok pinter
Transportasi antara dua kota ini sebenarnya mudah. Motor, bus, atau nebeng selalu ada. Tapi perjalanan pertama survei kos justru penuh drama. Saya nyasar bahkan di area kampus sendiri. Google Maps sering memberi jalur aneh, dan saya cuma bisa pasrah.
Teman saya pernah menertawakan hal itu sambil menepuk bahu, “Ning Sragen apal gang-gang cilik, ning Solo kok iso nyasar ning kampuse dewe?” Saya cuma bisa cengengesan malu. Tapi jujur, banyak maba mengalami hal yang sama. Nyasar kampus sendiri adalah fase yang harus dilewati.
Ngekos juga mengajarkan hal-hal sederhana tapi penting. Mencuci, mengatur waktu, mengelola barang, sampai belajar makan seadanya ketika sedang malas keluar. Hal-hal kecil itu membangun kemandirian yang tidak diajarkan kampus.
Identitas ganda: Sragen bangga, Solo untuk penjelasan
Di Solo, saya selalu bangga memperkenalkan diri sebagai anak Sragen. Rasanya hangat membawa identitas kecil dari kota tenang yang selalu jadi tempat pulang. Teman-teman saya berasal dari banyak daerah, dan cerita asal kami justru membuat pertemanan jadi lebih seru.
Tapi ketika bertemu orang luar provinsi, biasanya saya jawab, “Dari Solo.” Bukan karena malu, tapi lebih praktis. Tidak semua orang tahu Sragen itu di mana, dan menjelaskannya panjang bisa menghabiskan energi. Identitas ganda ini tidak membuat saya bingung. Justru jadi hal yang umum dialami mahasiswa daerah.
Pulang mingguan: Merantau versi hemat jarak
Salah satu keuntungan kuliah dekat rumah adalah mudah pulang. Banyak mahasiswa sekitar Solo melakukan hal yang sama. Rumah memberi energi baru, sementara kos menjadi tempat fokus kuliah. Cucian pun sering saya bawa pulang, dan orang tua tidak keberatan selama saya tetap sehat.
Siklus ini menciptakan keseimbangan. Solo memberi tantangan, Sragen memberi ruang. Dua kota ini seperti dua sisi hidup saya yang saling melengkapi.
Dua kota, dua Ritme, satu kepala
Hidup di dua kota bukan sekadar soal jarak. Sragen mengajari saya tenang, Solo mengajari saya bertahan. Kadang saya kuat, kadang tersiksa, tapi tiap minggu saya tetap berjalan. Jika saya nyasar kampus lagi pun, saya cukup tertawa.
Sragen tetap rumah yang damai. Solo tetap kota yang menantang. Dan di antara dua dunia itu, saya tumbuh lebih kuat dengan tujuan yang tetap sama: lulus, kembali, dan bangga.
Penulis: Sonia Yuni Rahayu
Editor: Yamadipati Seno
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.