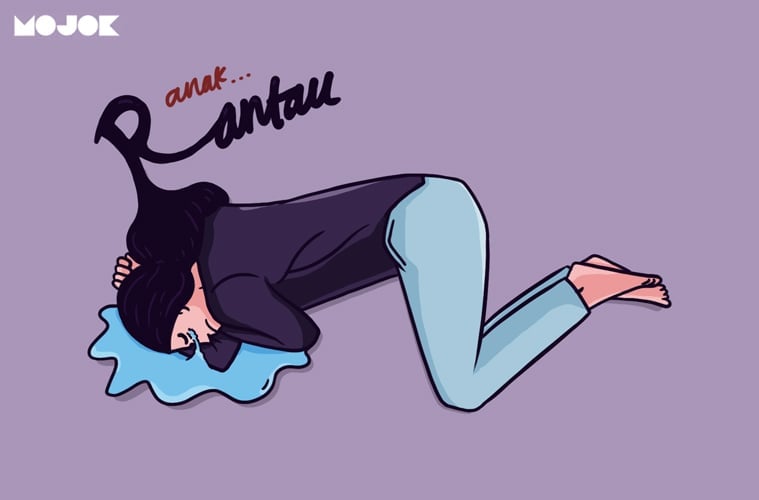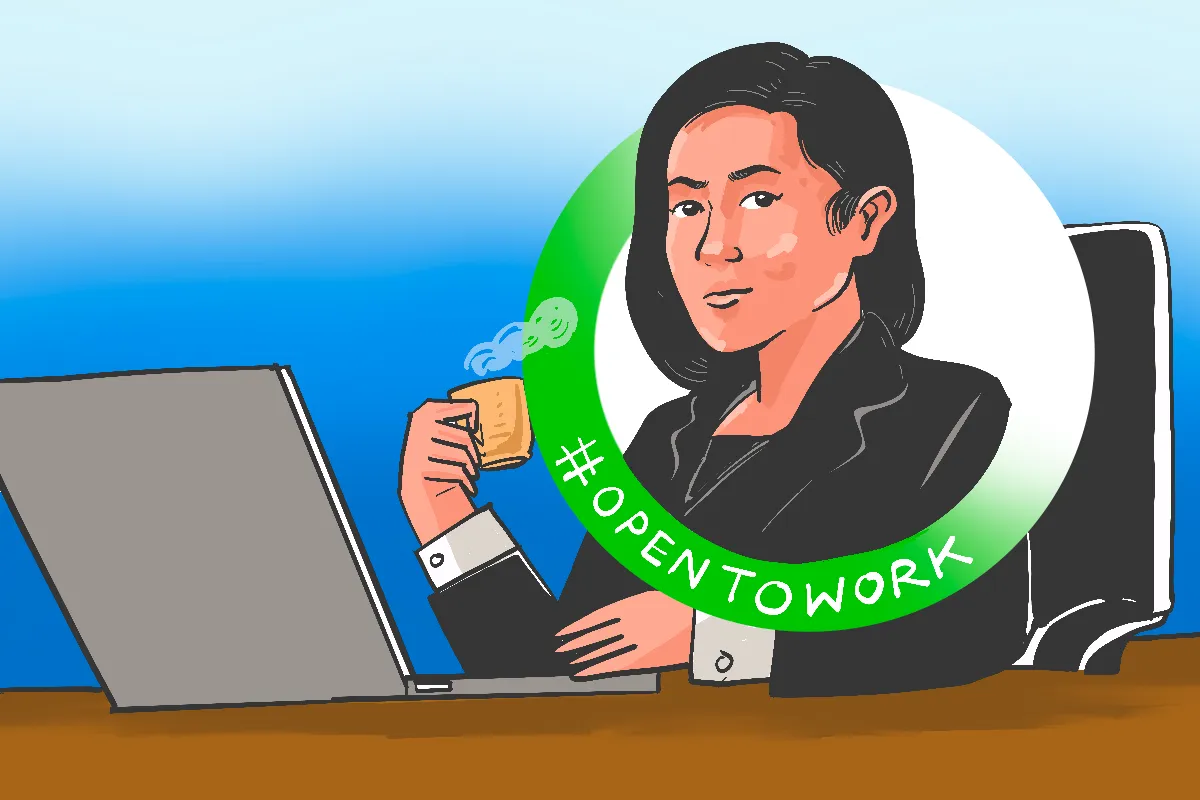Saya tak ber-KTP Jogja, pun sudah tak tinggal di dalamnya. Namun, berbekal semangat dan wujud bertenggang rasa, ada baiknya saya tetap menulis artikel ini.
Sebentar lagi malam tahun baru akan tiba. Gegap gempita membahana, segala suka cita dirasakan bersama, dan Jogja akan penuh sesak seperti biasanya. Jogja adalah kata lain dari istimewa, antitesis dari biasa saja, dan magnet wisata yang sesungguhnya. Akhir minggu selalu diserbu, hari biasa juga tak kalah sibuk, apalagi mau tahun baru. Ia seolah jatuh di bumi dan menjadi tujuan utama muda-mudi dari segala penjuru negeri.
Jogja akan penuh sesak oleh wisatawan, dan itu adalah sirine bagi para warga Jogja untuk kembali menggalakkan budaya di masa pandemi lalu: di rumah saja. Ini sebenarnya adalah hal yang dianggap lumrah pada masa sekarang. Di mana sebuah kota sudah bukan lagi milik warga kotanya. Saya bukannya tak hormat dan menyindir, lho. Saya justru sedang ingin berdiri di samping warga Jogja yang makin sulit menikmati kota miliknya sendiri.
Bayangkan, alun-alun yang diperindah dan dibubuhi pasir, sudah tak bisa dimasuki lagi. Trotoar mulus dengan lampu-lampu Instagrammable sudah bukan lagi digunakan untuk warga asli, tapi beralih fungsi menjadi sarana rekreasi dan spot selfie. Dan setiap jengkal tanahnya yang mudah diromantisasi, selalu dan selalu dijejali kaki-kaki orang luar. Lalu apa yang terjadi? Warganya justru diminta menutup diri dan menatap segala fasilitas yang gemerlap itu dari jendela rumah masing-masing.
Oleh karena itulah, ada baiknya Jogja ditutup saja saat tahun baru nanti. Tentu agar tak ada wisatawan yang mengganggu kesenangan warga Jogja. Biarkanlah sesekali warga asli yang menikmati keistimewaan dan keromantisan suasana Jogja. Izinkanlah warga asli merasakan hidup di tengah-tengah lagu Katon Bagaskara dan rekan satu bandnya. Siapa tahu, masih banyak warga asli Jogja yang belum pernah berfoto di bawah plang Malioboro. Atau ada warga asli yang malah belum pernah sekalipun mengunjungi Alun-alun Kidul.
Apalagi saat tahun baru, masa warga asli tak boleh keliling kota sembari menikmati semilir angin daerah istimewa yang semriwing. Masa kembang api dan lampu-lampu warna-warni itu bukan untuk mereka?
Jogja adalah ikon wisata Indonesia, saya tahu itu. Tapi, bukan berarti ia milik wisatawan, apalagi punya dinas pariwisata. Mau bagaimanapun juga, yang menjadikan Jogja hidup adalah warganya. Bukan kepentingan penguasa, apalagi kepentingan wisata. Menurut saya tak adil jika warga asli justru diimbau duduk diam, padahal ia punya kota yang katanya tertata dan indah. Masa hanya wisatawan yang boleh menikmatinya. Memangnya Jogja memperindah dan membangun kotanya untuk wisatawan? Tentu saja tidak, kan?
Padahal Jogja sering digembar-gemborkan sebagai wujud dari kota yang ramah dan merakyat. Ini kota yang berbudaya, dan sudah pasti mengutamakan kesejahteraan warganya. Tak mungkin ia dibangun hanya untuk memanjakan wisatawan dan justru makin menggusur warganya. Saya juga paham, jika pada akhirnya ada warganya merasa dikucilkan oleh kotanya sendiri, biasanya masih bisa ditanggulangi dengan petuah “narimo ing pandum”.
Namun, saya tetap tak rela jika warga Jogja masih tak bisa memiliki kotanya sendiri. Maka dari itu, saya berharap ide saya direalisasikan. Minimal setahun sekali warga Jogja bisa memiliki kotanya sendiri. Minimal, lho ini. Karena gedung-gedung besar dan berbudaya itu, harga apa-apa katanya murah, serta citra kota yang aman dari tindak kejahatan, semua itu masih berjarak dengan para penghuni aslinya. Semua itu sepertinya hanya dirasakan oleh wisatawan saja.
Oleh karena itulah, Jogja perlu menunjukkan siapa dirinya. Apakah ia hanya sebatas kota wisata, atau kota yang bisa memanusiakan manusia. Wallahu’alam Bissawab.
Penulis: Bayu Kharisma Putra
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Membongkar 10 Kebohongan Jogja yang Diyakini Banyak Orang