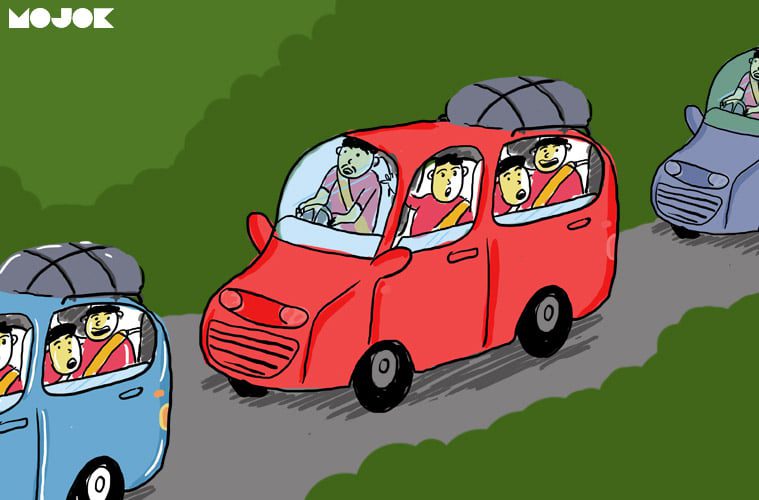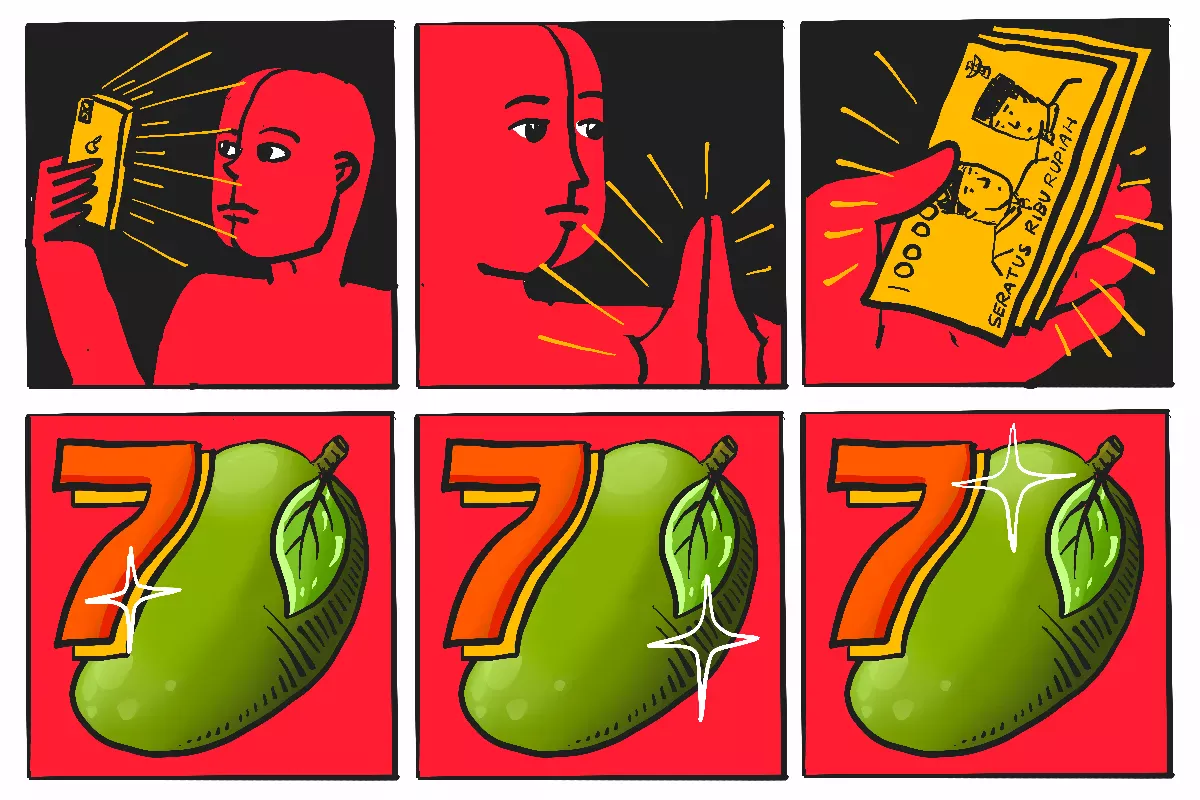Ini bisa jadi unpopular opinion, tapi jujur saja, ada yang salah dengan cara kita memandang desa. Romantisasinya sudah mulai berlebihan dan tidak sehat. Desa di mata masyarakat kota kerap digambarkan sebagai tempat yang indah dengan hamparan sawah, udara yang sejuk dan masyarakat yang rukun. Juga sering disandingkan dengan kedamaian, ketenangan, dan kenyamanan.
Padahal, desa nggak gitu-gitu amat. Maksudnya, nggak semirip itu dengan surga yang kerap kalian gemborkan. Bahkan, bisa jadi tak lebih menyenangkan ketimbang kota. Dan lama-lama, romantisasi ini terasa menggelikan, sebab, apa yang digemborkan, begitu jauh dengan realitas.
Meromantisasi desa secara berlebihan dengan berbagai macam keindahannya hanya akan membuat kita abai dan tidak peka terhadap realitas yang sesungguhnya. Saya adalah orang yang lahir dan tumbuh di desa, tepatnya di Baureno Kabupaten Bojonegoro. Ketika kecil hingga remaja, saya memang tidak merasakan ada masalah dengan desa.
Namun, saat kuliah di Surabaya, saya baru menyadari ada cara pandang keliru orang kota terhadap desa. Ada banyak permasalahan yang kemudian tidak dianggap sebagai sebuah masalah oleh negara, salah satunya ya karena desa kerap diromantisasi sebagai tempat yang damai dan adem ayem, bahkan oleh media arus utama.
Penderitaan petani
Bagi kalian yang suka meromantisasi petani di sawah, barangkali belum tahu jika banyak di antara petani tersebut menderita dan hidup sederhana bukan karena pilihan, tapi kahanan. Ada banyak orang di desa yang bekerja di sawah dengan upah harian—kadang juga borongan, untuk menggarap tanah milik orang lain. Percayalah, tidak semua orang yang sedang membajak sawah adalah petani, sebagian besar dari mereka adalah buruh tani. Lho, beda ini.
Modernisasi juga membuat petani “terpaksa” menjual tanahnya demi proyek infrastruktur dan industrialisasi yang katanya untuk kesejahteraan dan mendukung kemajuan zaman. Negara mengasumsikan warga desa yang kehilangan tanahnya akan terserap industrialisasi dan dipekerjakan oleh perusahaan modern atau pabrik, nyatanya tidak demikian.
Warga desa justru lebih sering menemukan jalan buntu ketika tanah yang dimilikinya sudah tiada. Mereka kemudian berbondong-bondong ke kota, menyerahkan nasib kepada pengusaha di pabrik atau tetap bertahan di desa sebagai buruh di lahan pertanian milik orang lain yang masih tersisa.
Petani yang untung, petani yang buntung
Saya ingat betul, saat masih kecil tetangga saya banyak yang bertani tembakau. Di desa saya juga ada pergudangan tembakau yang lumayan besar, kebetulan pemiliknya adalah saudara kakek dan kakek saya juga bekerja di sana. Ada banyak tetangga saya bekerja di gudang tersebut, termasuk Ibu-Ibu yang tugasnya merajang (memotong tembakau), mengeringkan, hingga mensortir tembakau yang layak dijual. Semua pekerja di gudang tersebut adalah orang di kampung kami, beberapa di antaranya bahkan sudah sepuh—tapi masih cukup sehat dan teliti melihat kualitas tembakau.
Kini, komplek gudang tersebut telah dibeli oleh perusahaan Wismilak dan jadilah pabrik rokok Wismilak. Hanya sedikit orang di desa saya yang berhasil bekerja di pabrik tersebut. Buruh-buruhnya pun sudah terstandardisasi —salah satunya ya menerapkan batas usia. Kalaupun ada tetangga saya yang bekerja di pabrik tersebut, palingan jualan di kantin atau menjadi satpam. Pabrik megah tersebut memang membuat kampung kami terlihat lebih modern. Namun, kehadirannya tidak membuat warganya lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya.
KKN di desa cukup tinggi
Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa korupsi paling banyak justru terjadi di desa dan kasus korupsi dana desa terus meningkat sejak tahun 2015. Pada 2021 saja, ada 154 kasus korupsi terkait dana tersebut. Namun, berapa banyak dari kita yang menyadari hal tersebut?
Saat lurah ramai-ramainya minta masa jabatannya diperpanjang menjadi sembilan tahun, pejabat kita justru mengusulkan agar dananya saja yang ditambah. Cara pandang negara melihat desa seperti orang kota, dianggap rumah segala kebodohan dan kebaikan bercampur jadi satu. Di satu sisi, warganya dianggap terbelakang dan butuh dimodernkan. Di sisi lain desa kerap dianggap tempatnya orang baik sehingga tidak perlu dikhawatirkan ada penyelewengan.
Bagi Anda yang terbiasa hidup di desa, mungkin sudah familiar dengan suap-menyuap. Sudah bukan rahasia lagi jika ingin menjadi perangkat desa dibutuhkan “biaya pemulus”. Saya tidak mengatakan semua perangkat korupsi atau memberi suap, tapi oknum yang melakukannya jumlahnya banyak dan sering kali tak terekspos media sehingga praktik suap menyuap langgeng.
Nggak hanya itu, kasus nepotisme juga kerap mewarnai kehidupan di desa. Besar kemungkinan Anda menjadi orang yang bekerja di pemerintahan desa jika Anda adalah keluarga dan kolega orang-orang penting atau perangkat desa.
Masyarakatnya tidak homogen dan rawan konflik kepentingan politik
Gotong royong dan rukun adalah dua sifat yang sering dilekatkan pada masyarakat pedesaan. Memang benar, Anda masih bisa dengan mudah menemukan orang rewang (membantu) tetangganya saat ada hajatan. Orang desa juga cukup perhatian dengan tetangganya. Namun, mengatakan penduduk desa homogen dan adem ayem adalah cara pandang yang berlebihan.
Konflik politik terutama saat pemilihan kades jauh lebih mengerikan ketimbang di kota. Kadang, antar botoh (baca: tim sukses) baku hantam sampai ada yang meninggal. Pemilihan lurah lebih rawan konflik lho ketimbang Pemilu Presiden. Pemilihan lurah bisa membuat satu keluarga dengan keluarga lain tidak saling menyapa sampai lebih dari satu tahun. Nggak jarang, pihak yang kalah dalam bursa pemilihan kades akan menjadi oposisi dan menolak sebagian besar program kepala terpilih meskipun program tersebut baik.
Ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah warga yang bahkan tidak tahu menahu urusan politik.
Bencana ekologi meningkat
Desa sering diromantisasi sebagai tempat yang sejuk, hijau dan indah sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya karena tak banyak kemacetan dan suara bising kendaraan bermotor, bukan berarti terbebas dari ancaman ekologis.
Anda yang mencoba mengurangi polusi udara di kota dengan beralih menggunakan motor dan mobil listrik sebenarnya telah mengalihkan polusi tersebut ke desa di Halmahera karena di sanalah pertambangan nikel (baca: bahan utama baterai kendaraan listrik) beroperasi selama 24 jam.
Walhi mencatat sejak 2013 hingga 2015, ada peningkatan bencana ekologi yang terjadi di desa. Jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun seiring makin banyaknya alih fungsi lahan. Salah satu contoh mengerikan dari alih fungsi lahan yang gagal dan justru mengakibatkan bencana ekologi adalah project food estate di desa yang ada di Kalimantan dan Papua.
Jika kita terus-terusan mengabarkan desa sebagai tempat yang nyaman dan secara berlebihan meromantisasinya dengan pemandangan indah. Saya takut, kita justru tak melihat ada masalah yang mengancam masyarakat ke depannya.
Penulis: Tiara Uci
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA 5 Hal yang Bikin Saya Nggak Betah Tinggal di Desa
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.