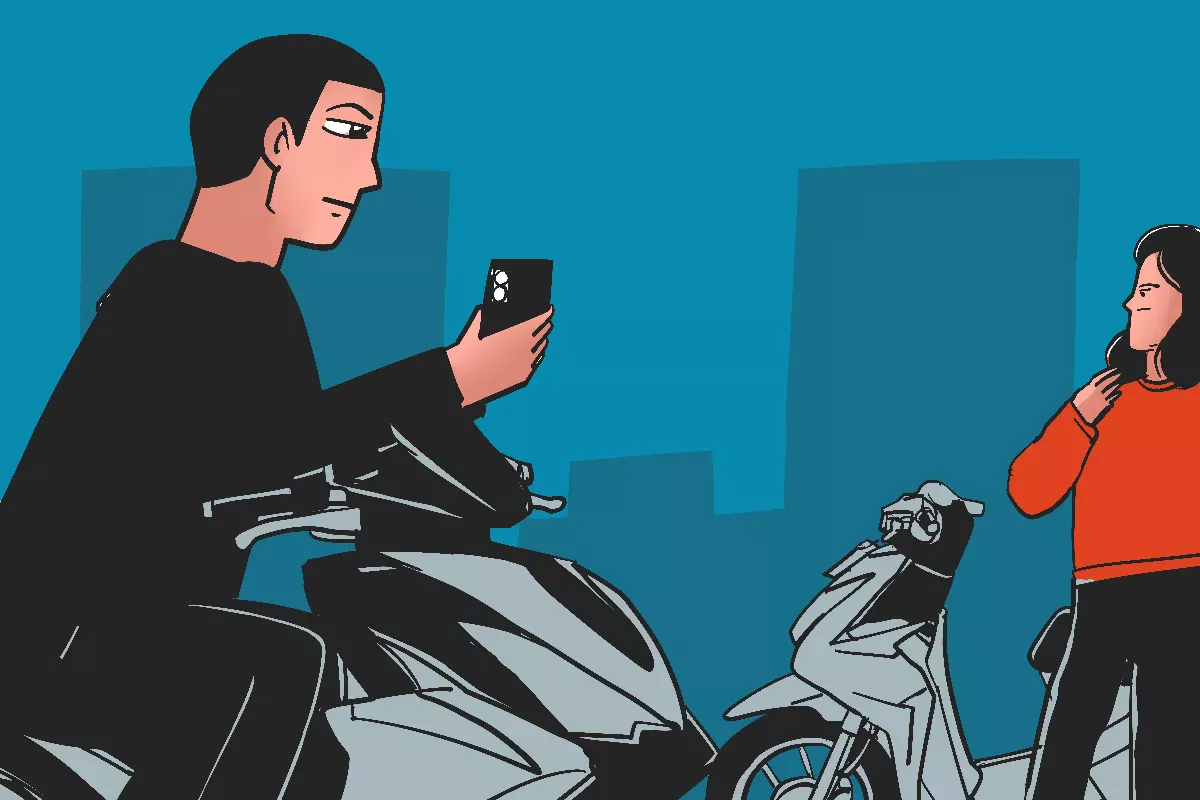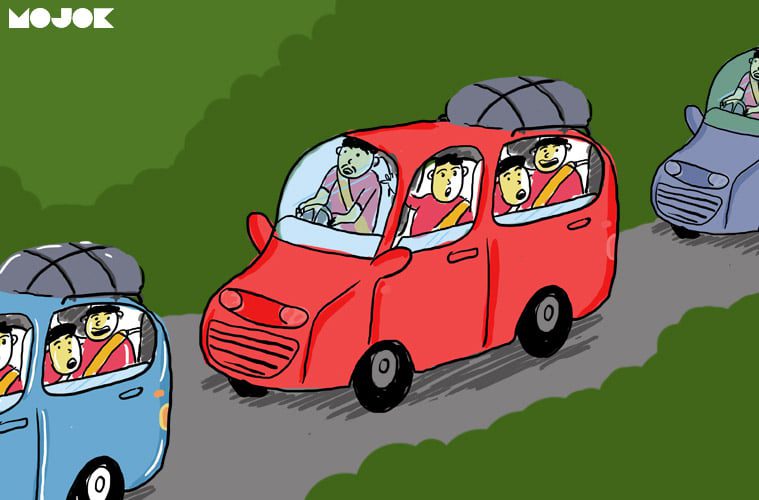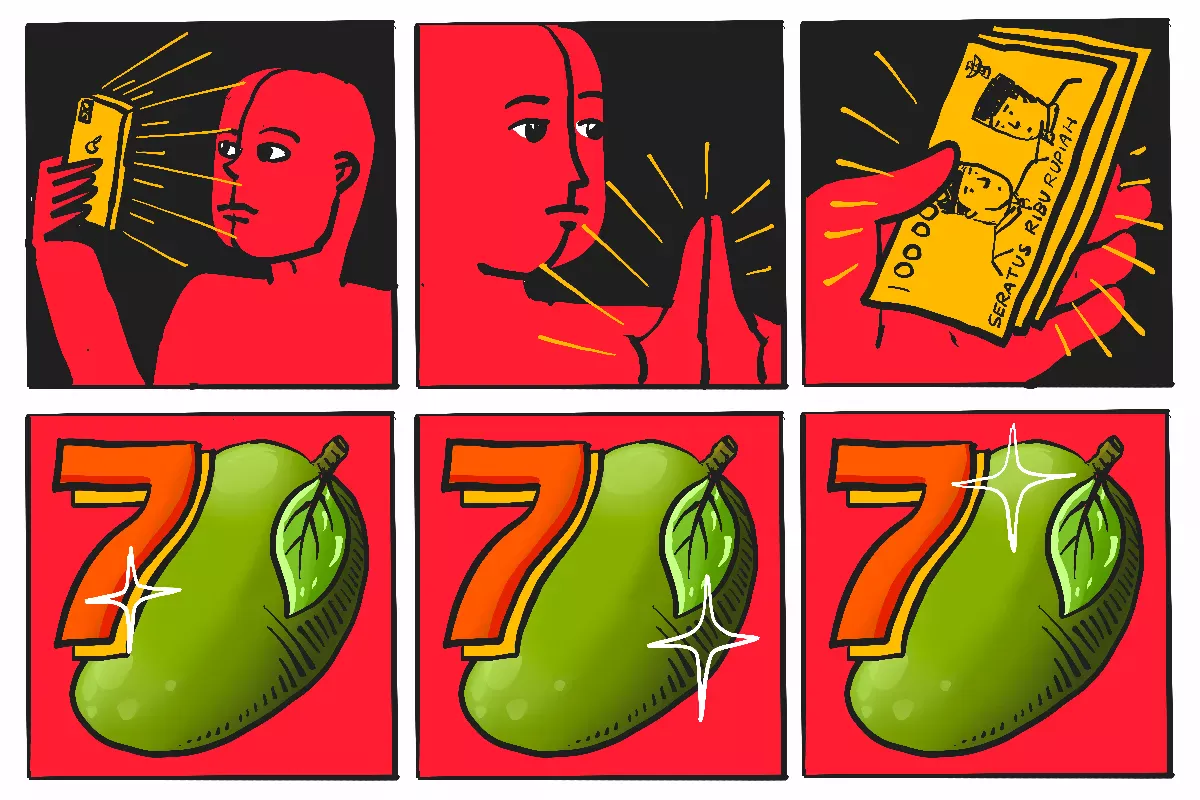Setelah mengikuti rilis Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang disiarkan lewat channel YouTube Kemdikbud RI, saya mencoba menyempatkan diri untuk membuka rapor selama menjalani proses pendidikan di tingkat TK sampai dengan SMA. Tujuan saya melakukan itu hanya ingin bernostalgia dengan perolehan “ranking” ketika duduk di bangku sekolah.
Perolehan “ranking” pada zaman saya sekolah dulu memang menjadi tolok ukur orang tua tentang keberhasilan pendidikan anaknya di sekolah. Bahkan “ranking” pada rapor itu juga menjadi penentu nasib saat pulang ke rumah. Apakah memperoleh hadiah atau hukuman. Nggak peduli nilai yang tertulis di situ berapa, yang penting jika tidak masuk “ranking” 10 besar, sudah pasti selama libur sekolah tidak akan bisa menikmati liburan secara paripurna.
Saya baru sadar jika sistem ranking pada perolehan hasil belajar ini terakhir tertulis di rapor saya SMP. Ketika duduk di bangku SMA, sistem ranking ini sudah tidak saya temukan lagi. Jadi, jika dihitung-hitung, sistem “ranking” ini berakhir sekitar 18 tahun yang lalu.
Narasi kebanggaan skor PISA yang kurang membahagiakan
Pertanyaannya kemudian adalah, kok bisa-bisanya Mas Menteri Pendidikan menyampaikan narasi kebanggaan tentang kenaikan “ranking” PISA? Bukankah sistem pendidikan kita sudah lama menghapus sistem ranking?
Padahal jika dilihat lebih detail lagi kenaikan peringkat PISA itu tidak dibarengi dengan kenaikan skornya lho. Malahan skor PISA-nya juga turun. Bisa jadi hasil belajar murid di Indonesia “begini-begini” saja, tetapi murid di negara lain mengalami penurunan yang signifikan. Terus ngapain bangga, kan skornya turun???
Jika ini terjadi pada 18 tahun silam, Mas Mendikbud patut berbangga karena memang era saat itu ranking lebih penting daripada skor. Lha kalau sekarang kan eranya sudah beda. Pendidikan era sekarang lebih mengarahkan kepada pembelajaran yang bermakna. Capaian pembelajaran juga sudah bukan lagi ditentukan angka ketuntasan minimalnya. Akan tetapi lebih ditekankan pada kriteria apakah murid sudah mencapai level mahir, cakap, berkembang, atau belum berkembang. Jika di sekolah paradigma ranking sudah bergeser, masak di level elite malah menjadi sebuah acuan? Harusnya Mas Menteri lebih bijak ketika menyikapi dan berkomentar tentang hasil PISA ini.
Seharusnya narasi yang disampaikan juga realistis
Saya mungkin semakin semangat jika Mas Menteri menyampaikan narasi seperti ini, “Indonesia dan negara di seluruh dunia memang mengalami learning loss pada saat pandemi, sehingga hasil PISA kita juga mengalami penurunan. Meskipun peringkat kita naik, tapi itu tidak bisa dijadikan indikator keberhasilan, karena skor PISA kita juga tidak begitu baik. Untuk itu mari hasil PISA ini kita jadikan pemacu semangat kita semua agar kualitas pendidikan kita mampu naik dan bersaing dengan negara-negara maju. Kita lebih optimalkan lagi instrumen-instrumen yang sudah kita susun bersama.”
Jika narasi yang disampaikan adalah semacam itu, kita sebagai insan pendidikan akan kembali mengevaluasi diri kemudian menentukan langkah yang harus segera diambil. Ini lebih logis dan bermakna daripada menyampaikan hasil kenaikan ranking yang ujung-ujungnya kita terlena karena terbuai dengan kenaikan peringkat. Tentu jika ini dibiarkan akan berbahaya, karena “seolah-olah” kita telah berhasil. Padahal kita juga sedang mengalami penurunan secara kualitas.
Semoga kita tidak jadi terbuai dengan ranking PISA Indonesia dan segera berbenah untuk memperbaiki kelemahan sistem pendidikan nasional. Ketangguhan sistem pendidikan nasional bukan soal kenaikan peringkat, akan tetapi jika skornya sama dengan 2018, artinya selama ini memang tidak ada perkembangan. Atau, usaha yang ada nyatanya mentok dan butuh dievaluasi.
Turunnya skor PISA ini sebenarnya juga menjadi bahan refleksi saya sebagai seorang guru. Mungkin karena saya kurang optimal dalam menjalankan tugas sehingga kualitas capaian belajar murid juga masih “begini-begini” saja.
Penulis: Eri Hendro Kusuma
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Sistem Pendidikan Indonesia dan Skor PISA yang Buruk