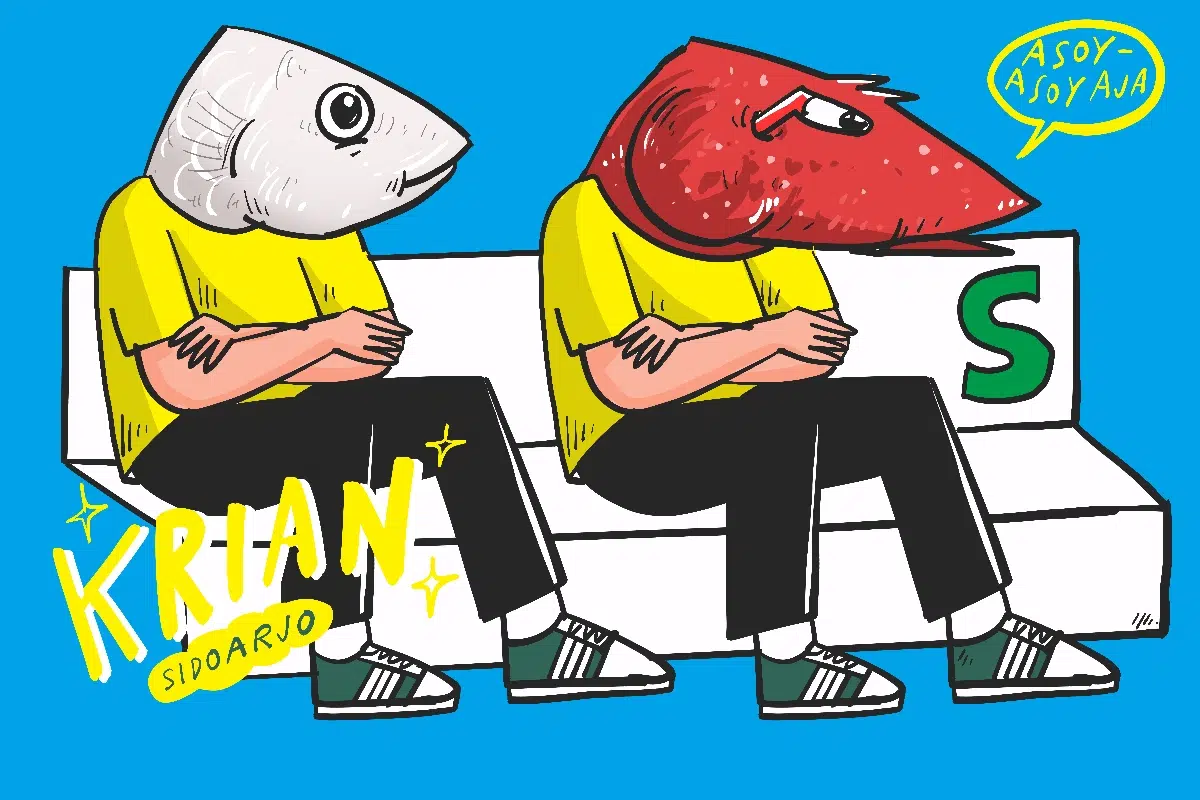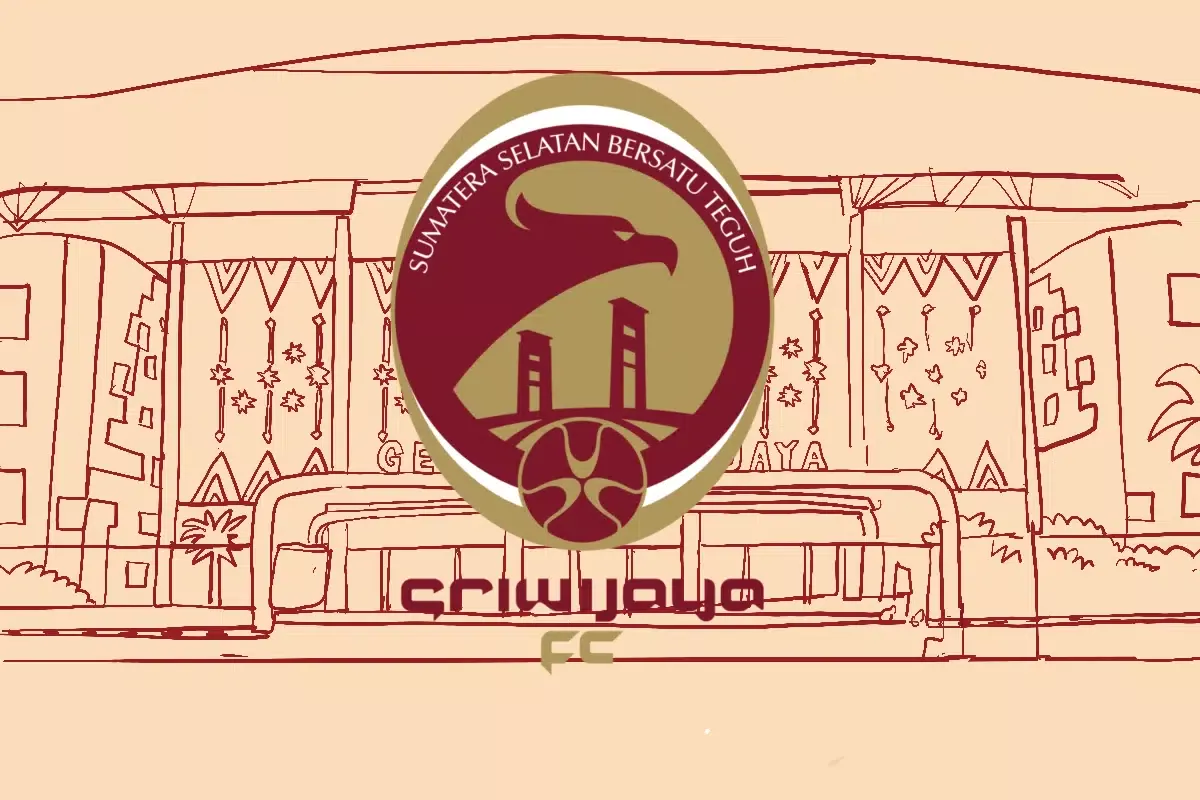Saya orang Kebumen. Purwokerto bukan kota asing bagi saya. Jaraknya dekat, sering dilewati, dan kerap disebut sebagai salah satu kota tujuan wisata di Jawa Tengah. Di media sosial, Purwokerto bahkan mulai dikenal sebagai “kota healing” yang tenang, hijau, dekat alam, dan cocok untuk melepas penat.
Namun ada satu pengalaman yang berulang setiap kali saya atau orang yang saya kenal datang ke Purwokerto sebagai pendatang, yaitu kebingungan. Bukan bingung karena kotanya rumit. Justru karena terasa terlalu biasa. Terlalu datar. Kenapa? Karena ketika orang datang ke kota ini, mereka tidak dibimbing. Seakan-akan, kota ini tak butuh didatangi siapa pun dan ketika didatangi, kota ini memberi kesan “silakan urus semua sendiri”.
Purwokerto, kota wisata yang kurang memberi arah
Begitu turun di Stasiun Purwokerto, suasana memang hidup. Lalu lintas berjalan, ojek lalu-lalang, warga beraktivitas seperti hari biasa. Tapi sebagai wisatawan, pertanyaan sederhana langsung muncul, setelah ini ke mana? Kurang ada penanda yang mengarahkan pengalaman wisata.
Tidak ada peta narasi kota. Tidak ada petunjuk yang secara halus memberi tahu, “kalau ke Purwokerto, sebaiknya mulai dari sini.” Akhirnya, Purwokerto sering terasa seperti rumah besar yang pintunya terbuka, tapi tamunya dibiarkan mencari kursi sendiri.
Potensi ada, cerita kurang disusun
Secara geografis dan kultural, Purwokerto punya banyak modal. Ia dekat dengan kawasan wisata alam seperti Baturraden. Punya kuliner khas Banyumasan. Ritme hidupnya lebih pelan dibanding kota besar. Semua itu cocok dengan citra kota tenang yang belakangan dijual sebagai “healing.” Masalahnya, potensi itu kurang dirangkai menjadi pengalaman.
Wisatawan datang, tapi tidak disambut oleh sistem. Tidak ada alur kunjungan yang terasa. Semuanya seperti berjalan sendiri-sendiri. Kalau tidak punya kendaraan pribadi atau kenalan lokal, wisata di Purwokerto sering bergantung pada tebakan dan rekomendasi acak.
Terlalu mengandalkan “nanti juga nemu sendiri”
Ada kesan bahwa Purwokerto terlalu percaya wisatawan akan memahami kotanya secara otomatis. Seolah-olah ketenangan kota dianggap cukup tanpa perlu penjelasan tambahan. Padahal, wisatawan hari ini tidak selalu mencari hiruk-pikuk. Mereka justru ingin pengalaman yang sederhana tapi jelas.
Bukan diarahkan secara kaku, tapi diberi petunjuk agar tidak merasa tersesat. Healing tidak berarti kebingungan. Justru rasa aman dan rasa diterima adalah bagian dari proses itu.
Purwokerto dibandingkan dengan daerah sekitar
Sebagai orang Kebumen, saya sering membandingkan secara reflektif. Kebumen bukan kota besar. Bahkan sering dilekatkan dengan label daerah miskin. Tapi dalam konteks wisata tertentu, pantai misalnya, narasinya jelas ke mana, lewat mana, dan apa yang bisa dilakukan. Purwokerto punya status kota, fasilitas yang lebih lengkap, dan nama yang lebih dikenal. Tapi justru sering sedikit kehilangan artikulasi tentang dirinya sendiri sebagai tujuan wisata.
Catatan dari pendatang dekat
Tenang memang nilai jual. Tapi tanpa panduan, ketenangan bisa berubah jadi kekosongan. Kota wisata tetap perlu memberi sinyal bahwa kehadiran orang luar diperhitungkan. Purwokerto terasa hidup untuk warganya, tapi belum sepenuhnya komunikatif bagi pendatang. Ia berjalan normal, seolah tidak ada yang perlu disesuaikan ketika wisatawan datang.
Tulisan ini bukan keluhan, apalagi serangan. Ini lebih seperti catatan dari orang luar yang cukup dekat, bukan warga tapi juga bukan orang asing. Purwokerto punya semua bahan untuk menjadi kota wisata yang ramah dan berkesan. Yang dibutuhkan mungkin bukan pembangunan besar, melainkan penyusunan cerita, bagaimana kota ini ingin dialami oleh orang yang baru pertama datang. Karena kota wisata bukan hanya soal tempat yang ada, tapi juga tentang bagaimana kota itu menyapa.
Penulis: Akhmad Alhamdika Nafisarozaq
Editor: Rizky Prasetya