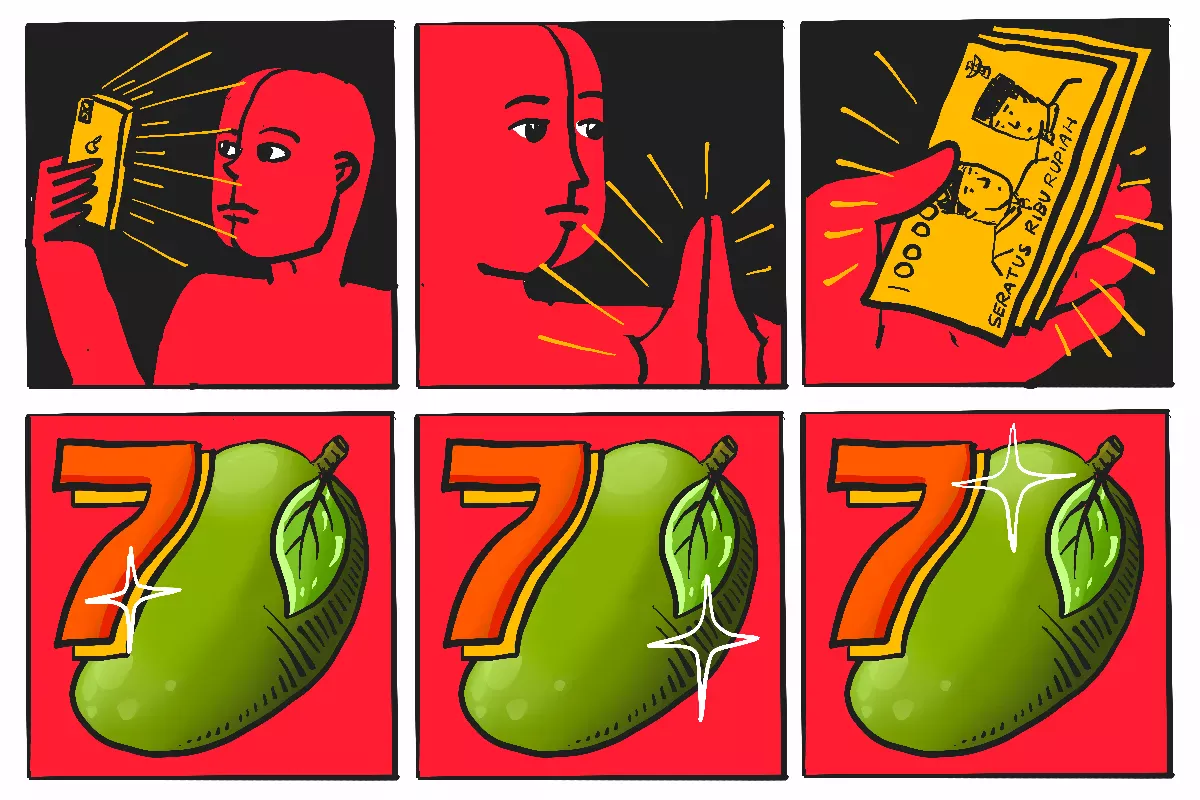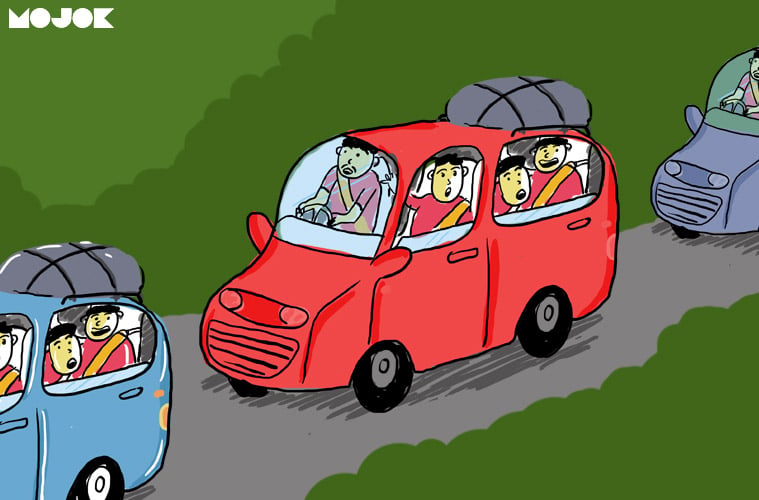Dalam dunia pendidikan Indonesia, guru honorer hidup di bawah bayang-bayang dua istilah yang menentukan arah masa depan mereka, PPG dan Dapodik. Keduanya kerap disebut sebagai instrumen peningkatan mutu dan penataan data.
Tetapi bagi guru honorer, yang terjadi tidak (sesederhana) seperti itu. PPG dan Dapodik lebih terasa sebagai gerbang sempit yang menentukan hidup dan mati status profesional mereka. Masuk berarti ada harapan. Sedangkan tertutup, berarti masa depan kembali kabur atau malah tidak ada sama sekali.
PPG diposisikan sebagai jalan resmi menuju pengakuan profesional guru. Sementara Dapodik menjadi basis data yang memvalidasi eksistensi seorang pendidik di mata negara. Ketika dua sistem ini disatukan, lahirlah satu kombinasi yang sangat menentukan, sekaligus menimbulkan keresahan berkepanjangan.
Dapodik yang tidak ramah realitas lapangan
Secara konsep, Dapodik berfungsi sebagai pusat data pendidikan nasional. Namun dalam praktiknya, sistem ini sering kali jauh dari realitas yang dihadapi guru honorer. Dapodik hanya mengenal angka, jam mengajar, dan status administrasi. Ia tidak membaca cerita pengabdian, tidak menghitung lamanya guru bertahan di sekolah terpencil, dan tidak mencatat kondisi darurat kekurangan tenaga pendidik.
Banyak guru honorer yang sudah lama mengajar justru terhambat hanya karena jam mengajarnya dianggap tidak linier atau status sekolahnya bermasalah. Kesalahan kecil dalam penginputan data bisa berdampak besar dan sulit diperbaiki. Di titik ini, Dapodik bukan lagi alat bantu, melainkan penentu yang kaku dan dingin.
PPG yang menjadi simbol harapan sekaligus tekanan
PPG selalu dibicarakan sebagai tiket emas menuju kesejahteraan dan pengakuan. Lulus PPG berarti satu langkah lebih dekat pada sertifikasi dan status yang lebih layak. Namun di balik itu, PPG juga menjadi sumber tekanan psikologis bagi guru honorer.
Seleksi yang ketat, kuota terbatas, dan persaingan nasional membuat banyak honorer merasa peluangnya sangat kecil. Bagi sebagian guru, PPG bukan lagi soal peningkatan kompetensi, tetapi soal bertahan dalam sistem yang penuh persyaratan administratif. Ketika tidak lolos, kekecewaan terasa berlapis karena kegagalan sering kali bukan disebabkan kemampuan mengajar.
Ketika PPG terkunci oleh Dapodik
Masalah terbesar muncul saat PPG sepenuhnya bergantung pada Dapodik. Tanpa data yang sempurna dan sesuai aturan, guru honorer otomatis tersingkir dari proses PPG. Nama boleh ada, tetapi jika jam tidak cukup atau tidak linier, sistem menolak tanpa kompromi.
Kondisi ini membuat nasib honorer terasa ditentukan oleh mesin, bukan oleh manusia. Pengabdian bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena satu kolom data tidak memenuhi syarat. PPG yang seharusnya menjadi ruang pembinaan berubah menjadi arena seleksi yang keras.
Beban psikologis guru honorer
Kombinasi PPG dan Dapodik menciptakan tekanan mental yang serius. Guru honorer tidak hanya mengajar, tetapi juga terus-menerus waspada terhadap perubahan sistem. Setiap pembaruan data memicu kecemasan baru. Takut nama hilang, takut status berubah, dan takut peluang PPG lenyap begitu saja.
Tekanan ini perlahan menggerus semangat mengajar. Fokus guru terpecah antara tanggung jawab di kelas dan urusan administratif yang tak ada habisnya. Pendidikan yang seharusnya berpusat pada murid justru dikalahkan oleh ketakutan terhadap sistem.
Kebijakan yang berubah tanpa transisi manusiawi
Keresahan semakin dalam ketika kebijakan sering berubah secara mendadak. Aturan linieritas diperketat, syarat jam mengajar dinaikkan, dan kriteria peserta PPG diperbarui tanpa mempertimbangkan kesiapan lapangan. Guru honorer dipaksa beradaptasi cepat, sementara kondisi sekolah sering kali tidak mendukung.
Di banyak daerah, keterbatasan guru membuat honorer harus mengajar di luar bidangnya. Namun ketika aturan berubah, kondisi tersebut justru menjadi alasan untuk menggugurkan mereka. Sistem seolah menuntut kesempurnaan di tengah keterbatasan nyata.
BACA JUGA: Sisi Gelap Jadi Guru Honorer yang Tidak Diketahui Banyak Orang
PPG dan Dapodik sebagai sumber keresahan berkepanjangan guru honorer
PPG dan Dapodik juga memperlebar jurang ketimpangan. Sekolah besar di perkotaan cenderung lebih siap secara administrasi dan infrastruktur. Sekolah di perkotaan bisa dikatakan lebih unggul. Sekolah-sekolah di perkotaan bisa dikatakan penguasa dalam hal ini.
Sementara sekolah kecil di daerah terpencil sering tertinggal dalam urusan data. Akses internet yang terbatas dan minimnya operator terlatih membuat data honorer rawan bermasalah. Akibatnya, guru honorer di daerah menjadi kelompok yang paling rentan. Mereka bukan hanya berjuang mendidik. Akan tetapi juga melawan sistem yang tidak berpihak pada keterbatasan mereka.
Pada akhirnya, PPG dan Dapodik memang dibutuhkan sebagai alat standarisasi dan pendataan. Namun ketika keduanya menjadi penentu tunggal tanpa ruang empati, keresahan akan terus tumbuh. Bagi guru honorer, combo maut ini bukan sekadar sistem, melainkan simbol ketidakpastian masa depan.
Selama PPG dan Dapodik masih berjalan dengan logika kaku dan minim pemahaman lapangan, guru honorer akan terus berada dalam posisi rapuh. Mereka tetap mengajar, tetap mengabdi, sambil menunggu nasib yang ditentukan oleh layar dan data, bukan oleh dedikasi yang mereka berikan setiap hari di ruang kelas.
Penulis: Marselinus Eligius Kurniawan Dua
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Alasan Guru Honorer Muda Masih Bertahan dengan Pekerjaannya meski Gajinya Kelewat Rata dengan Tanah
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.