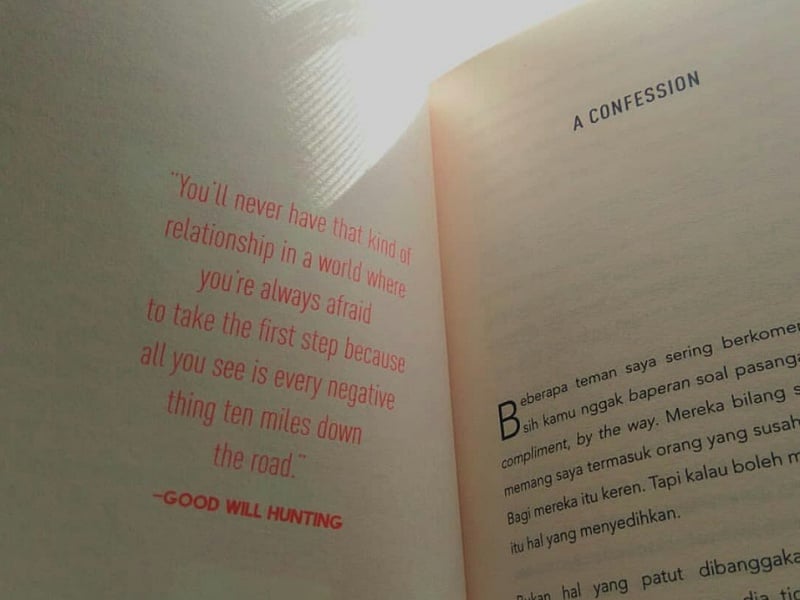Kita tumbuh dengan cerita-cerita cinta yang naif. Cinderella, si upik abu yang menikah dengan pangeran. Tangled, pencuri menikahi putri raja. Bahkan di film Stand By Me di mana Nobita dan Shizuka pada akhirnya menikah. Nobita si malas dan Shizuka yang sempurna itu…menikah!
Cerita-cerita itu, bagaimanapun, membuat alam bawah sadar kita setuju bahwa cinta yang sebenar-benarnya tidak memandang status sosial dan tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan percintaan. Silakan bermimpi untuk menikahi keturunannya Aburizal Bakrie mulai dari…sekarang. Tapi, semakin dewasa, semakin kita menyadari pula bahwa cerita-cerita itu omong kosong belaka. Padahal, kita sudah kadung jatuh cinta dan mencintai dengan landasan berpikir cinta tanpa syarat, cinta yang apa adanya, dan seterusnya, dan seterusnya.
Kaum-kaum yang tumbuh dengan pola pikir semacam itu kita sebut saja cah cinta, untuk tidak menyebut budak cinta alias bucin. Cah cinta di usia seperempat abad adalah individu-individu yang tersesat. Mereka tidak segan berkorban untuk orang yang dicintai, sebab menurut mereka tidak ada pengorbanan dalam mencintai. Atau sebaliknya, mencintai artinya berani berkorban. Keduanya sama-sama membawa mereka ke jurang curam penuh batu tajam bernama kesia-siaan.
Telanjur tumbuh dengan pola pikir yang terbentuk dari cerita roman picisan, cah cinta gagap menghadapi realita cinta yang tak seindah kehidupan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie (kalau betulan indah lho, ya). Yang cah cinta tahu hanya mencinta, mencinta, mencinta, memberikan dukungan semaksimal mungkin kepada orang yang dicintai. Dalam konteks hubungan asmara orang dewasa berusia seperempat abad, cah cinta akan dihadapkan dengan berbagai cerita cinta dan fenomena tragis seputar percintaan, baik yang dialami oleh orang-orang sekitarnya maupun dirinya sendiri.
Tak masuk akal! Begitu pikir cah cinta. Ya, memangnya ada yang masuk akal saja sejak kita dewasa? Lantas, apa saja sih perkara-perkara yang tidak masuk akal, tak masuk logika cah cinta itu? Berikut beberapa di antaranya:
“Cinta ya cinta, menikah ya menikah”
Kutipan ini berasal dari novel Seorang Laki-Laki yang Keluar dari Rumah karya Puthut EA. Versi lebih panjang kutipan tersebut ialah:
“Tidak selalu ada hubungan antara pernikahan dengan cinta. Cinta, ya, cinta. Menikah, ya, menikah. Hanya orang yang beruntung jika bisa saling mencintai lalu menikah.”
HAH? Apa? Kok gitu? Kok bisa? Seberapa pun menyebalkannya kutipan tersebut, atau jika mau ngeles ah, itu kan hanya kutipan novel, kutipan tersebut benar belaka. Banyak kok, pasangan yang menikah tanpa cinta. Lebih banyak lagi pasangan yang saling mencintai, tetapi tidak bisa menikah karena berbagai faktor. Tentang faktor-faktor ini, akan dijelaskan pada nomor selanjutnya.
Cah cinta, jika membaca kutipan tersebut, responnya mungkin melongo, lalu sedih dan kecewa, atau tidak percaya. Yang terakhir disebut biasanya denial sampai melihat atau mengalami langsung contoh kasusnya.
Dalam perkara ini, cinta saja seringkali dianggap tidak cukup untuk pondasi pernikahan. “Memang anaknya mau dikasih makan cinta?” adalah pertanyaan yang seringkali muncul bagi pasangan yang mengedepankan cinta dan cinta saja. Di sisi lain, kemapanan finansial, status sosial, dan beberapa prakondisi sebelum menikah, meskipun tanpa kehadiran cinta, dianggap cukup untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Nanti cintanya juga akan hadir dengan sendirinya, begitu kata mereka yang mengamini hal tersebut. Kita sering menjumpainya dalam perjodohan, termasuk ta’aruf. Saya sendiri percaya kalau adanya cinta sebelum menikah jauh lebih baik ketimbang menunggu cinta hadir setelah menikah. Ya kalau betulan datang, kalau absen? Kan repot.
Pada akhirnya, percaya atau tidak percaya adalah keputusanmu. Kalau saya sih, semoga kita semua adalah orang yang beruntung menurut kutipan di atas. Aamiin.
Harta, tahta, trah
Cah cinta percaya bahwa saat dua orang saling mencintai dan mau berkomitmen untuk saling memperbaiki diri, itu sudah cukup, katakanlah, untuk menikah. Sayangnya, dunia ini bukan milik berdua. Dunia ini adalah juga milik orang tua dan keluarga. Nasib lahir dan hidup di Indonesia, menikah bukan hanya urusan dua kepala, melainkan dua keluarga.
Ada sih, orang tua yang mendukung penuh pilihan anaknya. Tapi, tidak jarang pula yang mendukung sepenuhnya, dengan syarat si calon mantu berpenghasilan besar dan stabil, punya jabatan di instansi (kalau bisa instansi pemerintah), dan berasal dari keluarga baik-baik. Itu mah namanya mendukung setengah-setengah ya.
Lantas bagaimana nasib para wirausaha, penyintas broken home, atau anak-anak yang lahir di keluarga tanpa privilese tapi ia tetap mencoba untuk hidup sebaik mungkin—beranjak jauh dari kehidupan keluarganya yang gelap dan “kurang baik”, mengacu pada sebutan para orang tua?
Kenapa nggak melihat perjuangan dan track record si individu yang mau menikah saja? Tidak bisakah para orang tua percaya bahwa ada buah yang jatuh jauh, bahkan jauh sekali, dari pohonnya?
Di Jawa, kriteria calon mantu ini biasa diukur dengan 3B, yaitu bobot, bibit, dan bebet. Bebet tidak dibahas di sini karena tidak berhubungan dengan harta, tahta, dan trah.
Bobot mengacu pada kualitas diri secara lahir dan batin. Yang termasuk dalam bobot ialah keimanan, pendidikan, pekerjaan, kecakapan, dan perilaku si calon mantu.
Kecenderungannya, orang tua ingin anaknya memperoleh pasangan hidup dengan yang seiman, setara pendidikan, pekerjaan, dan kecakapannya, serta berperilaku baik seperti pegawai KPK (sebagian). Lantas bagaimana dengan pasangan yang tidak seiman, atau seiman tapi beda aliran? Nah lo. Juga bagaimana missal yang satu lulusan S1, satunya lulusan S2, lantas orang tua yang kedua merasa anaknya pantas mendapatkan yang lebih baik (yang lulusan S2 juga) untuk jadi pasangan hidup?
Setiap pertanyaan melahirkan pertanyaan baru. Semua tidak masuk akal. Kalau cinta, ya mbok boleh saja menikah, gitu kepinginnya cah cinta tuh. Lalu semesta tidak bekerja, dan malah berkata, “Ha ha ha tidak semudah itu, Aldebaran.”
Kemudian ada bibit yang bukan aplikasi reksadana. Bibit mengacu pada keturunan, asal usul yang menentukan karakter atau watak seseorang. Betul bahwa karakter seseorang sedikit banyak ditentukan oleh sifat turunan (genetik) dan pengasuhan. Tapi, jangan lupa, faktor lingkungan juga memengaruhi. Bisa saja lingkungan membuat karakter seseorang sama sekali berbeda dengan orang tuanya. Anak yang lahir dari orang tua pemarah bisa jadi sangat penyabar. Apalagi jika si anak ini punya kesempatan bertumbuh di luar lingkungan rumah, misalnya, saat merantau sebagai mahasiswa. Jadi, sebenarnya tidak masuk akal ketika nilai seseorang ditentukan dari keturunan alias trahnya di sini, kecuali keturunan kerajaan itu beda lagi ya, Jeung.
Kalau benar dia mencintaimu, seharusnya…
Versi lain dari kalimat tersebut ialah, “Coba minta dia buktikan perasaan cintanya padamu”, “Kalau betul dia mencintaimu, coba minta dia A, B, C, D.”
Contoh yang banyak dijumpai di dunia nyata: “Kalau dia sayang sama kamu, harusnya dia mau pindah ke Jawa dan cari kerja di sini. Masak kamu mau dibawa ke luar Jawa? Kerjaanmu gimana? Jauh dari orang tua, dari semuanya.” Padahal di Jawa nggak ada kerjaan yang sesuai bagi si pasangan anak ini. Kalaupun ada, gajinya jauh di bawah gaji pekerjaan yang di luar Jawa. Artinya, jika si anak menikah dengan pacarnya yang lalu pindah ke Jawa itu, kesejahteraannya malah tak terjamin. Cinta macam apa yang dimaksudkan para orang tua itu?
Maksud kalimat itu tentu saja menguji seberapa besar cinta pasanganmu kepadamu. Kalau kamu juga termasuk orang yang suka mengetes pasangan, berarti kamu bukan cah cinta. Cah cinta tidak mengenal konsep menguji pasangan dengan berbagai hal bodoh. Tas tes memangnya mau jadi PNS?
Berkenaan dengan mengetes ini, kita patut mengingat kata-kata Sudjiwo Tedjo,
“Jangan pergi agar dicari, jangan sengaja lari agar dikejar. Berjuang tak sebercanda itu.”
Anggaplah kita dengan pasangan sama-sama berjuang. Nggak usah dipertanyakan, cukup dilihat saja, kalau dirasa si dia sudah nggak memperjuangkan, baru deh putusin. Tesnya seleksi alam aja gitu lho, nggak perlu kita yang repot-repot bikin tesnya.
BACA JUGA Usai Patah Hati, Terbitlah Mati Rasa