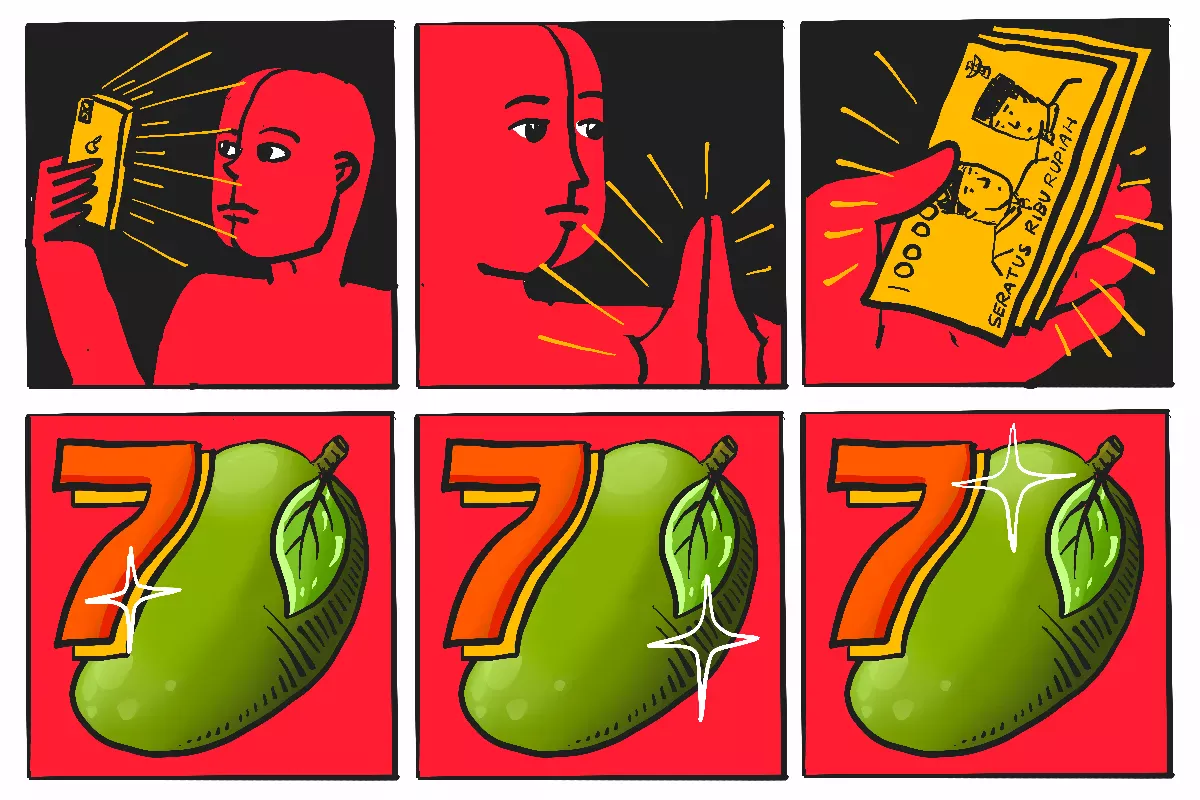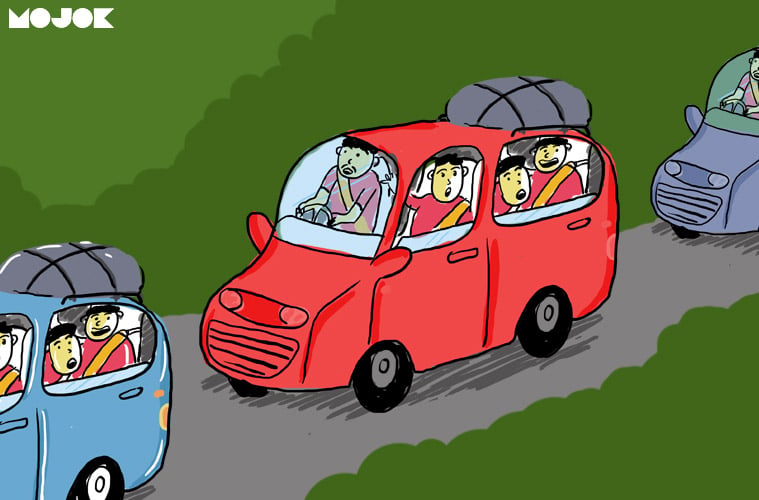Satu malam di Kota Pare. Gerimis mengiringi setiap sendok nasi goreng yang ditelan malam itu. Di sebuah gubuk sederhana, saya dan beberapa teman menikmati nasi goreng 6000-an, sambil sesekali melihat orang berlalu lalang menggunakan sepeda mini dengan khas keranjang di depannya.
Para akhwat yang bersepeda tampak begitu anggun dengan tas slempangan yang kebanyakan bertuliskan “love in pare” . Tas itu menjadi ciri khas Kota Pare. Beramai-ramai mereka berkelompok menyusuri tepian jalan Pare yang basah karena gerimis.
Gerimis tidak mematikan keramaian di kota ini. Masih banyak pejalan kaki pulang dari tempat kursus. Sesekali tidak jarang suara-suara berseliweran beraksen Inggris mengiringi sepanjang jalan. Meski ramai, Pare menawarkan ketenangan. Orang-orang yang ramah, dikombinasi dengan harga makanan yang begitu murah. Meski sangat jarang menemukan angkringan, kafe-kafe semi klasik hadir tanpa membuat khawatir kantong terkuras.
Nasi goreng di piring telah mencapai sendok terakhir, ditutup dengan setengguk teh manis, maka ritual makan malam ini pun berakhir. Itulah kondisi saat malam hari di Kota Pare. Kota yang juga sering disebut sebagai Kampung Inggris ini.
Pare, sebuah kota kecil di utara Kota Kediri. Kota memiliki lebih dari 250 lembaga kursus berbahasa Inggris yang tersebar di desa Tulungrejo dan Palem. Lantaran dua desa tersebut letaknya di Kecamatan Pare, lantar muncullah predikat Pare sebagai Kampung Inggris.
Meski secara administrasi Pare bukanlah kota, tapi bagi saya ia telah terdefinisikan sebagai kota. Di sini banyak pendatang dari berbagai daerah sehingga begitu heterogen dengan berbagai latar belakangnya. Bahkan ada sekitar 5000 orang berganti setiap bulannya. Jelas, ini menjadikannya sebagai kota kecil yang berada di dalam dua desa.
Mereka yang datang ada yang ingin mengadu nasib, me-refresh niat, dan menjadikan Pare sebagai sarana untuk mencapai bermacam-macam cita-cita. Bukankah kota biasanya selalu demikian? Menjadi tujuan bagi mereka yang ingin mengubah nasib dan mengejar cita-cita?
Bahkan sebelum saya sampai di sini, ada pula yang menyebut kota ini sebagai tempat bagi para “pelarian”. Bagi saya, justifikasi ini terlihat sedikit kejam. Pasalnya, dalam benak saya kota pelarian adalah tempat yang berisi orang gagal dan lari dari kenyataan. Apalagi dengan melihat kondisi zaman yang rentan membuat depresi, menjadikan stereotip kota ini sebagai kota pelarian malah memicu perasaan was-was.
Namun, setelah dua bulan berada di kota ini, stereotip tersebut justru semakin kuat. Bedanya, anggapan itu tidak dibarengi dengan definisi awal saya. Sehingga kekhawatiran dan keparnoan saya malah berubah menjadi semangat positif.
Sebab kenyataannya, Pare memang destinasi pelarian. Pelarian bagi mereka yang kebingungan, pelarian bagi mereka yang ingin menggapai cita -cita, pelarian bagi mereka yang sedang me-refresh kehidupannya yang sebelumnya sungguh padat. Bahkan Pare juga pelarian bagi mereka yang ingin mencari jodoh.
Terlepas dari itu, urgensi utama Pare jadi kota pelarian adalah karena bahasa Inggris telah bertransformasi jadi kebutuhan utama dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan.
Pasalnya, tidak sedikit orang yang kebingungan setelah lulus kuliah dan akhirnya melipir ke Pare. Dengan skill pas-pasan dan fakta bahwa saat kuliah tidak pernah serius membuat mereka belum siap dilepas ke dunia kerja atau tahapan pendidikan selanjutkan. Kondisi ini membuat mereka memilih Pare sebagai pelampiasan. Setidaknya bagi mereka, dengan menguasai bahasa Inggris dapat menambal kekosongan skill mereka di tahapan hidup selanjutnya.
Oleh karena itu, di Pare semua terlihat saling belajar. Di kafe, warung-warung makan, di balkon kos-kosan atau camp. Tidak ada pembahasan lain selain berdiskusi seputar rumitnya materi grammar, sulitnya belajar pronunciation, atau memahami kata demi kata pada kelas speaking. Semua itu menjadikan Pare memiliki kultur belajar yang tinggi, sehingga membuat orang-orang yang ke sana dituntut untuk serius belajar.
Oleh karena itu, menjadi wajar bila Kota Pare dianggap sebagai kota pelarian. Ia bukan sekadar kampung yang berisi banyak tempat kursus. Lebih dari itu, ia berhasil membuat sistem yang membuat orang-orang yang berada di dalamnya lebih serius dalam mempersiapkan hidup.
BACA JUGA Do’s and Don’ts Ketika Belajar Bahasa Inggris atau tulisan Muhamad Iqbal Haqiqi lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.