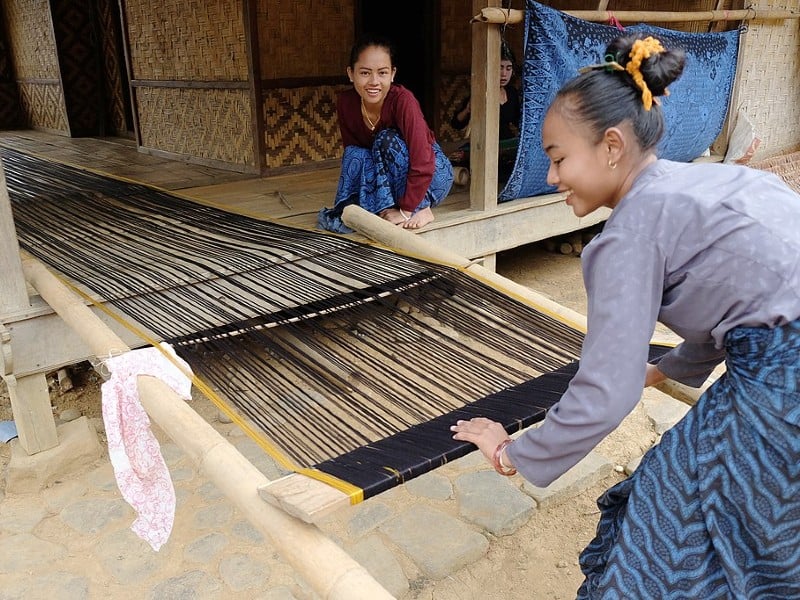Di internet banyak bertebaran video menyindir orang yang ngomong lu-gue tapi logat medok. Ada yang bilang nggak cocok, ada yang bilang jangan sok Jakarta, ada yang bilang aneh, dan lain sebagainya. Sebenernya penggunaan kata lu-gue bukan berarti yang mengucapkan sok Jakarta, tapi dia bingung mencari kata yang pas untuk tidak menggunakan dua kata itu.
Misalkan bila kita menggunakan saya-anda dianggap terlalu formal dan kurang friendly, lalu menggunakan kata aku-kamu malah terkesan jijik, coba bayangkan dua laki-laki ngobrol menggunakan aku-kamu. Lalu bagaimana solusinya? Ya solusinya gunakan kata lu-gue.
Biasanya orang yang menyindir penggunaan kata lu-gue pada orang yang beraksen medok, karena mereka belum terbiasa dengan lingkungan yang menggunakan kata lu dan gue. Apabila mereka terbiasa, paling juga mereka kagok menggunakan kata aku-kamu, lalu secara terpaksa mereka akan membiasakan diri dengan kata lu-gue.
Mengapa mereka kagok? Ya karena rasanya sudah beda. Bukankah bahasa itu mengandung rasa? Oleh sebab itu, ketika kita ingin belajar bahasa, maka kita perlu belajar juga budaya asal bahasa tersebut guna dapat merasakan makna berbagai kata dalam bahasa tersebut.
Perasaan superior yang aneh
Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan orang yang terbiasa hidup di lingkungan lu-gue tapi juga nyindir logat medok yang bilang lu-gue? Ya, mungkin mereka merasa superior dengan kata lu-gue yang mereka anggap gaul dan modern. Tapi kemungkinan besarnya, mereka yang nyindir itu tidak memahami bagaimana perubahan rasa dalam berbahasa orang yang disindir.
Bayangkan mereka yang sebelumnya terbiasa ngomong aku-kamu, lalu sekonyong-konyong merasa aneh bahkan jijik, terutama ketika ngomong dari laki-laki ke laki-laki. Akhirnya ketika mereka ngomong lu-gue dengan logat medok langsung disindir nggak cocok.
Sepengalaman saya saat di Malang, saya sendiri lebih sering menggunakan lu-gue ketika ngobrol dengan teman satu kost. Mengapa? Karena teman kost saya saat di Malang memang kebanyakan non-Jawa. Dan entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba kos tersebut bernuansa Jakarta, padahal yang dari Plat B hanya dua orang.
Awalnya memang saya kagok menggunakan lu-gue, karena sebelumnya kata lu-gue hanya pernah saya lihat di TV. Namun akhirnya saya terbiasa juga. Saya juga tidak pernah terkena sindiran dari teman-teman kos saya karena menggunakan kata lu-gue dengan logat medok, mereka nyaman-nyaman saja.
It’s okay to be medok
Nah, ketika di Depok, saya tidak bisa menghindari lagi untuk ngomong lu-gue. Meskipun memang ada saja teman yang sulit untuk ngomong lu-gue, dan pada akhirnya dia malah ngomongnya ane-ente. Kalau tidak ingin makai lu-gue atau ane-ente, ya biasanya langsung panggil nama saja. Dan saya juga tidak pernah terkena sindiran ketika ngomong lu-gue dengan logat medok selama di Depok, khususnya di lingkungan UI.
Sepanjang saya amati, teman-teman saya yang menggunakan kata lu-gue namun beraksen medok nyantai-nyantai saja ngomong lu-gue ke teman-teman mereka, dan teman-teman mereka juga tidak pernah mempermasalahkan soal aksen.
Mengapa teman-teman mereka tidak mempermasalahkan penggunaan lu-gue dengan aksen medok? Kalau dalam pandangan saya, itu karena alasan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan kita, pikiran kita semakin terbuka terhadap perbedaan. Sehingga dengan aksen berbeda pun, kita masih bisa menerima dan memahami apa yang mereka katakan.
Pemberian apresiasi adalah kunci sukses dari penerimaan perbedaan aksen ini. Sebagai contoh saya pernah mendengar seorang dosen mengatakan, “Itu lihat, profesor sejarah asal Inggris yang kita undang kemarin, tidak pernah beliau menertawakan seorang penanya yang mengucapkan Raffles, padahal bacanya Reffles, kalian juga harus demikian.”
Oke mungkin kalian akan mempermasalahkan contoh tersebut, soalnya ini jatuhnya ke ranah pronunciation, bukan aksen. Tapi the point still stands, selama pesan sampai, apakah aksen jadi masalah yang perlu dipikir sebegitu dalam?
Nanti juga terbuka sendiri
Pada akhirnya kita jadi memahami bahwa orang yang menyindir penggunaan kata lu-gue dengan aksen medok berarti berpikiran tertutup atau close-minded. Biasanya orang yang close-minded kurang memiliki pengalaman hidup di lingkungan heterogen, sehingga pemahaman perbedaan budaya mereka kurang.
Oleh sebab itu dengan orang yang close-minded tidak perlu berdebat, karena akan menghabiskan waktu dan tenaga kita. Lalu bagaimana cara mengubah pemikiran mereka yang close-minded? Kalau mainnya makin jauh, nanti terbuka sendiri pikirannya.
Jadi daripada menguras tenaga berdebat dengan kaum close-minded, lebih baik kita memberikan pengertian secara perlahan, sambil mendorong mereka untuk menambah pengalaman baru. Seiring berjalannya waktu pemikiran close-minded pasti akan lebih terbuka. Toh kalaupun pemikiran mereka nanti tidak terbuka, itu urusan mereka sendiri dan tidak ada urusannya dengan kita. Jadi kita cukup memahami saja kaum close-minded tanpa memaksakan perubahan terhadap mereka.
Penulis: Yogaswara Fajar Buwana
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Medok Sebagai Identitas Bahasa Ibu, Bukan untuk Diremehkan