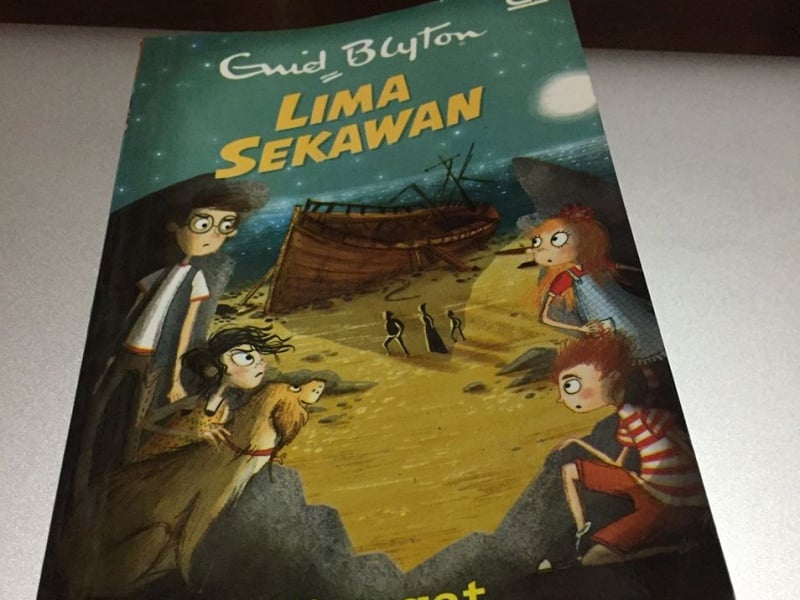Mari membaca fiksi. Barangkali begitu kalimat pertama yang saya musti tulis yakni sebuah kalimat ajakan. Tidak sembarangan, meskipun tidak terlalu serius, kalian perlu hiraukan. Sebab jika saya diizinkan beragumen, maka argumen saya tulis demikian: kehidupan nyata kita akhir-akhir ini—terutama di Jakarta—tidak lebih fiksi daripada fiksi itu sendiri.
Sedangkan, novel sebagai sebuah karya tulis, sudah jadi stereotip massal bahwa ia merupakan fiktif belaka. Fiksi sebagai kata dasar, menurut KBBI, adalah cerita rekaan atau secara gamblang bisa disebut tidak nyata. Sekadar selingan, saya beberapa kali menulis fiksi sehingga diketahui bahkan oleh salah seorang sahabat bapak saya. “Ngapain kamu hidup di dunia angan-angan?” kata dia, membantah saya agar saya kembali ke jalan hidup nyata sebagai calon Sarjana Teknik. Saya diam belaka.
Padahal kalau saya ambil contoh novel Pedro Páramo, di mana Juan Rulfo sang penulis, berani menarasikan ‘aku’ sebagai sudut pandang pertama di permulaan cerita yang mengunjungi kota mati. Berkat wasiat ibunya, Juan Preciado berkelana ke Media Luna dan desa Comala secara khusus, tanah kelahiran ibu sekaligus tinggal bapak Juan Preciado sebelum mereka berpisah. “Buat dia membayar, Nak. Untuk tahun-tahun ketika dia melupakan kita,” gumam Dolorita, ibu Juan Preciado sebelum sekarat.
Ketika tiba di Comala, Juan dibimbing seorang pengembara ke rumah Doña Eduviges, yang kemudian wanita itu bercerita kalau dia teman kecil ibunya. Kemudian Juan sedikit heran ketika Eduviges menyatakan sudah tahu kalau Juan akan datang. Bahkan—menurut pembacaan saya—mungkin Juan tak sadar kalau Eduviges telah lama mati, begitu pun pengembara yang mengantarkan dia sebelumnya.
Comala dan Media Luna benar-benar mati. Meski dengan segala kepolosan saya, saat pertama kali membaca, tidak membau kematian hakiki kota sekaligus para penduduknya.
Belum lagi di tengah-tengah cerita, saya dibikin pusing oleh narator yang berganti-ganti jadi orang ketiga serba tahu. Apalagi orang ketiga serba tahunya tidak hanya satu. Meskipun begitu, saya cukup menikmati novel ini. Saya terhanyut di dalam kerumitan sudut pandang narator. Yang mana—in my arrogant opinion—di dalam diri Juan Rulfo terbagi aku berjumlah banyak. Semacam alter ego, lalu dia mainkan secara ciamik ke dalam tokoh-tokoh yang dia reka sehingga dia puas dengan itu. Maka, di dalam kepuasan itu Juan Ruflo cukup menerbitkan dua buku untuk jadi mahakarya dan membuat dia dikenang.
Bahkan, di dalam kata pengantar, Gabriel Garcia Marquez mengaku jika sepuluh tahun sebelum membaca novel ini dia tak pernah merasa begitu tergugah. Saya membayangkan Marquez sekian lama merasa hampa, bahwa hidup ini tidak menyediakan apapun kecuali duka, lalu sekita dia merasa bergairah sampai ereksi. Dan gairah itu mencuat dari cerita rekaan kematian.
Padahal kematian, yang kemudian Juan Preciado mengalaminya dan tetap jadi narator dari dalam kubur, ditulis oleh Juan Rulfo seakan bukan perubahan yang menakutkan. Kematian sebenarnya bukanlah cerita spesial amat, dan hanyalah keniscayaan.
Saya ulangi, kematian hanyalah keniscayaan. Seperti yang telah dialami penduduk kota; termasuk Pedro Páramo: penguasa Media Luna yang membayar warisan utang keluarga dengan cara menikahi anak perempuan pemberi hutang; termasuk Bapa Rantería: yang menyesal seumur hidup karena mengampuni dosa saat Miguel Páramo(anak Pedro Páramo yang lain) yang memperkosa keponakan atau yang membunuh saudaranya dengan imbalan uang; termasuk Donis: yang semasa hidup mencintai saudarinya sendiri; termasuk banyak tokoh lain yang semua telah mati.
Kematian-kematian itu, saya yakin, ditulis dan direka ulang oleh Juan Rulfo berdasar kehidupan nyata saat itu, atau setidaknya kalau bukan saat itu menurut cerita-cerita sejarah maupun turun-temurun yang pernah dia dengar. Sebab bagaimanapun, Juan Ruflo tidak mungkin terlahir seketika menjadi penulis. Dia melewati proses kehidupan, dengan otomatis mengamati dunia nyata untuk kemudian dia olah dan tulis. Semua cerita fiksi bermula dari kisah nyata.
Kemudian, yang menentukan fiksi itu jadi ‘nyata’ menurut saya ada dua. Pertama, kemampuan menulis penulis itu sendiri; seperti yang telah dilakukan Juan Rulfo dengan labirin super rumitnya.
Kedua, kesenjangan batas makna kenyataan hidup dengan ‘nyata’ itu sendiri. Dan untuk alasan kedua, saya kalau esok diberi kesempatan, saya akan sampaikan sesuatu kepada sahabat bapak saya. Barangkali begini: “Pak, kemarin lihat TV?” kemungkinan besar dia menjawab iya, sebab semua pensiunan PNS menonton TV bahkan YouTube.
“Bagaimana kita menyebut kejadian 22 Mei 2019 itu, kalau bukan fiksi?” dia mungkin kaget karena aku tiba-tiba tanya begitu. Tapi saya tetap melanjutkan tanpa peduli. “Bagaimana dua kelompok bisa bentrok, hanya karena pihak yang satu untuk mempertahankan, yang pihak kedua untuk berebut kekuasaan yang menjijikkan?”