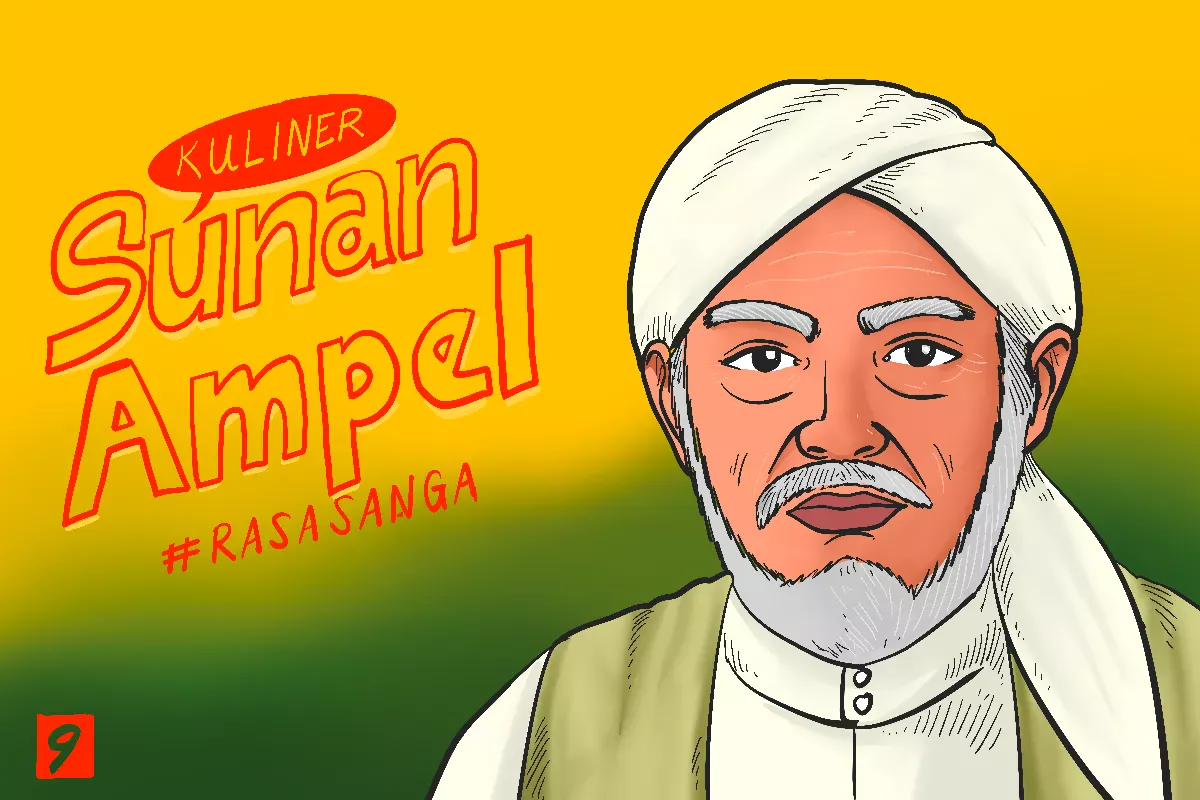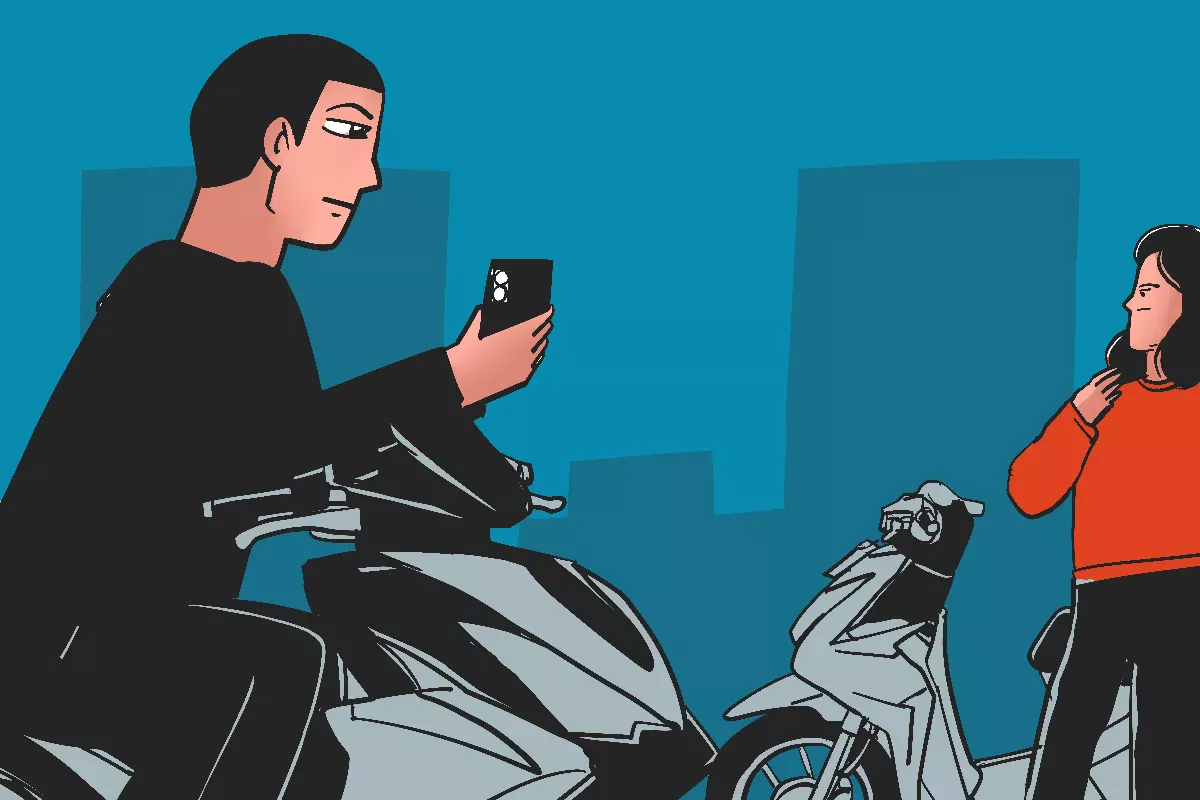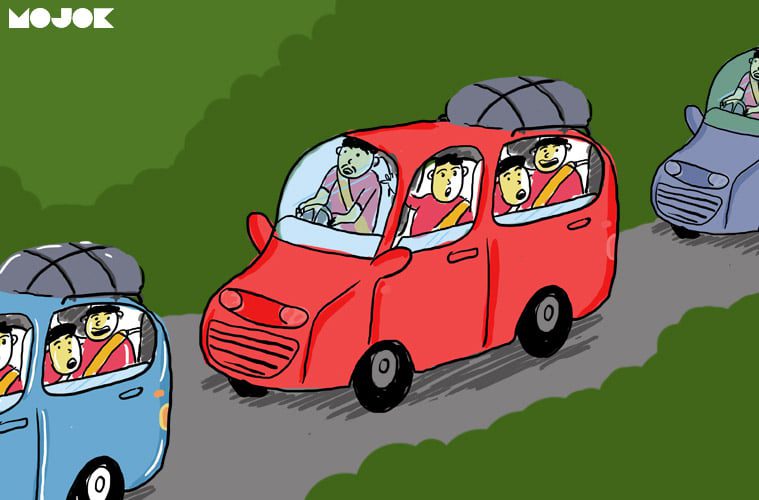Ada sebuah kebiasaan masyarakat yang berkembang entah sejak era kapan. Saya memberi nama “menghakimi secara sosial” untuk kebiasaan dan tradisi ini. Dari namanya saja, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Menghakimi yang berarti ada satu, dua, tiga atau banyak orang yang berkedudukan sebagai hakim. Dia atau mereka bertindak secara nyata menentukan seseorang bersalah atau tidak. Lalu jika ada hakim disana tentu saja harus ada seorang, dua orang atau lebih yang berkedudukan sebagai orang terdakwa. Dia atau mereka yang dengan kesalahan entah apa lantas harus secara spontan duduk di kursi pesakitan sebagai seorang bersalah. Entah nanti terbukti atau para hakim massal ini yang memaksanya bersalah.
Tradisi “menghakimi secara sosial” ini seperti yang saya jelaskan diatas, bukan hal yang baru dalam masyarakat. Bahwa ketika terjadi sesuatu hal terjadi diluar norma yang berlaku umum lantas semua orang berhak menjadi penegak norma. Norma yang dilanggar dan orang-orang merasa berhak menjadi pengadil itu kebanyakan adalah norma sosial. Jikapun ternyata bukan norma sosial bisa juga norma hukum. Namun dengan tradisi menghakimi yang sama.
Misal saja seorang melakukan pencurian, lantas semua orang sebagai para pengadil mengejar pelaku. Seteah tertangkap sang pelaku, pekerjaan sebagai penegak norma dengan dalih “menghakimi secara sosial” ini belum selesai. Mereka para hakim dan pengadil ini merasa memiliki hak untuk memberikan sedikit dua dikit kepalan tangan di wajah atau di perut si pelaku pencurian. Apakah fair? Atau dengan pertanyaan lain, apakah benar secara hukum? Bisa jadi tidak. Tapi secara sosial, bisa jadi hal ini dibenarkan.
Kita bisa menebak apa yang selanjutnya terjadi. Bahkan tanpa harus menelisik secara lebih mendalam apa yang dilakukan para hakim dan pengadil, kita pernah disuguhi berita orang yang dibakar hanya karena diduga mencuri amplifier milik masjid. Di mata hukum, apa yang diduga dilakukan sang pencuri adalah salah. Namun, melihat dengan mata telanjang dalam perspektif seorang netral, membunuh bahkan dengan cara dibakar? Hukuman apa yang lebih sadis dari itu?
Dan kita juga bisa melihat hal lain yang bisa saja terjadi. Katakanlah, provokator. Mereka yang merasa tidak senang dengan seseorang lantas memprovokatori sebuah aksi dengan menuduh seseorang sebagai seorang pelaku. Lantas orang yang percaya dengan itu kemudian berdiri dalam posisi sebagai hakim dan pengadil. Lantas ikut menghakimi pelaku. Dan kejadian yang masih hangat diingatan kita adalah ketika seorang mahasiswa menjadi korban pengeroyokan di dalam masjid karena difitnah menjadi maling toa masjid. Padahal faktanya dia hanyalah korban provokator. Miris!
Sebagai akibat ketakutan atas tradisi “menghakimi secara sosial” ini, juga terjadi dalam konteks hal-hal kecil. Beberapa waktu lalu saya naik kapal dari Wakatobi menuju Bau-bau. Lantas sebuah kejadian terjadi, seorang wanita tidak sengaja menjatuhkan gelas berisi tehnya (untung gelasnya tidak pecah). Bunyi gemericik. Dan bisa kita tebak apa yang terjadi selanjutnya. Semua orang menatap tajam kepada si wanita ini.
Mungkin hal biasa aja ketika si wanita ini tidak sengaja menjatuhkan gelas berisi tehnya. Lalu hal biasa juga ketika orang-orang lantas melihat kearahnya. Apalagi jika mereka memang kaget akan hal itu. Apalagi kalau ada diantara mereka yang latah ye kan? Bisa sambil dansa dia tuh. Tapi yang ingin saya perjelas disini adalah sikap orang-orang terhadap kejadian ini. Mereka dengan tatapan yang begitu sinis dan tajam seolah lantas menjadi hakim kepada si wanita ini.
Bahwa apa yang dilakukan si wanita ini entah sengaja atau tidak adalah sebuah kesalahan. Dan semua orang lantas berkedudukan sebagai seorang hakim. Dan mereka yang mengaku hakim dan pengadil ini tidak memberi ruang kepada si wanita tersebut untuk menjelaskan ketidaksengajaannya.
Semua kejadian yang saya ceritakan diatas menjadi cerminan kehidupan keseharian kita sebagai bangsa yang katanya “beradab”. Bahwa orang, entah sengaja atau tidak sengaja, korban provokasi atau bukan, jika dia salah maka harus dihukum.
Bahwa ketika seorang salah, memang harus dihukum. Dan sebisa mungkin hukumannya sesuai porsi kesalahannya, itu benar adanya. Tapi kita melupakan hal bahwa untuk kesalahan secara hukum, kita masih memiliki penegak hukum yang memang punya tugas dan fungsi itu. Atau kita bisa memaafkan mereka sebagai pelaku yang tidak sengaja melakukan kesalahan. Atau yang lebih parah, mereka melakukan kesalahan dalam kondisi yang kepepet. Saat mereka butuh uang saat itu juga untuk mengobati anaknya yang sakit padahal uangnya sudah habis.
Kita sering kali lebih melihat tradisi “menghakimi secara sosial” ini lebih tinggi posisinya dari “memaafkan karena kemanusiaan”. Kita lebih sering ingin tampil sebagai pahlawan karena menyelamatkan seorang ibu yang kecopetan dengan membuat sang pelaku babak belur, misalnya. Padahal untuk alasan tertentu, kadang kitalah yang membuat kondisi “pelaku” berada pada posisi melakukan kesalahan, lebih-lebih kejahatan.