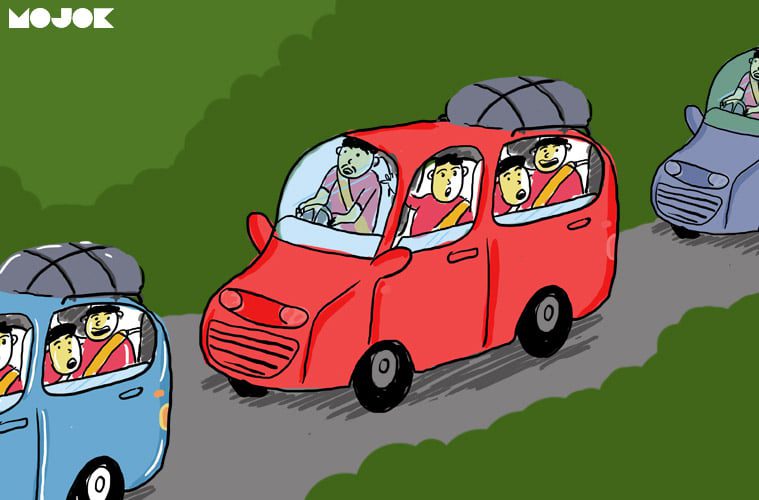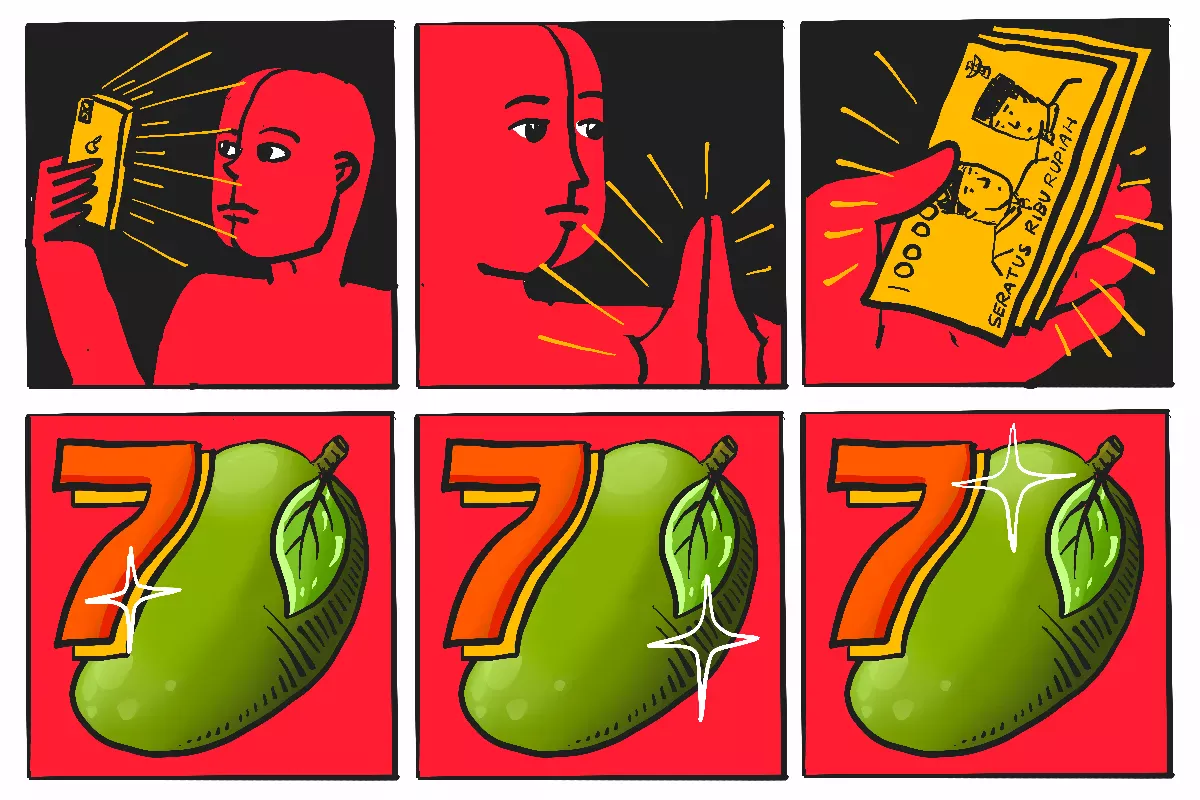Saya tidak setuju dengan pendapat Firda Fortuna Nasich yang mengatakan kalau Mojokerto bisa menjadi opsi slow living pengganti Malang yang kian amburadul. Sebagai orang asli Lumajang yang bisa dibilang sering pergi ke Mojokerto karena punya mas ipar di sana, saya melihat Mojokerto bukan menjadi ruang nyaman untuk hidup slow living.
Dari segi arus lalu lintas, entah kenapa Firda mengatakan, jalanan di Mojokerto lengang-lengang saja. Padahal, setiap kali nyampe di Mojokerto pas jam pulang kerja, saya sering terjebak macet di daerah Mojosari. Kemacetan di Mojosari terjadi karena jalur antarkabupaten dan banyak aktivitas perekonomian. Macetnya pun, tidak tanggung-tanggung. Saya pernah sampai terjebak macet lebih dari 30 menit.
Titik macet lainnya adalah jalan By Pass Mojokerto-Surabaya. Kemacetan di sana terjadi karena jembatannya kecil dan ada perlintasan kereta api.
Selain masalah kemacetan, arus lalu lintas di Mojokerto bisa dibilang sebelas dua belas sama jalanan di Gresik, alias menegangkan. Soalnya, jalanan di Mojokerto, utamanya yang dekat wilayah industri dan perbatasan, banyak bus dan truk besar yang melintas. Jadi, bagi yang tidak terbiasa melewati jalanan penuh “kendaraan transformer”, pasti jantung bakal deg-degan.
Lingkungan di Mojokerto menakutkan juga
Terlepas dari masalah arus lalu lintas, lingkungan di Mojokerto terbilang menakutkan juga. Dari segi kualitas udara, udara di Mojokerto buruk, jauh dari tempat asli saya, Lumajang. Ini berdasarkan indeks dari AccuWeather yang menyebutkan, kualitas udara di Mojokerto mencapai tingkat polusi tinggi. Maklum, Mojokerto banyak pabrik-pabrik, apalagi berada di jalur lintas kota/kabupaten dan provinsi, membuatnya banyak dilalui kendaraan.
Saya jadi teringat ketika masa kuliah, sering pergi ke Mojokerto naik sepeda motor. Selama di jalan, dada saya terasa sesak. Terus, wajah saya saat dibersihkan dengan milk cleanser, kapasnya hitam pekat. Itu menjadi indikasi bahwa jalanan di Mojokerto penuh polusi dan debu.
Masalah lingkungan lainnya di Mojokerto, bukan cuman buruknya kualitas udara. Di Mojokerto, sering terjadi bencana longsor dan banjir. Banjir di Mojokerto, bukan banjir ecek-ecek. Salah satu contoh kasusnya, pada awal Juni 2025, ada enam desa di Mojokerto yang dilanda banjir.
Dengan seramnya kondisi arus lalu lintas dan buruknya lingkungan di Mojokerto, hidup slow living yang seharusnya bikin hati tentram, malah jadi makan hati. Kalau gitu, apa bedanya Mojokerto sama Malang?
Lumajang FTW!
Dari situ saya kepikiran, sebenarnya yang punya peluang besar untuk menjadi tempat slow living di Jawa Timur adalah Lumajang. Jalanan macet bukan “sahabat karib” masyarakat sana. Meski dilalui banyak bus dan truk, jalannya lebar. Apalagi, Lumajang bukan wilayah pabrik-pabrik sehingga jarang ada truk berukuran besar.
Terus dari aspek ekonomi, dari pengamatan saya yang sering pulang kampung, masyarakat Lumajang, tidak terburu-buru mengejar masalah materi. Pernah pas saya beli ikan, orang di pinggir saya memanggil temannya, yang dari pakaiannya terlihat mau bekerja ke sawah. Orang yang mau pergi ke sawah itu, memilih berhenti dan mereka berdua ngobrol cukup lama.
Saya juga ingat keluarga saya yang punya bisnis, dia tidak pernah menolak jika diminta menjemput atau mengantar ke terminal. Padahal, di belakang harus ada bisnis yang harus diatur dan tak boleh ditinggalkan. Atau keluarga saya yang pedagang, kalau saya bertamu ke rumahnya, dia akan meninggalkan dagangannya.
Gaya santai pengejaran nilai ekonomi masyarakat Lumajang maklum terjadi karena biaya hidup di sana terbilang murah. Mau nongkrong di kafe dengan biaya di bawah 15 ribu, bakalan dapat. Menariknya, meski punya menu yang murah, suasana dan cita rasa menunya tetap enak. Misalnya saja, waktu saya ke cafe Magnolia. Di sana, menunya murah, tapi suasananya sejuk dan kualitas produknya top markotop.
Mau cari nasi di bawah harga 15 ribu, bakal nemu. Rasanya? Dengan harga di bawah 15 ribu, tersaji makanan dengan bumbu yang medok dan porsi mengenyangkan. Cari makanan di bawah 10 ribu? Ada juga. Saya pernah terkaget-kaget beli nasi jagung dengan harga 7 ribu, padahal porsinya kuli dan ikannya melimpah.
Budaya Lumajang yang gotong royong
Alasan lainnya adalah budaya masyarakat Lumajang yang mirip sama masyarakat Madura, yakni saling tolong-menolong. Orang sana kalau ada rezeki lebih akan berbagi makanan ke tetangga. Atau kalau ada tetangga yang sakit, masyarakat bakal membantu apa yang tidak bisa dipenuhi oleh keluarganya.
Kemiripan lainnya, dari aspek memasrahkan segalanya pada Ilahi. Masyarakat Lumajang percaya bahwa selama bekerja dengan cara halal, rezeki sudah diatur sebaik mungkin oleh Tuhan. Makanya, saya jarang melihat keluarga atau tetangga saya yang bekerja sampai loyo, mereka bekerja secukupnya.
Selain itu, hidup di Lumajang makin slow living karena nyari tempat wisata tidak sulit. Mau wisata gunung, pantai, danau, air terjun, sejarah, dan budaya, semuanya ada. Apalagi jalan menuju tempat wisata, tidak macet. Terus harga tiketnya juga murah.
Mau wisata gratis? Juga ada. Kalian tinggal pergi menikmati sawah yang terbentang hijau. Apalagi menikmati sawahnya, pas pagi-pagi, bisa bikin suasana hati makin syahdu. Menikmati sejuknya sawah di Lumajang tidak sulit karena masih terjaga dengan baik.
Mau mencari makna dan membahagiakan diri di Lumajang, bukan barang yang sulit dan mahal. Karena menginjakkan kaki di Lumajang, seperti berpindah dimensi. Di sana, waktu seperti berjalan dengan lamban. Di sana, kedamaian seperti teman yang akan menemani kita.
Penulis: Akbar Mawlana
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.