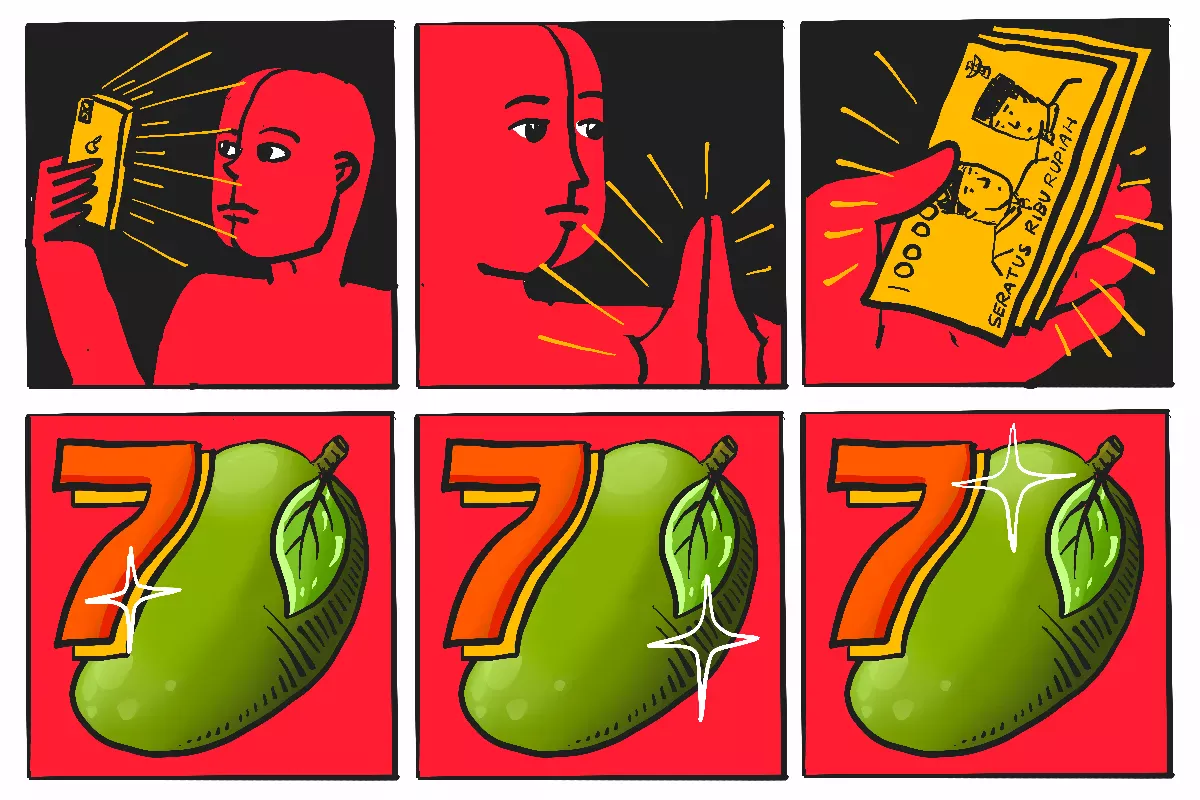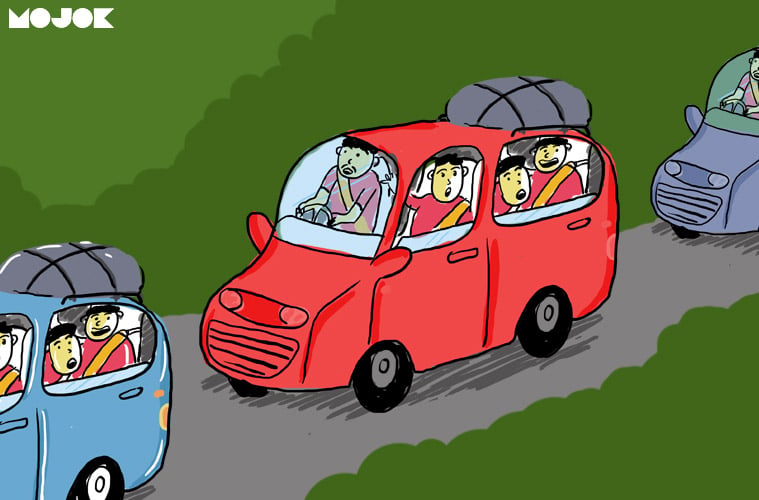Kalau ada kota di Jawa Timur yang paling sering disebut tapi paling jarang menjadi tujuan untuk tinggal, mungkin jawabannya Lamongan. Sebab, kota ini bukan kota yang lahir untuk jadi rumah bagi anak mudanya. Banyak anak muda yang lahir di Lamongan, besar sebentar, lalu pergi jauh. Entah ke Surabaya, Jakarta, atau bahkan luar negeri.
Jika hari ini kalian makan pecel lele di emperan jalan Jakarta, atau menyeruput soto Lamongan di gang sempit Jogja, hampir bisa dipastikan masakan itu karya orang Lamongan yang sedang merantau. Anehnya, yang terkenal justru makanannya, bukan kotanya.
Makanan yang mendahului kotanya
Lamongan memang bukan apa-apa kalau bukan karena makanannya. Pecel lele, soto Lamongan, sampai wingko babat sudah jadi ikon kuliner yang dikenal nyaris di seluruh Indonesia. Orang boleh nggak tahu letak Lamongan di peta, tapi kalau ditanya pecel lele, semua langsung paham dan mengaitkannya dengan kuliner nikmat, sambal, dan tenda-tenda di pinggir jalan.
Fyi saja, jika kalian penasaran kenapa awalnya warga Lamongan banyak yang merantau, maka jawabannya sederhana, semua gara-gara alam. Iya, orang sini punya ungkapan khas, “Wayah ketigo raiso cewok, wayah rendeng raiso ndodok.” Secara harfiah artinya, musim kemarau susah cebok karena air kering, musim hujan susah duduk karena banjir.
Ungkapan ini menggambarkan realitas keras Lamongan di masa lalu. Mau kemarau salah, mau musim hujan tambah salah. Hidup di kondisi begitu bikin orang berpikir ulang: bertahan di sini atau pergi cari rezeki di luar daerah? Maka merantau jadi pilihan rasional.
Pecel lele: dari tenda ke tenda
Kalau bicara pecel lele, ceritanya selalu sama. Seseorang dari Lamongan merantau ke kota besar. Awalnya cuma jadi asisten jualan, bagian goreng-goreng, atau tukang cuci piring. Lama-lama belajar resep, belajar teknik menggoreng sampai renyah, belajar belanja bumbu, jualan, dan ikut gabung komunitas.
Begitu sudah mahir, mereka buka tenda sendiri. Besoknya, saudara ikut bantu. Minggunya, tetangga datang. Bulan depannya, ada tenda baru di seberang jalan. Begitulah terus, sampai akhirnya pecel lele Lamongan jadi kuliner jalanan paling merakyat di negeri ini.
Kalau dilihat sepintas, ini seperti kisah sukses. Tapi kalau dipikir lebih dalam, ini sebetulnya ironi. Kenapa orang Lamongan harus pergi jauh-jauh hanya untuk bisa makan? Kenapa mereka tidak menjual pecel lele langsung di tanah kelahiran mereka sendiri dengan hasil yang layak?
Desa miliarder pecel lele di Lamongan: kisah inspiratif atau bukti gagal?
Belakangan, viral lagi fenomena “desa miliarder pecel lele.” Banyak yang memuja, banyak yang bangga. Katanya, anak-anak Lamongan hebat, bisa survive di mana pun. Tapi kalau kita jujur, itu bukan kisah inspiratif, melainkan bukti gagalnya pemerintah daerah.
Sebab, jika di sini tersedia lapangan kerja yang layak, siapa yang mau pergi ke kota besar dan jauh dari keluarga? Kenapa harus jadi TKI atau TKW jauh-jauh ke luar negeri kalau sebenarnya bisa hidup mapan di kampung sendiri?
Teman saya pernah meliput fenomena yang bikin miris: di beberapa dusun Lamongan, populasi anak muda Gen Z mulai langka. Bukan karena wabah atau zombi, tapi karena hampir semua sudah merantau. Desa jadi sepi, tinggal orang tua yang menjaga rumah.
Harapan untuk anak muda Lamongan
Saya tidak sedang menafikan kerja keras para perantau Lamongan. Mereka luar biasa. Tapi akan lebih luar biasa lagi kalau mereka bisa memilih merantau karena ingin berkembang, bukan karena terpaksa mencari penghidupan yang layak.
Di titik ini, pemerintah daerah mestinya introspeksi. Bagaimana membuka lapangan kerja baru? Bagaimana membangun infrastruktur yang mendukung? Dan bagaimana menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang sehat? Jangan cuma bangga bikin jargon dan baliho wisata, tapi lupa dengan inti persoalan: orang Lamongan pergi karena di rumah sendiri tak ada masa depan.
Kota yang harus belajar jadi rumah
Lamongan adalah kota yang selalu dikenang dari makanannya, tapi entah kenapa jarang dibahas dari kenyamanan hidupnya. Kalau pemerintah serius, seharusnya mereka berusaha menjadikan Lamongan bukan sekadar tempat kelahiran, tapi juga menjadi tempat yang bisa ditinggali dengan bangga oleh siapa saja warganya.
Supaya nanti tenda pecel lele di kota besar bukan lagi simbol anak Lamongan yang “mengungsi” demi hidup, melainkan simbol mereka yang melebarkan sayap karena di kampung halaman sudah mapan. Sebab, jika terus begini, Lamongan akan tetap jadi kota yang tak pernah lahir untuk jadi rumah bagi anak mudanya.
Penulis: M. Afiqul Adib
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Lamongan Megilan: Tagline Kabupaten Paling Jelek yang Pernah Saya Dengar, Mending Diubah Aja
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.