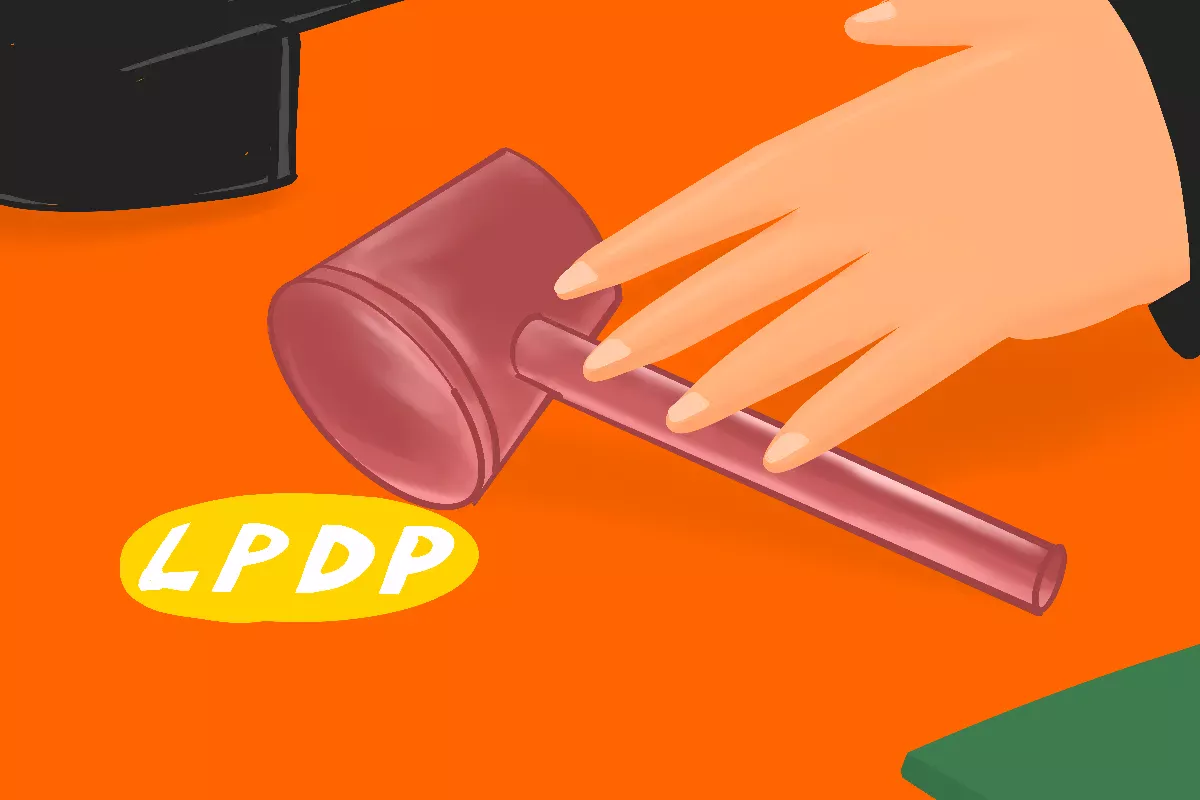Di banyak lingkungan, pernikahan masih sering diukur dari seberapa besar pesta atau resepsinya. Itu mengapa, ketika kami memilih jalan yang berbeda, tanpa pesta dan hanya menikah di KUA, banyak orang menganggap aneh dan berbicara yang tidak-tidak.
Saya dan pasangan memang sepakat untuk mengadakan pernikahan yang nggak ribet. Kami menginginkan pernikahan yang intim, tenang, dan bermakna. Bukan pesta besar yang menguras tenaga, emosi, dan tabungan hanya demi satu hari euforia. Namun, rupanya, pilihan itu justru melahirkan tuduhan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya.
Dikira macam-macam
Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang menyimpulkan sendiri, ada pula yang terang-terangan menganggap saya hamil di luar nikah. Logikanya sederhana tapi menyakitkan: menikah diam-diam di KUA berarti ada yang disembunyikan. Padahal tidak ada rahasia apa pun selain keinginan untuk hidup sederhana dan waras secara finansial.
Di titik itu, saya sadar bahwa bagi sebagian orang, pernikahan bukan lagi tentang akad dan komitmen, melainkan tentang konsumsi sosial. Tentang tenda besar, katering berlapis, dekorasi mahal, dan foto yang bisa dipamerkan. Ketika elemen-elemen itu absen, maka narasi negatif dengan mudah diciptakan.
Padahal, niat saya sangat sederhana. Saya menyayangi uang yang dimiliki. Saya tahu betul betapa melelahkannya bekerja, menabung, dan bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu ramah. Membayar gedung, konsumsi ratusan orang, suvenir, hiburan, dan biaya tambahan lain hanya untuk pesta satu hari terasa tidak masuk akal bagi saya. Terlebih, jika setelahnya harus hidup dengan cicilan dan utang yang membayangi rumah tangga baru.
Bukannya saya antipesta. Saya tidak menganggap pernikahan sederhana seperti di KUA lebih suci daripada pernikahan mewah. Saya hanya memilih apa yang paling masuk akal untuk hidup saya sendiri. Bagi saya, pernikahan bukan tujuan akhir, melainkan pintu awal menuju hidup bersama yang panjang. Dan hidup panjang itu butuh kestabilan, bukan sekadar kenangan satu hari.
Ironisnya, masyarakat sering kali lebih sibuk mengomentari cara orang menikah dibanding membantu orang bertahan setelah menikah. Banyak pasangan yang terlihat “sukses” di hari pernikahan, tetapi diam-diam kelimpungan menghadapi cicilan, konflik finansial, dan tekanan ekonomi. Namun kisah-kisah seperti itu jarang menjadi bahan gunjingan, karena yang dinilai sudah terlanjur sempurna di mata sosial.
Sementara mereka yang memilih jalan sunyi seperti nikah di KUA saja, justru harus menghadapi stigma. Perempuan, khususnya, sering menjadi sasaran paling empuk. Tuduhan hamil duluan masih menjadi senjata sosial yang dengan mudah dilontarkan, seolah pilihan hidup perempuan selalu harus dibenarkan dengan alasan moral yang sempit.
Menikah di KUA saja bukanlah dosa
Menurut saya tidak ada yang salah. Menikah di KUA bukan pelanggaran. Tidak mengundang satu kampung juga bukan dosa. Dan, menjaga keuangan bukan tanda ketidakmampuan. Justru, bagi saya, keputusan ini adalah bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, pasangan, dan masa depan yang ingin kami bangun bersama.
Pernikahan intim yang kami pilih memberi ruang untuk fokus pada hal yang lebih penting mengenai kesiapan mental, komunikasi, dan rencana hidup. Tidak ada stres berbulan-bulan memikirkan undangan. Tidak ada pula tekanan sosial soal standar pesta, dan rasa bersalah setelah hari H karena tabungan terkuras habis.
Saya tidak menyangkal bahwa komentar orang sempat melukai. Ada hari-hari ketika saya lelah harus terlihat kuat, seolah pilihan ini harus selalu dijelaskan. Namun seiring waktu, saya belajar bahwa tidak semua opini perlu dijawab. Hidup saya tidak dijalani oleh mereka yang bergosip, melainkan oleh saya sendiri.
Di tengah budaya yang masih mengagungkan pernikahan sebagai ajang pembuktian status sosial, memilih kesederhanaan seperti nikah di KUA memang terasa seperti melawan arus. Tetapi, saya percaya, keberanian terbesar bukanlah membuat pesta megah, melainkan berani berkata cukup. Berani hidup sesuai kemampuan, bukan tuntutan.
Jujur saya tidak menyesal. Saya lebih memilih digunjing oleh mulut tetangga sekarang daripada hidup nelangsa bertahun-tahun karena utang pesta. Lebih baik dinilai aneh oleh lingkungan, daripada tercekik oleh cicilan yang tidak perlu. Pernikahan saya mungkin tidak ramai, tetapi hati saya tenang. Dan bagi saya, itu sudah lebih dari cukup.
Penulis: Intan Permata Putri
Editor: Kenia Intan
BACA JUGA Pengalaman Pertama Kali Jadi Wali Nikah untuk Saudari Sepupu Sendiri.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.