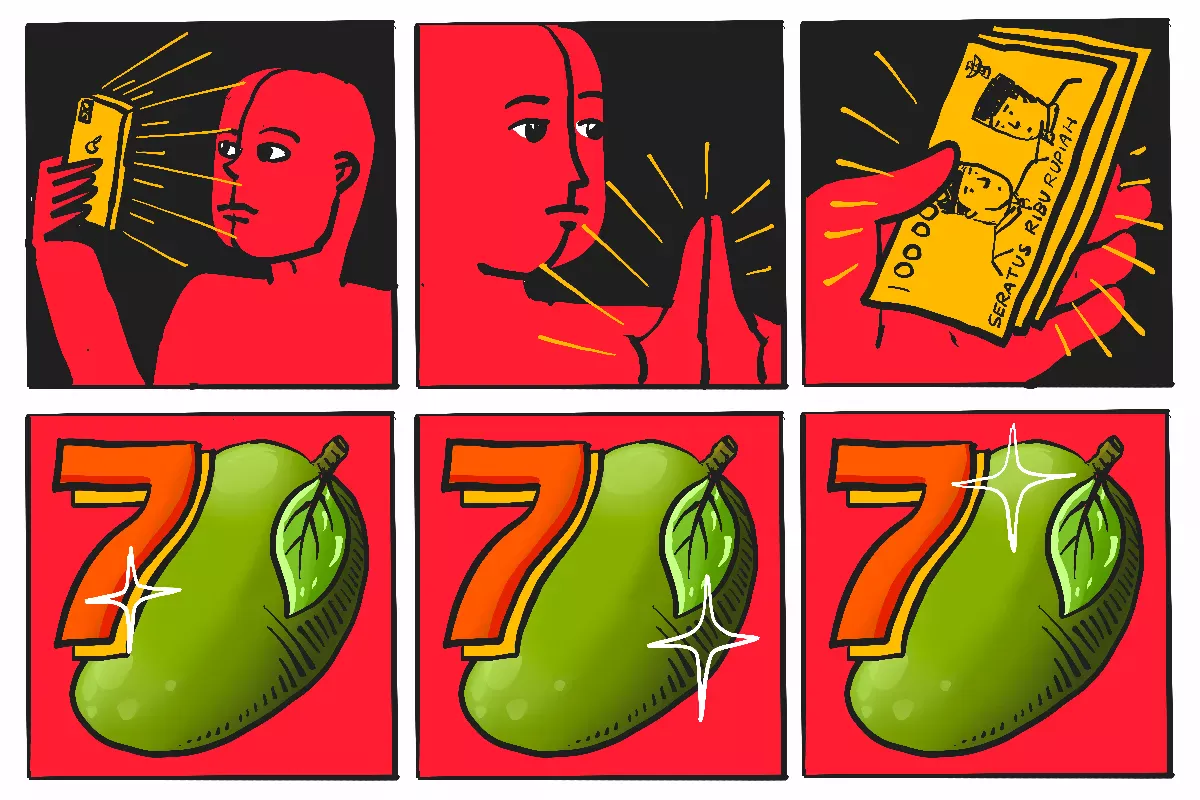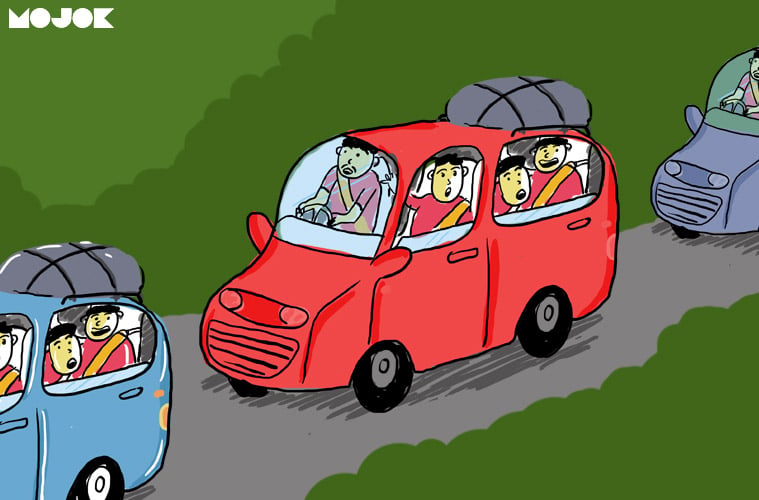Ini cerita saudara saya yang tinggal di Kudus. Dia tinggal di sebuah perumahan, lebih tepatnya di rumah yang berada di ujung gang buntu. Awalnya hidupnya tenang dan damai. Hingga pada suatu ketika, tetangganya memutuskan untuk pelihara ayam di lahan kosong yang terletak di depan rumah. Agak aneh memang, seolah-olah lahan kosong itu miliknya dan bisa dipakai sesuka hati.
Tetangga itu beralasan pelihara ayam bisa jadi solusi atas banyak persoalan. Salah satunya, sisa nasi dan lauk tidak akan berakhir di tong sampah. Sisa makanan bisa dimanfaatkan jadi pakan ayam. Istilah zaman sekarang, zero waste.
Sayangnya, tetangga saudara ini sepertinya lupa memikirkan bahwa kotoran ayam bisa membawa persoalan baru. Terlebih, tetangga ini tidak punya pengetahuan maupun teknologi untuk mengolahnya. Pada akhirnya, kotoran ayam jadi polusi udara yang mengganggu untuk lingkungan sekitar. Terlebih saudara saya yang rumahnya berada di seberang kandang ayam,
Saya tidak pernah membayangkan jadi saudara saya. Tiap kali buka jendela bukan udara segar yang dihirup melainkan bau kotoran ayam. Pagi, siang, hingga malam bau kurang sedap itu siap menyerang. Tidak ada kata istirahat. Benar-benar mengganggu.
Tetangga pelihara ayam dan nggak peka adalah sumber masalah
Merasa tidak tahan lagi, saudara saya melaporkan ketidaknyamanan terkait pelihara ayam ini ke ketua RT. Harapannya, dengan melibatkan RT, masalah ini bisa teratasi dengan cara kekeluargaan. Misal, kandang ayam dipindah ke belakang atau diperbaiki agar lebih higienis.
Sayangnya, yang terjadi justru kebuntuan. Tetangga itu malah merasa jadi korban. Dia menuntut toleransi. Seakan-akan bau adalah sesuatu yang harus disyukuri sebagai bagian dari keberagaman hidup. Di sinilah muncul ironi: toleransi dipakai sebagai tameng bagi perilaku egois.
Padahal, dalam kajian sosiologi perkotaan, toleransi adalah hasil negosiasi antar warga demi menjaga harmoni. Ia bukan lisensi untuk mengganggu kenyamanan orang lain. Mengutip adagium klasik, “Hak seseorang untuk mengayunkan tinju berhenti di ujung hidung orang lain.” Jika diperluas, hak seseorang untuk memelihara ayam berhenti di titik ketika bau kotorannya merusak hidung tetangganya.
Urban farming yang gagal
Fenomena pelihara ayam di perumahan sering kali diasosiasikan dengan tren urban farming. Media sosial penuh dengan konten inspiratif “Cara Beternak Ayam di Lahan Sempit” atau “Tips Panen Telur Organik di Tengah Kota”. Gagasan ini terdengar progresif, apalagi di tengah isu ketahanan pangan. Namun, sebagaimana banyak tren viral lainnya, tidak semua praktik cocok diterapkan tanpa memikirkan konteks.
Perumahan modern bukanlah desa agraris. Ia dibangun dengan asumsi ruang yang terbatas, sanitasi yang terjaga, serta kualitas udara yang homogen. Ketika kandang ayam hadir di dalam ekosistem itu, ia menjadi anomali ekologis. Seperti memarkir truk gandeng di halaman kluster, tentu, bukan salah truknya, tapi salah konteksnya.
Selain bau, ada pula risiko kesehatan. Kotoran ayam menyimpan amonia dan patogen yang berpotensi memicu penyakit pernapasan. Di lingkungan rumah berdempetan, potensi penularan menjadi berlipat ganda. Belum lagi keberadaan lalat yang tiba-tiba menjadi “populasi tambahan” dalam rantai ekologi perumahan. Dengan kata lain, ayam di perumahan bukan sekadar gangguan sosial, melainkan ancaman ekologis mini yang luput dari perhatian regulasi.
Pelihara ayam dilihat dari politik bau dan krisis komunikasi
Dalam ilmu politik, ada konsep the politics of smell atau politik bau. Mungkin terdengar remeh, tapi bau sering kali menjadi sumber konflik sosial yang lebih tajam daripada sekadar suara bising. Bau menyusup ke ruang intim, tidak bisa dihindari, dan memicu emosi bawah sadar.
Kasus tetangga saudara saya yang memelihara ayam ini bisa dibaca sebagai bentuk politik bau. Sang pemilik ayam menguasai ruang dengan cara paling halus: lewat udara. Ia tidak berteriak, tidak membuat gaduh, tapi berhasil memaksakan kehadirannya ke hidung semua orang di sekitar.
Krisis muncul ketika komunikasi macet. Pihak yang terganggu dianggap kurang sabar. Pihak yang mengganggu merasa punya hak. Padahal, dalam teori komunikasi komunitas, konflik semacam ini adalah tanda gagalnya mediasi dan absennya regulasi yang jelas. Tidak ada aturan eksplisit soal pelihara ayam. Misal, sebenarnya berapa ekor ayam yang boleh dipelihara di perumahan? Sengketa pun berubah menjadi perang tafsir: antara hak individu dan kenyamanan kolektif.
Etika bertetangga
Kasus ayam di perumahan ini mungkin terdengar sepele. Namun, ia mencerminkan problem mendasar dalam kehidupan sosial kita. Tentang bagaimana mengelola ego, ruang, dan lingkungan bersama.
Bau ayam hanyalah gejala. Intinya adalah absennya kesadaran ekologis yang lebih luas bahwa hidup berdampingan berarti mengatur diri, bukan sekadar menuntut pengertian orang lain. Kita boleh punya hobi, idealisme, bahkan klaim ekologis, tetapi semua itu tidak boleh mengorbankan kenyamanan publik.
Mungkin sudah saatnya dibuat aturan yang lebih eksplisit, urban farming boleh, tapi dengan standar higienitas. Jika tidak, konflik akan terus terjadi, dari ayam hingga entah hewan apa berikutnya. Dan selama itu belum ada, kita semua terjebak dalam politik bau, di mana yang berkuasa bukan siapa-siapa, melainkan aroma. Dan jujur saja, tidak ada demokrasi yang sehat bila setiap hari warganya dipaksa hidup dalam udara busuk.
Penulis : Budi
Editor : Kenia Intan
BACA JUGA 3 Penderitaan Punya Rumah Dekat Sawah yang Nggak Disadari Kebanyakan Orang Kota.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.