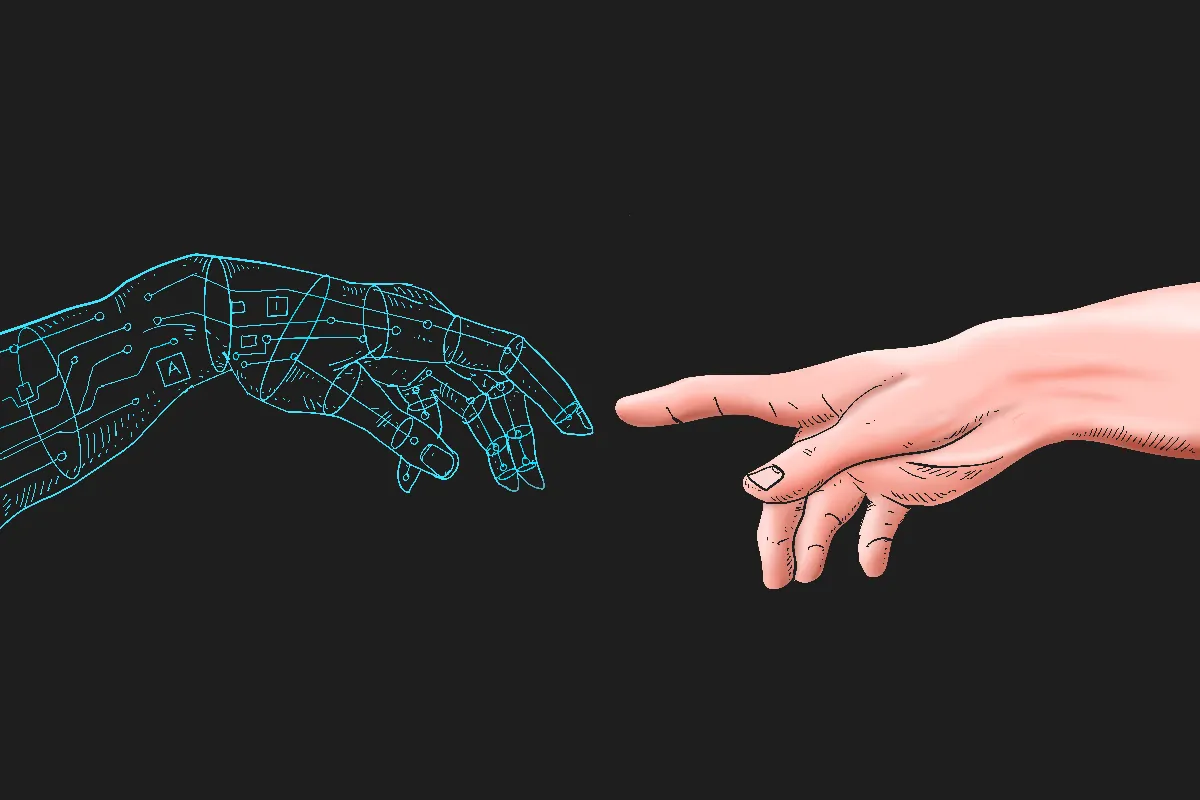Menikah dengan orang yang berlainan suku dan budaya bisa jadi perkara rumit. Tapi menikah dengan orang yang sukunya sama pun tetap ada potensi gegar budaya. Sebagai orang asli Madiun yang kuliah 4 tahun di Jogja, saat berjodoh dengan orang Jogja, saya pikir tidak akan ada masalah. Perbedaan tidak mencolok. Sama-sama Jawa. Apa sih yang akan bikin kaget? Saya saja sudah tertular dialek khas Jogja. Aman lah.
Namun saya lupa bahwa selama di Jogja, saya “cuma” tinggal di bawah atap kampus yang memayungi mahasiswa seluruh Nusantara, tidak betul-betul bersinggungan dengan orang Jogja asli. Tertular dialek yang hanya sekelumit itu tidak seharusnya membuat saya merasa memahami Jogja. Akibatnya, setelah berkeluarga dengan orang Jogja, tetap saja saya mengalami culture shock alias gegar budaya.
Tentu saja ya, paling pertama perkara resepsi. Kita mulai yang awal-awal dulu, nanti baru ngomongin perkara kehidupan.
Meski tidak menyertakan upacara adat dalam acara ngunduh mantu di Jogja dulu, rombongan keluarga yang datang dari Madiun lumayan tidak familiar dengan meja-meja yang ditaruh di antara kursi tamu. Di atas meja itu sudah tersedia aneka snack dan gelas-gelas berisi teh manis. Hospitality ketika resepsi seperti itu tidak pernah saya jumpai di Madiun. Saat itu baru menyadari bahwa Jogja pun memiliki budayanya sendiri dalam menyambut tamu resepsi.
Selain perkara menyambut tamu resepsi, yang paling bikin saya terkaget-kaget adalah bahasa.
Bahasa Jogja dan Madiun yang amat berbeda
Ini realitas yang tidak bisa dihindari. Jangankan Madiun dengan Jogja, Ngawi yang bersebelahan dengan Madiun saja punya kosakata yang tak pernah ada di kamus orang Madiun, yakni “mboyak” yang bermakna bodo amat. Demikian, ketika suatu hari pasangan saya mengucapkan kata “oglangan”, saya tergelak sekaligus terheran-heran. Ternyata orang Jogja punya kosakata khusus untuk menamakan kondisi pemadaman listrik.
Kosakata ini cukup asing bagi telinga orang Jawa Timur seperti saya, yang ketika ada pemadaman akan tetap bilang “listrik mati” dalam satu frasa.
Kosakata lain yang membuat saya mindblowing adalah ketika bapak mertua yang orang asli Kauman mengucapkan kata “kremun”, untuk menyebut gerimis sangat tipis atau hanya setitik-setitik. Kata ini juga tak pernah familiar di benak saya, sekaligus tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Demikian pula dengan kata “lemut” yang awalnya membuat saya tak paham. Ternyata bermakna nyamuk, sangat berbeda dengan orang Madiun yang menyebut nyamuk sebagai “jingklong”.
Selain istilah-istilah baru itu, ternyata kami juga sering tidak sepakat dalam menyebut jenis-jenis sayuran. Misalnya, ketika saya pulang dari berbelanja, pasangan saya menyebut “loncang” mengacu pada salah satu jenis sayuran yang saya beli, membuat saya ternganga karena bingung. Ternyata yang ia maksud adalah daun bawang yang oleh orang Madiun disebut “bawang prei”.
Begitu juga dengan sayuran lain seperti petai cina yang orang Jogja menyebutnya “mlandhing”, sementara selama ini orang Madiun mengenalnya dengan nama “lamtoro”. Bagi orang Jogja, kecambah adalah “thokolan”, sementara orang Madiun menyebutnya “gantheng”.
Mari? Emang sakit apa?
Begitu pula untuk urusan perut yang keroncongan. Orang Jogja mengucapkan “ngelih” untuk mengekspresikan rasa lapar. Ini agak sulit diterima orang Jawa Timur seperti saya, karena “ngelih” lebih bermakna memindahkan daripada lapar. Bagi orang Madiun, selamanya lapar adalah “luwe”. Memang agak rumit, seperti halnya kata “mari” yang bermakna selesai bagi orang Surabaya, padahal orang Jawa Tengah mengartikannya sebagai sembuh dari sakit.
Satu lagi, orang Jogja menyebut kecamatan dengan “kapanewon”. Sungguh lain daripada yang lain dan tidak biasa. Pertama kali membaca kata ini rasanya sedikit rumit, sama halnya ketika orang luar Bandung menjumpai tulisan Ciumbuleuit di plang penunjuk arah pinggir jalan, bikin lidah kesrimpet.
Perkara perbedaan dialek ini jika ditelisik satu persatu mungkin akan jadi tabel yang panjang, dan bisa jadi bahan menulis skripsi sosiolinguistik. Maka, lebih baik disudahi saja meskipun kadang-kadang kami mengalami lost in translation.
Perbedaan selera makanan
Jujur saja, saya tidak benar-benar akrab dengan makanan khas Jogja meskipun kuliah di Jogja. Setelah berkeluarga dengan orang Jogja, saya baru paham bahwa kuliner khas Jogja itu bukan gudeg semata. Ada wedang secang dan wedang uwuh, minuman tradisional berbahan rempah yang tak pernah saja jumpai di Madiun.
Untuk gudeg, sambal krecek, dan oseng mercon masih bisa diterima oleh lidah saya. Akan tetapi, maaf saja, lidah ini tidak mampu mengatakan enak untuk brongkos dan mie lethek yang menjadi kuliner kebanggaan warga Bantul itu. Begitu pula dengan jadah tempe yang sering diplesetkan jadi burger Jawa. Menurut saya itu perpaduan yang cukup aneh, kenapa tidak jadah dan tempe bacem itu dimakan sendiri-sendiri saja.
Sebaliknya, pasangan saya juga tidak pernah berminat menjajal rujak petis—kuliner kebanggan orang Madiun dan sekitarnya, yang mana ini sangat lezat bagi lidah saya. Tentu ada sedikit rasa sedih ketika kangen menyantap rujak petis, tapi tak bisa menyantap bersama pasangan lantaran perbedaan selera makanan. Tapi, mungkin ia juga merasakan sedih ketika suatu kali ingin menyantap mie lethek, sedangkan saya tidak berminat.
Dari sekian perbedaan berlatar budaya yang berbeda tersebut, semua masih bisa dikompromikan dan tak pernah menjadi bahan konflik yang tidak perlu. Sebagai orang yang pernah ditempa di kampus budaya, perbedaan-perbedaan tersebut membuat saya bersyukur karena ternyata budaya dan bahasa dalam suku yang sama pun bisa berupa-rupa, tapi pernikahan menyatukannya tanpa harus kehilangan identitas budaya masing-masing.
Penulis: Septalia Anugrah Wibyaninggar
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA 5 Hal yang Bikin Saya Kaget Waktu KKN di Madiun
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.