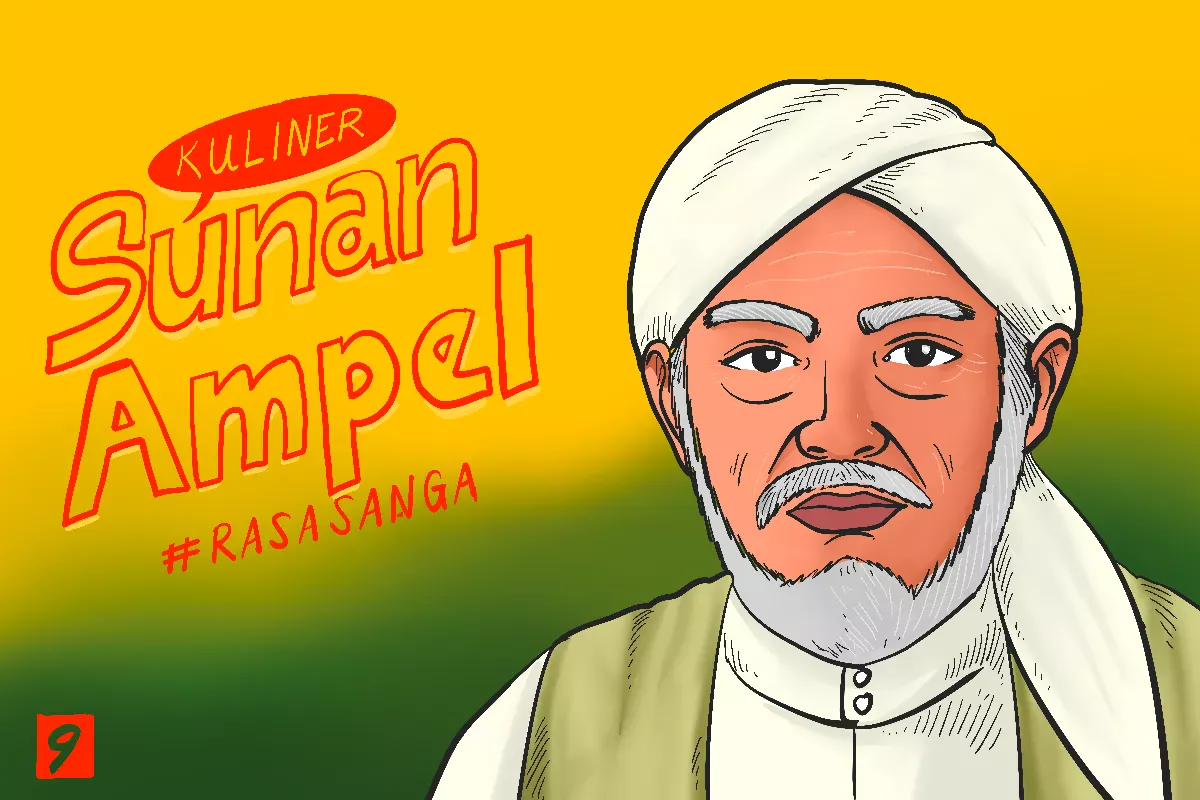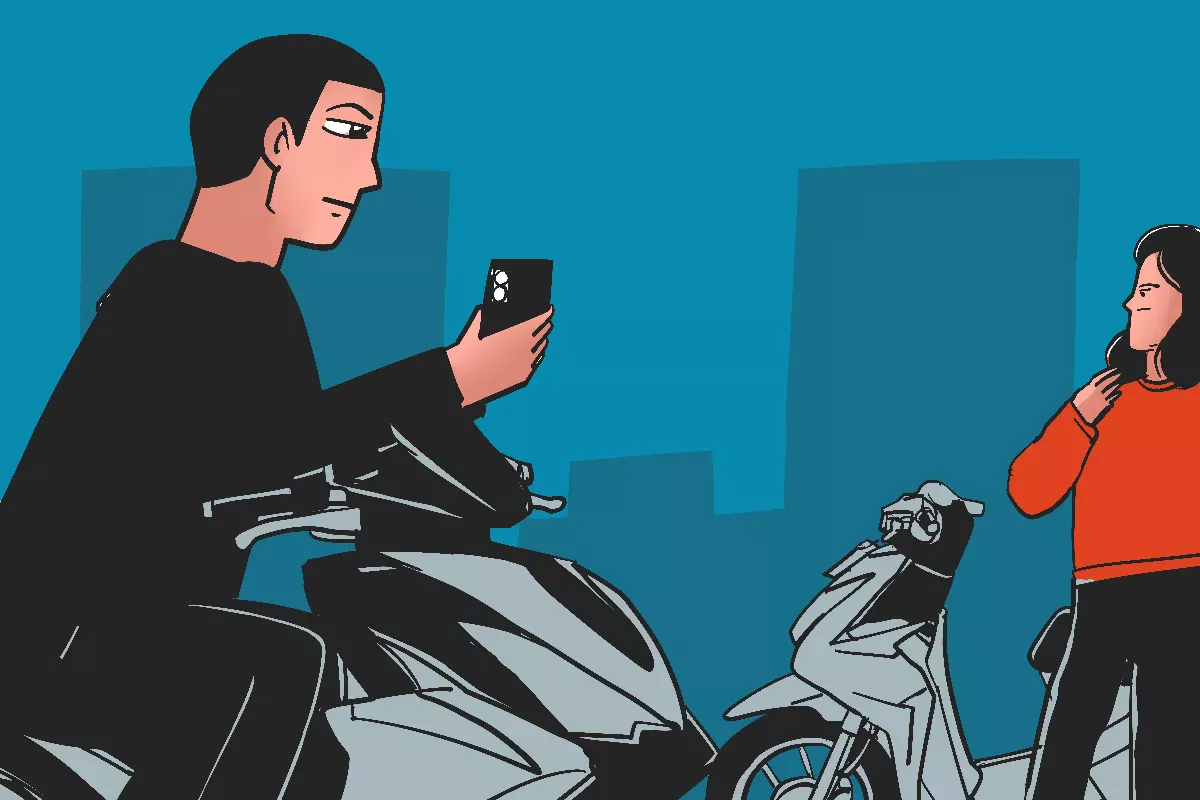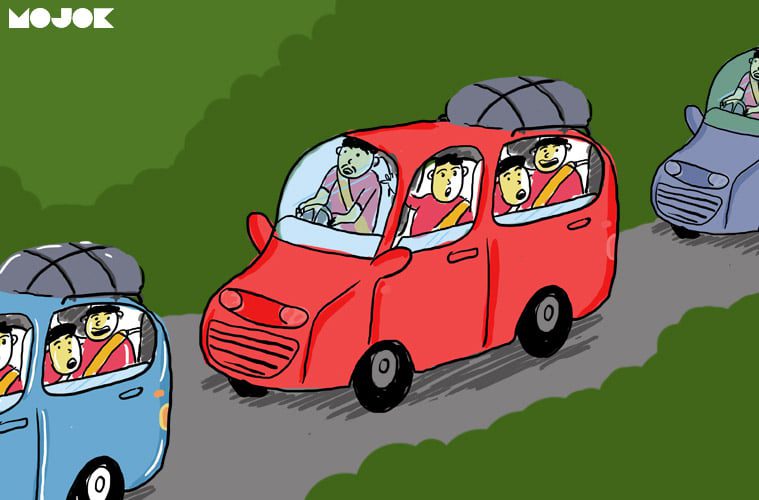Selepas membaca tulisan Mbak Utamy Ningsih berjudul “Kamus Bahasa Makassar Sehari-hari: Kenalan sama Partikel Mi, Ji, dan Ki,” saya, kok, jadi miris. Pasalnya, Mbak Utamy menunjukkan kalau bahasa Makassar itu tidak hanya dikenal orang Makassar, tapi juga orang lain. Bagaimana belio gamblang sekali menggambarkan orang luar Sulawesi yang mencoba mengakrabkan diri ketika bertemu orang Makassar dengan memakai bahasa Makassar. Contohnya dengan ditambahi partikel ji. Bagi saya, itu sudah cukup untuk bikin saya miris terhadap daerah saya sendiri: Pekalongan. Ketika saya ketemu orang luar, saya tidak mendapat pengalaman yang sama seperti Mbak Utamy. Orang-orang yang saya temui alih-alih mencoba mengakrabkan diri dengan menggunakan dialek Pekalongan, justru membombardir saya dengan bahasa yang sangat berbeda dari dialek Pekalongan.
Sampai di sini saya pun memaklumi, mungkin saja dialek Pekalongan begitu sukar untuk diucapkan oleh orang luar Pekalongan. Wong diucapkan saja sukar, apalagi dipahami. Salah satunya dalam dialek Pekalongan, ada penggunaan bunyi “o” di akhir kata.
Penggunaan bunyi “o” di akhir kata begitu sakral bagi masyarakat Pekalongan. Saya pikir, setiap orang asli Pekalongan tidak bisa tidak menambahi huruf vokal “o” dalam setiap dialog, terutama untuk menegaskan sesuatu hal (baca: ngotot). Itulah mengapa saya menyebutnya sakral, ya boleh jadi kedudukannya ibarat Tuhan.
Saking sakral dan begitu kuatnya menancap ke dalam diri setiap insan yang lahir di Pekalongan, akhiran bunyi “o” ini tak bisa ditiru orang daerah lain. Jangankan ditiru, ketika didengarkannya saja sudah seperti berbicara dengan makhluk asing. Bahkan bagi orang-orang asli daerah satu eks Karesidenan Pekalongan, misalnya orang Batang, Pemalang, Tegal, ataupun Brebes.
Imbuhan “o” di akhir kata dalam dialek Pekalongan juga memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai bahasa Pekalongan tulen. Yang artinya tanpa akhiran “o” kata tersebut bisa jadi sama sekali tidak bermakna.
Contohnya kata “kotomono”. Jujur, satu kata lengkap seperti itu saja saya susah memberikan maknanya, apalagi mungkin kalian yang baca. Tapi tak apa, saya akan coba jelaskan beberapa kata dalam dialek Pekalongan. Semoga kalian nggak puyeng bacanya, sebab saya sendiri juga sedikit pening ini nulisnya.
Oke, lanjut, kata “kotomono” jika tak diakhiri dengan huruf “o”, ia akan kehilangan makna. Orang Pekalongan sendiri juga tidak akan paham kata “kotomon”. Lain ceritanya dengan “kotomono” yang artinya kurang lebih “anggap saja”.
Contoh kalimatnya begini:
“Aku pak melu lomba badminton, kotomono iki sek latihan.”
Yang artinya:
“Aku ingin ikut lomba badminton, anggap saja ini sedang latihan.”
Sama halnya dengan kata “singoh-singoho”. Mungkin kalau akhiran kata tersebut tidak ada huruf vokal “o”, orang lain akan memaknai kata “singoh-singoh” sebagai bentuk jamak dari singa atau menunjukkan lebih dari satu singa, seperti kata “orang-orang”.
Kata “singoh-singoho” oleh masyarakat Pekalongan kurang lebih bermakna “bebas”, “terserah”, “yang mana saja”. Ini kalau dalam bahasa Jawa umum seringnya memakai “karepe”.
Contohnya begini:
Bapak: “Ke, Le, tak kei duet.”
Aku: “Nggo opo, Pak?”
Bapak: “Singoh-singoho.”
Artinya kurang lebih begini:
Bapak: “Ini, Nak, saya kasih uang.”
Aku: “Buat apa, Pak?”
Bapak: “Terserah.”
Imbuhan “o” bagi masyarakat Pekalongan sering dipakai pula untuk mempertanyakan sesuatu dengan tegas, dan memberikan penegasan pada satu pernyataan. Contohnya dialog berikut ini:
“Kowe rung adus’o?”
“Bebas’o”
Artinya:
“Kamu belum mandi, ya?”
“Bebas dong!”
Atau dalam contoh lain seperti ini:
“Kowe kok rung ndue pacar, sih?”
“Yo pak orak’o!!!”
Artinya:
“Kamu kok belum punya pacar?”
“Ya biarin, sih.”
Lantaran begitu sakralnya huruf “o” di akhir kata, maka sampai pada praktik-praktik yang bernuansa kapitalistik dan feodalisme, orang Pekalongan juga tak bisa terlepas dari pemakaian “o” di akhir kata.
Misalnya seperti:
“Kowe mbuk kerja’o sing bener men dadi wong sugih!”
Yang artinya:
“Kamu itu kerja yang bener supaya dari jadi orang kaya!”
Saya tidak tahu sejak kapan huruf “o” yang acap kali muncul di akhir kata ini menjadi bagian dari dialek Pekalongan. Kalau saya boleh mengira-ngira, mungkin saja cikal bakalnya dari masyarakat pesisir, atau bisa dikatakan Pekalongan bagian utara.
Kalau dirunut sejarah, perdagangan, kebudayaan, sampai bahasa Pekalongan, barangkali memang berasal dari daerah pesisir. Pasalnya, di daerah utara ini menjadi semacam titik awal para pelancong dari seluruh negeri datang ke Pekalongan melalui armada laut. Lantaran, Pekalongan konon memiliki pelabuhan terbesar di era Hindia-Belanda.
*Terminal Mulok adalah segmen khusus yang mengulas tentang bahasa dari berbagai daerah di Indonesia dan dibagikan dalam edisi khusus Bulan Bahasa 2021.
BACA JUGA Pekalongan Itu Nggak Cocok Dijadiin Kota Wisata, Pemerintah Jangan Ngeyel dan tulisan Muhammad Arsyad lainnya.