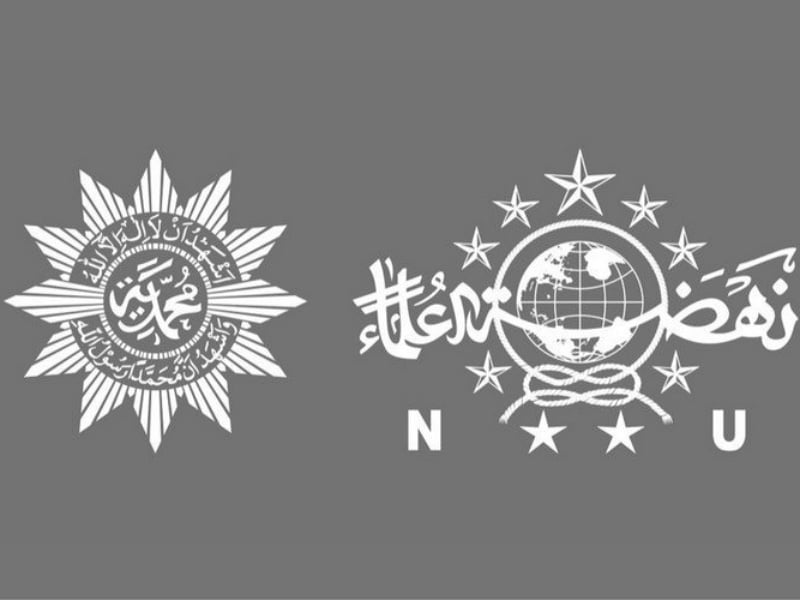Kalau hidup berjalan sesuai rencana, mungkin saya tidak akan pernah bersekolah di SMA Muhammadiyah. Waktu itu, rencana saya sederhana dan sangat umum: masuk SMA negeri. Seperti kebanyakan siswa SMP lain, SMA negeri dianggap tujuan paling “normal”, paling aman, dan paling diakui.
Sayangnya, sistem zonasi berkata lain. Nama saya tidak terpanggil, jarak rumah kalah hitung, dan harapan pun ikut gugur. Bukan karena nilai kurang, tapi karena peta. Di titik itulah saya sadar, dalam sistem pendidikan, kadang usaha tidak selalu sejalan dengan hasil.
Di waktu yang mepet, saya dihadapkan pada pilihan yang awalnya terasa seperti opsi cadangan yaitu sekolah swasta. Salah satunya SMA Muhammadiyah. Jujur saja, waktu itu saya tidak punya ekspektasi tinggi. Yang penting sekolah dulu.
Dua tahun setelah lulus, saya justru bisa berkata dengan yakin yaitu bersekolah di SMA Muhammadiyah adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya ambil, meskipun awalnya bukan pilihan pertama.
Guru yang membuka pikiran, bukan menutup pertanyaan
Hal pertama yang paling saya syukuri adalah kualitas guru-gurunya. Banyak dari mereka masih relatif muda, segar secara pemikiran, dan tidak alergi pada pertanyaan kritis. Di kelas, saya tidak merasa dipaksa menelan jawaban mentah-mentah. Diskusi justru didorong, bahkan kadang dipancing.
Meskipun sekolah berbasis keagamaan, saya tidak menemukan ceramah kosong, apalagi pseudo-sains yang sering ditakuti orang saat mendengar istilah “sekolah agama”. Yang saya temui justru pendekatan rasional: agama dijelaskan berdampingan dengan ilmu pengetahuan, bukan saling meniadakan.
Di sinilah daya pikir kritis saya pelan-pelan terasah. Bertanya tidak dianggap melawan. Berbeda pendapat tidak langsung dicap kurang iman. Saya belajar bahwa berpikir kritis dan beragama tidak harus saling curiga.
Lingkungan religius SMA Muhammadiyah yang membentuk, bukan menekan
Pembiasaan seperti tadarus, salat duha, dan latihan ceramah awalnya terasa biasa saja. Bahkan kadang terasa melelahkan. Namun efeknya baru benar-benar terasa setelah saya keluar dari lingkungan SMA Muhammadiyah.
Lingkungan religius ini pelan-pelan membentuk disiplin, kepercayaan diri, dan kemampuan berbicara di depan umum. Latihan ceramah, misalnya, ternyata menjadi bekal public speaking yang manfaatnya masih saya rasakan sampai sekarang. Saya jadi lebih berani bicara, lebih terstruktur menyampaikan gagasan, dan tidak kaku ketika harus berdiri di depan orang banyak.
Ini bukan pembentukan karakter yang instan atau penuh tekanan. Tidak ada paksaan menjadi “suci”. Yang ada adalah pembiasaan. Pelan, konsisten, dan manusiawi.
BACA JUGA: Alasan Sekolah-sekolah Muhammadiyah Enggan Pakai Istilah ‘Islam Terpadu’
Organisasi yang mengajarkan struktur dan tanggung jawab
Di sekolah Muhammadiyah, kehidupan organisasi tidak berhenti di OSIS dan pramuka. Ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) sebagai pengganti peran OSIS dan Hizbul Wathan (HW) sebagai gerakan kepanduan, dengan struktur yang rapi dari tingkat ranting hingga pusat.
Lewat organisasi ini, saya belajar tentang kepemimpinan, koordinasi, dan tanggung jawab. Bukan sekadar nama jabatan, tapi benar-benar bekerja. Rapat, program, evaluasi—semuanya dijalani dengan serius. Saya belajar bahwa berorganisasi bukan soal keren-kerenan, tapi soal melayani dan menyelesaikan masalah.
Pengalaman ini membuat saya lebih siap menghadapi dunia setelah lulus, di mana kerja tim dan tanggung jawab bukan lagi teori.
Pertemanan yang bukan sembarangan
Hal lain yang baru saya sadari setelah menjalaninya adalah kualitas pertemanan. Ternyata bukan saya saja yang mengalami nasib serupa. Banyak teman-teman saya di SMA Muhammadiyah adalah anak-anak yang sebenarnya pintar, punya potensi besar, tetapi tidak diterima di SMA negeri bukan karena kemampuan, melainkan karena zonasi.
Dari situ saya masuk ke lingkungan belajar yang unik: kompetitif, tapi tidak saling menjatuhkan. Kami sama-sama sadar bahwa kami “terdampar” di tempat yang sama. Alih-alih larut dalam kekecewaan, kami justru saling mendorong untuk berkembang. Suasana kelas jadi hidup. Diskusi berjalan. Bercanda ada, tapi belajar tetap serius.
Di titik ini saya belajar bahwa sekolah bukan cuma soal gedung dan label, tapi soal siapa saja orang-orang yang tumbuh bersama kita di dalamnya. Berteman dengan orang-orang yang mau belajar dan mau berkembang itu pengaruhnya panjang—bahkan setelah lulus.
BACA JUGA: SMA Muhi Jogja: Sempat Bubar Karena Perang Sebelum Sukses Lahirkan Tokoh-tokoh Besar
SMA Muhammadiyah: dari opsi cadangan menjadi tempat bertumbuh
Hal lain yang patut dicatat adalah soal toleransi. Di sekolah saya, ada teman-teman yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama, bahkan ada yang aktif di LDII. Tidak ada tekanan untuk “harus jadi Muhammadiyah”.
Pelajaran kemuhammadiyahan diberikan sebagai pengenalan, bukan doktrin. Kami diajak memahami sejarah dan nilai, bukan dipaksa mengafirmasi. Bagi saya, ini justru cerminan pendidikan yang sehat: mengenalkan nilai tanpa menghilangkan kebebasan berpikir.
Pada akhirnya, bersekolah di SMA Muhammadiyah terasa seperti masuk ke sebuah workshop kehidupan. Tempat belajar akademik, sekaligus ruang membangun karakter.
Saya masuk karena gagal zonasi. Saya keluar dengan versi diri yang lebih siap menghadapi dunia. Kadang, hidup memang bekerja seperti itu: rencana gagal, tapi justru membuka jalan yang lebih tepat.
Dan untuk itu, saya bersyukur pernah menjadi bagian dari SMA Muhammadiyah.
Penulis: Faris Firdaus Alkautsar
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA 7 SMA Muhammadiyah Terbaik di Indonesia Ada di DIY dan Jawa Tengah
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.