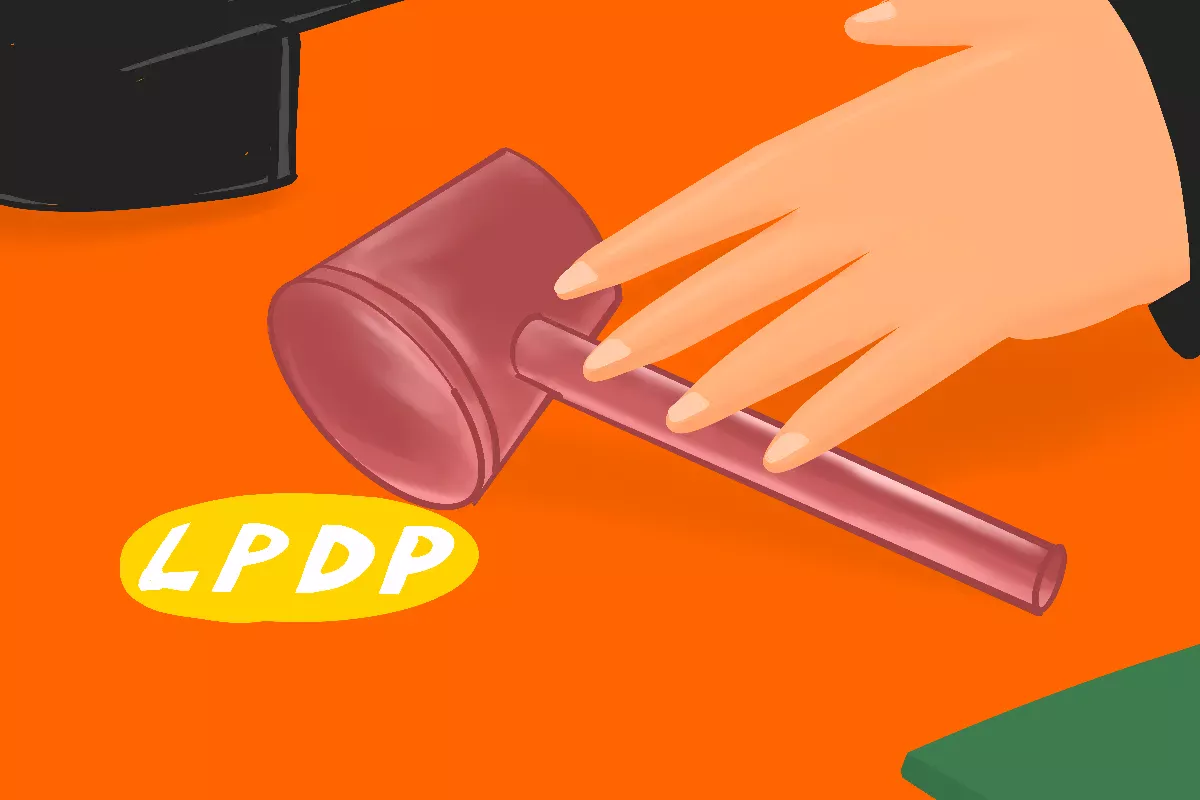Pernah dengan pepatah Jawa yang mengatakan culke ndase cekeli buntute—maknanya dilepaskan kepalanya tapi dipegang ekornya. Hasilnya kloget-kloget—sekilas nampak bebas akan tetapi tidak bisa kemana-mana. Mungkin itu kalimat yang tepat untuk menggambarkan penerimaan siswa baru Sekolah Dasar di negara kita tercinta, Indonesia.
Bagaimana pasalnya?
Menurut Pemerintah, setiap SD dilarang mengadakan tes calistung (membaca, menulis, dan berhitung) dalam proses penerimaan siswa baru. Jadi calon murid tidak boleh diseleksi berdasarkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung-nya. Selama masih dalam satu zonasi, wajib diterima. Sepintas aturan itu masuk akal. Anak kecil masuk sekolah kan niatnya memang mau belajar. Dari yang semula tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung masuk sekolah dasar agar bisa membaca menulis dan berhitung.
Logika itu masuk akal jika diterapkan pada zaman dahulu—zaman Pak Harto belum bisa dibuat meme “Enak zamanku to”. Sebab saat itu pelajaran kelas 1 SD adalah ini Budi, ini bapak Budi, ini ibu Budi, ini kakak Budi, ini adik Budi, dan Budi-Budi yang lain. Fokus pelajaran kelas 1 adalah latihan membaca dan menulis. Lha sekarang? Pelajaran kelas 1 SD saja sudah berat. Tebal bukunya saja sudah naudzubillah—kita ambil contoh, buku tema Diriku tebalnya 170 halaman. Anak dituntut sudah bisa membaca dan menulis agar bisa memahami materi yang ada.
Ah, kamu yang kuno. Model pembelajaran jaman sekarang kan memang harus begitu. Bukan hapalan tetapi pemahaman. Halo mas bos. Bagaimana mau memahami, kalau membedakan huruf b dan d saja kebalik, membaca angka 10 saja dengan bunyi satu puluh dan membuka buku saja masih kebalik.
Kan sudah dilatih membaca ketika masih TK?
Itu dia masalahnya. Pemerintah juga melarang guru-guru TK untuk mengajarkan anak-anak dengan materi membaca dan menulis. Alasannya karena pada usia tersebut belum waktunya untuk membaca dan menulis. Usia tersebut adalah usia bermain. Kalaupun sebagian besar TK mengajarkan siswa-siswanya untuk membaca dan menulis, itu adalah materi “sembunyi-sembunyi”. Coba cek kurikulum resmi yang mereka gunakan, materi pelajaran membaca dan menulis tidak akan kita temukan.
Jadi pelajaran membaca dan menulis pada khasanah pendidikan kita itu ibarat anak haram—ada tetapi tidak dianggap. Di level TK tidak boleh diajarkan sedangkan di level Sekolah Dasar tidak mungkin diajarkan. Entah pepatah apa yang tepat untuk menggambarkan keadaan tersebut.
Mungkin Pemerintah bisa berkilah. Anak-anak jaman sekarang kan makanannya bergizi, otaknya cepat berkembang, sehingga tanpa bisa membacapun dia bisa memahami. Buktinya mereka sudah bisa main game di smartphone tanpa perlu bisa membaca. Jangan bandingkan dengan masa kecilmu yang hanya makan tiwul dong mas.
Nyuwun sewu, Pemerintah—anak-anak kecil jaman sekarang bisa main HP itu karena ikon-ikonnnya mudah dipahami dan itu hanya khusus untuk HP Android. Saya punya buktinya meski hanya dalam skala kecil. Di rumah saya ada 3 jenis HP—HP jadul khusus untuk menelpon, HP Symbian sisa kejayaan Nokia dan HP Android. Anak saya yang masih usia TK hanya bisa menggunakan HP Android. Yang jadulvtidak pernah disentuhnya—padahal sama-sama ada gamenya. Di samping ikonnya tidak menarik, untuk memakainya perlu kemampuan membaca.
Mari kita bayangkan situasi kelas 1 pada awal tahun pelajaran dari sisi murid. Dengan asumsi di kelas tersebut berjumlah 20 orang siswa. 11 orang siswa bisa membaca dan sisanya belum bisa membaca sama sekali. Murid yang sudah bisa membaca akan mengikuti pelajaran dengan baik. Saat bapak ibu guru menyuruh, “Ayo buka bukunya anak-anak—halaman 5 ya”. Si murid langsung membuka dengan cepat—wusssh. “Coba lihat judul dan gambarnya, lalu baca tulisan di bawahnya”. Si anak dengan mudah akan membaca “Ikan” karena memang gambarnya ikan dan tulisannya ikan. Tetapi ingat, si anak ini bisa membaca karena guru TK nya melanggar aturan Pemerintah. Jadi ibaratnya ilmunya tidak sah.
Siswa yang belum bisa membaca ketika disuruh membuka halaman 5 akan ikut membuka akan tetapi bukan karena tahu angka 5 akan tetapi karena mencari halaman yang sama dengan temannya, yang sama-sama ada gambar ikan. Saat disuruh membaca, dia juga akan ikut membaca akan tetapi dengan narasi yang berbeda. Dia akan berkata “iwak” atau bahkan “lele” dengan penuh percaya diri. Saat dia ditertawakan sebagian teman-temannya dan disalahkan oleh ibu gurunya—saat itulah bibit minder dan tidak percaya diri akan muncul.
Mari situasinya kita balik. Kita lihat dari sudut pandang guru. Dengan asumsi bahwa 11 muridnya sudah bisa membaca dan 9 murid belum bisa membaca. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh ibu guru kita ini. Satu, dengan telaten mengajari anak-anak yang belum bisa membaca. Dua, mengajarkan materi sesuai kurikulum pada anak yang sudah bisa membaca. Tiga, melakukan dua-duanya. Secara ideal kita akan berteriak, ya harus melakukan dua-duanya.
Padahal hidup adalah pilihan. Kadang kita ingin memilih dua hal yang semuanya baik, akan tetapi kondisi memaksa kita untuk memilih salah satunya. Jika ibu guru tadi mengajarkan anak-anak yang belum bisa membaca dengan pelajaran membaca. Maka harus ada banyak hal yang disediakan, mulai dari waktu, buku khusus membaca dan lain sebagainya. Nah katakanlah semua itu dilakukan, pada saat yang bersamaan anak-anak itu sudah ketinggalan materi dengan teman-temannya. Sebab latihan membaca tidak cukup hanya 1 atau 2 kali pertemuan langsung bisa. Perlu proses yang panjang untuk melatihnya.
Pemerintah, tolong kasih solusi dong~