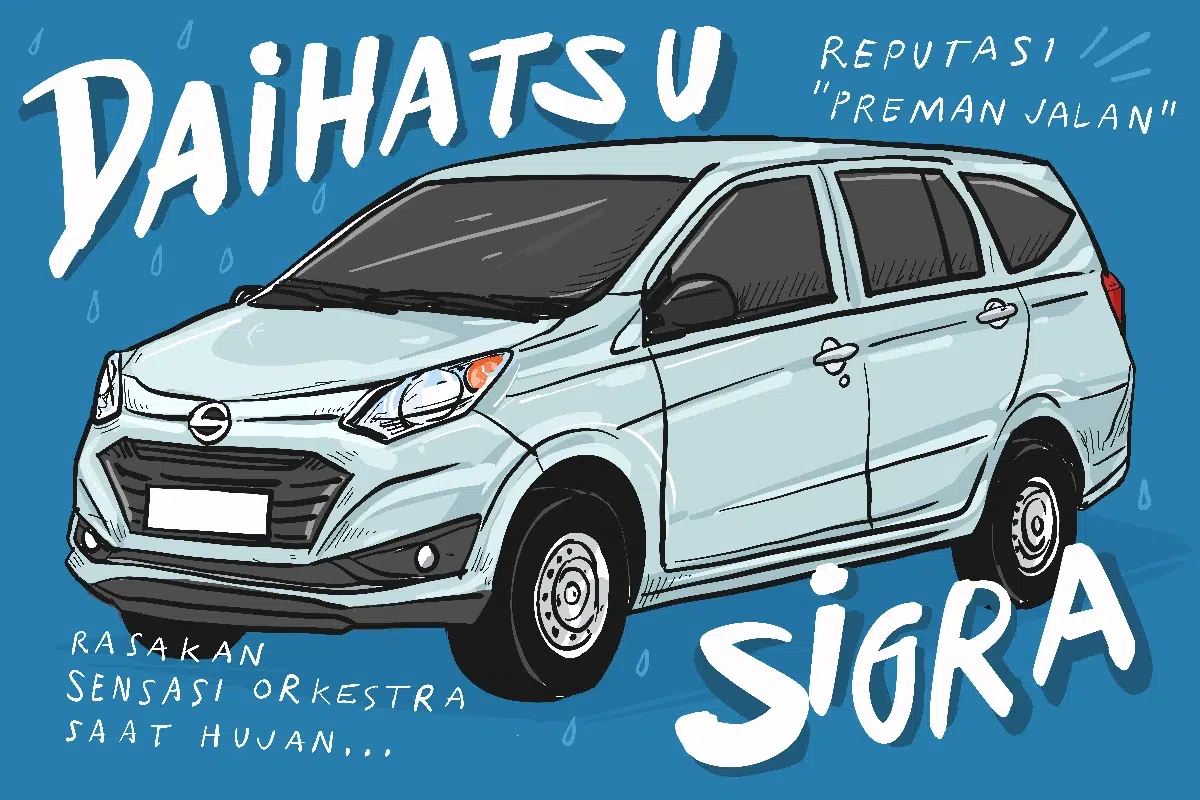“Filsafat itu seperti gula. Jika dipendam tanpa dijadikan energi kerja, hanya berakhir jadi diabetes.” Kira-kira seperti itulah pendapat saya ketika membaca artikel Saudara Nikma Al Kafi. Sepertinya, berbalas artikel adalah cara terbaik untuk merebus ide dan argumen.
Artikel ini adalah balasan dari artikel blio perihal filsuf kedai kopi. Sebenarnya saya sudah mengupas opini perihal ini dalam artikel yang dibalas Nikma Al Kafi. Tapi, saya merasa ada pesan yang tak sampai dalam artikel balasan blio. Jadi demi kepentingan mencapai sintesis, saya balas balik melalui artikel ini. No hard feeling ya, Mylov.
Bicara filsafat memang menyenangkan. Alasannya akan saya sampaikan nanti. Tapi, memang filsafat seperti gula. Mengkonsumsi ilmu filsafat berlebih dan dipendam sebagai ide bisa menyebabkan penyakit. Bukan diabetes apalagi diare, tapi saya sebut sebagai jebakan filsafat.
Sebenarnya, saya temukan istilah ini di Reddit. Tapi, saya memandang istilah ini sangat relevan untuk menjelaskan fenomena filsuf kedai kopi.
Jebakan filsafat saya pakai untuk menyebut efek samping dari mengkaji filsafat berlebih tanpa mengkaji berdasar realitas hari ini. Sebenarnya, inilah inti dari sindiran saya kepada filsuf kedai kopi. Tapi, blio Nikma Al Kafi melewatkan poin ini dalam antitesisnya. Ya nggak apa-apa sih, suka-suka blio.
Mari kita mereka sebuah adegan. Bayangkan para filsuf kedai kopi berkumpul. Di antara mereka, terselip diskusi dan adu argumen perihal teori filsafat. Diskusi ini terdengar seru, sampai akhirnya mereka harus pulang. Di luar diskusi, mereka menemukan realita yang berlawanan dengan diskusi kemarin. Negasi pada realita ini membuahkan diskusi di malam berikutnya. Dan berulang lagi.
Inilah yang saya sebut sebagai jebakan filsafat. Pernah melakukan? Atau sekadar menyaksikan?
Jebakan filsafat terjadi ketika teori filsafat klasik bertentangan dengan realitas hari ini. Padahal, teori tadi dipandang sebagai kondisi ideal. Negasi yang terjadi menggiring si filsuf kedai kopi untuk memaksakan teori idealnya terhadap realitas. Paksaan yang sebatas ide ini tentu berakhir dalam pikiran. Pikiran ideal tadi kembali terbentur realitas. Dan seterusnya seperti itu.
Kok bisa? Bukankah ide itu abadi? Dan filsafat adalah pancaran ide? Memang demikian. Tapi, memandang filsafat klasik semegah itulah sumber dari “sindrom” jebakan filsafat.
Pertama, saya menolak keabadian semua hal. Termasuk ide. Ide tercetus sebagai jawaban dari problematika. Maka, ide akan relevan pada problem tertentu saja. Ketika dunia ini berevolusi, maka ide juga akan muncul menjawab problem selama evolusi itu.
Sebagai pancaran ide, filsafat juga demikian. Sudah saya tekankan kemarin, teori filsafat memang landasan keilmuan. Ibarat rumah, filsafat adalah pondasi yang menentukan bagaimana sebuah bangunan berdiri. Tapi, apakah kita akan sibuk memperdebatkan pondasi ketika hujan badai menerpa?
Filsafat mengawali terbentuknya berbagai disiplin ilmu. Dari politik, sosial, budaya, sampai psikologi diawali dari filsafat. Bahkan reproduksi ayam dikaji melalui pendekatan filsafat oleh Aristoteles. Tapi, filsafat bukanlah ilmu itu sendiri. Kajian ilmiah yang mengkristalisasi perdebatan dalam ranah pikiran menjadi metode praktis dalam realitas.
Di sinilah jebakan filsafat hadir. Ketika perdebatan di ranah konsep pemikiran masih menguasai, realitas yang terus berjalan akan terasing. Seperti rumah tadi, golongan yang saya sebut sebagai filsuf kedai kopi berdebat perkara pondasi. Sedangkan mereka sendiri tengah terpapar terik matahari dan hujan badai.
Jebakan filsafat akan menjebak seseorang dalam dialektika yang sebenarnya sudah selesai. Menjebak sekelompok orang dalam tesis dan antitesis, ketika sintesis telah tercapai dan dipraktikkan. Seperti kiasan genjutsu Izanami saya. Para filsuf kedai kopi terjebak dalam philosophy loop yang seharusnya selesai berabad-abad silam.
Tapi, saya memaklumi fenomena ini. Perdebatan filsafat klasik adalah zona nyaman. Membicarakan sesuatu yang sifatnya ideal akan memberi rasa aman pada individu. Tapi, dunia di sekitarnya bergerak diluar kehendak yang ideal ini. Hari ini dunia tengah melawan resesi global ketika para filsuf kedai kopi sibuk memetakan landasan sosial budaya masyarakat.
Perkara meniru tokoh sebelumnya juga bisa saya maklumi. Manusia menurut psikologis humanis adalah kertas kosong, dan meniru adalah coretan yang membentuk karakter manusia.
Tapi, meniru mentah-mentah pemikiran lampau hanya menjadi gerbang masuk jebakan filsafat ini. Sebab, sekali lagi, pemikiran para tokoh tersebut dilandasi kondisi lingkungan pada saat itu. Apakah Anda perlu meniru persis pemikiran dan metode Aristoteles? Anda akan berakhir seperti anak SMP saat belajar biologi.
Inilah yang menyebabkan terjebak dalam urusan ndakik-ndaki bisa berbahaya. Penyampaian filsafat memang membuat terbuai. Siapa sih yang tidak terpukau pada semboyan “cogito ergo sum”? Tapi, urusan bagaimana seseorang berpikir dan membentuk sudut pandang telah terjawab oleh ilmu psikologi. Ilmu kognitif telah diuji dan melampaui konsep filsafat Descartes.
Itulah yang mendasari ungkapan “dinosaurus”. Ketika manusia telah mencapai pembebasan iptek, beberapa manusia lain masih berputar dalam dasar-dasar ilmu pengetahuan. Bukankah perdebatan perkara pondasi ini harusnya sudah punah?
Maka, saya akan menegasi tudingan sebagai orang kolot. Menurut saya, orang kolot adalah mereka yang terjebak dalam pusaran pemikiran lampau, serta memaksakan pada realitas hari ini. Apalagi memuliakan pemikiran yang sebenarnya sudah dikaji secara ilmiah.
Orang-orang kolot itulah dinosaurus peradaban. Mereka adalah gerombolan yang menolak berevolusi, dan bertahan sebagai reptil raksasa yang tidak relevan dengan iklim sosial budaya hari ini.
BACA JUGA Upah Layak, Tanah Murah, atau Lapangan Pekerjaan: Mana yang Lebih Worth It bagi Pekerja Jogja? dan artikel Prabu Yudianto lainnya.