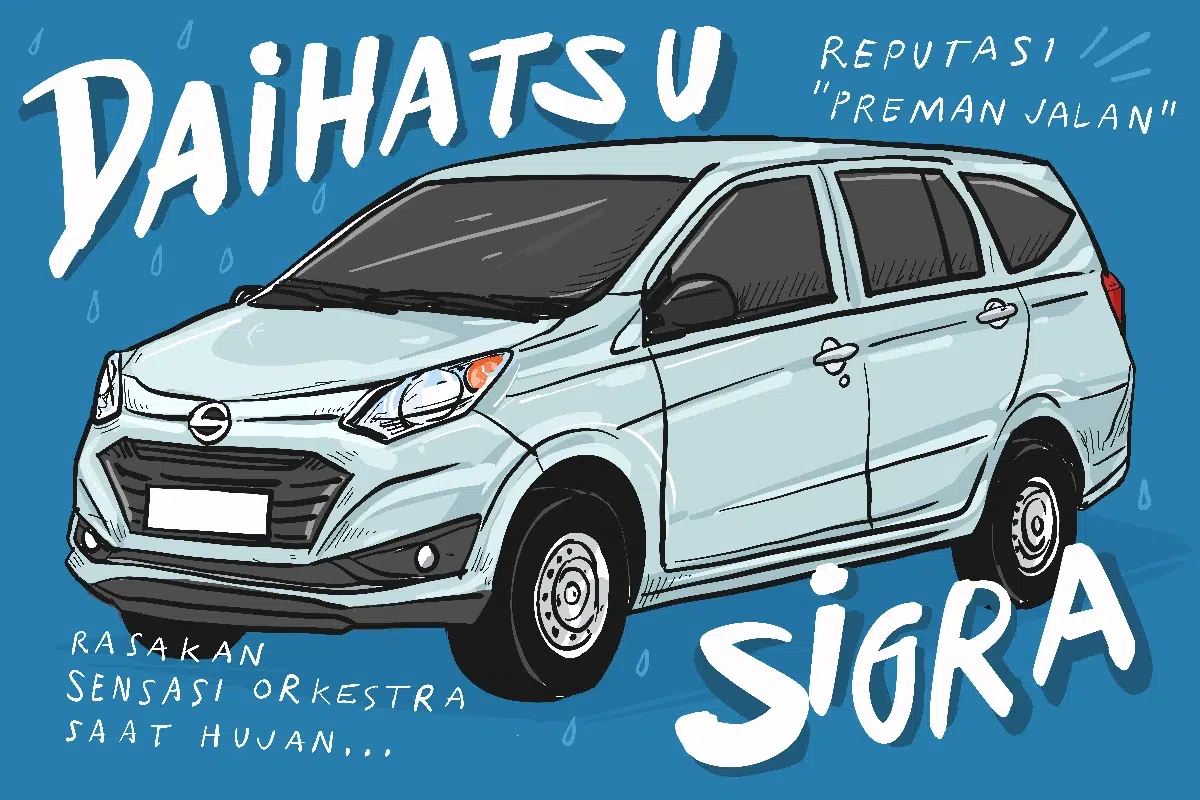Beberapa hari yang lalu, Ariel Heryanto menulis status di Facebooknya, “Di dua universitas Australia aku diangkat jadi professor. Di negeri itu ga ada yang nyapa ‘prof’ di luar (up)acara resmi. Di kampus para mahasiswa, panggil aku “Hai, Ariel”. Tapi temen2 Indonesia umumnya nyapa aku ‘prof’. Juga di berbagai forum tak resmi, termasuk medsos. Iih, geli. Kayak ada yang mengkili-kili ketiak”.
Rupanya selama ini, dalam kesehariannya dosen di Monash University, Melbourne, Australia itu memang risih dipanggil dengan gelar akademik yang diperolehnya. Di Negeri Kanguru itu, pemanggilan orang dengan gelar, agaknya menjadi sesuatu yang ganjil.
Lalu saya menyisir kolom komentar. Banyak yang menyetujui pandangan kolumnis tersebut. Kesepahaman mereka ini seperti menunjukkan bahwa mereka juga tinggal di luar negeri yang budayanya mirip atau mereka punya pengalaman yang sama kendati mereka warga negara Indonesia.
Coba kita comot satu contoh kalimat, “Di kampus para mahasiswa, panggil aku ‘Hai, Ariel’”. Silakan kalimat ini diimajinasikan. Dilontarkan di salah satu kampus di Indonesia oleh seorang mahasiswa kepada dosennya yang juga menyandang guru besar, ditambah dengan dua gelar profesor dari luar negeri.
Katakanlah ada seorang guru besar di kampus Anda, namanya Profesor Wahyu. Ia berpapasan dengan sekumpulan mahasiswa yang sedang asyik bercengkerama di taman kampus. Lalu para mahasiswa ini menyapa “Hai, Wahyu, apa kabar?”. Lihat, apakah rasanya masih sama dengan yang disebut Ariel Heryanto tadi? Tentu tidak. Syukur-syukur kumpulan mahasiswa itu tak ditempeleng. Guru besar gitu lho.
Saya tak hendak menggugat keadaan di Australia, toh memang begitulah budayanya. Sudah pakem. Bukan sesuatu yang mengejutkan seperti gegar budaya bagi saya. Sebab di film-film ber-setting Amerika atau Australia, tak jarang diperlihatkan bagaimana seorang bocah mengucapkan selamat pagi ke tetangganya yang sudah kakek-kakek dengan panggilan namanya saja.
Awalnya pada titik skeptisme tertentu, saya sampai mempertanyakan, kenapa budaya memanggil orang di Australia tak ada embel-embel gelar? Gelar apapun. Baik gelar itu didapat gara-gara sebuah jabatan di pemerintahan, pekerjaan, atau status di keagamaan misalnya.
Jangan-jangan pemanggilan gelar-gelar ini adalah warisan budaya kerajaan? Ingat bagaimana sebuah gelar “Sir” di Inggris? Sebuah gelar yang diberikan oleh kerajaan kepada seseorang karena sebuah jasa yang bersama gelar itu melekat tanda kehormatan. Misalkan gelar Sir yang disandang oleh fisikawan Isaac Newton atau mantan pelatih Manchester United Alex Ferguson. Lalu datanglah raja menobatkannya dengan segala bentuk seremonial, simbol, norma-norma kesopanan.
Tradisi-tradisi semacam inilah yang tidak ada di Negara Benua seperti yang digelikan oleh Ariel Heryanto itu. Kita sama-sama tahu, Australia bukanlah negara kerajaan. Mereka membentuk negara itu dengan spirit orang-orang buangan yang terhukum. Jadi, tidak ada jejak-jejak budaya feodal di sana. Meskipun, dulu nenek moyang mereka berasal dari Inggris.
Di tanah air pun pemanggilan gelar-gelar pada orang ini hampir dapat kita temukan di seluruh daerah. Bisa jadi, ini warisan feodal dari kerajaan-kerajaan yang berdiri di tiap wilayah Nusantara. Meski ada perubahan dengan yang sekarang, namun tetap saja nama orang selalu disematkan embel-embel gelar.
Kita tidak mungkin memberlakukan keadaan layaknya Australia di sini. Memanggil orang tanpa gelar penghormatan, terlebih orang itu memang sudah “punya”, seperti ada yang kurang oke. Bahkan cenderung menabrak norma umum. Memang seperti itulah adanya budaya kita. Tak perlu ada gugatan lagi.
Contoh saja pada tatanan adat misalnya. Laki-laki pada orang Minangkabau, setelah menikah akan dipanggil gelar Sutan. Sebuah gelar yang diberikan sebagai bentuk penghormatan. Atau pada orang Batak yang kasusnya mirip. Pemanggilan berubah demi untuk penghormatan.
Bagi orang batak yang sudah menikah, terlebih sudah punya anak, pemanggilan namanya sudah tidak berlaku lagi karena dianggap tidak sopan. Sekalipun yang memanggil orang tua bahkan pasangannya sendiri. Tak boleh itu. Nama panggilan akan berubah menjadi anak.
Misalkan namanya Tigor punya anak bernama Rinto. Maka Tigor hanya boleh dipanggil “Pak Rinto”. Begitupun nanti jika Rinto telah menikah dan punya anak. Katakanlah nama anaknya Luhut. Maka Tigor akan berubah panggilan lagi menjadi “Oppung Luhut”, dan Rinto berubah menjadi “Pak Luhut”. Betapa pun saat ini ada menteri bernama Luhut, tapi dipanggil Oppung Luhut, orang-orang Batak atau yang mengerti akan memakluminya. Lha iya dong, kalau mau memanggil gelar Oppung kepada Luhut Binsar Panjaitan, harus pakai nama cucunya yang paling besar.
Saya juga pernah kagok setelah tahu bahwa “Cak” adalah panggilan di Jawa Timur yang maknanya setara dengan “Mas”. Sebab sebelumnya saya memanggil seorang kawan dari Malang dengan sebutan Mas Cak Yudi. Saya menyangka “Cak” adalah bagian namanya, bukan gelar panggilan.
Dari sekian contoh daerah-daerah yang saya paparkan saja, sudah mengesankan betapa kelunya lidah orang Indonesia memanggil orang tanpa gelar. Apa yang “menggelitik ketiak” Ariel Heryanto tadi saya anggap, ya, kurang pas saja. Aantara budaya Australia dan Indonesia perihal pemanggilan gelar ini memang kutubnya sudah berlawanan. Lingkungan Australia lebih plong saja. Kurang lebih seperti Amerika. Nama, ya untuk dipanggil, bukan untuk dipugar-pugar dengan sejumlah embel-embel gelar akademik, sosial, agama. Apalagi Ariel Heryanto ini orang Indonesia, lahir dan besar di Indonesia. Hal itu yang bikin makin tidak pas.
Nah, coba bayangkan kejadiannya di Indonesia. Siapa di sini yang sanggup dengan serampangan memanggil seorang profesor cukup dengan nama? Atau ada yang masih ingat nggak, ada capres belum jadi presiden sudah dipanggil “siap presiden!”? Mana ada yang merasa ketiaknya dikili-kili kayak yang dibilang Prof. Ariel Heryanto itu.
BACA JUGA Buanglah Khayalan Romantis Pernikahan kalau Masih Serumah dengan Mertua dan tulisan Fitra Aidil Akbar Siadari lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.