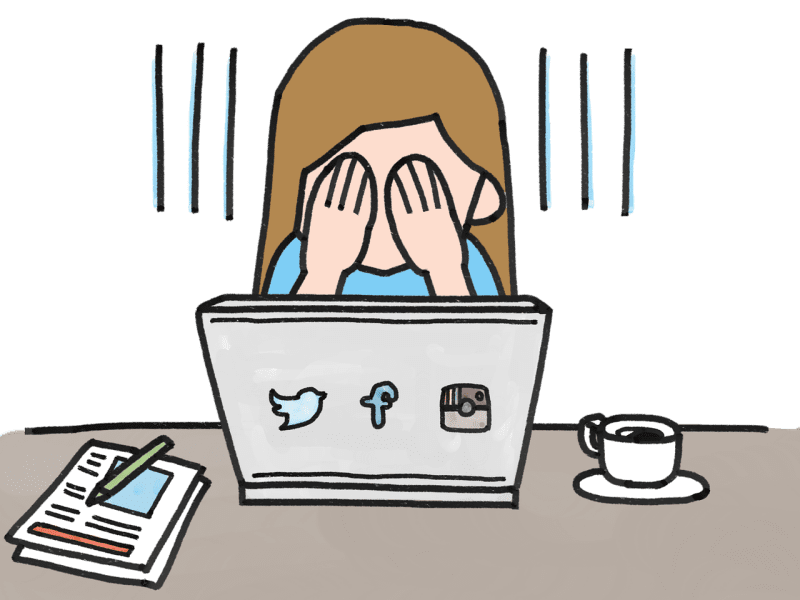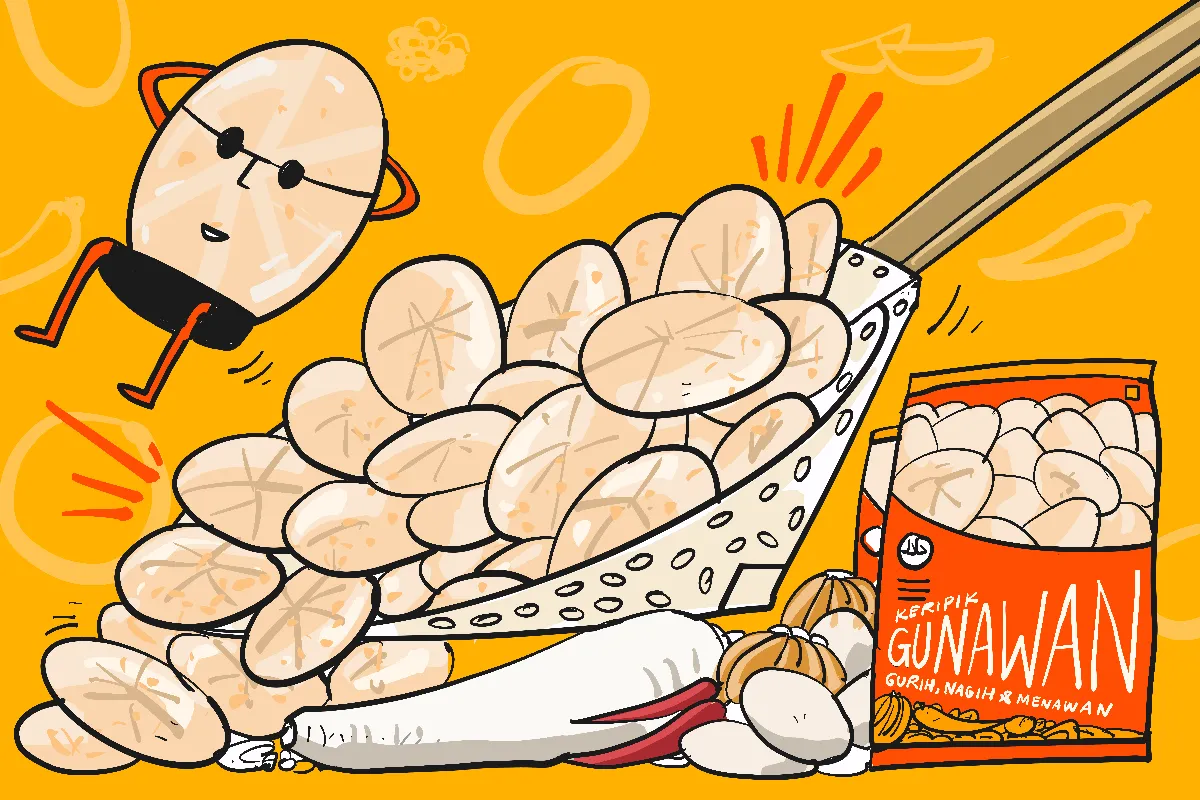Saya masih ingat momen pertemuan saya dengannya, seorang mahasiswa baru penyandang disabilitas. Ia tengah duduk di atas kursi roda. Di sebelahnya, ada teman disabilitas sensorik netra (tidak bisa melihat) yang duduk di lantai tanpa menggunakan alas. Mereka mengamati dan mendengar materi ospek tepat di pojok belakang gedung pusat kegiatan mahasiswa.
Saya menghampirinya dan menawari pindah ke tempat yang lebih nyaman. Kebetulan saat itu saya tengah menjalankan tugas sebagai panitia PK2MABA Universitas Brawijaya (ospek universitas) 2012. Tapi, mereka berdua menolak dan memilih tetap memperhatikan materi ospek dari kejauhan.
“Sudah enak di sini, Mbak,” kata mereka.
Saya merasa bersalah karena panitia tidak bisa mempersiapkan tempat dan lokasi yang accessible bagi teman-teman penyandang disabilitas. Hal pertama yang muncul di benak saya adalah rasa iba, yang dikemudian hari saya baru menyadari sikap seperti itu keliru.
Kalau mendengar istilah difabel dan disabilitas, biasanya orang akan membayangkan seseorang dengan ketidaksempurnaan fisik (cacat) dan patut menerima belas kasihan. Tragedi tentang disabilitas juga sering diberitakan secara berlebihan (supercrip) sebagai objek inspirasi. Penyandang disabilitas dianggap sebagai individu yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan.
Lalu, bagaimanakah seharusnya kita bersikap dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas?
Pertama, mulailah untuk menghindari pelabelan cacat dan stereotifikasi ketidakmampuan. Saat kita bertemu dengan teman-teman disabilitas di tempat umum, kamu bisa menghargai mereka dengan cara bertanya apakah mereka membutuhkan bantuan atau tidak. Jika mereka menolak, tidak perlu memaksa. Sementara itu, saat berbicara dengan pengguna kursi roda, posisi mata kita harus sejajar dengan mata pengguna kursi roda. Lalu, jangan pernah menggunakan jalur mobilitas mereka. Pelanggaran-pelanggaran tersebut masih banyak ditemui di fasilitas publik dan di lingkungan pendidikan.
Kepada penyandang disabilitas sensorik netra, lakukan salam sapa. Saat menuntun, tanyakan apakah dia merasa lebih nyaman untuk berjalan di sebelah kanan atau kiri kita dengan posisi tangan memegang pundak (umumnya). Juga jangan lupa memberikan instruksi yang jelas di setiap langkahnya. Misalnya, jika ada gundukan atau jalan licin dan lain-lain.
Dalam berkomunikasi, penyandang disabilitas netra biasanya mengoptimalkan indra pendengaran, perabaan, dan penciuman. Saat menjadi sukarelawan pendamping mahasiswa difabel di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya, saya pernah mendapat protes bernada candaan dari salah satu teman penyandang sensorik netra karena dia merasa pusing melihat saya. Tiba-tiba dia nyeletuk.
“Kamu pakai baju garis-garis ya?” Nah, dari sini saya banyak belajar bahwa memahami teman-teman disabilitas pun butuh proses beradaptasi dengan gangguan sensorik netra dalam level-level berbeda. Jadi, tidak sepenuhnya semua penyandang disabilitas sensorik netra tidak bisa melihat sama sekali. Sebab, jenis penyandang disabilitas bermacam-macam, jadi etika kita untuk berinteraksi dengan mereka pun disesuaikan dengan keterbatasan mereka.
Kembali lagi ke persoalan stigma dan diskriminasi yang dialami panyandang disabilitas. Dominasi cara pandang medis (medical model) di masyarakat menggambarkan bahwa disabilitas sebagai bencana bagi orang yang mengalaminya. Pendekatan tersebut hanya berfokus antara hubungan disfungsi tubuh atau mental dan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, berinteraksi, dan berpartisipasi secara sosial.
Dalam tulisan Ishak Salim, Ketua PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan), ia menggambarkan pandangan intelektual Mansour Fakih tentang hegemoni medis dan pendekatan mainstream yang kurang tepat kepada orang disabilitas. Mansour Fakih, orang yang memperkenalkan istilah difabel pertama kali di Indonesia, melalui diskusi intensif dengan para aktivis penyandang disabilitas mengkritik model penyelesaian problematisasi difabel yang dilakukan oleh para ahli dan pemerintah.
Sebab, mereka hanya berupaya melakukan pengentasan kemiskinan dengan menyalahkan orang difabel sebagai individu yang lemah. Dalam kasus lain, Vernor Munoz, salah satu pelapor untuk PBB, pernah menuliskan laporan bahwa pemerintah Indonesia kurang mempunyai kemampuan politik untuk mencapai tujuan universal pendidikan inklusif.
Gagalnya aparatus negara dalam mengatasi stigma dan diskriminasi penyandang disabilitas menandakan bahwa negara tidak bisa selamanya melakukan penyelesaian melalui pendekatan-pendekatan mainstream. Melalui jalur aktivisme, kita bisa duduk berdampingan dengan penyandang disabilitas untuk berdiskusi, meneliti, dan mengkaji tanpa memandang mana yang lebih tinggi atau rendah karena prinsipnya semua orang setara.
Sebagai kisah penutup, pernah suatu ketika saat mengikuti workshop Kelas Volunteer Difabel Jombang. Salah satu pemateri bernama Alfian yang penyandang disabilitas netra bercerita tentang pengalaman tidak mengenakkannya. Saat itu ia sedang dalam perjalanan pulang ospek menggunakan tongkatnya dan masih mengenakan almamater kampusnya. Tiba-tiba sembari menunggu jemputan, ada seseorang yang memberinya uang dua ribu rupiah. “Dikira saya pengemis kali ya,” katanya sambil terbahak.
BACA JUGA Penyandang Disabilitas dan Stigma Salah yang Menghantuinya dan tulisan Firda Alfiani lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.