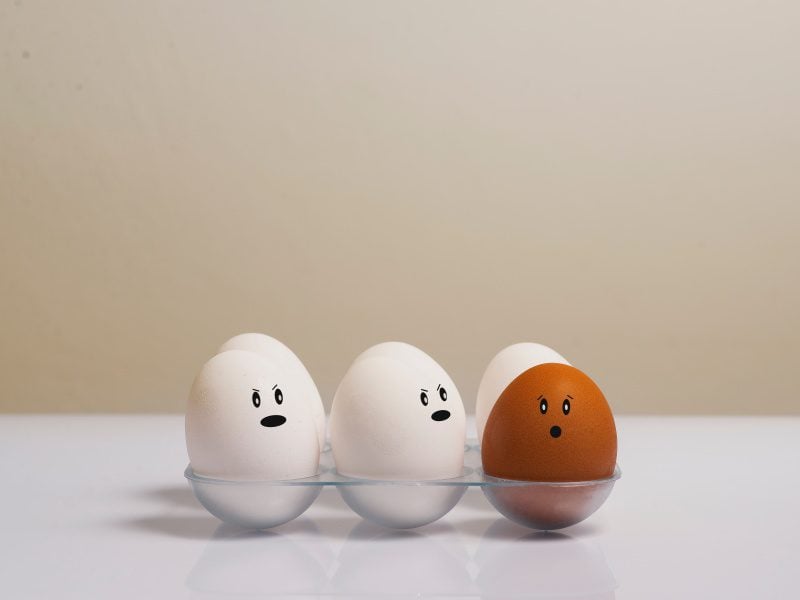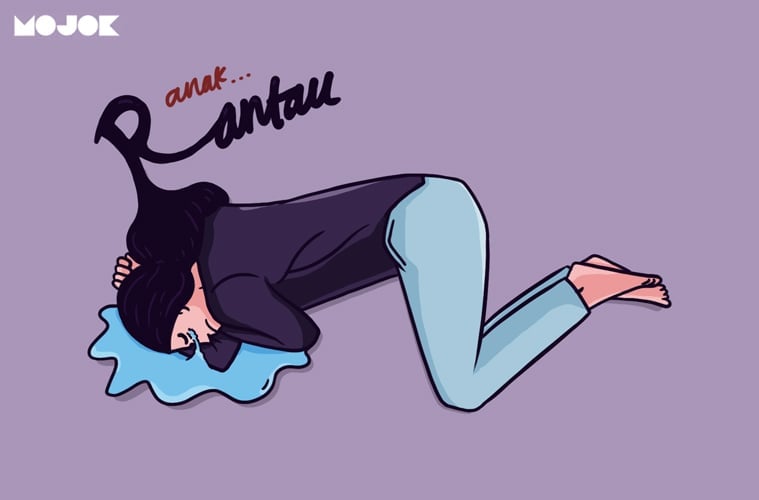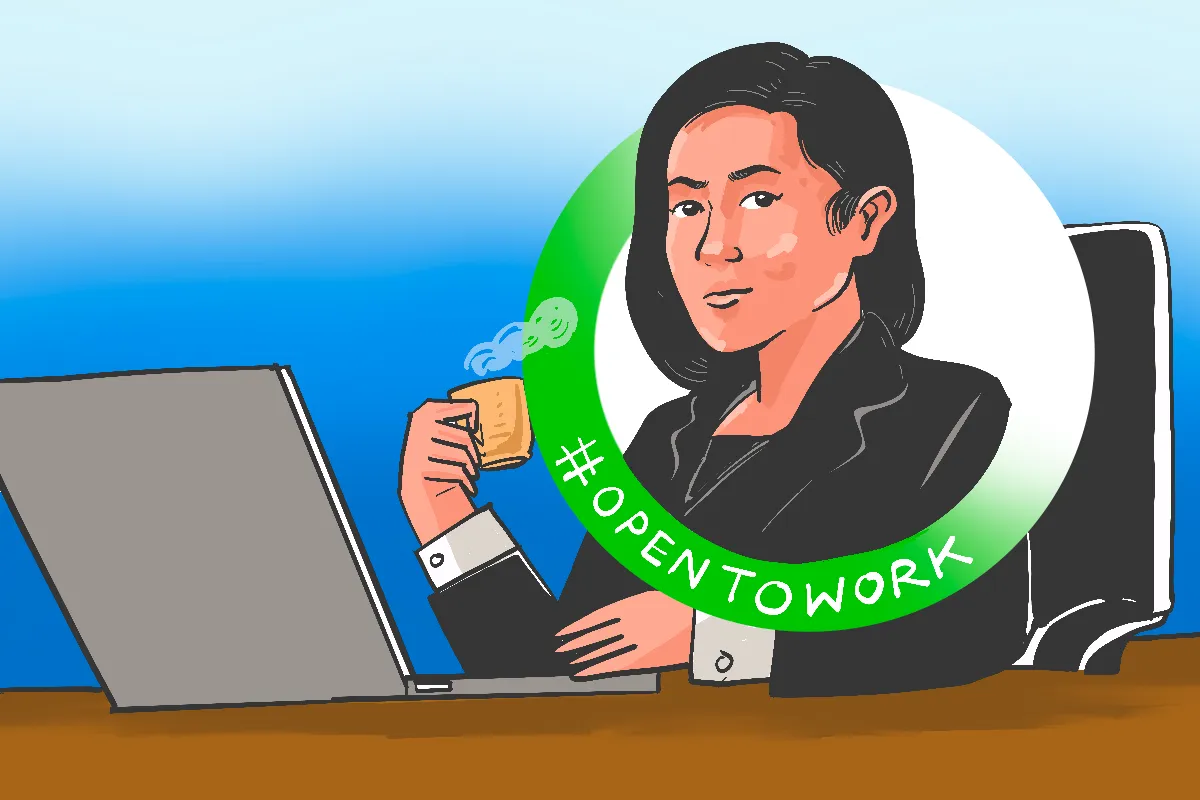Selama duduk di bangku sekolah—baik SD, SMP, maupun SMA—guru saya selalu menjelaskan dan menegaskan bahwa masyarakat Indonesia itu sangat ramah. Dijelaskan lebih lanjut, orang Indonesia itu mudah tersenyum dan memberi senyuman serta gemar menyapa satu sama lain—meski dengan orang yang belum dikenal sekalipun.
Omongan sekaligus penegasan tersebut masih saya ingat hingga saat ini. Keramah-tamahan pun memang saya alami sendiri ketika jalan-jalan ke kampung halaman Bapak di kawasan Jawa Tengah dan kampung halaman Ibu yang berlokasi di kawasan Jawa Barat. Budaya ramah ini sudah seperti bagian dari diri setiap orang di Indonesia—tidak peduli asal dan bahasa sekalipun. Jika seseorang itu ramah maka kesan yang didapat dari orang tersebut adalah baik.
Sampai ada anggapan bahwa keramah-tamahan orang Indonesia ini sebagai ciri juga jati diri bangsa. Saya pikir itu tidak berlebihan dan sejauh ini saya mengamini anggapan tersebut tanpa perlu dibandingkan dengan masyarakat yang ada di negara lain.
Sampai akhirnya, masyarakat kita seakan terbagi dalam tiga kubu, kubu A, kubu B, dan yang berada di tengah sebagai pemerhati dan selalu hati-hati dalam mencuitkan sesuatu—baik di kehidupan nyata atau di dunia maya—khususnya dalam menentukan pilihan politik. Tidak ada yang salah dengan pilihan tersebut, toh negara kita pada dasarnya memang terdiri dari beragam suku dan bahasa sudah seharusnya sudah terbiasa dalam keanekaragaman—harapannya seperti itu.
Nyatanya saat ini apa yang diucap dan diyakinkan oleh guru sewaktu sekolah mengenai masyarakat kita yang ramah seakan sulit dibuktikan kebenarannya. Ramah dari mana dan apanya—yang pada saat memberi tahu terkadang masih ada bumbu nyinyir di dalamnya dengan diselipkan kalimat “maaf sekadar mengingatkan”. Namun jika pengingat tersebut tidak diikuti justru akan dilanjutkan dengan menghakimi—tidak jarang pula dihujat.
Saat ini, masyarakat kita seperti ada sensitivitas sendiri jika beda pilihan dan sudut pandang juga sulit sekali untuk beramah-tamah—apalagi jika berbeda pandangan politik. Tidak perlu dalam cakupan masyarakat luas—dalam ruang lingkup keluarga saya mengalami sendiri bagaimana ketika berkumpul, bukan sapaan ramah yang didapat melainkan obrolan berisi caci maki dan sumpah serapah terhadap beberapa pejabat negara.
Dalam foto bersama pun, rasanya jadi canggung dan tidak biasa. Bagaimana tidak, jika saya acungkan jempol bagi sebagian orang sudah pasti auto-cebong. Lalu jika saya gunakan simbol dua jari (peace) maka secara otomatis akan dipikir kampret. Demi apapun, romansa cebong-kampret ini harus diakhiri—cepat atau lambat karena permasalahannya sudah terlalu luas dan melebar.
Apa yang ditampilkan di media sosial pun seakan menjadi representasi dari masyarakat kita saat ini. Mudah sekali menyebarkan kabar yang belum pasti kebenarannya—parahnya banyak dari teman saya tidak tabayyun terlebih dulu. Pokoknya yang mereka anggap benar dan sesuai dengan dukungan politik langsung dibagikan di timeline media sosialnya.
Sudah sewajarnya jika mahasiswa hormat dan ramah terhadap dosen atau pengajarnya terdahulu. Namun, salah satu teman saya justru memilih cara sebaliknya. Hanya karena beda pilihan politik, teman saya sampai menantang salah satu dosen dan melayangkan kata umpatan. Parahnya lagi, hal itu dia lakukan di media sosial yang bisa dilihat oleh banyak orang. Sadar atau tidak, kelakuan yang seperti itu bisa menjatuhkan harga diri dan mempermalukan diri sendiri.
Contoh kecil seperti itu dan yang dekat dengan keseharian saya membuat saya bertanya-tanya—apakah masyarakat Indonesia masih layak diberi label ramah?
Saat SMP, saya ingat persis kala itu diberi tugas oleh guru Bahasa Inggris untuk mewawancara turis mancanegara dengan Bahasa Inggris untuk dijadikan salah satu tugas. Dengan bahasa Inggris seadanya, saya beranikan diri mengajukan pertanyaan perihal apa yang disukai dari Indonesia? Sang turis menjawab—intinya—orang Indonesia ramah dan murah senyum, serta selalu menyapa turis walau belum kenal satu sama lain dengan penuh semangat dengan sapaan, “Halo, Mister!”
Mengenang hal tersebut—jika memang benar ramah dan murah senyum adalah bagian dari ciri juga jati diri kita—seharusnya tidak sulit untuk menerapkan kembali kebiasaan baik tersebut pada saat ini. Selain menenangkan, sifat ramah dan senyum juga menyenangkan. Paling penting—masyarakat di Indonesia yang saya kenal itu suka beramah-tamah, bukan suka marah-marah.