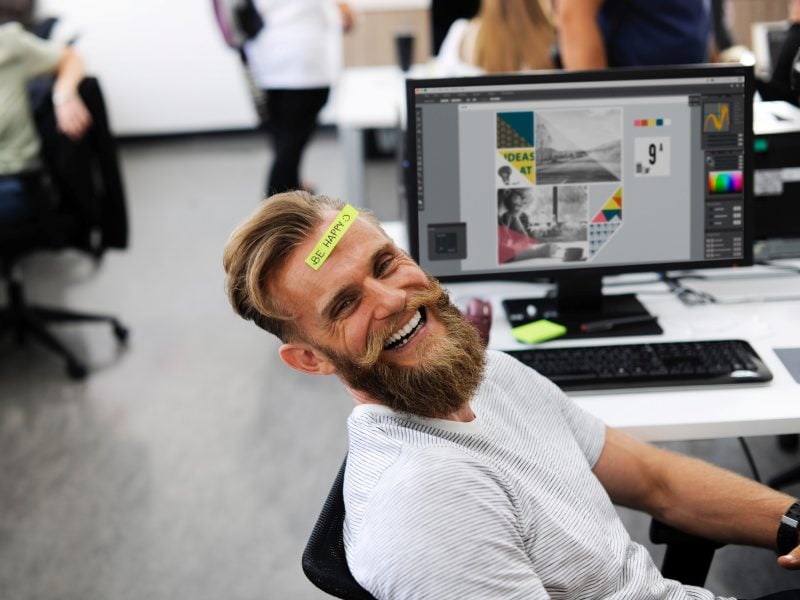Tahukah kamu bahwa di negeri ini ada sebuah balapan yang sangat tidak adil? Yaitu balapan antara harga properti dengan gaji seorang buruh yang hanya ngepas UMR.
Maksud saya, harga properti terus melaju secepat pembangunan unit-unitnya, sementara UMR bergerak selambat kendaraan para pekerja. Dengan begitu, jangankan untuk mempunyai properti atau hunian sendiri, buat memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih banyak orang kelimpungan sampai merasa mau mati.
Itulah mengapa banyak dari penduduk Indonesia, mungkin juga termasuk kalian, punya side job alias kerja sampingan buat nambah-nambah pemasukan. Atau setidaknya, kita semua ingin memiliki side job. Dan, ini hal yang wajar banget, bukan? Soalnya mau bagaimana lagi, wong kebutuhan dengan ditambah secuil saja keinginan kita, tak dapat benar ter-cover oleh pendapatan utama, kok. Alias, bukannya enggan bersyukur, tapi ya emang kurang!
Meski memiliki side job merupakan kewajaran bagi sebagian besar kita, tapi tidak halnya bagi warga Singapura yang dimaksud dalam twit ini. Ia mempertanyakan, kenapa orang Indonesia yang ia kenal kebanyakan memiliki side job? Dan, kenapa nggak bekerja keras saja supaya bisa mendapat penghasilan yang lebih?
Ada keheranan serius nan tak terjawab di kepalanya atau bahkan mungkin mereka orang luar negeri kebanyakan. Dan itu, menurut saya, adalah hal yang wajar sebenarnya. Sebab beberapa hal berikut tidak pernah tertangani dengan benar secara sistem maupun budaya kerja di Indonesia. Sementara di negara mereka mungkin sudah cukup baik.
Pertama, tentu saja dari masalah UMR di sini yang mana pertimbangan utama kenaikan per tahunnya hanya berdasar inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Di mana pergerakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nggak sampai 10% per tahunnya. Akibatnya, kenaikan dari 2020 ke tahun ini saja secara nasional hanya 3.27%.
Dengan kata lain, penambahan upah para pekerja di negara kita itu nggak seberapa. Itu pun naiknya cuma per tahun. Sementara dari kebutuhan kita sehari-hari naiknya bisa sewaktu-waktu. Maka dari itu, memiliki side job seakan sudah jadi barang wajib.
Kedua, pertimbangan kenaikan gaji dari perusahaan. Memang kadang perusahaan mengapresiasi karyawannya dengan menaikkan gaji. Namun, seberapa sering, sih? Lalu, seberapa banyak orang yang punya kesempatan untuk dinaikkan gajinya atau diangkat jabatannya? Satu banding sepuluh pun sulit untuk dibayangkan.
Sementara aspek perusahaan untuk mengapresiasi karyawannya secara umum, agak gimana gitu. Contohnya dengan mempertimbangkan prestasi karyawan. Hal ini kan nggak bisa berlaku bagi semua jenis pekerjaan.
Okelah, ada pertimbangan seberapa loyal karyawan untuk bertahan di perusahaan, tapi aspek ini kan butuh pembuktian dengan waktu yang lama. Lah wong butuhnya sekarang kok bukan nunggu setia lima tahun ke depan di tempat yang sama. Maka, sekali lagi, tak heran banyak dari kita mencari penghasilan di luar pekerjaan utama.
Ketiga, adalah soal budaya kerja di negara kita yang eksploitatif dan kurang apresiatif apalagi perhatian. Maksud saya, seberapa besar, sih, uang tambahan untuk lembur? Mungkin secara nominal besar. Tapi, jika menimbang hal lainnya macam kejenuhan di kerjaan yang sama, kesehatan fisik yang kerja non-stop macam itu, masih mau bilang uang lemburan itu mashok?
Lalu, budaya kerja yang lebih ngguateli adalah menggarap pekerjaan yang bukan job desc-nya. Contoh di tempat kerja saya, seorang HRD bisa merangkap sebagi humas dan bendahara. Atau, seorang satpam merangkap sebagai OB. Saking seringnya kita mendapati itu, mungkin sebagian dari kita pun masih mengaggapnya sebagai hal yang lumrah.
Bahkan Mas Andri Saleh melalui salah satu tulisan, sampai memberi saran untuk menyembunyikan skill yang bakal dimanfaatin oleh “bos” kita di kerjaan. Betapa parah memang budaya kerja toxic yang satu ini.
Ditambah lagi, sudah dimanfaatin macam itu, eh, bentuk apresiasi dari atasan paling cuma acungan jempol atau mentok sebungkus nasi Padang. Sebuah pertukaran yang sangat timpang.
Mungkin itu juga yang diherankan orang Singapura di atas, yang bertanya-tanya: mengapa nggak bekerja lebih keras saja di kerjaan utamanya? Dari keheranannya itu kita tahu bahwa ada perbedaan definisi antara kerja keras di sini dengan di luar negeri sana.
Kalau di sini bekerja keras berarti mengerjakan yang bukan tugasnya. Sementara di luar negeri, mengerjakan kerjaannya supaya mendapat hasil yang maksimal dan akan mendapat tambahan upah yang sesuai.
Lagipula, bukankah banyak studi sudah mematahkan bahwa nggak ada korelasinya antara kerja keras dengan peluang keluar dari kemiskinan?