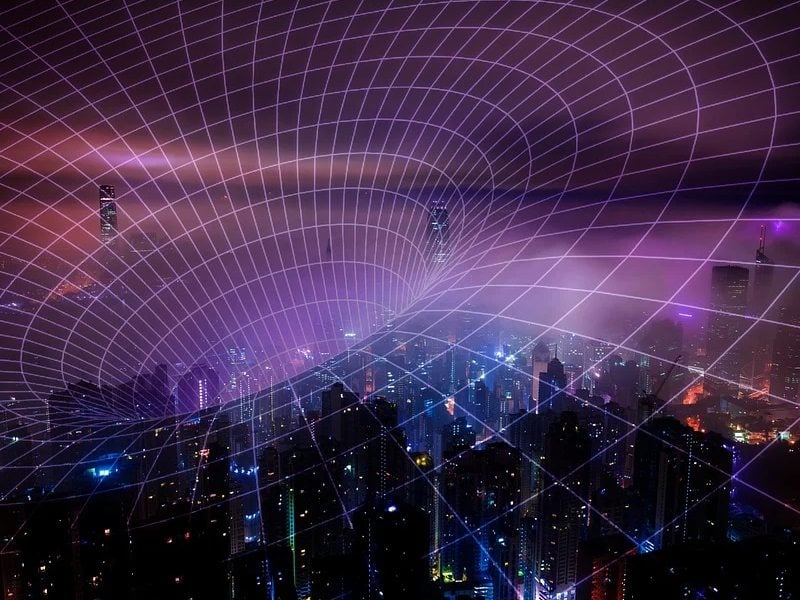Seperti judul di atas, tidak antusiasnya saya dengan peluncuran jaringan 5G bukan karena saya percaya konspirasi Covid-19, jelas saja bukan. Bukan pula karena perangkat saya belum mendukung jaringan 5G, tapi kalau ini juga bener, sih. Tapi, alasan yang paling kuat tak lain karena jaringan internet masih sungkan masuk desa saya. Padahal, saya monggo-monggo saja. Sok, silakan.
Berjarak satu jam perjalanan menggunakan Mio dari kota Solo, kota yang turut kebagian jatah peluncuran sinyal jaringan 5G, di situlah desa tempat saya dibesarkan. Tidak bisa dibilang terlalu jauh dari perkotaan, tapi lumayan jauh dari persepsi orang kota, bahwa tinggal di desa itu enak-enak saya. Belum tau saja mereka, bagaimana rasanya punya perangat dan kuota 4G, tapi yang ada malah menguras energi.
Serupa “onggo-inggi”, jaringan internet cepat dan merata di desa saya itu takhayul. Kuliah online di masa pandemi ini merupakan salah satu ujian berat yang membuat anak-anak di desa saya bingung. Setahun berjalan, anak-anak yang tadinya bingung, lama-lama terbiasa, terbiasa bingung.
Beruntungnya kampus saya tidak melakukan pembelajaran video conference semacam Zoom dan Google Meet. Ya, bisa modyar saya. Mentok hanya grup WhatsApp dan Google Classroom, pun masih mesti mengeluarkan effort. FYI, di rumah saya, spot sinyal terkuat berada di jendela kamar, jadi selama memantau kelas, saya mesti duduk di balik jendela bak pujangga menggali kata. Internetan sambil rebahan itu privilese!
Nah setelah beberapa kali melakukan uji coba, ternyata saya menemukan spot baru yang mendukung saya buat rebahan, syaratnya satu: rebahan, tapi tangan harus membentuk sudut 90 derajat. Mesti presisi, bergeser sedikit, sinyalnya hilang banyak. Bahkan pernah, yang tadinya muncul jaringan 4G, tangan miring, jaringan langsung amblas ke “G”. “G”, loh, ini, bukan bukan “3G”, bukan “E”, apalagi “Y”, “G!” Ra mashok!
Adik saya unik lagi, selama kelas online, ia sering mondar-mandir ke dapur. Saya pikir ia meluangkan waktunya untuk belajar masak dari situs Cookpad. Ternyata, adik saya cuma duduk di pintu dapur sambil menyimak kelas online. Nah, ini spot terkuat ketiga, ditemukan adik saya. Padahal kelas onlinenya cuma via WhatsApp.
Teman saya tak kalah miris, rumahnya hanya berjarak satu RT dari rumah saya, katanya pernah telat mengirimkan tugas via Google Classroom, cuma perkara sinyal. Bahkan “katanya” ia sampai naik ke genteng alias atap, pun ia sudah ancang-ancang selama setengah jam. Beruntungnya, teman saya ini nggak ditotol burung dara, dikira nasi aking dijemur.
Dan fakta dari ketiganya ialah, sama-sama menggunakan provider yang konon memiliki jaringan terluas. Bisa dibayangkan kalau pakai provider “juara Liga Champions” dan sejenisnya? Ya, bisa kering teman saya naik ke genteng terus. Tapi teman saya sudah keburu minggat balik kos, lama-lama makin stres mikir sinyal, katanya. Pun ia juga kebagian kuliah online via video conference.
Buruk dan tidak meratanya jaringan turut pula membuat ponsel saya sering panas dan demam. Mungkin culture shock, sering hidup di kota, pindah ke desa. Saya juga paham betapa lelahnya ia bekerja. Bahkan saking panasnya, ponsel saya kalau ditembak thermogun, bisa dikira kena Covid-19 loh, ini. Hadeuh.
Sejujurnya, beberapa spot di desa saya memiliki jaringan yang “lumayan” kuat. Lumayan loh, ya, tapi jauh dari kata bagus dan cepat juga. Masalahnya, rumah saya merupakan salah satu yang terburuk di antara yang buruk lainnya. Kalau kata Pak Dul, “jeleknya jelek.” Dan, kalau dipikir-pikir mbah dan bapak saya ini ternyata tidak visioner dalam membeli tanah dan membangun rumah.
Sementara beberapa spot di desa saya yang lumayan menjangkau sinyal itu berada di tengah perempatan jalan. Lumayan menjangkau semua jaringan, selain tempat ngumpul orang, ternyata tempat ngumpul sinyal juga. Atau beberapa tempat lain, di antaranya seperti rumah pak kades dan di balai desa. Pengecualian sebenarnya, karena kedua tempat ini dipasangi WiFi. Hmmm.
Setelah mengalami banyak problematika, saya malah berniat memindahkan rumah saya yang jaringannya “jeleknya jelek” itu ke tengah perempatan, apalagi tradisi “njunjung omah” di desa saya masih lestari. Atau ngelukir keluarga kades ke rumah saya? Toh secara hierarki bapak saya yang juga perangkat desa (kadus) setara dengan benteng, Pak Kades rajanya. Atau opsi ketiga, saya tidur di pendopo balai desa saja? Hasssh, yang lain antusias dengan jaringan 5G, saya malah bingung cara mindahin tempat tinggal. Benar-benar purba.
BACA JUGA Dear Rama Sugianto, Tidak Perlu Lucu untuk Jadi Komentator Sepak Bola dan tulisan Dicky Setyawan lainnya.