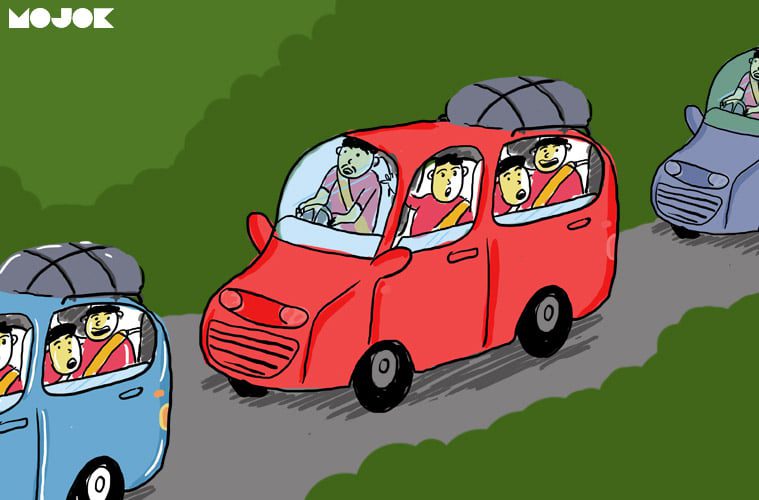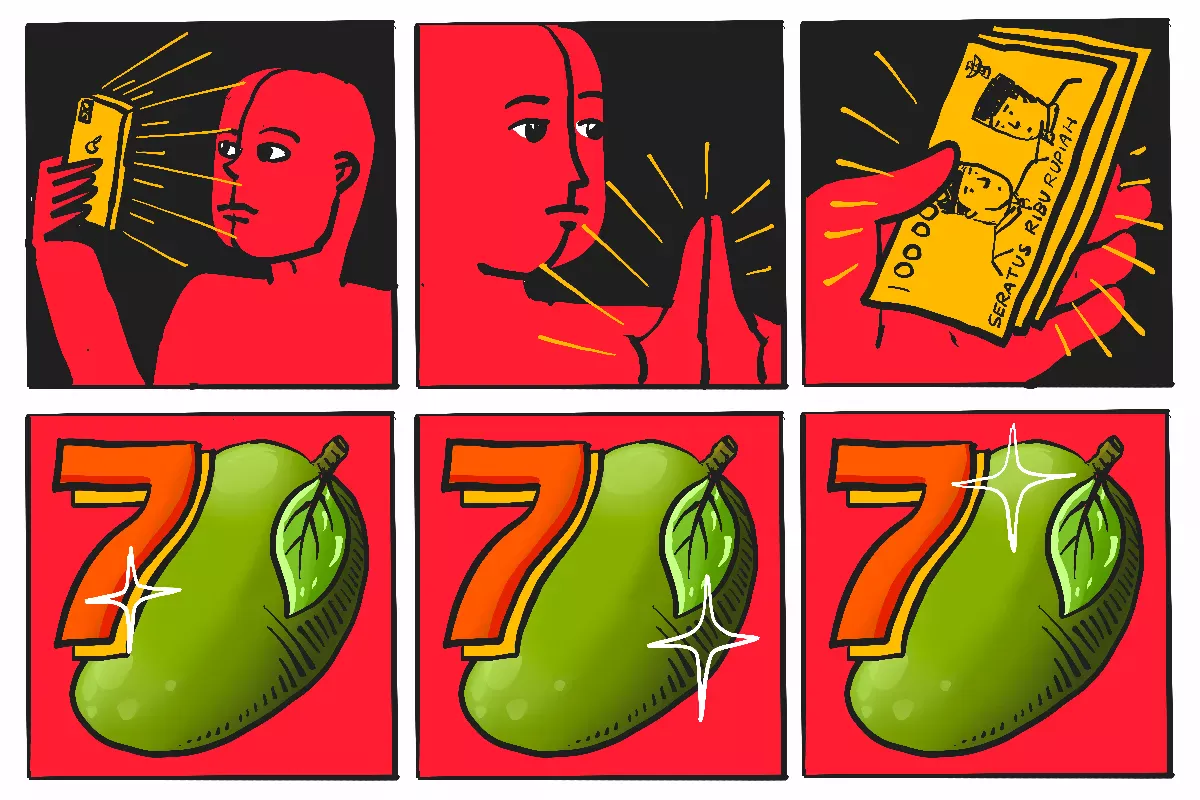Menjadi dosen merupakan cita-cita saya sejak masa ospek. Entah mengapa, melihat para dosen berdiri di depan kelas dengan penuh wibawa saat memperkenalkan diri membuat saya terkesan. Saat itu, saya masih mengenakan atribut cupu ala mahasiswa baru, tapi sejak detik itu pula saya bertekad: suatu hari nanti, saya ingin menjadi dosen.
Waktu berlalu. Studi S1 saya selesaikan singkat, lalu dilanjutkan S2 dengan gerak cepat berbekal beasiswa. Semua itu saya lakukan demi satu tujuan: segera menjadi Mbak Dosen. Saat itu usia saya baru 24 tahun—masih cukup imut untuk mengajar bocil-bocil Gen Z. Namun, pada tahun pertama resmi menyandang status dosen, saya langsung dihadapkan pada berbagai realitas yang jarang sekali dibicarakan orang tentang dunia perdosenan.
Terjebak di kampus kecil dengan gaji yang sangat imut
Jika kamu menjadi dosen di kampus kecil, terlebih lagi di luar Pulau Jawa, bersiaplah untuk hidup sepenuhnya mengabdi pada kampus. Kondisi akan terasa lebih sadis jika kampus tersebut merupakan kampus swasta kecil. Tidak jarang ijazah ditahan atas nama kepentingan akreditasi, homebase sudah permanen, dan kesempatan untuk keluar mencari peruntungan lain nyaris tertutup.
Lowongan dosen yang terbatas membuat banyak orang bertahan bukan karena nyaman, melainkan karena tidak ada pilihan lain. Jika kesempatan sudah di depan mata dan tidak diambil, entah kapan lagi kesempatan serupa datang. Apalagi bagi lulusan S2, pilihan karier di luar dosen sering kali tidak ramah dengan ijazah yang dimiliki.
Saya menemui banyak rekan yang akhirnya terjebak di kampus swasta kecil akibat kontrak-kontrak yang tidak masuk akal dan jelas mengganggu well-being. Bahkan, ada yang harus membayar penalti besar jika nekat mengundurkan diri. Jangankan menabung, yang ada malah boncos.
Obrolan dengan dosen senior pun membuka mata kami lebih lebar. Jika dikorelasikan dengan harga emas per gram, gaji dosen hari ini bahkan tidak cukup untuk membeli satu gram emas, jika dibandingkan dengan gaji dosen sepuluh tahun lalu. Inflasi berjalan, tetapi kenaikan gaji tidak pernah benar-benar menyusul. Bayangan hidup mapan sebagai dosen pun runtuh yang ternyata hanyalah utopia. Kini, standar hidup kami sederhana saja: yang penting tidak punya utang!
Dosen hanya mengajar adalah mitos
Ketahuilah, wahai calon dosen. Mengajar hanyalah sekitar satu persen dari keseluruhan tugas dosen. Sembilan puluh sembilan persen sisanya adalah pekerjaan-pekerjaan tak terduga yang datang silih berganti.
Dulu, saya juga sempat menganggap meme dosen seperti Doctor Strange yang punya banyak tangan untuk mengerjakan pekerjaan dosen hanyalah hiperbola. Nyatanya, saya mengalaminya sendiri. Akreditasi, Audit Mutu Internal, panitia dies natalis, lustrum, purnabakti, hibah universitas, hingga menjadi asisten riset profesor; semuanya datang bersamaan. Itu belum termasuk kewajiban penelitian dan pengabdian masyarakat yang entah kapan sempat dikerjakan.
Sebelum menjadi dosen, menulis artikel ilmiah populer adalah ritual mingguan saya. Kini, tulisan pergibahan duniawi ini terasa seperti artikel pertama sekaligus terakhir setelah satu tahun hiatus, akibat ‘terpaksa’ ditunjuk sebagai Sekretaris Departemen.
Banyak duit? Tidak. Tipes? Iya.
Dosen muda sering disangka mahasiswa
Memasuki tahun keempat menjadi dosen, diusir dari parkiran karyawan sudah menjadi rutinitas. Menjelaskan bahwa saya bukan mahasiswa dan bukan pula dosen yang ‘muda-muda amat’ setidaknya terjadi dua kali seminggu.
Pengalaman lain yang tak kalah absurd adalah digodain mahasiswa tingkat akhir, padahal saya sedang membawa map merah berisi presensi. Mengunggah foto selepas kelas pun tak luput dari komentar teman media sosial: “Dosennya yang mana, ya?” Sebuah lelucon yang awalnya lucu, tapi lama-lama bikin muak.
Meski begitu, semua ini masih bisa dinikmati. Anggap saja hiburan bagi kakak-kakak milenial yang pinggangnya sudah sering encok karena usia mulai merangkak ke arah senja.
Menulis artikel jurnal ternyata harus bayar
Sebagai dosen PNS golongan 3B dengan jabatan Asisten Ahli, saya cukup terkejut saat menyadari bahwa menulis artikel di jurnal tidak selalu gratis. Sisa gaji di akhir bulan sering kali tidak cukup untuk membayar APC jurnal bereputasi.
Jika beruntung, kita bisa lolos hibah penelitian dan biaya publikasi pun tertutupi. Jika tidak, bersiaplah merogoh kocek hingga 80% dari gaji pokok demi satu artikel. Opsi publikasi gratis kini umumnya hanya tersedia di jurnal non-akreditasi yang tentu saja tidak diakui untuk kredit BKD.
Terlepas dari semua realita pahit tersebut, saya tetap menikmati menjadi dosen. Ada kepuasan tersendiri dalam berbagi ilmu, menulis, membaca, dan terus belajar tanpa henti meski gaji yang diterima jauh dari sepadan dengan effort yang dikeluarkan.
Pekerjaan ini mungkin cocok bagi saya sebagai seorang istri bekerja, di mana kebutuhan rumah tangga sepenuhnya dipenuhi suami. Gaji dosen—yang mungil ini—bisa disimpan sebagai dana darurat atau self-reward. Sulit membayangkan jika dosen muda dengan jabatan rendah dan tanpa pekerjaan sampingan harus menjadikan profesi ini sebagai sumber penghasilan utama.
Kini, semakin banyak serikat dosen yang mulai mengangkat isu kesejahteraan hingga ke pusat. Semoga kebijakan ke depan menjadi lebih berpihak dan benar-benar memperhatikan nasib penyandang profesi ini.
Semangat, doseners!
Penulis: Indah Sari Rahmaini
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Berambisi Jadi Dosen biar Terpandang dan Gaji Sejahtera, Pas Keturutan Malah Hidup Nelangsa
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.