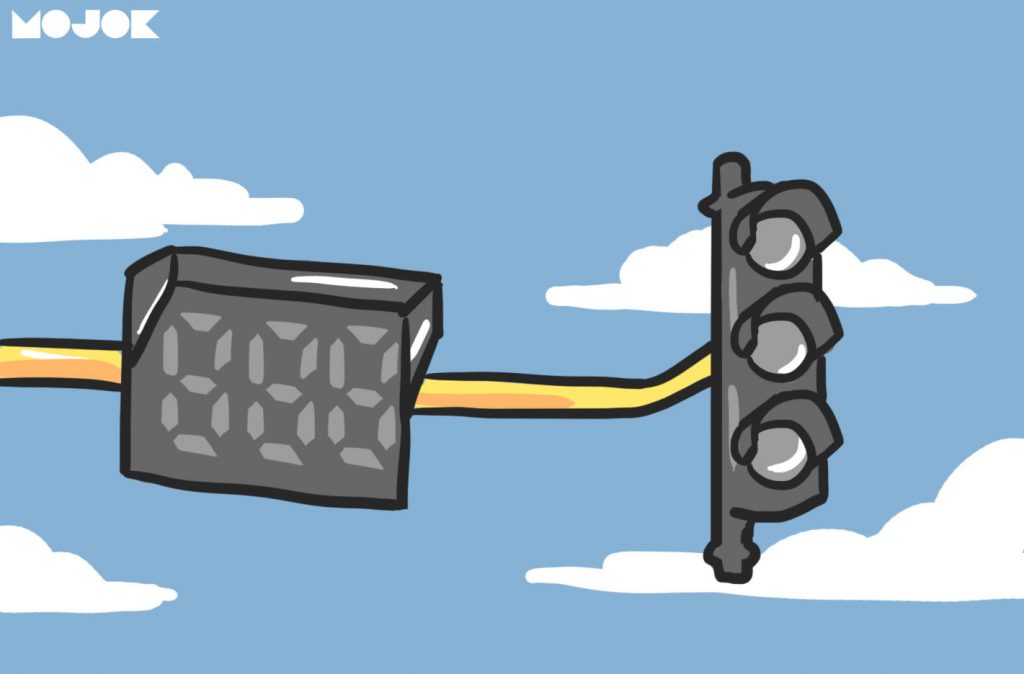Bagi banyak orang yang bekerja di Jogja, dengan pekerjaan yang nggak berat-berat amat, dan dengan gaji yang nggak rendah-rendah amat, rasanya tak ada yang lebih menyenangkan ketimbang mensyukuri kehidupan di Jogja dan menggunjingkan orang-orang yang hidup dan bekerja di Jakarta.
Puji Tuhan, saya termasuk dalam golongan ini.
Dan semalam, saya, bersama beberapa kawan yang juga berada dalam satu golongan, asyik melaksanakan ritual pergunjingan tersebut.
Kami memang sepakat, bahwa Jakarta bukan tempat yang ramah untuk hidup, setidaknya bila dibandingkan dengan Jogja.
Dafi, si redaktur Mojok yang bahkan tidak tahu apa arti kata Bucin itu, menceritakan pengalamannya saat sempat beberapa bulan bekerja di Jakarta. Ia mengatakan betapa di Jakarta, orang-orang punya logika jarak yang sangat menyedihkan.
Bayangkan, di Jogja, perjalanan dalam kota sejauh 30 kilometer bisa ditempuh dengan perjalanan santai dalam waktu satu jam. Waktu tempuh tersebut tentu saja tak bisa dicatatkan oleh orang-orang di jakarta. Lha orang-orang Jakarta itu mau bepergian 10 kilo saja bisa sampai 1 jam. Bahkan pada jam-jam tertentu, bisa berkali-kali lipat.
“Kantorku di Kemang, kosku di Senayan, paling cuma 7-8 kilo, tapi perjalananya bisa sampai satu jam,” katanya.
Dafi juga menceritakan bagaimana ia pernah menempuh waktu empat jam hanya untuk berkendara dari Jakarta selatan ke Bekasi.
“Bayangkan, Gus. Empat jam perjalanan. Itu kalau dipakai buat motoran dari Jogja, sudah sampai Semarang aku.”
Saya tentu saya mengamini apa kata dia, sebab saya pun berkali-kali mengalaminya. Terjebak dalam perjalanan berjam-jam padahal jarak yang ditempuh kerap tak lebih dari 10 kilo.
Kokok Dirgantoro, penulis Mojok yang sekarang nggak pernah menulis lagi di Mojok itu pernah suatu ketika datang ke acara Mojok di Jogja pukul 4 sore, padahal acara baru dilaksanakan pukul 6 dan jarak antara venue acara dengan penginapannya tak sampai 3 kilo. Ketika kami tanya, kenapa ia datang terlalu awal, jawabannya bikin kami geleng-geleng. “Wah, Aku lupa kalau ini di Jogja. Aku terbiasa menggunakan jam Jakarta. Kalau ada acara, aku terbiasa berangkat dua jam sebelumnya biar nggak terlambat.”
Lain jarak, lain pula kepekaan sosial.
Kawan kami yang lain, yang masih satu golongan, sebut saja Yanto, tak mau kalah. Ia menceritakan betapa orang Jakarta sangat berbeda dalam menyikapi kecelakaan.
“Kalau di Jogja, begitu ada orang jatuh dari motor, orang-orang pasti ngerubung dan menolong. Ada yang menggotong korban,ada yang menepikan motornya, atau memberikan air putih. Tapi kalau di Jakarta, beberapa kali aku saksikan sendiri, ketika ada orang jatuh dari motor di jalan raya, orang-orang sekitar hanya melihat dan nggak menolong. Butuh waktu sampai beberapa saat sampai kemudian ada satu atau dua orang yang menghampiri si korban untuk sekadar menanyakan kondisinya.”
Saya mendengarkan ceritanya seraya mangut-mangut.
“Pokoknya ya lihat sekelebat, trus berlalu begitu saja. Seakan-akan semua punya kegawatan masing-masing sampai-sampai nggak punya waktu untuk sekadar menolong,” lanjut Yanto.
Hidup di Jakarta, memang nyatanya keras. Tahun 2013 silam, saya pernah terpaksa “kesasar” di Jakarta. Saya tak punya kenalan, juga tak punya banyak uang.
Dalam kondisi yang demikian, saya pun mencari musala. Tentu saja untuk numpang tidur. Maklum, di Jogja, saya biasa tidur di warnet atau musala kalau saya kemalaman.
Tapi ternyata, susah cari musala yang boleh ditumpangi untuk tidur. Beberapa kali saya ditegur oleh penjaga musala agar saya tidak tidur di musala yang mereka jaga.
“Jakarta ini memang kejam, og,” kata Dafi.
“Iya, jauh lebih enak Jogja.”
“Bener, kalau di Jakarta, sudahlah jalanan panas, macet, ramainya ngaudubillah, ditambah klaksonnya nggak berhenti-berhenti. Ya wajar kalau banyak orang yang stres di sana. Nggak betah,” sahut Yanto.
Jogja boleh jadi memang semakin macet. Namun, dalam kemacetan itu, nuansa srawung dan tepo seliro masih cukup terasa.
Ini nyata adanya. Dalam kemacetan Jogja, kita masih sering berjumpa dengan pengendara-pengendara yang saling meminta dan menerima maaf sembari menyunggingkan senyum saat kendaraan mereka menyenggol dan tersenggol kendaraan lain. Mereka sadar, bahwa dalam macet, bersenggolan adalah hal yang lumrah. Macet memang menyempitkan jangkauan kendaraan mereka, tapi sekaligus juga melapangkan hati mereka.
“Kalau di Jakarta, senggol dikit, panas semua.”
Obrolan semalam entah kenapa menjadi klop. Mungkin karena obrolan tersebut melibatkan orang-orang yang sama-sama pernah merasa sakit hati dengan Jakarta. Dan sudah mahfum, bahwa obrolan orang-orang yang punya musuh yang sama, cenderung sangat mengasyikkan.
“Tapi kamu sadar nggak, Daf, To, bahwa orang-orang Magelang, Wonosobo, Temanggung, Klaten, dan kota-kota kecil di sekitar Jogja juga merasa seperti kita?”
“Maksudnya?”
“Ya merasa bahwa hidup mereka jauh lebih mengasyikkan ketimbang hidup orang-orang Jogja. Sama seperti kita yang merasa sangat nyaman kerja di Jogja dan membandingkannya dengan orang-orang Jakarta.”
“Bisa jadi. Dan kelihatannya sangat mungkin.”
Hidup memang sawang-sinawang.