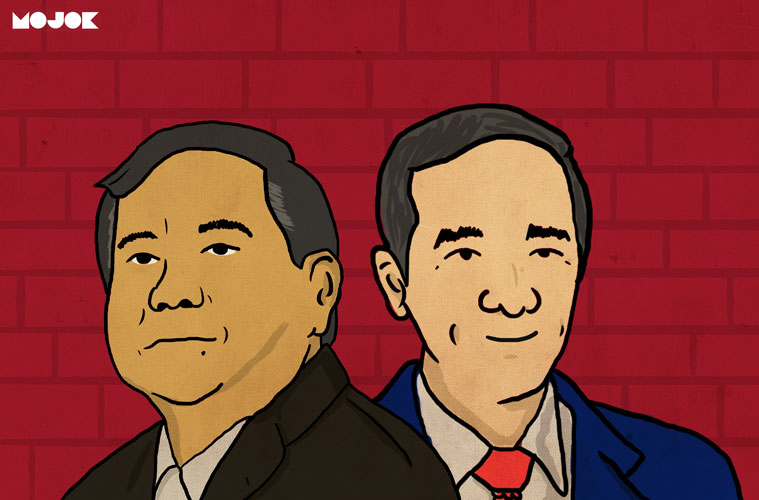Kontestasi politik dalam lima tahun terakhir ini memang terasa betul sangat memuakkan. Diawali dengan pemilihan presiden 2014, kemudian dilanjut dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, dan kemudian akan segera disusul dengan pemilihan presiden 2019.
Selama lima tahun terakhir ini, setidaknya terbentuk polarisasi kubu yang begitu berlawanan satu sama lain. Pertarungan antara dua kubu seakan memang sudah didesain untuk menjadi pertarungan urat syaraf yang abadi. Dua kubu ini yang saling bertentangan ini seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, punya banyak penyebutan nama, dari mulai bani taplak dan bani serbet, jokowers dan prabowers sampai kecebong dan kampret.
Dua kubu yang saling berlawanan ini benar-benar menguasai setiap dinding-dinding kebencian di media sosial. Setiap isu yang berhubungan dengan kontestasi selalu bisa digiring menuju keributan. Saling serang, saling sindir, saling hujat.
Pertentangan dua kubu ini tentu saja menimbulkan efek yang bukan main ngeheknya. Dari mulai keyakinan untuk tidak mau menyalatkan mayit saudara sendiri, menghilangkan rasa empati dan pembiaran terhadap tindak pembullyan, sampai yang paling parah, putus hubungan sahabat, saudara, sampai asmara.
Kalau sudah begini, rasanya kita bisa maklum jika pada suatu masa, Thomas Jefferson pernah menulis, “Jika masuk surga harus melalui partai politik, maka aku memilih untuk tidak masuk surga.”
Pada titik ini, agaknya memang kita harus mulai berkaca dan belajar pada dangdut koplo. Dalam urusan pertentangan, dangdut koplo adalah suri tauladan yang paling bijak dan bisa diandalkan.
Seorang pecinta Sera, misalnya, ia tak akan segan untuk tetap membeli kaset CD Monata. Atau seorang sahabat New Pallapa yang tak akan keberatan jika ia harus mendengarkan lagu-lagu dari Sagita.
Contoh yang lebih sederhana, dalam sebuah konser dangdut, akan ada satu kesempatan ketika si biduan bertanya kepada para penonton ingin dibawakan lagu apa. Para penonton kemudian mulai berebut, saling berteriak mengusulkan lagu favoritnya.
“Bojo galaaaak!” teriak seorang penonton.
“Kimcil kepolen!” sahut penonton lain.
“Secawan madu!” balas penonton yang lainnya lagi.
Pada akhirnya, tidak semua lagu bisa dibawakan. Namun begitu, penonton yang usul dan lagunya tidak dibawakan akan tetap legowo dan tetap menerima lagu usulan dari penonton lain.
Mau yang lebih dalam? Boleh.
Kita bisa contohkan pertentangan antara fans Via Vallen dan Nella Kharisma dalam jagad perkoploan.
Hubungan fanatisme Vyanisty (fans Via Vallen) dan Nellalovers (fans Nella Kharisma) sering kali bersifat vice versa. Banyak orang mengamini hal ini.
Namun begitu, sefanatis-fanatisnya seorang Vyanisty, kalau ia sedang berada di depan panggung dengan Nella Kharisma sebagai biduannya, ia akan tetap bergoyang menikmati musiknya. Begitu pun sebaliknya, semilitan-militannya seorang Nellalovers, kalau ia sedang berada di depan panggung dengan Via Vallen sebagai biduannya, ia juga akan tetap berjoget menikmati musiknya.
Mengapa dalam dangdut koplo hal-hal di atas bisa terjadi? Mengapa pertentangan dan persaingan selalu bisa berada dalam koridor yang lentur dan tetap damai? Jawabannya hanya satu: Sebab masing-masing kubu sadar, walaupun pilihan hati berbeda, namun di depan dangdut koplo, semua lebur menjadi satu.
Yah, andai saja fanatisme ala dangdut koplo bisa diaplikasikan pada fanatisme Jokower dan Prabower, pastilah indah rasanya.
Sayang, hal tersebut mustahil terjadi, sebab Jokowi memang bukan Via Vallen, Prabowo bukan Nella Kharisma, dan yang jelas, politik bukan dangdut koplo.