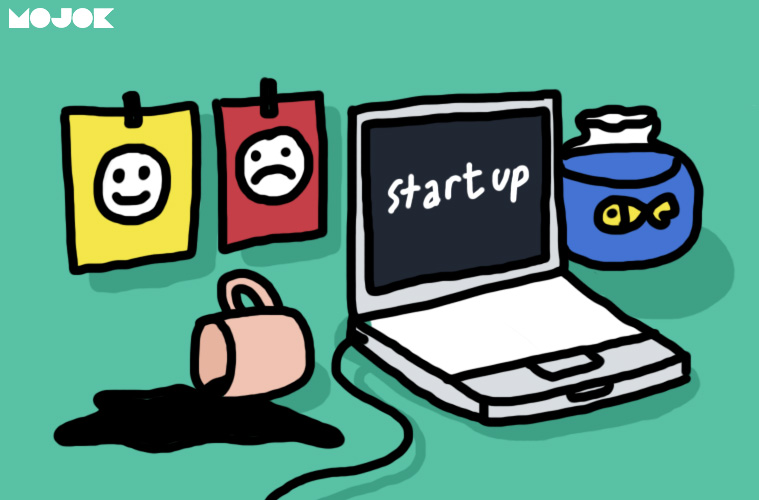MOJOK – Tidak banyak orang yang tahu bahwa perempuan pekerja di startup begitu rentan baik dari segi mental maupun fisik. Terutama saat memutuskan menjadi seorang working-mom.
Alkisah, sebut saja Andin, dia sudah 7,5 tahun kerja di startup yang berpusat di Jakarta dan telah tiga kali berpindah perusahaan. Perempuan berusia 31 tahun itu tengah duduk di ambang pintu sambil klepas-klepus ketika Mojok menyimak ceritanya.
Tahun lalu, Andin memutuskan resign dari kantornya, startup decacorn, dengan berbagai pertimbangan ala orang dewasa. Lantas, ia memilih startup kecil yang masih berada di level series-A. Banyak rekan kerjanya mencibir, sebagian bilang dia kurang bersyukur. Atasannya apalagi, langsung menawarkan promosi biar dia tidak ke mana-mana.
Lantas, apa penyebab Andin memilih mundur dari perusahaan bonafide impian generasi milenial?
Andin seorang working-mom, mempunyai satu anak di bawah usia tiga tahun. Ia terpaksa LDR dengan suami karena baginya Jakarta bukan kota yang ramah anak. Lagipula, ia butuh dukungan pengasuhan dari ibunya alias nenek anaknya. Beruntung, pandemi sempat membuatnya bisa bekerja di mana saja. Dan ia memilih pulang kampung ke Yogyakarta.
Menurut Andin, sebenarnya kerja di startup cukup menyenangkan dan menantang. Ia yang awalnya mempunyai ketertarikan menulis, mengembangkan keterampilannya ini dengan menjadi copy writer.
“Ada beda antara kerja nulis di media sama startup, karena ini tech-industry jadi aku ngulik hal-hal baru yang punya irisan dengan isu itu. Rasanya, bagi penulis, potensial banget kerja di startup,” ujarnya kepada Mojok, Sabtu, 4 Februari 2023.
Di kantor barunya kini, Andin bergeser menjadi UX writer, dan ini adalah pengalaman pertamanya belajar menulis yang sama sekali berbeda sensasinya.
Terkait suka-duka bekerja di perusahaan rintisan, Andin dengan lugas bilang bahwa selain gaji yang tinggi, iklim kerja di start-up cukup egaliter. Tidak ada ketimpangan dalam sistem pengupahan jika ditilik dari poin gender. Baik pekerja laki-laki maupun perempuan dipandang sama.
Selain itu, bekerja di startup menurutnya juga bikin bagus portofolio. Dalam artian, pekerja yang punya pengalaman bekerja di startup akan lebih diperhitungkan bekerja di startup lain, ketimbang yang belum pernah.
“Kerja di startup bikin CV di LinkedIn jadi keren,” ujarnya berkelakar.
Banyak perusahaan rintisan mencari calon pekerja di LinkedIn, itu mengapa aplikasi ini sangat populer di ekosistem pekerja startup. Namun, ternyata gara-gara tradisi ini pula, susah sekali bagi Andin untuk undur diri sewaktu-waktu dari kantor lamanya.
“Pernah aku udah putus asa banget pengen resign, tapi nggak dibolehin. Strategi atasanku di momen evaluasi malah ngasih bonus dan bilang kalau performa kerjaku bagus. Ujung-ujungnya, aku harus nahan diri buat cabut saat itu. Karena kalau aku tetap bersikeras, kantorku bakal ngasih catatan buruk di LinkedIn-ku dan itu bikin perusahaan lain mikir-mikir mau ngerekrutku,” curhat Andin berapi-api.
Fleksibel sekaligus bikin pusing
Kendati pada awalnya startup dilihat sebagai tempat kerja yang ideal, seiring berjalannya waktu pandangan Andin berubah. Awalnya, ia mengira bekerja dengan orang-orang muda atau setidaknya sebaya dengannya akan membuat pekerjaan terasa lebih mudah.
Kantornya yang dulu tetap memiliki jam kerja, namun banyak rekannya yang punya rutinitas fleksibel. Misalnya, setelah dugem tiba-tiba dapat ide kreatif, lembur sampai pagi, tepar saat siang. Akhirnya ini menimbulkan masalah.
“Ibaratnya palugada, apa yang lu butuhin gue ada. Misalnya jam sembilan malam ada meeting, ya harus ikut. Atau tengah malam masih chat tek-tokan soal kerjaan. Jam berapapun ada panggilan kerja, sekadar brainstorming atau mengedit naskah, harus mau ngerjain,” sambungnya.
Akibatnya, Andin mengaku ini berpengaruh pada kondisi psikisnya. Ia pun beberapa kali mengalami burnout.
“Kadang aku nggak habis pikir, sih sama perempuan-perempuan berkeluarga yang sanggup kerja di bawah iklim kerja hustle hanya karena ngoyak status ataupun cuan. Bahkan ada tuh, mbak-mbak startup yang levelnya udah senior, dia tetap buka laptop di atas kasur rumah sakit menjelang operasi caesar.”
Gaya hidup hustle culture seperti ini semakin parah saat mayoritas anggota timnya adalah pekerja lajang atau sudah menikah tapi belum punya anak. Sehingga, ritme kerja mereka cenderung bikin working-mom seperti Andin kelimpungan menyesuaikan jadwal antara quality time dengan anak dan mengerjakan PR dari kantor.
Kesehatan mental jadi isu utama
Andin menuturkan, kesehatan mental menjadi isu utama yang kerap menghantui para pekerja startup, seperti dirinya. Ada beberapa penyebab mengapa pekerja startup lebih mudah stres dalam bekerja.
Menurut Andin, alasan pertama karena ketidakpastian nasib perusahaan rintisan, atau istilahnya “masa depan abu-abu”. Menurutnya, hari ini banyak sekali startup yang tidak bisa mengembalikan dana investasi yang sudah ditanam para investor. Akhirnya, banyak yang gulung tikar. Bahkan, untuk selevel decacorn—seperti tempat kerja Andin terdahulu—ada potensi PHK besar-besaran karena collapse.
Sebagaimana diketahui, sepanjang 2022 lalu, banyak perusahaan startup yang mengklaim pailit dan terpaksa melakukan PHK besar-besaran atas pekerjanya. Istilahnya, startup kini tengah memasuki tech winter, atau penurunan minat dan investasi dalam bidang teknologi.
“Isu itu akhirnya yang bikin pegawai seperti aku merasa anxiety, cemas karena kapan saja kita bisa kena lay-off [PHK],” ujar Andin.
Lebih lanjut, di dalam startup juga belum ada serikat pekerja, yang bisa menjadi wadah bagi para pekerjanya untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada perusahaan. Akibatnya, karena “tidak ada pendamping”, ancaman PHK semakin nyata.
Ini bisa saja diperburuk dengan beberapa pekerja yang “dipaksa resign secara baik-baik”, sehingga tak dapat pesangon.
“Makanya, pegawai startup rentan kena mental illness, cemas terus. Gaji gede tapi nasib untuk hari besok tidak menentu,” lanjutnya.
Selain itu, beban kerja yang kurang masuk akal juga memengaruhi tingkat stres para pekerja, sehingga kerapkali mengalami burnout. Sebagaimana ia singgung sebelumnya, jam kerja fleksibel dalam start-up memungkinkan pekerja tetap melakukan tugas di jam-jam istirahat.
“Beban kerja tinggi. Jam kerja tidak menentu, nggak ada namanya worklife balance. Jadinya pada burnout,” tukasnya.
Berharap lebih diperhatikan
Seperti dilaporkan Data Indonesia akhir tahun lalu, 91 persen karyawan di startup terbuka atau mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tempat mereka bekerja. Hal ini didasarkan pada laporan survei Growth & Scale Talent Playbook yang dirilis oleh Alpha JWC Ventures, Kearney, dan GRIT.
Berdasarkan hasil survei tersebut, diketahui bahwa ketidaksesuaian visi-misi dan budaya perusahaan menjadi alasan terbesar bagi pekerja startup yang baru saja bergabung dengan perusahaan. Sementara itu, bagi pekerja yang sudah lebih dulu masuk, alasan kompensasi menjadi alasan terbesar untuk mengundurkan diri.
Hal tersebut juga dialami Andin. Ia memutuskan keluar dari startup decacorn setelah merasa tidak cocok lagi dengan iklim kerja di perusahaan rintisan tersebut. Bagi Andin yang baru saja punya peran baru sebagai ibu, lingkungan di sana tidak lagi kondusif dengan situasinya.
Ia mengaku, bahwa sebagian besar startup memang tidak terlalu ramah bagi perempuan yang punya peran ganda—pekerja sekaligus ibu—seperti dirinya.
“Ini pandangan pribadiku, sih. Misalnya, di startup kan dituntut cepat, jam kerja juga tidak menentu. Sementara bagi perempuan seperti aku yang sudah harus membagi peran, jelas tidak mungkin terakomodasi dalam sistem kerja startup,” jelas Andin.
Atas kondisi yang demikian, ia pun berharap bahwa kelak pekerja startup berkonsolidasi untuk membentuk serikat buruh demi perlindungan kerja yang lebih baik dan sistem kerja yang lebih sehat.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Amanatia Junda
BACA JUGA Balada Kuda Startup: Kerja, Kerja, Tifus