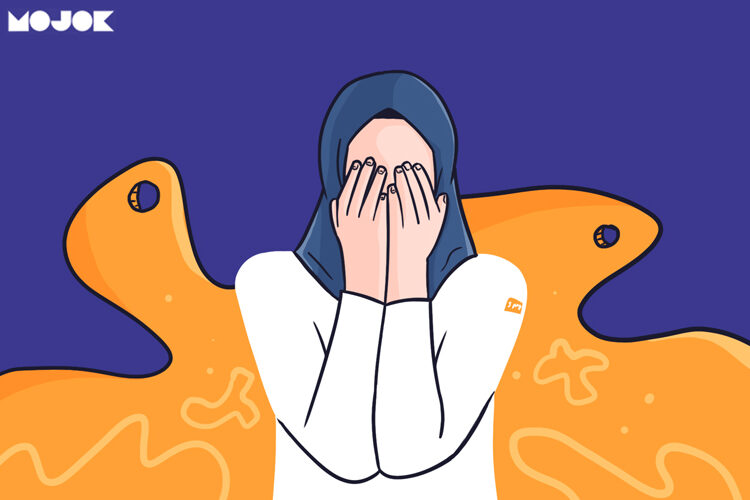MOJOK.CO – Di sejumlah daerah dengan mayoritas muslim seperti Aceh, Madura, Makassar, Gorontalo, dan Ternate, tradisi khitan perempuan masih dipraktikkan. Ifah, perempuan asal Gorontalo, menceritakan betapa tradisi ini menyakitkan bagi perempuan.
Khitan perempuan –dalam istilah Gorontalo disebut mongubingo– adalah ingatan yang paling asing bagi saya. Di usia kurang dari 3 tahun, bayi perempuan mana yang bisa merekam peristiwa atas pengalaman dirinya, apalagi tentang tubuhnya. Mungkin titik berangkat ingatan tentang khitan perempuan justru saya sadari di usia 17 tahun.
Tradisi tersebut adalah mopolihu lo limu, yang berarti mandi air lemon/jeruk. Setiap anak gadis Gorontalo yang mendapat menstruasi pertama wajib mengikuti mopolihu lo limu. Ritual ini juga dilakukan serangkaian dengan khitan perempuan. Maka, ketika acara mandi air jeruk berlangsung, rasa penasaran tentang mengapa perempuan Gorontalo harus mengikuti tradisi ini, memantik ingatan saya. Bila alasannya adalah untuk melanggengkan adat dan tradisi Gorontalo, mengapa praktik yang kemudian terbukti mengandung represi dan standarisasi atas tubuh dan moralitas perempuan, penting untuk dilanggengkan?
Bagi masyarakat Gorontalo praktik ini menekankan pada proses legitimasi identitas keislaman anak perempuan. MUI melalui Fatwa No 9A tahun 2008 menyatakan bahwa khitan perempuan adalah bagian dari syariat Islam, sehingga membuat keberadaan praktik ini terus dilaksanakan. Salah satunya di Gorontalo, sebagai provinsi dengan mayoritas muslim yang memegang falsafah hidup “adat bersendikan sara, sara bersendikan Al-Quran”.
Pembicaraan seputar khitan perempuan menunjukan dinamika wacana yang beragam, diiringi dengan respons dan perdebatan panjang. Khitan perempuan menjadi isu kontroversial setelah World Health Organization (WHO) secara tegas menyatakan bahwa tradisi ini merupakan tindakan mutilasi yang dilarang atau yang disebut female genital mutilation (FGM) yang melanggar hak asasi manusia.
KUPI Melarang Khitan Perempuan
Kemudian, pada wacana agama –yang juga menjadi ruang krusial– pembahasan mengenai khitan perempuan terus mengalami beragam respons, pengetahuan alternatif, hingga pernyataan sikap yang tegas dari sejumlah organisasi Islam. KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) misalnya, sebagai salah satu ruang yang membahas khitan perempuan melalui kongres ke dua tahun 2022 kemarin.
Musyawarah selama 3-4 hari tersebut menempatkan isu khitan perempuan atau praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) sebagai pembahasan utama. Banyak cerita dan testimoni dari peserta kongres terkait bentuk pelaksanaan praktik ini di daerah mereka masing-masing.
Kongres tersebut membuahkan sejumlah keputusan. Salah satunya adalah sikap tegas KUPI terkait pelarangan khitan perempuan (P2GP) dengan menyampaikan bahwa haram hukumnya melaksanakan dan melanggengkan praktik ini atas nama agama Islam. Bu Nyai Nur Rofiah menyampaikan bahwa tidak pernah ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad mengkhitan anak-anak perempuannya. Beliau juga menambahkan penjelasan tentang bagaimana praktik ini telah membawa mudharat bagi banyak perempuan.
Berseliweran di media mainstream hasil penelitian yang menampakkan betapa banyaknya kisah tentang dampak yang dialami perempuan. Baik itu perempuan sebagai ibu yang direpresi, atau perempuan dewasa yang akhirnya merasakan sesuatu yang negatif di tubuhnya akibat dari khitan yang ia lakukan sewaktu kecil.
Kisah Layla dan Ati
Misalnya, kisah dari Layla, seorang perempuan korban khitan perempuan di Mesir. Bersama BBC News, Layla bercerita tentang situasi ketika ia dikhitan secara paksa. “Waktu itu saya berusia 11 tahun. Saya dipegang dan dikhitan secara paksa oleh para orang tua. Di usia itu, alih-alih memberi saya penghargaan atas nilai bagus saya, keluarga justru memberi saya seorang bidan, berpakaian serba hitam, mengunci saya di kamar dan mengelilingi saya,” kenang Layla.
Ketika ia menjadi seorang ibu dan melahirkan anak perempuan pertamanya, ia berniat untuk tidak mengkhitan anaknya tersebut. Namun, tekanan dari keluarga suaminya yang membuatnya kalah dan terpaksa mengalah.
Trauma dan rasa marah Layla hadir kembali, mendorongnya untuk bergabung dalam komunitas perlawanan kekerasan perempuan. Ia bersedia bercerita kepada banyak pihak atas pengalaman dirinya sebagai representasi suara perempuan korban khitan.
Serupa tapi tak sama, kisah yang dialami oleh kawan saya di Gorontalo. Ati, seorang ibu dari 2 anak perempuan berusia kurang-lebih 5 dan 3 tahun. Sebelum menikah, ia aktif bergabung dalam organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam isu perempuan dan anak.
Ati yang lahir dan besar di Gorontalo, membuatnya harus dikhitan sewaktu kecil. Pun ketika menjadi seorang ibu, dia berterus-terang tentang ketidakmampuannya melawan perintah keluarga untuk mengkhitan anak perempuannya. “Mereka bilang aku ibu yang egois, jika tidak mengkhitan anak-anakku. Namun berulang kali aku bilang ke dukun anak itu agar jangan melukai klitoris anakku,” kata Ati pada saya.
Jika kita tarik lebih luas lagi, akan banyak sekali cerita tentang dampak negatif khitan terhadap perempuan. Ada kejadian tentang infeksi luka, diskriminasi sosial, dan perasaan tidak memiliki atau memahami tubuh sendiri. Keseluruhannya jelas sekali membuktikan betapa berbahayanya praktik ini, sedangkan Alquran sendiri melarang perbuatan yang membahayakan orang lain dan menimbulkan kemudharatan.
Pendisiplinan dan Politik Tubuh
Poin tentang pengalaman perempuan dikhitan ini beririsan dengan isu terkait politik tubuh perempuan. Pada kenyataannya, meskipun setiap orang memiliki kuasa penuh atas tubuhnya, namun selalu ada kuasa di luar tubuhnya yang menuntut orang tersebut agar bisa sesuai dengan aturan yang berlaku.
Foucault dalam Sejarah Seksualitas: Seks dan Kekuasaan menyampaikan, kuasa ini berkaitan erat dengan pengetahuan, dan melalui wacana atau diskursus, kekuasaan pengetahuan bisa direalisasikan (2002:44). Tujuan dari pendisiplinan tubuh tidak lepas dari membentuk atau menciptakan tubuh – serta tentu saja seseorang sebagai pemilik tubuh – agar tunduk, patuh, dapat dimanfaatkan, dan dikontrol. Pada khitan perempuan, aspek kekuasaan yang dimaksud dapat ditemukan melalui represi kuasa wacana agama yang dilegitimasi pada wilayah paling dekat – yakni keluarga – dengan diri perempuan yang dikhitan.
Namun pada level institusional, negara juga menjadi salah satu pemilik kontrol atas tubuh masyarakat terutama perempuan. Di Indonesia misalnya, peraturan tentang cara berpakaian perempuan atau kampanye program keluarga berencana, merupakan bentuk dari kontrol negara atas otoritas tubuh masyarakatnya.
Melalui peraturan dan kebijakan pada ruang keluarga, pendidikan, agama, kesehatan, ekonomi, dan politik, tubuh dan perilaku warga diintervensi pada tingkat yang tidak dapat ditoleransi dalam kehidupan sosialnya.
Di Gorontalo, khitan perempuan menjadi aspek kontrol atas perilaku seksual dan tubuh perempuan. Melalui proses mopolihu lo limu (mandi air jeruk), juga terdapat simbol yang menunjukkan tujuan tersebut. Di antaranya, kukuran kelapa sebagai tempat ibu duduk sambil memangku anak perempuan adalah simbol domestikasi. Agar perempuan tidak melupakan tanggungjawab mengurusi hal domestik untuk keluarga. Pelepah pinang sebagai simbol kepatuhan, telur ayam kampung simbol kehormatan, dan tujuh bambu kuning yang berisi air sebagai makna atas kemuliaan, kesucian perempuan agar terhindar dari dosa mulut, telinga, mata, hidung, kaki, tangan, dan alat kemaluan (Lamusu, Sance. 2016).
Respons negara
Hingga saat ini belum pernah ada sikap tegas negara atas pembahasan praktik ini di masyarakat. Hanya keputusan MUI melalui fatwa No 9A tahun 2008 yang bisa saya anggap sebagai respons negara atas perlawanan masyarakat atas praktik ini. Namun, alih-alih mempersoalkan praktiknya yang bermasalah, respons tersebut malah turut melegitimasi dan melanggengkan praktik yang berakibat pada ketidakadilan gender ini.
Padahal, tubuh adalah wilayah privat, yang tentu saja hanya pemilik yang berhak mengatur serta menjaga tubuhnya. Masih banyak perempuan yang tidak mengetahui tentang otoritas tubuh dan isu praktik khitan perempuan, dan negara justru membiarkan praktik ini dianggap sebagai ‘kearifan lokal’. Apakah negara memiliki kewenangan yang terbatas dalam mengintervensi tradisi yang melanggengkan ketidakadilan gender bagi warga negaranya? Atau mungkin memang negara – yang katanya sebagai pemegang kekuasan – sebenarnya tidak tahu dan tidak paham bagaimana cara menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya?
Penulis: Ifah Magfirah
Editor: Amanatia Junda
Disclaimer: Nama-nama yang penulis sebutkan di tulisan ini bukanlah nama sebenarnya. Seluruhnya adalah nama samaran yang berdasar pada konsensus.