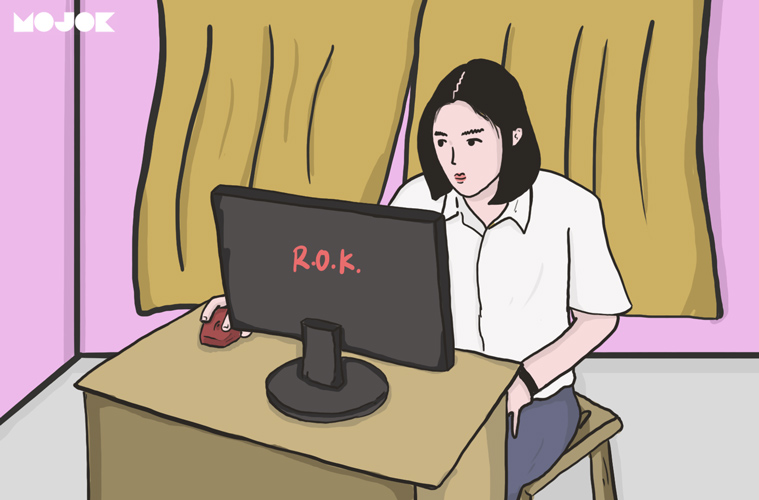MOJOK.CO – Polemik soal zonasi sekolah memang bikin ribut. Emak-emak satu ini berbagi keresahannya, terutama soal stigma lulusan sekolah favorit yang malah bikin beban.
Emak-emak yang baik, karena sekarang lagi ramai soal zonasi sekolah, perkenanlah saya cerita soal pengalaman saya bersekolah di SMP dan SMA favorit.
Eh, kenapa saya menujukan cerita ini buat emak-emak, ya? Oh, karena dalam keseharian saya memang lebih sering crit-crat sama emak-emak. Apalagi topik yang sering dibahas di tongkrongan depan tukang sayur belakangan ini adalah soal zonasi sekolah.
Saya cerita begini karena yakin banyak dari kalian yang nggak pernah ngicipi sekolah favorit dan cuma bisa ngowoh lihat kami anak-anak “terpilih” yang tampak kinclong dari luar pagar.
Tapi tolong diingat ini cerita saya lho, Mak. Tidak mewakili semua mantan murid sekolah favorit. Jangankan semua, mewakili separuh saja mungkin nggak. Apa yang saya rasakan mungkin beda dari yang dirasakan mantan siswa lain.
Nggak cuma beda, mungkin berkebalikan. Ingat juga ini kejadian sekitar 20 tahun yang lalu. Sekarang? Dengan polemik zonasi sekolah-nya? Wah, nggak tahu saya.
Saya dulu malu, Mak, kalau ditanya, “Sekolah di mana?” sebab kalau saya jawab jujur mata para penanya ini membelalak kagum, “Wah, sekolah favorit. Pasti kamu pinter banget.”
Hya, ampun, Mak, mau mblesek ke bumi saja rasanya. Pinter gimana. Sampai sekarang saya nggak ngerti reaksi redoks itu apa. Sampai bingung juga, kok dulu saya bisa lulus ya?
Tetapi sebagian teman saya ada yang bangga sehingga selalu menjawab dengan mantap, “SMA Negeri XZY, Unggulan, Yogyakarta.”
Mereka mengenang masa-masa sekolah sebagai masa yang membahagiakan. Sementara yang teringat kuat dalam benak saya justru dlongap-ndlongop-nya saya waktu disuruh mengerjakan soal di papan tulis, selain tentu saja “lomba makan marning tanpa ketahuan” dalam kelas Antropologi.
Oke, saya mulai dari sebelum adanya polemik zonasi sekolah alias awal sekali.
Begini, Mak, saya dulu sekolah di SMP dan SMA negeri favorit di Jogja. Karena saya pinter? Aih, Alhamdulillah. Saya nggak pinter, Mak. Saya anggap saya cuma bejo.
“Ah, masak?”
Iya, mak, suwir, wong nilai bagus waktu saya SD jatuh begitu saja dari langit. Saya nyaris nggak pernah belajar. Tapi mbuh gimana, saya merasa pelajaran sangatlah gampang. Sampai saya bingung, kok ada teman saya yang ngerjain soal ping-pingan aja nggak mudheng. Wong gampang byanget gitu, lho.
Percaya nggak, Mak, saya sampai sengaja salah menjawab soal agar saya nggak kelihatan pinter-pinter banget. Rikuh je, kalau nilai saya sepuluh bulat sementara teman-teman cuma dapat tujuh. Itu pun dibela-belain sampai kemringet.
Berbekal NEM SD yang rata-rata sembilan, nggelundung-lah saya ke SMP kaporit, meski di sana saya mendadak jadi pekok kuadrat (nanti saya cerita). Tapi, pas mau ke SMA, bejo lagi saya. NEM saya mepet byanget.
Tapi di tahun yang belum ada sistem zonasi sekolah itu ada wacana sekolah unggulan yang mengharuskan siswa barunya menjalani semacam psikotes. Nah, gabungan antara NEM dan hasil psikotes itu yang akhirnya ngatrol saya hingga saya nyangkut masuk.
Saya langganan juara waktu SD, Mak, tapi begitu masuk SMP, keajaiban itu ambyar seketika. Saya plonga-plongo ngadepin rumus matematika atau fisika.
Di situlah saya justru menjadi obyek yang digumuni, “Halah, mosok cuma ngitung jam berapa kereta Lodaya bertemu dengan kereta Lodaya kalau satunya melaju dari Bandung jam sekian dengan kecepatan sekian. Berhenti tiga menit karena ada wedhus yang nyebrang rel. Sementara yang satunya melaju dari stasiun Solo jam sekian dengan kecepatan sekian—aja nggak bisa.”
Seriyes, mendadak saya merasa jadi makhluk paling goblok di muka bumi. Pengin bener saya jawab, “Emang saya pikirin? Pertanyaan paling krusial menyangkut kereta adalah ‘pesan pop mie atau nasi goreng’. Itu!”
Kalau ulangan, saya hanya menatap soal dengan nanar. Kagak ngerti, Mak, apa yang ditanyain. Soal-soal matematika seolah tertulis dalam aksara Jepang. Itu pun nggak komplet wong saya lupa simbol percepatan gravitasi.
G? G itu bukannya simbol Matahari? Eh Gramedia? Kalau beruntung, saya dapat contekan.
“Ada gitu contek-contekan di sekolah kaporit?”
Banyak lah. Kami kan anak-anak pintar, jadi harus dapat nilai bagus dong. Apapun caranya. Yang menyembunyikan kepekan juga ada. Yang nulis rumus di meja? Ada juga, meski kalau saya yang nulis rumus ya dijamin nggak ada gunanya.
“Lah, kirain di sekolah unggulan semuanya serba tertib.”
Ya nggak, lah.
Siswa yang mbolos ada nggak? Ada. Yang make narkoba? Ada. Yang terlibat perkelahian? Ada juga. Yang hobinya nggabrul (nilep) makanan di warung? Ada.
Memang mungkin jumlahnya lebih sedikit dibanding sekolah-sekolah non-favorit, tetapi saya cuma mau bilang sekolah unggulan bukan jaminan anak-anaknya berakhlak unggulan juga, Mak.
“Fasilitasnya gimana?”
Pas saya sekolah dulu sih, WC-nya tetap bau. Lab-nya ya tetap berdebu dan rada spooky.
Perpusnya?
Kebanyakan buku pelajaran dan penunjangnya. Buku fiksinya dikit dan nggak up to date. Pengunjungnya juga nggak banyak. Murid-muridnya lebih sibuk diskusi reaksi apa yang terjadi dari penggabungan asam bikarbonat dengan asam gelugur.
Guru-gurunya?
Biasa aja Mak. Kemampuan akademisnya rata-rata saja, tetapi memang oke soal kedisiplinan. Jarang ada jam kosong jadinya. Tapi kalau ada jam kosong, percayalah, siswanya juga bahagia.
Sttt, rahasia ya Mak, menurut saya cara ngajar gurunya juga biasa-biasa aja, tuh. Sebagian malah membosankan (mungkin karena saya pekok ya, Mak, jadi nggak ngerti apa yang diomongkan guru).
Seriusan, Mak. Ada guru tuh yang kalau ngajar cuma ngomong sama papan tulis. Muridnya ngilang setengah juga nggak sadar. Yang galak dan main tangan ada juga. Ada yang kalau muridnya nggak ngerti, dia frustrasi banget dan menyalahkan siswanya alih-alih mengoreksi cara ngajarnya.
Cara ngajarnya ya gitu-gitu aja, standar; nulis, nerangin, kasih soal, ulangan. Kalau lo nggak ngerti? Ya, derita lo. Usaha sendiri lah biar ngerti.
Ya pasti guru yang lucu, baik hati, dan menyenangkan. Tapi ini juga ada di sekolah-sekolah lain, kan? Nggak ada jaminan kalau sekolah favorit maka gurunya favorit juga. Mereka manusia, Mak.
Yang jelas saya nyaris nggak menemukan guru inspiratif macam Mr. Keating di pilem Dead Poets Society (tau nggak, Mak pilem itu? Nggak tau juga nggak pa-pa. Nggak keluar di Ebtanas, kan? Cie Ebtanas). Tetapi harap dimaklumi, sama seperti siswanya, mereka juga ditekan dari sana sini untuk mempertahankan status sekolah favorit.
“Tapi, Mak, guru-guru di sekolah ‘pinggiran’ itu parah banget tauk!”
Woah, gitu ya, Mak.
Tapi, Mak, saya merasa sekolah kaporit itu istimewa banget (mau bilang curang nggak berani saya). Muridnya pinter dan gurunya oke. Jadi yo jelas makin nggendero. Udah gitu, alumninya pada sukses. Jadi rajin gitu nyumbang almamater.
Nah, sekolah mana yang nggak mau jadi kaporit terus? Di sini roda berputar dan status bergeser kayak nggak boleh berlaku. Kalau sudah kaporit, ya kudu kaporit terus.
Nggak ada cerita kayak gini, “Karena sudah 25 tahun berturut-turut sekolah kami dapat NEM tertinggi, kami harap tahun ini sekolah lainlah yang mendapat gelar itu.”
Jadi tekanan buat dapat nilai bagus tinggi banget (macem panci presto aja, Mak). Akibatnya para siswa dikasih tugas ekstra, lebih sering ulangan, plus harus mengikuti tambahan pelajaran.
Beneran lho, Mak, tekanan buat dapat nilai-nilai-dan-nilai selangit itu begitu nyata. Meski kami tetap masih bisa bersenang-senang, kayak nge-band, main sepakbola, atau pacaran, beban itu tetap terasa.
Apalagi rasanya yang dihargai cuma siswa yang nilainya nyaris sempurna. Selain itu, udah jadi kayak kewajiban dapat bangku di PTN favorit. Kalau nggak keterima? Bisa depresi, Mak. Malu. Mungkin seumur-umur nggak berani datang reuni.
“Ah, tapi, situ ngakuin sendiri tadi sebagian besar alumni sekolah unggulan juga jadi manusia unggulan.”
Ya, tapi ada banyak (banget) faktor yang berperan di sini. Bahkan masalah di sistem zonasi sekolah itu mungkin cuma secuil aja.
Yang pertama, tentu bakat dan minat si anak serta ketekunannya. Yang kedua dukungan keluarga. Kenapa siswa sekolah favorit itu banyak yang kuliah di jurusan favorit dan sukses berkantor di gedung adem menghadap Bundaran HI? Karena rata-rata mereka berasal dari keluarga nggenah.
Kalau keluarganya nggenah saya yakin 90% anaknya bakal nggenah (maap, Mak, yang berani menjamin 100% itu cuma Delta FM. Seratus persen lagu enak katanya). Itulah makanya, meskipun alumni sekolah unggulan banyak yang sukses, alumni sekolah non-unggulan banyak yang suksesnya ngadi-adi.
“Jadi sekolah tidak berperan sama sekali?”
Eh, nggak perlu ngegas, Mak. Pakai cincing daster pulak.
Saya ndak bilang gitu. Bisa kualat saya. Dalam hati kadang saya juga bertanya-tanya, kalau dulu saya nggak sekolah di sekolah favorit, jangan-jangan saya sudah jadi pengusaha martabak atau Youtuber tajir.
Kita kan nggak pernah tahu, yak? Apalagi dulu, rata-rata siswa sekolah unggulan punya mindset sama, kuliah di PTN terus jadi dokter. Jarang ada yang pengin jadi editor buku misalnya.
Ngaku sajalah, berapa persen ilmu sekolah kalian (favorit atau bukan) yang terpakai sekarang? Meski saya dulu belajar rumus integral dan diferensial, penerapan ilmu matematika saya paling pol kini adalah, “Kalau harga sekilo gula Rp12 ribu, maka berapa harga 2 kg gula?”
Kalau tulisan saya sekarang bisa tembus di Mojok, apa karena dulu saya dibimbing oleh sekolah buat nulis artikel? Ya, ndak. Saya belajar sendiri.
Jadi yang penting bukan cari sekolah favorit, Mak, tapi bikin keluarga favorit, yang membuat anak-anak gemar belajar, gemar bersedekah, sekaligus gemar menabung. Jadi tak perlu pusing-pusing amatlah sama sistem zonasi sekolah yang acak-adul itu.
Ayo Mak, kalau biasanya anggota keluarga main gawai masing-masing, sekarang ajak keluarga piknik ke museum atau ke perpustakaan. Bapak-bapak, coba kurangi nongkrongnya, biar duitnya bisa buat ngelesin gitar anaknya.
Kalau kuota internet terbatas, jangan cuma buat download Drakor, sekali-kali yuk, nonton NatGeo Wild. Daripada mumet mikirin zonasi sekolah, ayo, Mak, jadikan rumah sebagai sekolah terbaiq buat anak-anak kita.