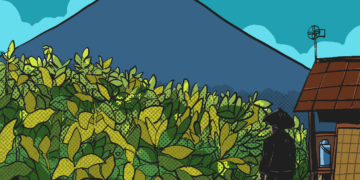Makam Raja-raja Imogiri jadi monumen kebesaran penguasa Jawa di masanya. Kompleks makam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir raja-raja dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta.
***
Nafas mulai terasa berat. Saya membungkukkan badan untuk istirahat. 10 meter di depan saya terdapat Gapura Supit Urang yang bentuknya khas dari batu bata merah. Kami hanya dipisahkan sedikit anak tangga. Saya langkahkan kaki ke arah kiri, mencari sebuah jalan yang mungkin tidak banyak diketahui orang.
Sebuah area berpagar hitam terlihat. Ini adalah kompleks makam Pakubuwono. Saya kemudian berbelok ke arah utara, menyusuri pinggiran pagar. Terlihat beberapa bekas longsoran. Sepasang pusara (nisan) bergaya Hanyakrakusuman terlihat di dekat sudut pagar dengan bunga segar di atasnya.
“Nderek langkung (izin lewat),” saya membatin. Tiga pusara lain terlihat di bagian belakang, hanya berjarak sekitar 3 meter dari jurang. Di dekat makam, terdapat formasi batu andesit berhimpitan dengan pagar, indikasi sederhana tentang aktivitas vulkanologi masa purba di Yogyakarta. Perbukitan ini merupakan bagian dari Pegunungan sewu.
“Bayangan kejayaan raja manusia akan pudar,” cetus Elrond, seorang pimpinan bangsa Elf yang ada dalam film The Lord of The Rings: The Two Towers. Dari atas perbukitan tetiba saya teringat kutipan percakapan tersebut. Raja-raja manusia punya aneka cara untuk menahan waktu agar tidak memudarkan kebesaran mereka. Entah dengan mewariskan kisah kejayaan atau mengawetkan tubuh ala raja-raja Mesir Kuno.
Barisan perbukitan di tempat saya berdiri, jadi saksi seorang raja besar tanah Jawa mencoba menahan laju kepudaran itu. Tepatnya di Dusun Pajimatan, Imogiri, mereka membangun sebuah kompleks pemakaman megah di atas bukit. Hingga kini monumen kebesaran itu masih kita bisa kita saksikan.

Kompleks makam Raja Jawa
Sultan Agung (bertahta tahun 1613-1645) punya satu keinginan untuk akhir hayatnya. Ia ingin dikebumikan di Mekah supaya dekat dengan makam Rasullulah. Namun, keinginan itu ditolak oleh Sunan Kalijaga. Sebab akan akan merepotkan keturunannya karena letaknya yang sangat jauh. Konon, sang raja kemudian melemparkan sebuah gundukan tanah dari Mekah demi mencari area untuk makamnya.
Cerita itu saya dapatkan dari Darto (72), seorang pria dengan baju peranakan yang lebih suka disebut pemandu wisata. Tak usah bingung dengan cerita seseorang yang mampu melempar tanah sejauh 12 ribu kilometer. Sebab, sang raja (Sultan Agung) bahkan dikabarkan kerap salat Jumat di Mekah.
Sambil menaiki anak tangga, saya mendengarkan cerita Darto. Terus naik menuju makam Sultan Agung. Makam ini dibangun pada 1632 dan memiliki 3 kompleks utama. Masing-masing adalah kompleks Makam Raja Surakarta, Yogyakarta, dan Sultan Agung. Ada sekitar 40 makam di area ini.
Melansir data dari laman Kemendikbud, total terdapat 8 kompleks di Makam Pajimatan: Sultan Agungan, Pakubuwanan, Bagusan, Astana Luhur, Girimulya, Kasuwargan, Besiyaran, dan Saptarengga. Dengan bahasa sederhana, Darto menuturkan bahwa area makam dibagi dalam beberapa blok berisi masing-masing 3 pusara raja.
Kompleks Sultan Agungan misalnya, di dalamnya terdapat pusara Sultan Agung serta Sunan Amangkurat II dan III. Kompleks Saptarengga bersemayam jasad Sultan Hamengkubuwono VII, VIII, dan IX. Area ini juga menjadi pusara bagi keluarga raja. Kompleks Sultan Agungan, Darto menyebut ada pusara Ratu Batang, permaisuri Sultan Agung. Selain itu, ada juga makam Kepala Staf TNI AD pertama GPH Djatikusumo, putra dari Pakubuwono X.

Kompleks makam ini sekarang tenar disebut Makam Raja-raja Imogiri. Namun jika melihat nama di pintu gerbang, akan terlihat tulisan “Pasareyan Dalem Para Nata”. Sementara beberapa orang menyebutnya dengan Pajimatan atau njimatan, merujuk ke nama dusun tempat makam ini berada yaitu Pajimatan, Wukirsari, Imogiri, Bantul.
Berdasarkan keterangan di laman Kemendikbud, nama Imogiri berasal dari kata hima (berarti awan yang menyelimuti gunung) dan giri (gunung). Lalu nama Pajimatan berasal dari kata jimat atau pusaka. Jimat atau pusaka bagi Kerajaan Mataram. Laman itu juga menulis nama Bukit Merak dengan ketinggian 100 mdpl sebagai nama lokasi ini di masa silam.
“Dulu disebut Bukit Merak karena di sini banyak burung merak,” kata Darto.
Darto lanjut bercerita soal arsitektur tempat ini. Ia mengenang, gempa 2006 membawa kerusakan cukup serius di area makam. Tujuh gerbang mengalami kerusakan. “Gapura itu,” ujar Darto sambil menunjuk Gapura Supit Urang, “Sudah dibongkar untuk dipasangi cor besi supaya kuat.” Dulu, sebut Darto, konstruksi bangunan ini menggunakan bahan perekat tradisional, antara lain dengan putih telur dan beras ketan.
Untuk area makam Raja Yogyakarta dan Surakarta, keduanya telah mendapatkan beragam pembaruan. Cat hitam di area makam Pakubuwono X misalnya, itu berasal dari peziarah yang doanya terkabul. Lalu di area makam Raja Yogyakarta, nuansa cat putih dengan gerbang bergaya lebih modern akan terlihat kontras dengan di area Sultan Agungan.
Untuk menuju ke kompleks Sultan Agungan, pengunjung masih harus meniti 99 anak tangga dan melewati beberapa gerbang. Jika sedang tutup, pengunjung tetap bisa berdoa di 2 tempat: depan Gerbang Kamandungan atau ruang khusus di dekat bangsal. Untuk masuk, pengunjung harus berganti baju Jawa dengan harga sewa sekitar Rp20 ribu dan mengisi kotak infak seikhlasnya.
Khusus untuk makam Sultan Agung, Darto mengatakan peziarah harus jalan jongkok untuk mendekati pusara. Selain itu, tidak ada pula pintu tembus ke kompleks makam lain. Artinya, peziarah harus masuk lewat area masing-masing sesuai pusara yang dituju. Area makam sendiri hanya buka pada hari Minggu, Senin, Jumat, 1 Syawal, 8 Syawal, dan 10 Besar/Zulhijah.
Kisah-kisah janggal
Selayaknya makam kuno lain, tempat ini juga punya beberapa cerita. Mulai dari mitos pesawat akan jatuh jika melintasi bagian atas makam, seorang pengkhianat kerajaan bernama Tumenggung Endranata dengan makam di 3 bagian tangga supaya terinjak-injak, hingga harumnya tanah di pusara Sultan Agung.
“Yang harum ya hanya di makam Sultan Agung saja, lainnya tidak,” tambah Darto. Konon, tanah itu harum karena merupakan tanah dari Mekah.
Tumenggung Endranata sendiri disebut berkhianat karena membocorkan rencana penyerangan Mataram ke Batavia. Namun, versi lain dari cerita ini mengatakan bahwa bukan Endranata yang dimakamkan di bagian tangga melainkan Jan Pieterszoon Coen alias Mur Jangkung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan rentang kekuasaan dari tahun 1619-1623 dan 1627-1629.
Dalam Puncak Kekuasaan Mataram, H.J. De Graaf menyebut pembangunan makam ini dibangun sebagai lanjutan dari pengangkatan Sultan Agung sebagai susuhunan pada tahun 1624. Ia juga punya versi lain berkaitan letaknya di atas bukit yang dalam laman Keraton Jogja disebut dipengaruhi kebudayaan dan kepercayaan masa Hindu.

Menurut Graaf, pembangunan ini hampir pasti meniru makam Syekh Ibnu Maulana alias Sunan Gunung Jati dengan lokasi di atas bukit. Ini adalah adalah salah satu hal di Mataram yang diilhami dari ilmu bangunan ala Cirebon dan bertujuan agar Sultan Agung mendapatkan kehormatan spiritual.
Berkaitan dengan nama Endranata, Puncak Kekuasaan Mataram juga mendeskripsikannya sebagai seorang pengkhianat tetapi bukan dalam konteks serangan Mataram ke Batavia. De Graaf menulis sosok ini sebagai seorang tumenggung penguasa Demak.
Ia dihukum mati setelah selesainya pemberontakan Adipati Pragola II terhadap Mataram. Alasan dari penjatuhan hukuman mati ini karena janda Adipati Pragola II melapor pada Sultan Agung bahwa Endranata sesungguhnya menjadi penghasut dalam konflik Pati-Mataram.
Nama Endranata dan Mur Jangkung bukanlah satu-satunya kisah yang janggal. Klaim Darto tentang Sultan Agung dan Sunan Kalijaga pun sejatinya cukup aneh karena sang sunan sudah meninggal pada 1513 Masehi atau 100 tahun sebelum pembangunan Makam Pajimatan.
Air tempayan dan para abdi dalem
Bunyi lonceng jam sesekali berbunyi di tengah riuh obrolan para abdi dalem. Sembari mendengarkan cerita Darto, saya mengamati kompleks Sultan Agungan. Menuju Gerbang Kamandungan, terdapat tempayan besar di kiri dan kanan jalan. Jika diurutkan dari kiri ke kanan, tempayan itu punya nama Kyai Danumurti, Kyai Danumaya, Kyai Mendung, dan Nyai Siyem.
Kata Darto, itu semua adalah hadiah dari berbagai negara sahabat Mataram. Mereka berasal dari Sriwijaya, Aceh, Turki, dan Thailand. Di masa Sultan Agung hidup, tempayan itu digunakan untuk berwudu. Kini, beberapa orang percaya air itu punya khasiat tertentu dan sering diminta oleh beberapa peziarah untuk dibawa pulang.
Area Makam Raja-raja Imogiri punya luas 5 hektar. Makam ini berada di lahan milik Keraton Yogyakarta yang terhampar seluas 17 hektar. Jika hendak menuju ke makam ini, pengunjung sejatinya bisa menempuh 2 jalan. Pertama adalah lewat pintu masuk utama dan harus meniti anak tangga. Kedua adalah lewat jalan kecil di dekat kompleks Makam Seniman Girisapto.

Ada beberapa kompleks makam umum milik warga di sekitar Makam Raja-raja Imogiri. Terutama di sekitar anak tangga menuju kompleks-kompleks makam. Saya bertanya pada Darto tentang makam di bagian belakang pagar yang saya temukan di awal perjalanan. Ia mengungkapkan bahwa itu adalah pusara sosok bernama Kyai Cinde Amoh, salah satu pamomong Sultan Agung yang enggan dimakamkan di dalam kompleks.
Sebagai makam para raja, area ini dijaga abdi dalem dari 2 Keraton Yogyakarta dan Solo. Jumlah totalnya mencapai 180-an orang. Abdi dalem Jogja berjaga di bangsal sebelah kiri gapura dan abdi dalem Solo berada di bangsal sebelah kanan. Terdapat pula beberapa abdi dalem berjaga di bangsal depan masjid di bagian bawah makam.
Hampir satu jam saya berbincang dengan Darto sebelum akhirnya kami berpisah. Saya lantas naik ke depan Gerbang Kamandungan untuk berdoa. Menjelang pulang, saya memutuskan untuk sejenak menikmati semilir angin di depan Gapura Supit Urang.
“There is only death”. Kata-kata itu masih milik Elrond. Mungkin itu adalah deskripsi paling jujur mengenai tempat ini. Sebuah sudut kecil di rangkaian perbukitan di selatan Yogyakarta, tempat raja-raja Jawa mengakhiri perjalanan dan kekuasaan di dunia. Mereka diantar pulang oleh para punggawa, meniti ratusan tangga, dan mengabadi di kompleks makam Para Nata.
Reporter: Syaeful Cahyadi
Editor: Purnawan Setyo Adi