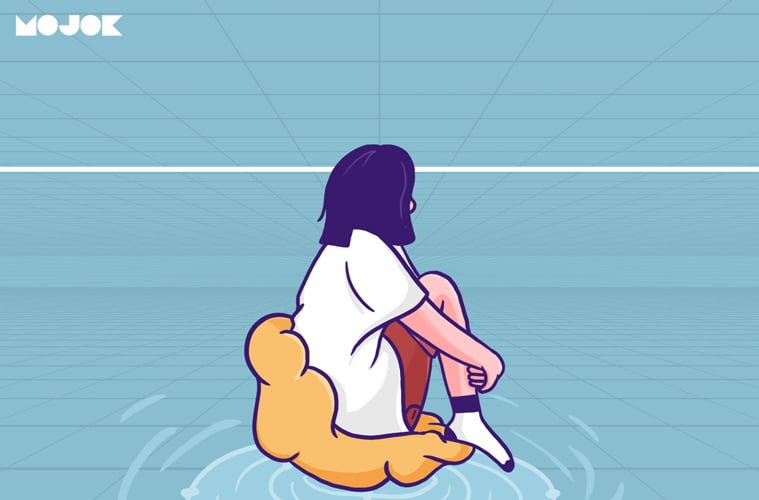Hampir semua orang tahu seperti apa rasanya kesepian. Hal itu terdengar aneh, karena kita hidup di dunia yang tampaknya selalu terhubung. Setiap hari kita berinteraksi dengan orang lain di tempat kerja, sekolah, jalanan, bahkan media sosial.
Namun, justru di era yang serba terkoneksi ini, banyak dari kita merasa semakin terasing dan sendirian. Koneksi ada di mana-mana, tetapi kedekatan yang sesungguhnya justru terasa langka.
Berbagai penelitian bahkan mengasosiasikan kesepian dan isolasi sosial dengan penyakit jantung dan stroke, diabetes tipe 2, dan kanker. Di masa sekarang, kesepian bahkan kerap disebut sebagai sebuah “epidemi”.
Adril (21), mahasiswa semester akhir Universitas Airlangga, adalah salah satu orang yang merasakan hal tersebut. Ia mengaku bahwa saat tahun baru kemarin saja, ada perasaan sepi saat berada di kos.
Sampai-sampai, dirinya tak mau membuat resolusi muluk-muluk untuk hidupnya. Mengutip lirik lagu “Cincin” dari Hindia, ia berharap hidupnya berjalan biasa-biasa saja tanpa banyak perubahan.
“Pergantian tahun dari 2023 ke 2024 aku malah habiskan sendirian di kos di Surabaya. Aku rayakan dengan tidur dan ngerjain tugas,” ujar Adril saat diwawancarai Mojok pada Jumat (27/12/2024).
Sepi di tengah keramaian memang sering dialami banyak orang
Sudah hampir empat tahun Adril merantau di Surabaya. Pemuda asal Nganjuk, Jawa Timur, ini mengakui bahwa ada rasa hampa yang muncul ketika ia sendirian. Ia kerap ingin mencurahkan isi hatinya, tapi tidak tahu harus berbagi cerita kepada siapa.
Senada dengan apa yang dirasakan Adril, dalam laporan WHO berjudul “From Loneliness to Social Connection”(2025), kesepian dijelaskan sebagai perasaan yang muncul saat seseorang merasa hubungan sosial yang dimilikinya tidak seperti yang diharapkan. Meski mungkin dikelilingi orang lain, seseorang tetap merasa sendiri atau tidak terhubung.
Laporan itu menyebut, perasaan kesepian bersifat pribadi dan dipengaruhi oleh harapan sosial atau pandangan masyarakat tentang seperti apa seharusnya hubungan dengan orang lain.
Kesepian tidak selalu berkaitan dengan seberapa sering seseorang berinteraksi dengan orang lain. Seseorang tetap bisa merasa kesepian meskipun memiliki banyak teman atau menjalani rutinitas sosial yang padat, jika kualitas atau kedalaman hubungannya tidak memenuhi kebutuhan emosionalnya, tulis laporan itu.
Bukan soal berapa teman yang kita punya
Menurut Dosen Psikologi Universitas Islam Indonesia (UII) Hazhira Qudsyi, kesepian bukan soal seberapa banyak teman yang kita punya, tapi seberapa dalam dan bermakna hubungan itu.
“Orang yang punya banyak teman justru bisa lebih merasa kesepian dibanding mereka yang hanya punya sedikit teman,” jelasnya.
Dalam konteks kehidupan urban yang sibuk dan penuh tekanan, relasi yang dangkal dan hubungan yang bersifat transaksional kerap menjadi norma. Maka tak heran jika kesepian justru sering tumbuh diam-diam di tengah keramaian, imbuhnya.
Salah satu contoh nyata dari kondisi ini adalah kasus Dheeraj Kansal (25), seorang akuntan muda dari New Delhi, India. Ia memiliki gelar pendidikan tinggi serta bekerja di lingkungan korporat. Meskipun begitu, sebagaimana dilaporkan The Indian Express, Dheeraj memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada (28/07/2025) dengan cara tragis: menghirup gas helium di sebuah kamar penginapan.
Dalam catatan terakhirnya, ia menulis bahwa “kematian adalah bagian terindah dalam hidupku,” dan bahwa ia “tidak pernah benar-benar terhubung secara mendalam dengan siapa pun.” Dalam pesan terakhirnya itu, ia menyebut sejak kematian ayahnya dan pernikahan kembali ibunya, ia merasa hidupnya dijalani dalam kesendirian.
“Orang Kota” lebih gampang merasa kesepian
Perasaan kesepian yang dialami Adril maupun Dheeraj, ternyata dirasakan juga oleh banyak orang. Jajak pendapat litbang Kompas yang dilakukan pada 16–19 Juni 2025 terhadap 512 responden di Indonesia, menemukan bahwa sekitar 1 dari 5 orang (19,97 persen) mengaku merasa kesepian—setidaknya sekali dalam sepekan.
Jurnalisme data Kompas juga mencatat Kota Jogja menempati skor tertinggi diantara 30 kota besar yang kesepian dengan skor 74,9 poin, diikuti Jakarta Pusat, Makasar, Surakarta, dan Jakarta Selatan.
Demografi, menurut Hazhira Qudsyi, berdampak pada tingginya prevalensi kesepian di kota-kota.
“Bisa jadi, banyak dari orang-orang yang tinggal di daerah urban adalah pendatang, yang pindah karena studi lanjut atau pekerjaan baru,” ujar dosen psikologi UII ini.
“Adanya migrasi ini tentunya akan mempengaruhi jaringan sosial mereka yang sudah ada, dan paparan terhadap lingkungan baru dapat menyulitkan mereka untuk menjalin relasi yang mendalam dengan orang lain,” imbuhnya.
Lingkungan tempat tinggal juga punya peran besar dalam memperkuat rasa kesepian. Menurut Qudsyi, sejumlah penelitian menunjukkan sedikitnya ruang hijau dan sulitnya akses ke ruang publik yang nyaman bisa membuat orang merasa makin terasing.
Bangunan yang terlalu “rapi dan tertutup”- seperti apartemen kecil tanpa ruang berkumpul, atau gedung-gedung yang tidak menyediakan ruang interaksi, secara tidak langsung mengurangi kesempatan orang untuk bertemu, ngobrol, atau sekadar menyapa, ujarnya. Padahal, hal-hal kecil seperti itu bisa jadi penawar ampuh bagi rasa sepi yang diam-diam mengendap.
“Ramalan” Simmel soal orang kota yang gampang didera sepi
Fenomena demikian, sebenarnya telah lama disinggung oleh filsuf Jerman, Georg Simmel, dalam bukunya The Sociology of Georg Simmel (1950). Dalam salah satu esainya di buku tersebut, berjudul “The Metropolis and Mental Life”, Simmel menjelaskan bahwa kehidupan mental orang kota didominasi rasionalitas dan sikap berjaga jarak yang kerap terjadi.
“Orang kota cenderung menekan emosi dan mengandalkan logika untuk menghadapi stimulasi berlebihan dari lingkungan urban,” katanya.
Ia menulis, “Daripada merespons sesuatu dengan perasaan, orang yang hidup di kota besar cenderung merespons dengan pikiran dan logika. Cara berpikir seperti ini terbentuk karena mereka harus menghadapi banyak tekanan dan rangsangan dalam kehidupan kota.”
Kondisi tersebut, kata Simell, mengakibatkan mengikisnya kedalaman suatu hubungan sosial di kota besar.
Orang kota yang serba transaksional bikin kesepian merajalela
Pandangan soal ekonomi di kota besar turut memperkuat sikap “rasional” yang dingin dan impersonal dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu termasuk hubungan antar individu diukur berdasarkan nilai tukar dan manfaat, bukan pada kualitas atau keunikan yang ada pada diri masing-masing orang.
Akibatnya, interaksi manusia di kota menjadi semakin mekanis dan terlepas dari keintiman emosional.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa orang-orang diperlakukan seperti angka: bernilai hanya sejauh mereka berguna secara fungsional.
“Semua hubungan emosional antarmanusia didasarkan pada keunikan masing-masing orang. Sementara itu, hubungan yang bersifat intelektual memperlakukan orang seperti angka—yaitu sebagai sesuatu yang sebenarnya netral atau biasa saja, dan hanya dianggap penting jika mereka punya sesuatu yang bisa dilihat atau diukur secara nyata,” kata Simell dalam bukunya.
Di sisi lain, dalam komunitas kecil, kedekatan antar individu menciptakan hubungan yang lebih emosional dan bermakna.
Relasi yang semacam itu sulit bertahan di kota besar karena tekanan ekonomi dan struktur sosial yang menuntut efisiensi dan objektivitas. Kondisi inilah yang, menurut Simmel, membuat kehidupan mental orang kota berada dalam ketegangan terus-menerus antara perlindungan diri dan keterasingan emosional.
Penulis: Khatibul Azizy Alfairuz
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Gawai adalah Candu: Cerita Mereka yang Mengalami Pembusukan Otak karena Terlalu Banyak Menonton Konten TikTok atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.