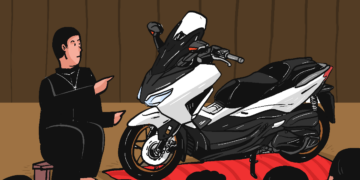MOJOK.CO – Menjawab pertanyaan tentang Tuhan dari seorang anak kecil memang mudah. Mendiskusikannya? Belum tentu semudah itu.
“Bapak, Tuhan itu apa sih?” itulah yang ditanyakan oleh anak sulung saya ketika masih kecil.
Usianya waktu itu 4 tahun jelang 5 tahun. Namanya Perdana. Dia lahir di Adelaide, South Australia, tapi antara usia 1 hingga 4 tahunan dia tinggal di Yogyakarta.
Ulang tahun ke-5 sudah dia rayakan di Perth, Western Australia. Beberapa waktu sebelum ulang tahunnya, itu lah yang dia tanyakan sambil duduk di pangkuan saya: Tuhan itu apa?
“Tuhan itu yang menciptakan kita dan seluruh alam ini.”
Gampang lah jawabannya. Saya yakin dengan jawaban itu. Tapi saya tidak yakin apakah dia paham atau puas dengan jawaban seperti itu.
“Tuhan itu sekarang di mana?” Dia lanjut bertanya.
Saya masih yakin dengan jawaban selanjutnya: “Tuhan ada di sini.” Saya menjawab sambil membelai dada kirinya. “Tuhan ada di dalam sini, di hati kita.”
Selama beberapa waktu setelah itu, Perdana sering saya lihat menyibak kerah baju atau lubang leher kaus yang dia pakai, dan berbicara ke arah dada kirinya: “Tuhan, saya ingin jalan-jalan ke McDonald’s.”
Saya mendiamkan saja dulu interpretasi seperti itu tentang keberadaan Tuhan, dan caranya berkomunikasi pada Tuhan. Toh itu tidak salah. Lagipula kebiasaan berbicara pada Tuhan ke dadanya sendiri itu berubah dengan cepat.
Sejak itu, hampir tak ada lagi pembicaraan tentang Tuhan antara saya dengan dia. Semua berjalan biasa saja, hingga beberapa tahun kemudian ketika kami sudah tinggal di Yogyakarta lagi.
Suatu ketika, saya lihat buku The History of God karya Karen Armstrong berada di meja belajar di kamar Perdana dan Afkar, adiknya.
Biasanya buku itu berada di perpustakaan dekat ruang tengah. Karena itu saya tanya pada mereka, “Who is reading this book?”
“I am,” jawab Perdana.
“Finish reading it already?”
“No, I just started chapter one.”
“Let’s talk about it once you finish reading it.”
“Ok, Dad.”
Saya lalu teringat bahwa beberapa tahun lampau, kalau tak salah tahun 2008 saat masih di Perth, Perdana juga membaca sampul depan buku itu, yang sub-judulnya adalah The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam.
Melihat kata “history of God” dan “4,000-Year” itu, Perdana waktu itu bertanya, “Is God 4,000 years old?”
“No,” jawab saya.
“That was the history of monotheism. The book is on the 4,000 years of monotheism.”
“What is monotheism?”
“Monotheism is a belief that there is only one God. The teaching is usually attributed to Nabi Ibrahim.”
Karena saya merasa topik ini masih terlalu berat untuk murid kelas 3 Primary School, saya katakan padanya kemudian: “Let’s talk about it later. You can read the book ten years from now.”
Nah, ketika itu belum ada sepuluh tahun, dan dia menyentuh lagi buku itu. Dua hari setelah melihat buku itu di kamarnya, saya tanya sampai di mana dia membacanya. Dia bilang belum terlalu banyak; masih di bab satu katanya.
Meski begitu, saya ajak dia membahasnya sekilas. Seingat saya, obrolan itu kami lakukan sambil saya menantarnya ke sekolahnya di Jl. Ringroad Utara.
Dia mulai menangkap gagasan bahwa agama itu evolutif. Saya tekankan bahwa evolusi agama itu fenomena sosial yang wajar. Tak ada agama yang merupakan hasil dari bertapa dan merenung semalam dua-malam.
Al-Quran juga mengisahkannya dalam metafora pencarian Tuhan oleh Ibrahim, mulai dari bintang, bulan, mentari, hingga Ibrahim menyimpulkan hanya ada satu Tuhan.
Kami juga bahas sekilas tentang konsep ketuhanan yang diajarkan Ibrahim dan dilanjutkan Nabi-nabi setelahnya.
Kami singgung juga soal konsep Trinitas. Ini konsep yang harus diperlakukan hati-hati. Saya minta dia membaca dulu terus, terutama bab empat yang membahas tentang Jesus sebagai Logos dalam konsep trinitas itu.
Tapi sebagai latar-belakang, saya berikan gambaran sejarah: Trinitas itu memuluskan konversi dari paganisme menuju monoteisme.
Kristen berkembang beberapa ratus tahun sebelum Islam, ketika paganisme masih sangat kuat di Romawi. Transisi yang kaku tak memungkinkan berkembangnya sistem kepercayaan baru. Orang akan resisten kalau mendadak dipaksakan pada monoteism. Trinitas adalah jembatan negosiasi antara keyakinan lama dengan keyakinan baru.
Itulah bedanya Kristen dengan Islam. Paganisme juga ada di Madinah dan terlebih lagi di Mekah (khususnya di Ka’bah) pada zaman Rasulullah, tapi jauh lebih cair dibandingkan kondisi di Romawi setengah milenium sebelumnya.
“Islam enjoyed clearer environment,” kata saya pada Perdana.
Karenanya, Islam bisa lebih tegas dalam transisi menuju monoteisme. Tapi Ka’bah, kata saya padanya, waktu itu sangat mirip seperti Pantheon di Roma, yakni tempat ibadah banyak agama, termasuk paganisme, dan tentu saja Kristen dan Yahudi. Haji dan ritualnya di Ka’bah, misalnya, adalah tradisi lintas agama.
Pemusnahan paganisme terjadi semasa Nabi Muhammad masih hidup, seperti yang dilakukan beliau dengan perintah menghancurkan semua berhala di Ka’bah saat menaklukkan Mekah.
Semua patung sisa sesembahan kaum pagan dihancurkan. Satu versi sejarah mengatakan bahwa lukisan Maryam dan Nabi Isa di Ka’bah tetap dibiarkan, dan baru lenyap ketika Ka’bah terbakar beberapa tahun setelah Rasulullah meninggal.
Saya tidak tahu seberapa paham Perdana, anak saya, anak kelas 3 SMP, tentang tema seperti itu. Tapi dia nampak manggut-manggut saat menyimak.
Diskusi harus berhenti karena kami sudah sampai di gerbang sekolah. Saya tutup obrolan dengan mengingatkan bahwa usai membaca buku itu, dia harus menghadap saya untuk ujian lisan.
“Whatttt….??!!!” anak saya pun lari masuk ke halaman sekolah.
BACA JUGA Apakah Surga Hanya untuk Orang Islam Saja? atau tulisan Abdul Gaffar Karim lainnya.
Penulis: Abdul Gaffar Karim
Editor: Ahmad Khadafi