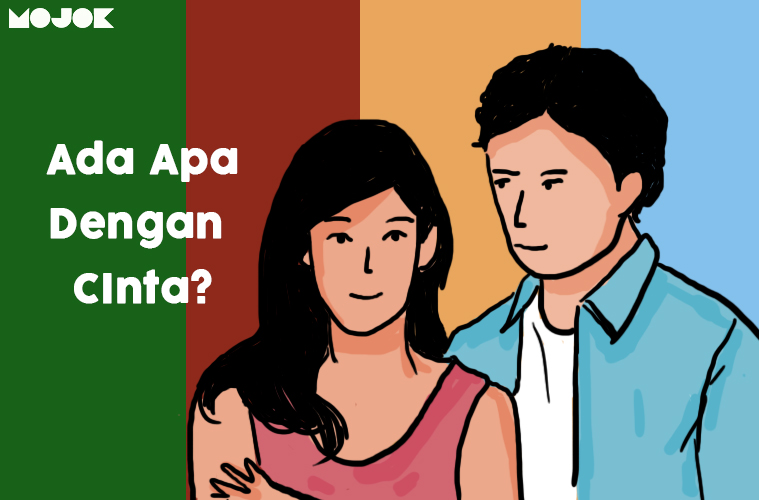Ketika AADC 2 diputar secara serempak di berbagai belahan wilayah Indonesia tanah air Cinta dan Rangga, termasuk di beberapa negara tetangga, saya sedang berada di kota Malang. Saya berniat menonton film yang sudah lama saya tunggu itu di bumi Kera Ngalam itu.
Hari pertama, saya gagal mendapatkan tiket. Semua ludes. Hari kedua, saya gagal pakai total. Ludes lagi. Akhirnya saya menyerah. Mungkin saya akan menonton di Yogya saja. Kepada seorang sahabat yang saya minta untuk mencarikan tiket AADC 2 di Malang, saya cuma bilang:
“Kamu itu mahasiswa progresif, ganteng, kuliah di Unibraw, HMI, Romanista, suporter Persegres, brewokan, jomblo, pokoknya sempurnalah kamu sebagai cowok keren. Tapi kekuranganmu hanya satu: cari tiket AADC 2 saja enggak dapat…”
Untuk menghibur diri, saya akhirnya memikirkan kalimat ngeles yang paling jitu: Biarlah massa rakjat yang berbondong-bondong duluan menonton AADC 2, sementara Kepala Suku menonton belakangan. Tut wuri handayani.
Ketika perjalanan saya sampai di kota Jember, hal pertama yang saya tanyakan kepada kedua kawan yang menjumpai saya adalah apakah AADC 2 diputar di Jember?
Jawabannya melegakan. “Diputar, Mas.”
Tapi kalimat selanjutnya menyesakkan dada, “Kira-kira dua bulan lagi baru diputar di sini.”
Sungguh dua kalimat diiringi jeda yang jancuk sekali.
Tapi Tuhan bersama seorang anak manusia yang disayanginya. Ketika hari keempat saya berada di kota penghasil tembakau terbanyak di Jawa Timur ini, saya mampir ke sebuah kedai kopi. Segera saya akrab dengan pemilik kedai kopi tersebut. Orangnya ramah dan jenaka. Saat saya singgung ingin menonton AADC 2, tiba-tiba dia menyahut:
“Siapa bilang AADC 2 tidak diputar di Jember? Kalau Sampeyan mau menonton, titip ke pegawai saya. Pacar pegawai saya tukang melayani pembelian tiket di bioskop Jember.”
Tanpa banyak ngomong segera saya pesan 4 tiket. Tentu bukan untuk saya sendiri. Saya menonton bersama tiga teman yang lain, termasuk dengan Cak Bebe, pemilik kedai kopi yang baik hati, ramah, dan jenaka itu.
Keesokan sorenya, saya sudah nongkrong menunggu giliran menonton. Saya mencoba mencubit pipi saya. Oh, sakit. Berarti tidak sedang bermimpi.
Di saat itulah, saya teringat semua ulasan, komentar, dan berbagai pendapat teman-teman saya yang sudah menonton AADC. Hampir semua mengatakan jelek. Ada yang berterus terang seperti Eddward S Kennedy, ada juga yang malu-malu. Ada pula yang mau mengkritik tapi terlalu rumit. Dibungkus ini-itu, muter-muter enggak karuan, hanya untuk bilang jelek. Seorang kenalan saya, cukup lugas saat saya tanya komentar dia tentang film AADC 2 yang barusan dia tonton: Mirip FTV, Mas!
Tapi saya tak terpengaruh sama sekali. Saya hanya ingin menonton.
Begitu masuk ke dalam gedung bioskop, saya merasa waktu dilempar ke belakang. Di bangku belakang saya, sepasang suami-istri mengajak menonton dua anak kecil seumuran Kali, anak saya yang sebentar lagi merayakan ulang tahun keempat. Mereka berdua bermain kejar-kejaran. Bunyi hape beberapa kali terdengar. Orang-orang sibuk menelepon dan ditelepon. Tapi saya tidak merasa terganggu sama sekali.
Saya melalui masa remaja di Rembang, sebuah kota kecil di Pantura. Sewaktu saya SMA, saya rajin menonton film. Film yang diputar adalah film-film India dan Hongkong. Penontonnya menyenangkan. Mereka bisa memanggil tukang mie ayam lalu memesan. Jadi sepanjang film diputar, penjual mie ayam hilir mudik. Kalau filmnya macet, atau adegannya menarik, para penonton bersorak-sorai. Melempar sandal ke arah layar adalah hal biasa. Terutama jika tokoh antagonisnya sudah menyebalkan.
Entah kenapa, saya menikmati menonton dengan situasi seperti itu.
Ketika saya menonton AADC 14 tahun yang lalu di bioskop Mataram Yogya (sekarang sudah tidak ada), situasinya agak mirip. Banyak anak-anak SMA yang tidak dapat tempat, mereka duduk di lantai, dan cerewet sekali. Bahkan ada yang bawa peluit. Peluit itu dibunyikan saat Rangga dan Cinta cipokan. Bisa saya pastikan, mereka bukan hanya sekali menonton. Sebab mereka hapal betul adegan demi adegan. Situasi pikuk. Gayeng.
Apakah saya terganggu? Tidak. Tertib menonton dengan adab seperti menonton bioskop di era kiwari, saya anggap tak menarik. Penonton kurang ekspresif. Tidak ada teriakan:
“Cipok wae!”
“Sikat!”
“Pateni wae!”
Penonton sekarang hanya bersuara ketika ada yang lucu sekali, atau menjerit ketika ada yang adegan yang menakutkan sekali. Itupun tawa yang tertib, jeritan lirih yang tertahan. Supaya tetap sopan.
Film AADC 2 dimulai. Tubuh dan pikiran saya betul-betul rileks dengan situasi yang agak berisik di dalam gedung bioskop. Kedua anak kecil itu masih cekikikan. Masih ada orang yang menelepon. Masih ada beberapa hape yang terdengar berbunyi.
Semua adegan film saya ikuti. Beberapa tidak bisa saya dengar dengan baik karena kualitas audionya, plus situasi yang agak gaduh. Tapi ya tak mengapa. Asyik-asyik saja. Toh saya tak mungkin menonton hanya sekali ini saja.
Semua kritik atau komentar yang saya dengar dan baca, tak saya temukan di AADC 2. Menurut saya, film itu keren. Bagi saya, AADC 2 adalah film tentang seorang pemuda yang susah tidur dan letih jiwanya, berhubungan dengan seorang perempuan yang pura-pura bahagia.
Dialognya juga oke. Kalau ada yang agak wagu, percayalah bahwa obrolan sehari-hari kita jauh lebih wagu. Kalau obrolan di film itu sempurna, malah justru bukan film yang menarik. AADC 2 itu seperti kopi. Ketidaksempurnaannya menjadikannya menarik.
Penonton di dalam gedung juga ekspresif. Saatnya lucu ya mereka tertawa ngakak. Ketika Rangga kepergok Trian di galeri milik Cinta, seorang penonton berseru, “Ajak gelut waeee!”
Sewaktu Rangga cipokan dengan Cinta, mereka juga berkomentar lepas. “Cipokane sing suweeeee!”
Seru sekali.
Saya memang agak terganggu sedikit saat tahu di film tersebut Alya telah meninggal dunia. Ya mbok jangan meninggal lah, sakit atau apa gitu. Sekolah di luar negeri, misalnya. Kasihan dia. Tapi ya enggak apa-apa. Perasaan itu hanya sekian detik saja. Plas! Cepat berlalu dari pikiran, dan saya sudah mengikuti adegan demi adegan selanjutnya.
Saya juga sempat kepikiran yang lain saat Marzuki Mohamad menyanyi. Saya kira ada adegan dia ngobrol dengan Cinta. Terus merayu atau apa gitu, lalu dikepruk gelas. Ternyata enggak ada.
Saya terhibur dengan munculnya Pepeng, juragan Klinik Kopi. Lucu juga ternyata dia. Besok-besok dia bisa diajak gabung main Teater Gandrik. Dan saya sempat berharap, Rangga bilang, “Peng, kopi tanpa gula itu ibarat Cinta tanpa Milly. Camkan!”
Atau saat Pepeng bilang, “Just coffee!” Lalu Rangga menyahut, “Just coffee itu apanya Top Kopi?”
Film berakhir dengan mulus. Sembilan. Itu kalau saya diminta memberi nilai dengan rentang 1 s/d 10. Nyaris sempurna. Mestinya film tersebut saya beri nilai 10. Hanya saja ada kekeliruan yang agak fatal, yakni Rangga balikan sama Cinta. Sebab dengan mereka berdua balikan, rasanya itu memberi penghalang besar akan hadirnya AADC 3. Sungguh bajingan sekali, bukan?
Ketika kami berempat sudah keluar dan istirahat sejenak sambil menunggu antrean kendaraan agak sepi dari parkiran, sembari menyulut rokok, Cak Bebe berkomentar, “Mas, saya itu paling suka tokoh Mamet…”
“Kenapa, Cak?” tanya saya sambil ikut menyulut rokok.
“Kisah cintanya sederhana. Menikah dengan Milly, teman satu SMA-nya. Kebanyakan orang menyukai Rangga, padahal kisah cinta mereka itu sesederhana kisah cinta Mamet.”
Saya kemudian teringat Agus Mulyadi yang menulis artikel ‘Seandainya Saya Menjadi Rangga’. Betul juga Cak Bebe ini. Kisah cinta Agus Mulyadi kan sederhana, paling juga nanti dia menikah sama tetangganya. Ngapain dia membayangkan menjadi Rangga?
Ketika berpikir seperti itu, mendadak saya mendengar suara Cak Bebe lagi. “Menikah dengan orang kayak Milly itu asyik lho, Mas…”
“Asyik gimana, Cak?”
“Ya setiap saat kita bisa tertawa. Itu kan menyenangkan. Kalau saya, daripada pusing mikir apa arti puisi dan ngurus galeri, lebih baik tertawa bersama istri yang seperti Milly.”
Benar juga, pikir saya. Dan tiba-tiba saya teringat teman-teman saya yang berkomentar bahwa film ini tidak bagus. Mungkin mereka kurang berpikir serileks Cak Bebe.
“Tapi, saya punya kemiripan dengan Rangga, Mas…”
Sebelum saya berkomentar, Cak Bebe sudah melanjutkan omongannya. “Kami sama-sama punya warung kopi.”
“Juga sama-sama ganteng kok, Cak…” balas saja.
“Ah, Sampeyan iku isok wae, Mas…” muka Cak Bebe kemerah-merahan, tapi terlihat sangat tersanjung hingga rokok yang dipegangnya terjatuh.