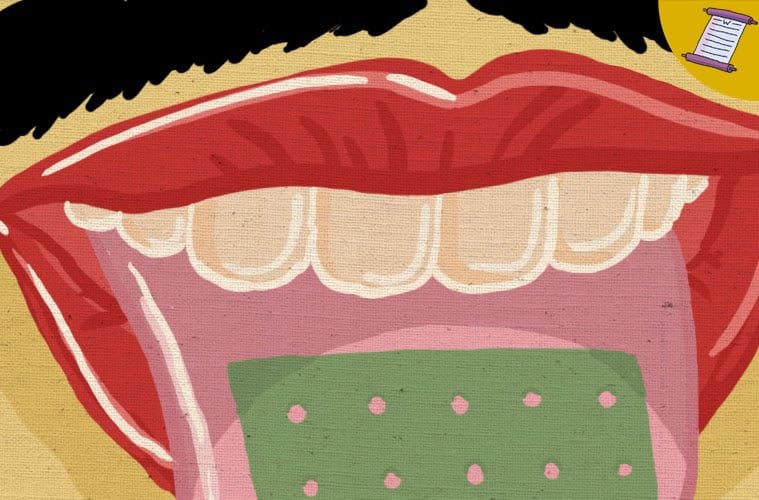MOJOK.CO – Sungguh aneh dan tidak pada tempatnya ketika Miftah Maulana, dan orang di belakangnya, tertawa karena lelucon yang melecehkan dan sama sekali tidak lucu.
Seorang dai utusan khusus presiden, Miftah Maulana, bikin jengkel warganet setelah potongan video ceramahnya viral di media sosial. Dari atas panggung megah pengajian, Miftah menegur-sapa seorang pedagang es teh dan lalu mengatainya “Goblok!” Untuk kronologi lengkap, teks verbatim, dan analisis teologis, atau bahkan meme Miftah Maulana bisa panjenengan cari dengan sangat mudah di medsos.
Yang ingin saya lencangkan di sini adalah kenapa bapak-bapak yang ada di atas panggung bersama Miftah Maulana bisa terbahak-bahak. Sementara netizen (dan saya salah satunya) terlihat getir dibuatnya. Dan, di atas itu, bagaimana humor di arena keagamaan bekerja? Apakah ia selalu menyatukan, atau justru memicu tensi sosial?
Sebelum lanjut, pertama-tama saya ingin angkat topi dulu sama sang pedagang, sebut saja Pak Pun, yang tak gentar mencari nafkah dengan menjajakkan air mineral dan es teh di tengah pengajian yang, katanya, hujan itu. Pak Pun saya kira layak dikenang sebagai man of the years di penghujung tahun paling gemoy ini.
Kuasa humor dan hal-hal lainnya
Saya belum lama ini mendaras buku David Feltmate (2024). Judulnya, Religion and Humour: An Introduction. Kata dia, humor dalam konteks agama memiliki fungsi kompleks. Bukan saja menjadi alat penguat komunitas, humor juga sering menciptakan ketegangan. Khususnya jika konteksnya tidak dipahami secara universal.
Nah, lepas dari teknik framing yang dilakukan oleh ngab-ngab kameramen dan/atau siapa saja yang pertama kali memotong-unggah ke internet, kasus video viral ceramah Miftah Maulana adalah satu contoh bagaimana humor keagamaan gagal menjangkau audiens lintas-batas.
Memang, humor di dalam dirinya tidak pernah sepenuhnya netral. Dalam format religius, humor bahkan sering digunakan untuk menegaskan (atau justru menantang) hierarki kekuasaan. Jika panjenengan akrab dengan literatur tentang kisah Abu Nawas, misalnya, maka mudah saja kita mengidentifikasi bagaimana humor bisa menjadi medium yang kuat.
Masalahnya adalah Miftah Maulana, sebagai figur yang secara simbolik punya “otoritas” keagamaan, mengendalikan narasi di panggung secara penuh. Sementara Pak Pun? Ya, kita bahkan tak perlu berdebat jika mujahid es teh itu seolah hanya menjadi “subjek pasif” dalam rangkaian adegan majelis pengajian tersebut.
Dan, ketika “lelucon” itu pecah, ditandai gelak tawa bapak-bapak di sebelah Miftah Maulana, itu lebih merefleksikan legitimasi sosial yang diberikan kepada Miftah daripada keberterimaan universal dari lelucon itu sendiri.
Baca halaman selanjutnya: Lelucon yang sungguh tidak lucu, malah menyakiti.
Dominasi Miftah Maulana sebagai penceramah
Lebih dari itu, yang sedang diperagakan Miftah itu dalam praktiknya justru mencerminkan dinamika dominasi. Pelawak (dalam hal ini pemuka agama), memanfaatkan posisinya untuk memperkuat kontrol simbolik atas audiens. Mengapa?
“Sebab panggung keagamaan adalah ruang di mana “modal simbolik” berperan penting,” begitu kira-kira ceramah Gus Pierre Bourdieu (1993) dalam buku The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature, Bab 1. Nah, itulah kenapa ketika humor Miftah Maulana dipindah ke dunia maya tanpa konteks panggung dan nuansa lokal yang menyertainya, ketimpangan kuasa ini menjadi lebih mencolok dan justru mengundang kritik.
Selain itu, watak media sosial sendiri cenderung menciptakan medan baru bagi humor keagamaan. Feltmate, yang di awal tulisan ini bukunya saya rujuk, menunjukkan bahwa humor religius ketika dilepaskan dari konteks lokalnya sering berubah jadi bahan perdebatan moral.
Jadi kalau misalnya Miftah atau timnya bertanya-tanya kenapa viral, maka jawabannya adalah karena dunia maya tidak hanya berisi jemaahnya saja. Media sosial juga menghadirkan audiens dari beragam latar belakang yang tidak selalu memahami konteks budaya atau norma komunitas tempat lelucon itu berasal atau dilontarkan.
Humor itu selalu milik audiens global, bukan peserta ceramah saja
Fenomena ini sejalan dengan konsep global village McLuhan (1964) di mana digitalisasi menciptakan ruang komunikasi global yang simultan. Dalam ruang ini, humor tak lagi hanya milik audiens lokal, tetapi menjadi konsumsi global dengan segala risiko misinterpretasi dan kritik.
Miftah Maulana, dengan demikian, mestinya bisa lebih peka bahwa dakwah di panggung keagamaan yang disponsori oleh kekuasaan itu peluangnya lebih menggelincirkan. Di sana, ada ratusan atau ribuan kamera yang siap menerkam dan memamahnya kapan saja.
Oke, mungkin pihak Miftah Maulana bisa saja berkilah bahwa leluconnya dimaksudkan sebagai humor ringan. Atau, bisa juga alasannya adalah karena gaya dakwah Miftah selama ini memang terlihat spontan, termasuk dalam hal bercanda. Dan, toh, Miftah pada akhirnya memborong es teh dari penjual yang telah diolok-olok sebelumnya.
Humor dalam Islam yang saya kenal
Tapi begini ya jamaah Miftah Maulana rahimakumullah. Humor jenis apa yang dimaksudkan untuk menghibur tapi justru menimbulkan rasa getir? Bukankah humor religius seharusnya mencerminkan nilai-nilai agama itu sendiri?
Saya memang tidak cukup punya kapasitas untuk bicara Islam. Namun, Islam yang saya kenal adalah Islam dengan nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kasih sayang, dan keberpihakkan terhadap mustadh’afin yang seharusnya menjadi kompas moral dalam setiap tindak-tanduk humor. Maka ketika humor kehilangan nilai-nilai ini, ia bukan hanya gagal menyampaikan pesan moral, tetapi juga merusak citra agama itu sendiri.
Lepas dari ontran-ontran ceramah Miftah Maulana, sekali lagi, saya ingin sampaikan salam respect kepada Pak Pun. Saya tidak tahu persis betapa struggling-nya kehidupan Pak Pun dan seberapa jauh dia pernah dilemparkan badai, tapi kalau mengutip Iwan Fals dalam “Nyanyian Jiwa”… nyatanya Pak Pun tetap berdiri!!! Tegar, Pak!
Penulis: Anwar Kurniawan
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Gus Miftah Ajak Selawatan Pemandu Karaoke di Klub Malam dan analisis menarik lainnya di rubrik ESAI.