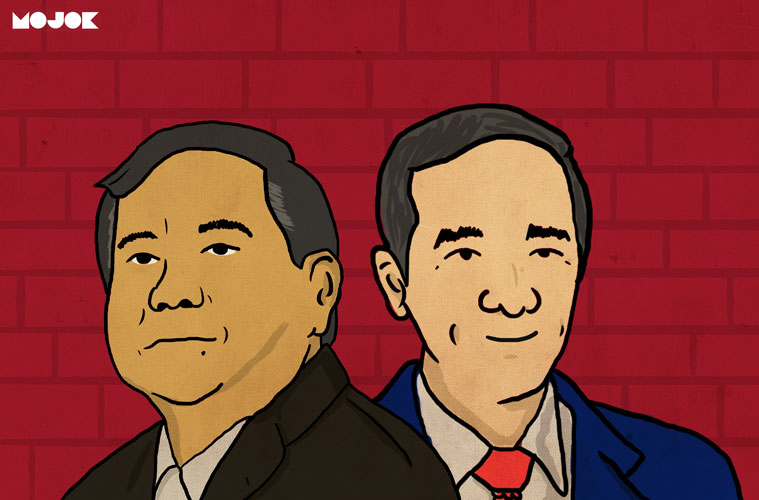[MOJOK.CO] “Jika Jokowi dan Prabowo maju di 2019, yang itu hampir bisa dipastikan, mereka tak bisa dan sebaiknya tidak mengulang strategi lama mereka di 2014.”
Hampir pasti Prabowo bakal berhadapan lagi dengan Jokowi di pilpres 2019. Kali ini situasinya sama sekali berbeda dengan situasi sosial pada laga pertama tahun 2014 lalu.
Pengantar paling panas laga ini adalah gelaran pilgub DKI yang akhirnya mengantarkan Anies Baswedan sebagai gubernur terpilih dengan mengandaskan Ahok. Sisa dentang lonceng usai pertandingan masih berdenging sampai hari ini. Dan pengantar kedua bersiap menyambut: pilkada serentak tahun 2018 yang tidak akan lama lagi digelar.
Lewat dua pemanasan itu, kondisi sosial masyarakat Indonesia tentu saja dalam situasi panas yang berlebihan. Dalam situasi panas yang berlebihan itu, jika tarung ulang Jokowi vs Prabowo tidak digelar dengan cerdik dan menarik, besar potensinya akan terjadi dehidrasi dan keletihan psikis pada masyarakat pemilih. Konsekuensi politiknya bisa buruk: pertama, politik irasional lebih utama. Atau yang kedua, masyarakat makin apolitis.
Mari kita lihat lebih jauh lagi. Ada beberapa hal yang mesti dilihat dengan jeli. Hampir bisa dipastikan dari sisi isu, dua kubu akan menggotong isu yang sama baik ketika pilpres 2014 maupun pilgub DKI 2017 lalu. Di kubu pendukung Prabowo, isu agama dan PKI akan tetap dominan. Sementara kubu pendukung Jokowi akan tetap mengusung isu kebinekaan dan HAM.
Tapi, sebetulnya isu itu justru akan merugikan pihak masing-masing. Isu agama misalnya, tidak bisa dipakai untuk menghajar Jokowi sebab Jokowi beragama Islam. Bahkan bukan hanya memeluk agama Islam, dia sejak dulu dikenal sebagai seorang muslim yang taat. Mau dipojokkan seperti apa pun, isu ini tidak akan membuat Jokowi kepepet. Isu PKI juga sudah terbukti tidak bisa dipakai untuk menjegal Jokowi. Pada tahun 2014 isu itu sudah digunakan dan terbukti gagal. Hanya ketololanlah jika kedua isu ini dipakai lagi oleh pendukung Prabowo.
Sementara itu, isu kebinekaan yang diusung oleh pendukung Jokowi juga bakal kontraproduktif. Sebab, tangkisan atas isu ini sejak awal sudah mudah sekali dipatahkan. Klaim diri bahwa pendukung Jokowi sebagai yang pro-kebinekaan dan pluralis justru seperti menunjuk muka bahwa mereka tidak pluralis dan cenderung fasistik.
Kegagalan itu mudah sekali dilihat jejaknya dalam pilgub DKI, karena begitu mudahnya pendukung Ahok mengeksploitasi pluralisme dan kebinekaan, tapi watak politik mereka menunjukkan sebaliknya, maka lepaslah sebagian besar potensi pemilih masyarakat sipil. Isu HAM juga tidak lagi bisa dipakai untuk menghajar Prabowo. Alasannya juga mudah, selama pemerintahan Jokowi berlangsung, tidak ada upaya dari pemerintah untuk menyeret Prabowo sesuai tuduhan. Jadi, ketika diulangi lagi isu ini, bukan saja akan aus, melainkan bisa jadi bumerang bagi pendukung Jokowi.
Sekarang yang jadi masalah adalah dalam dua kutub pendukung ini, ada bagian yang gemuk di tengah. Bagian gemuk ini lebih mudah berpindah posisi dan pilihan. Sekaligus mudah terdehidrasi dan letih.
Dari berbagai survei jelas sekali. Misalnya, kenapa jarak antara persentase orang yang puas dengan kinerja Jokowi begitu jauh dengan elektabilitas Jokowi. Artinya, mereka puas dengan Jokowi tapi kalau ada pilihan yang lebih baik, mereka tidak akan memilih Jokowi lagi.
Survei itu memang tidak mungkin terjadi pada Prabowo. Sebab dia tidak sedang memimpin. Mau diuji dengan alat survei apa untuk menunjukkan tingkat kepuasan publik?
Namun, cair dan gemuknya masyarakat pemilih ke tengah itu tidak bisa dimungkiri. Sebab, ada fakta statistik lain yang terjadi pada Prabowo. Berbagai survei menunjukkan bahwa pemilih Prabowo pada tahun 2014 sudah tidak punya interes yang sama untuk memilih Prabowo lagi. Bahasa mudahnya, Prabowo juga punya kecenderungan ditinggalkan basis pemilih lamanya dengan berbagai pertimbangan.
Pada titik inilah kedua kubu harus hati-hati dalam menerapkan strategi. Artinya, akan tiba saatnya nanti, pendukung kedua kubu akan mengerucut di dua kutub yang berlawanan, tapi makin mengecil dan makin terisolasi dari masyarakat pemilih. Apalagi jika jargon dan strategi mengusung isu lama dilakukan lagi (isu agama dan PKI pada pendukung Prabowo, dan kebinekaan dan HAM pada kubu pendukung Jokowi).
Terisolasinya pendukung kedua kubu secara otomatis juga mengurung dan mengisolasi Prabowo dan Jokowi.
Kedua pendukung itu makin terisolasi lagi jika misalnya pendukung Jokowi menggunakan sentimen pembabatan dan pembungkaman suara kritis masyarakat sipil, entah itu atas nama istana, stabilitas politik, atau apa pun. Ini sudah sering terjadi. Bahkan pendukung Jokowi sendiri sudah banyak yang jengah dengan strategi seperti ini, karena pasti akan merugikan Jokowi. Ini norak sekali. Dalam bahasa verbal, “Kalau menjilat, mbok jangan berlebihan lah….”
Cara-cara merisak para aktivis, tokoh masyarakat, dan ilmuwan yang kritis terhadap Jokowi dianggap sebagai hambatan. Itu ketololan besar. Sebab dalam demokrasi elektoral, kritik tidak selalu identik dengan preferensi pemberian suara. Jokowi dikritik tapi tetap dicoblos. Tapi, kalau pendukungnya membungkam mekanisme demokratis ini, Jokowi akan ditinggalkan pendukung kritisnya. Memang tidak serta-merta suara pendukung kritis akan diberikan kepada lawan Jokowi. Tapi, absennya mereka, bakal menjadi malapetaka bagi Jokowi sebagaimana malapetaka saat pilgub DKI lalu. Barangkali pendukung Jokowi harus lebih mengenal lagi watak masyarakat sipil Indonesia, dan arti apa itu “pendukung kritis”.
Hal yang sama terjadi juga pada pendukung Prabowo. Politik identitas memang mengemuka. Tapi, Indonesia bukan Jakarta. Pilpres 2019 tidak sama dengan pilgub DKI 2017. Kalau isu agama dijadikan sajian utama, masyarakat pemilih justru makin menjauh dari Prabowo. Terlebih ada sederet kejadian yang menautkan langsung antara tidak sehatnya agama dijadikan isu politik dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Indonesia sudah tumbuh makin sehat secara intelektual. Cara-cara lama yang dikemas ulang, justru akan menghajar balik kreatornya.
Kekeliruan menerapkan strategi kedua kubu makin jelas bakal berpotensi merusak dan mengisolasi Prabowo dan Jokowi. Sementara, sampai hari ini, realitas politik hanya menunjukkan kedua calon inilah yang berpotensi besar untuk saling berhadapan. Tidak ada atau belum ada calon alternatif lain. Kalaupun toh ada, potensi terpilihnya kecil sekali.
Dan hal lain yang patut diwaspadai adalah ketika masyarakat mengalami “keletihan politik”. Sisa pertarungan pilgub DKI 2017 belum usai, disambung pilkada serentak 171 wilayah, dan dilanjutkan lagi dengan perhelatan pilpres-pileg serentak 2019.
Keletihan ini, ditambah menjauhnya masyarakat pemilih pada kutub yang berhadapan, plus luka yang makin sulit sembuh, akan menatah sekelompok besar pemilih Indonesia dalam dua pilihan yang tidak sehat: irasional dan apolitis.
Hal ini sudah mulai tampak pada berbagai penelitian via dunia medsos, orang yang terlalu banyak bicara politik elektoral akan dibisukan, di-unfollow, dan tidak disukai. Kalau hal semacam ini tidak dilihat dengan cermat, pertarungan pilpres 2019 akan rendah peminat dan tingkat destruksinya makin tinggi. Karena masyarakat apolitis dan irasional, tidak mudah dipetakan pergerakannya.
Tapi ini lagi-lagi bukan salah mereka. Mereka hanya letih saja. Dan makin letih karena menghadapi strategi norak dan lebay pendukung kedua kubu. Lebih tepatnya lagi, dipaksa menjadi letih oleh kebodohan strategi politik kedua kubu.
Mumpung masih cukup waktu, sebaiknya kreator strategi kedua pihak melakukan penyegaran tema, cara pandang, dan pola pendekatan. Sebab, Indonesia bukan hanya butuh pemilu, tapi juga butuh demokrasi yang bermutu.