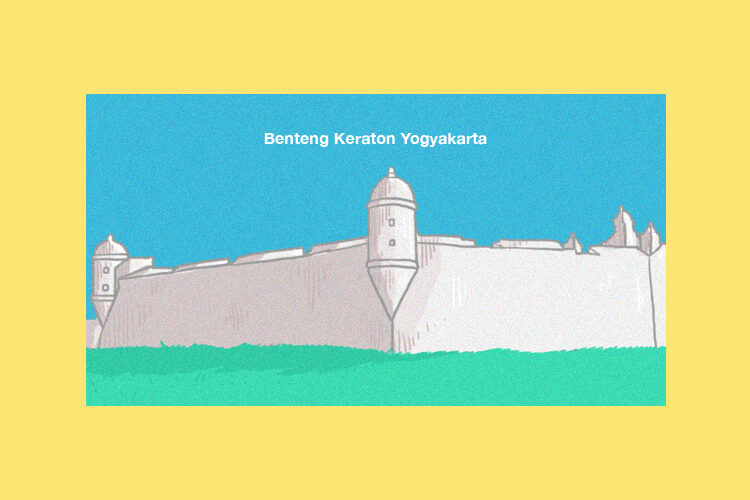MOJOK.CO – Saat 80% tetanggamu di dalam benteng Keraton Yogyakarta harus pindah, rasa sedih akan kondisi Jogja menjadi konflik batin tersendiri.
Pernah nggak, teman-teman kerjamu hampir semuanya resign dari kantor dan tidak ada yang menggantikan? Lalu, karena satu dan lain hal, kamu dan hanya sedikit orang lainnya tetap harus kerja di kantor yang perlahan mati itu?
Aktivitas harian di kantor yang semula seru, penuh dinamika dan drama, berganti dengan pemandangan orang-orang yang mengemas barang mereka lalu pergi satu per satu. Sedih, nggak?
Kira-kira itulah situasi yang saya alami di sini, beberapa minggu ini. Tapi lebih parahnya, ini bukan sebuah kantor dengan para pekerjanya yang resign. Ini soal sebuah kampung yang mayoritas warganya harus pindah.
Kondisi rumah-rumah di dalam benteng Keraton Yogyakarta
Saya tinggal di area dalam benteng Keraton Yogyakarta, berhadapan dengan rumah-rumah yang menempel dengan tembok benteng. Atas keinginan Keraton untuk merestorasi tembok, tetangga depan rumah saya yang statusnya tinggal di lahan milik Keraton itu harus pindah semua, awal bulan depan.
Supaya lebih dramatis, saya kasih gambaran situasi lingkungan khas Jogja ini dengan lebih rinci.
Rumah-rumah depan tempat saya itu ukurannya kecil. Kadang disebut rumah kios. Tidak ada halaman, lalu panjang ke belakang hanya sekitar 5 meter. Lebar ke sampingnya bervariasi. Lalu ada area publik yang hampir setiap harinya ada warung tenda mie ayam serta bakul angkringan tersohor di lingkungan benteng Keraton Yogyakarta.
Sebaliknya, rumah saya dan rumah-rumah di sebelah-sebelah saya, kanan dan kiri, luas lahannya jauh lebih besar. Bahkan lengkap dengan halaman. Tapi, jumlahnya tidak banyak.
Ada beberapa lahan kosong, lalu ada rumah-rumah yang sudah dijual dan dibeli warga luar kota (bisa ditebak mayoritas dari kota mana) yang jarang ditinggali. Di antara rumah-rumah itu ada gang-gang sempit yang di kanan-kirinya ada rumah-rumah lagi. Selain diperjualbelikan, secara umum, banyak juga rumah-rumah di sini yang sudah beralih fungsi jadi penginapan maupun tempat makan/minum.
Rutinitas kami di kampung Jogja
Setiap pagi, ada bapak-bapak dan ibu-ibu pensiunan yang nongkrong di depan rumah mereka. Mereka rajin menyapa dan ngobrol dengan warga-warga lain yang lewat. Lalu saat sore dan malam, ada anak-anak kecil bermain di jalanan serta para pemuda yang bercengkrama tentang perkembangan keseharian mereka. Sementara itu, bakul angkringan selalu siap sedia melayani warga dan pekerja yang jajannya mungkin nggak seberapa, tapi curahan hatinya tak terhingga sepanjang masa (bukan saya ya).
Kalau ada kegiatan kampung, kegiatan ibu-ibu PKK, atau saat bulan Ramadan, suasananya jauh lebih ramai lagi. Benar-benar lingkungan khas Jogja yang hidup, berwarna, dan bikin awet muda.
Namun, semua itu perlahan hilang. Hari-hari ini, pemandangan yang kerap terlihat di dalam benteng Keraton Yogyakarta adalah orang-orang yang membongkar rumahnya (mengambil pintu dan jendela untuk dipasang di rumah baru), berkemas, lalu mengangkutnya pergi. Saya membayangkan, sebulan ke depan, ketika besok rumah-rumah itu sudah kosong, orang-orangnya sudah pergi semua, lalu rumahnya dirobohkan, hingga akhirnya diganti tembok. Semua prosesnya akan terlihat di depan mata saya.
Gesekan yang terasa lumrah di dalam benteng Keraton Yogyakarta
Jangan salah. Tinggal di permukiman semi-padat seperti di dalam benteng Keraton Yogyakarta tidak sepenuhnya suka dan senang. Banyak gesekan. Kadang ada yang rasan-rasan dan bergosip, bertengkar hingga terdengar ke mana-mana. Ada juga perkara utang dan berutang, dan seterusnya. Setelah beberapa kali pembelajaran, ya anggap saja semua itu wajar. Toh kalau mau jujur juga, saya juga kadang rasan-rasan ngomongin orang, cuma nggak kenceng aja.
Lha mbok mau tinggal di permukiman elite pun pasti ada masalahnya. Misal, orang meninggal sendirian di rumahnya tapi nggak ketahuan berhari-hari karena semua orang di situ kelewat individualis. Siapa sih, warga yang semuanya serba sempurna?
Meskipun tidak berbudaya sekolektif di desa di mana ekspektasi interaksi antar warganya lebih wajib dan menyita lebih banyak waktu, urusan privasi dan sosialisasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta tetap ada tuntutan. Warga yang tinggal di lingkungan kampung idealnya bisa berpartisipasi dalam acara-acara di sini biar kenal satu-sama lain. Minimal, sesekali nongol berinteraksi. Ikut ngerumpi di angkringan kek, “menonton” kerja bakti, aktif di masjid, atau yang lain.
Kontribusi ke warga juga bisa dibantu dengan bentuk lain. Misal, halaman depan rumah saya biasa dipakai anak-anak untuk area bermain. Sementara itu, teras rumah ibu saya di sebelah sehari-harinya sudah berfungsi untuk tempat kumpul warga dan acara RW.
Kedekatan warga yang sebetulnya sangat menyenangkan
Buat orang seperti saya yang dari sononya agak individualis dan punya defisit dalam berkomunikasi, privasi dan sosialisasi ini menantang. Tapi, semua itu adalah kompromi yang dilakukan untuk bisa memperoleh manfaat tinggal di lingkungan benteng Keraton Yogyakarta.
Saya, dan khususnya ibu saya, yang notabene bukan warga asli kampung sini merasakan manfaat itu. Kalau ibu saya yang sudah lansia itu ada kenapa-kenapa, misalnya, perlu bantuan dan sebagainya, banyak tetangga yang mau bantu. Beliau pun jadi banyak teman ngobrol sehari-harinya, serta ada aktivitas tambahan supaya tetap waras.
Berbeda dengan permukiman yang lebih kelas atas yang mengandalkan kekuatan modal individu untuk keberlangsungan hidup penghuninya. Permukiman seperti di sini lebih mengandalkan kerja sama antar-warganya untuk bisa hidup tenteram (terlepas dengan segala gejolak yang ada).
Buat saya pribadi, aspek-aspek itulah yang utama, yang membuat tinggal di Jogja itu nyaman. Istimewa kalau mau dilebih-lebihkan lagi. Kalau semua itu digusur ya jadinya hambar, spiritnya hilang. Hanya bungkus dan tampilan luarnya saja yang dipasarkan sebagai “istimewa.”
Jogja yang tidak lagi sama
Rasanya kok berat ya. Saya memang bukan warga asli benteng Keraton Yogyakarta. Namun, dari kecil, saya sering datang ke sini. Saya pertama kali pindah ke Jogja tahun 1998. Saya ingat benar rasanya waktu itu.
Masih SMP, pulang sekolah naik bis kota Rp200, saya merasa bebas mampir ke mana-mana sendirian tanpa merasa khawatir. Seakan batin saya disinari matahari sore yang hangat. Saya merasa tentram dan aman. Kesederhanaan ala orang Jogja waktu itu ibarat sebuah pilihan sekaligus tujuan yang layak dikejar, dan saya bangga menjadi salah satu warganya.
Dulu, sewaktu tinggal dan kerja di Jakarta pun, sesekali pulang ke Jogja menjadi cara saya untuk kembali membumi. Saya jadi bisa rehat sejenak dari kehidupan kantor ibu kota di mana manusia benar-benar dibudayakan untuk selalu ke atas, mengejar materi dan posisi.
Sekarang situasinya jauh berbeda. Karena derasnya pariwisata apalagi gentrifikasi, orang Jogja yang bergaya hidup “sederhana” di masa kini itu bukan karena pilihan. Selain kepepet secara ekonomi, itu juga karena terhimpit mereka-mereka yang datang dan lebih punya modal. Warga setempat semakin bergantung pendapatannya pada mereka, atau pindah. Kadang saya bertanya-tanya, dulu orang Bali apa rasanya seperti ini, ya?
Rasa tentram itu semakin pudar
Semua perubahan sosial itu sebelumnya masih bisa diredam dengan suasana kehidupan kampung di dalam benteng Keraton Yogyakarta. Sekarang sudah tidak. Rasa tentram itu sudah semakin pudar.
Entahlah, mungkin saya salah dan terlalu berlebihan. Mungkin pola pikir saya usang, seperti mungkin dulu generasi sebelum saya memandang bahwa Yogyakarta versi generasi saya sudah tidak se-Jogja saat masa generasi mereka dulu.
Atau saya memang perlu berpikir untuk pindah juga? Ibarat kamu punya pasangan, lalu pasanganmu itu berubah dan sudah tidak bisa memberikanmu rasa tentram, apa yang kamu lakukan?
Tembok benteng Keraton Yogyakarta ini direstorasi katanya dalam upaya mendapatkan status warisan dunia (world heritage) dari UNESCO. Maksudnya menjadi bagian dari kawasan Historical City Centre of Yogyakarta. Ada satu sok-sok kebetulan yang sedikit lucu tentang status ini buat saya pribadi.
Ambisi mengejar sebuah status
Status world heritage sudah diberikan kepada tempat dan kota-kota di seluruh dunia sejak 1978. Meskipun demikian, ternyata ada 3 situs/kota yang statusnya dicabut karena arah pembangunan kawasannya dianggap tidak selaras dengan aslinya. Ini terakhir kejadian pada 2021 lalu, dengan kota yang dicabut statusnya adalah Liverpool, Inggris.
Liverpool mendapatkan status world heritage pada 2004 karena kontribusi pelabuhan dan maritimnya di masa lalu. Status itu dicabut pada 2021 karena pembangunan fisik kotanya seiring waktu dinilai sudah melenceng dengan banyaknya bangunan baru bergaya kontemporer.
Itu saya sebut kebetulan karena 2015 lalu saya tinggal dan studi di Liverpool sebelum pulang ke Jogja awal 2016. Kalau menilik situs web UNESCO, Historical City Centre tadi sudah terdaftar di daftar tentatif (tahap pertama atau inventarisasi) untuk nominasi status itu pada 2017.
Jadi, saya sebelumnya tinggal di kota yang status world heritage-nya kini dicabut, lalu sekarang saya tinggal di kota yang berambisi untuk mendapatkan status yang sama.
Sok-sok kebetulan, kan?
Penulis: Suryagama Harinthabima
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Tinggal di Pinggiran Kota Jogja Itu Nggak Enak dan kisah menarik lainnya di rubrik ESAI.