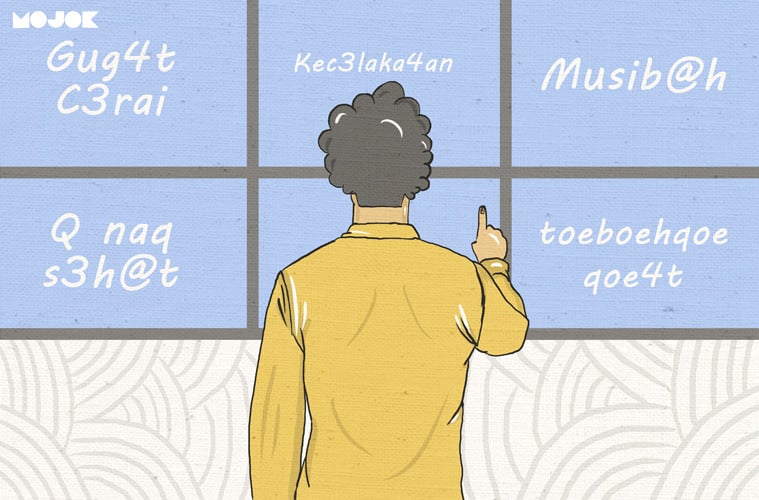Orang bisa terpesona oleh kata, entah itu lewat lisan atau tulisan. Kata-kata tak hanya dipakai untuk menyampaikan apa-apa yang tersimpan dalam hati dan pikiran, tetapi juga untuk memengaruhi orang, entah demi tujuan baik atau buruk.
Pada masa keemasan motivator, orang rela menyimak walau harus membayar mahal. Atau, kita tentu pernah mendengar ada sebagian perempuan jatuh cinta kepada penyair yang pandai merangkai kata. Tak heran muncul ungkapan, “Jika wanita bisa takluk oleh puisi, maka penyair adalah profesi yang paling buaya.”
Tetapi kata bisa berbahaya. Para tiran takut pada kekuatan kata. Kita tahu ada buku yang dilarang, atau orang dihukum mati karena menulis sesuatu. Orang bisa berkelahi dan saling bunuh karena lisan.
Kata-kata juga bisa menjadi liar saat meluncur dari lidah atau tulisan seseorang. Sebab orang lain sering menafsirkan kata-kata secara berbeda dengan maksud yang ingin disampaikan oleh pembicara, sehingga tak jarang timbul keributan. Kata-kata menjadi seperti debu ditiup angin, tafsirnya liar dan beranak-pinak sebanyak pikiran manusia yang menafsirkannya secara berbeda. Dunia menjadi bising oleh polusi kata-kata.
Karena demikian besar dampak dari daya kata-kata, Kanjeng Nabi pernah bersabda: “Keselamatan seseorang bergantung pada lisannya.”
Kini kita mungkin bertanya-tanya, mengapa orang bisa terpesona dan terpengaruh oleh kata-kata dari manusia ketimbang Firman dari Tuhan Yang Mahakuasa. Apakah daya Firman-Nya tak sekuat ucapan dan tulisan manusia?
Firman-Nya adalah salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dan memberitahukan apa-apa yang Dia kehendaki kepada manusia. Karena sumbernya adalah Yang Maha Benar dan Maha Suci, kebenaran suci ini tak bisa didekati dengan hati dan pikiran keruh atau kotor. Nabi bersabda, “Tak boleh menyentuh al-Qur’an bagi orang yang tidak punya wudu.” Wudhu itu lambang penyucian dan pembersihan. Secara lahir, kita harus wudu sebelum memegang mushaf al-Qur’an. Secara batin, kita harus wudu hati sebelum bisa menyentuh makna asli dari Firman-Nya sebagaimana yang Dia ketahui, bukan sebagaimana yang kita pikirkan.
Hati kerap keruh karena dicemari kata-kata atau tulisan buruk seperti ejekan, kebencian, dan fitnah. Sayidatuna Aisyah pernah ditegur Kanjeng Nabi ketika beliau berkata sesuatu yang merendahkan seseorang karena fisiknya. Begitu berbahayanya kata-kata buruk bagi kebersihan jiwa sehingga Kanjeng Nabi berkata kepada istrinya itu, “Engkau telah mengucapkan kata-kata yang jika dimasukkan ke dalam lautan, niscaya keruh air laut itu.”
Kalau kita membaca ayat suci dengan hati dan pikiran keruh karena hawa nafsu yang terus bergejolak, kita sesungguhnya membaca dengan pandangan yang buram. Bahkan kita kadang menyampaikan kalam Ilahi dengan menjejalkan prasangka atau kepentingan duniawi ke dalamnya, sehingga makna dari ayat suci itu bias dan berbeda dari yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Ilahi lalu dijadikan berhala baru untuk menopang berhala dalam diri kita sendiri.
Oleh karenanya, bagaimana mungkin hati yang sudah keruh bisa menerima dan dipengaruhi oleh Firman Tuhan?
Lalu bagaimana kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan dalam firman-Nya dan membuat diri kita berubah sesuai dengan kehendak-Nya? Salah satu cara menurut ulama arif adalah dengan menjadikan diri kita “buta huruf,” sebagaimana sebutan yang disematkan kepada Kanjeng Nabi, sebagai nabiyyil ummiyi.
Secara metaforis, buta huruf melambangkan keadaan di mana pikiran dan hati kita bersih dan diam (muthmainah), atau menep dalam bahasa Jawa, bersih dari prasangka, gejolak hawa-nafsu dan egoisme.
Hanya hati yang muthmainah dan pikiran jernih yang bisa mendengar suara Tuhan yang ada di balik kata. Itulah suara tanpa bunyi, sebagaimana kita sering “mendengar” suara dalam hati dan pikiran yang tak berbunyi. Ia bersuara, tetapi tak terdengar bunyinya oleh telinga kita dan orang lain.
Berusaha mendengar suara Tuhan adalah seperti usaha penulis mendapatkan inspirasi. Penulis butuh tempat tenang, di mana ia bisa berpikir dan merenung, mendengarkan hati dan pikirannya sendiri, yang lalu dituangkan ke dalam tulisan. Saat kita memasuki kondisi diam atau muthmainah, kita bukan sedang berusaha menghilangkan kemampuan untuk mendengar, tetapi justru berusaha meningkatkan kemampuan mendengarkankan suara yang lebih halus, suara tanpa bunyi. Misalnya, saat menulis dalam diam, penulis tetap bisa mendengar suara musik, sekaligus “mendengar” suara-suara hati dan pikirannya.
Tuhan bersifat mutakalliman, berbicara. Dia berbicara kepada kita melalui organ ruhani yang biasa diistilahkan sebagai qalbu, atau hati. Ucapan-Nya bukan dengan bunyi lahiriah. Suara itu amat dekat, sebab “Tuhan lebih dekat kepadamu ketimbang urat lehermu.” Suara Tuhan ini tak terdengar bila kita lebih sibuk memproduksi kata-kata kita sendiri berdasarkan hawa-nafsu.
Hawa nafsu buruk ini akan menghijab hati dari kebenaran, sehingga muatan kebenaran dari teks suci sulit memengaruhi diri kita walau kita baca setiap hari, sebab yang membaca adalah nafsu kita, bukan Tuhan “yang membacakannya” kepada kita. Jika ini terus dilakukan, nafsu akan makin pandai memanfaatkan ayat Tuhan untuk melayani kemauannya, sehingga kata-kata suci itu justru menambah kekotoran hati, seperti diperingatkan sendiri oleh Tuhan: “Dan adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, maka (firman dalam kitab suci) itu hanya akan menambah kekufuran dan kekotoran diri mereka” (at Taubah:125) atau bahkan menambah kesesatan, “Dan Qur’an yang diturunkan oleh Tuhanmu justru menambah kesesatan/kedurhakaan dan ketertutupan dari kebenaran” (al-Maidah 64).
Sebagaimana kita sejak kecil diajari untuk berbicara dengan kata-kata, barangkali ada baiknya juga kita mulai mengimbanginya dengan belajar bagaimana diam, menjadi menep pada pikiran dan hati, setidaknya selama beberapa waktu dalam sehari, agar terhindar dari polusi kata-kata yang tak perlu.
Dengan menep atau muthmainah, hati akan mampu mendengar suara Tuhan. Sehingga mudah-mudahan kita tak dimasukkan ke dalam golongan yang disebut dalam surat al-Isra ayat 100 sebagai orang yang telah “Kami segel hatinya sehingga tak bisa mendengar [suara Tuhan].”
Wa Allahu a’lam bi muradihi