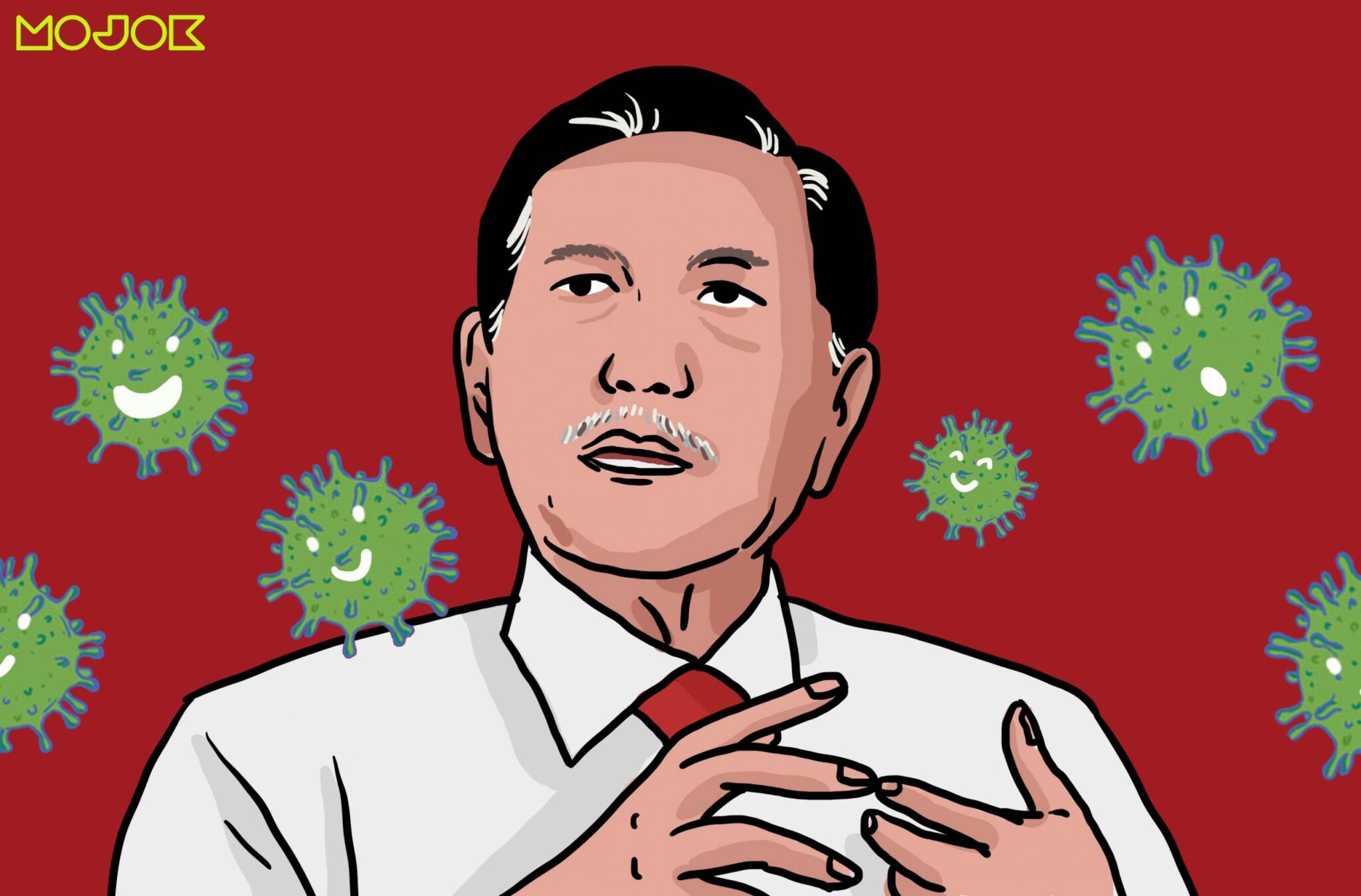MOJOK.CO – Kita sedang mengalami kecemasan yang sama. Jangan sampai ekspresi kecemasan itu justru akan membahayakan dan melukai sesama manusia.
Tidak banyak di hidup ini di mana setiap manusia punya kecemasan yang sama. Hal besar yang lazimnya sering menautkan satu orang dengan yang lainnya tentang kecemasan adalah kematian. Tapi kematian itu konsekuensi dan sekaligus ada, langsung tercipta, begitu muncul kehidupan. Karena sudah dari dulu ada, dan sudah jamak dipahami, maka kecemasan akan kematian tidak pernah lagi menjadi “kecemasan sosial”, kecemasan yang dalam satu waktu membuat orang merasakan hal yang sama, lalu merasa perlu memikirkan bersama untuk mengatasinya.
Kini di seluruh dunia, juga di Indonesia, kita punya kecemasan yang sama. Pandemi corona. Orang cemas kalau tertular, terpapar, kena, positif, lalu entah bisa bertahan entah tidak. Negara Amerika punya kecemasan yang sama dengan Prancis. Para taipan punya kecemasan yang sama dengan kelas menengah dan kaum papa.
Sebelum itu, kita hampir tidak pernah punya kecemasan seperti ini. Memang, kecemasan macam ini tidak sering terjadi dalam peradaban manusia. Bahkan karena kepentingan ekonomi dan politik, setiap kecemasan parsial dan bahkan kontroversial. Para pengusaha yang mengeksploitasi lingkungan punya kecemasan proyek bisnis mereka dilawan oleh masyarakat setempat. Sementara masyarakat setempat melawan karena punya kecemasan alam mereka rusak karena tambang atau pertanian bersekala besar. Biasanya dalam kecemasan seperti ini, energi purba manusia untuk bekerja sama akan mengalami soliditas kembali.
Memang pasti ada pertentangan-pertentangan di dalam situasi seperti ini. Buzzer politik masih bekerja dengan cara kontraproduktif, yang pasti akan dilawan oleh masyarakat kritis. Atau sengkarut kebijakan yang memantik perbedaan pendapat dan pemikiran. Bahkan di level masyarakat bawah pun, masih ada warga yang menolak jenazah positif corona untuk dimakamkan.
Dan memang tidak mudah mengelola kecemasan yang sifatnya massal. Jangankan setrategi penanggulangan, ekspresi emosi setiap orang berbeda. Ada orang yang tetap berusaha berpikir jernih, ada yang panik.
Sialnya, manajemen kecemasan yang sifatnya massal ini tidak banyak pelajarannya. Sehingga referensi perilaku manusia dalam mengatasi kecemasan dalam skala dunia ini juga minim. Ini yang tampaknya harus segera diatasi, sebab besar kemungkinan kita akan menghadapi masa puncak pandemi pada bulan Mei. Sebentar lagi. Masa yang kita tidak bisa bayangkan bagaimana reaksi orang maupun pasar. Reaksi pemerintah baik pusat maupun daerah dengan warga negara. Bahkan reaksi antar-orang dalam lingkup komunitas kecil seperti perumahan atau kampung.
Diperkirakan, jika puncak pandemi terjadi, maka akan ada situasi di mana orang yang positif terkena corona, namun dianggap sehat, akan diminta untuk melakukan swakaratina di rumah. Sebab rumah sakit penuh, juru medis dan alat kesehatan terbatas. Maka yang diprioritaskan dirawat di rumah sakit pastilah orang-orang yang sudah akut, yang membutuhkan pengawasan melekat, serta butuh bantuan peralatan medis spesifik seperti misalnya ventilator.
Masalahnya adalah jika pada orang tersebut dilakukan penerapan swakarantina di rumah, maka harus ada persiapan lingkungan yang baik. Di sini, edukasi, sosialisasi, berserta juklak dan juknisnya juga mesti jelas. Sebab jangan sampai orang yang mengidap positif corona, ketika dilakukan swakarantina di rumah, justru tidak diterima oleh tetangga dan lingkungannya. Padahal daya dukung sosial adalah kata kunci dalam melakukan protokol ini.
Orang tersebut sudah pasti harus berada di tempat yang jelas, supaya mudah diawasi dan dirawat oleh otoritas pemerintah dan kesehatan di daerah tersebut. Dia tidak boleh diusir. Mengusir orang yang kena corona sementara dia diminta swakarantina di rumah bisa sangat kontraproduktif dalam skema besar penanganan pandemi ini.
Kita tidak menerapkan lockdown, itu artinya kita masih bisa keluar dari rumah untuk keperluan yang sangat penting. Tinggal di rumah pun kita masih membutuhkan hubungan dengan orang lain, yang itu artinya potensi kita terpapar masih sangat besar. Kita semua. Karena corona tak pilih kasih. Sehingga cara paling mudah memahamkan itu dimulai dari berpikir: Bagaimana jika saya yang kena? Apakah enak diusir dari lingkungan? Apakah bisa bertahan tanpa bantuan dan daya dukung sosial?
Saya setuju dengan salah satu dokter yang diwawancara di sebuah televisi, dia bilang kurang lebih begini: Kalau belum ada anggota keluarga kita yang kena, memang belum dapat pelajaran berharga. Orang yang ngeyelan, menyepelekan, sering menolak masukan orang, memang hanya bisa belajar dari kenyataan. Lewat dirinya yang kena atau anggota keluarganya yang kena. Tapi mengasumsikan hal seperti itu mesti terjadi sungguh berat rasanya. Karena manusia dilengkapi oleh imajinasi, akal, dan perasaan, salah satu pintu masuk penyadarannya adalah cukup membayangkan saja dirinya yang kena.
Maka mulai sekarang, kita harus membicarakan hal seperti ini di keluarga kita, teman dan kerabat dalam satu kota, dan yang sangat penting adalah tetangga serta lingkungan terdekat kita.
Kita sedang mengalami kecemasan yang sama. Jangan sampai ekspresi kecemasan itu justru akan membahayakan dan melukai sesama manusia.
BACA JUGA Ketika Badai Mengamuk, dan ketika Cuaca Bersahabat dan esai Puthut EA lainnya di KEPALA SUKU.