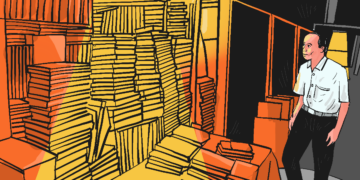MOJOK.CO – Pembeli buku yang pura-pura bodoh dan bertanya balik, “Lho bukannya gratis?” itu ada. Eksis di dunia yang fana ini. Sialnya, yang sedang ditanya itu saya.
“Minat baca masyarakat kita memang rendah, tapi minat minta buku gratis sangat tinggi,” begitu seorang teman penulis berseloroh, menggambarkan betapa antusias dan doyannya sebagian masyarakat kita saat minta buku gratisan. Bahkan, antusiasme ini mungkin lebih tinggi ketimbang minta traktir nonton bioskop, misalnya.
Biasanya hal semacam ini dialami oleh seorang penulis yang bukunya baru terbit dan melakukan promosi secara online. Di sana selalu saja ada orang nyeletuk-berkomentar: “Buat aku gratis ya,” atau, “Minta dong,” atau, “Teman sendiri masa beli,” tanpa perasaan malu. Baik orang itu kenal dekat atau hanya sebatas teman di media sosial, dan parahnya biasanya mereka adalah orang-orang yang tak punya track record yang bagus soal budaya literasi.
Dari kejadian seperti ini, rasanya tidak salah kalau saya mengambil kesimpulan sementara bahwa masyarakat kita jangan-jangan bukan tak berminat membaca. Bukan. Masyarakat kita sebenarnya punya minat baca, sayangnya tak berminat untuk beli buku.
Barangkali karena membeli buku bukan termasuk membeli barang yang pemakaiannya dikategorikan praktis semacam membeli pulsa untuk kuota internet atau membeli bedak yang bisa langsung dipakai dan efek atau manfaatnya bisa dirasakan seketika.
Saya tak tahu apa yang ada di benak orang-orang semacam ini. Mungkin ketika ada orang menerbitkan buku, mereka berpikir orang yang menerbitkan buku itu sudah otomatis berkecukupan dan mendapatkan limpahan rezeki dari bukunya secara langsung. Atau dianggap penulis tidak keluar modal sama sekali, sehingga dengan enteng meminta jatah atau mencicipi percikan karya tersebut.
Baiklah, masih mending jika penulis yang bukunya diterbitkan oleh penerbit mayor yang tak perlu rogoh kocek untuk biaya cetak—biayanya ditanggung penerbit dan penulis dapat 10 eksemplar dari penerbit sebagai bukti terbit. Nah, 10 buku yang didapatkan secara gratis itu masih bisa dibagikan secara gratis.
Kalau yang menerbitkannya pakai jalur self publishing? Yang secara teknis semua biayanya ditanggung si penulis gimana? Mulai dari membayar tukang lay out, tukang sampul, editor sampai biaya cetak. Jangankan mendapatkan untung atau balik modal, tekor sampai gulung karpet iya.
Di satu sisi, memang perlu kita mafhum—meski ucapan meminta buku gratis itu kadang menyakitkan—atas keawaman beberapa orang mengenai fakta di balik proses sebuah buku diterbitkan.
Bahwa untuk mengembalikan modal satu buku yang diberikan secara gratis, seorang penulis harus menjual beberapa eksemplar buku. Itu merupakan perkara yang sangat perlu bagi pembaca-pembaca buku gratisan ini.
Atau mungkin mereka berkaca pada kesuksesan penulis-penulis yang tajir dari karyanya. Katakanlah macam Tere Liye, Habiburrahman El Shirazy, atau Andrea Hirata yang konon dengan royalti bukunya bisa untuk beli es cendol buat berenang keluarga satu kelurahan. Oke deh, mereka ini pengecualian. Lah, bagaimana dengan penulis buku puisi atau penyair yang nggak laku-laku amat karyanya?
Padahal buku puisi merupakan salah satu buku yang agak sulit diperdagangkan. Dalam arti bukan barang yang bisa dijadikan komoditas dan nilai jualnya bisa begitu populer layaknya novel atau kumpulan cerpen. Kalaupun ada yang laku keras, saya kira tidak banyak buku puisi yang bisa selaku genre buku lainnya.
Saya sendiri tahu ada banyak sekali penyair yang tertatih-tatih dalam menjual buku puisinya, terutama yang dijual secara pribadi baik online maupun offline, atau melalui acara-acara bedah buku. Bagi buku puisi, laku 300 eksemplar itu sudah masuk kategori karomah. Itu pun tidak dalam jangka waktu yang pendek semisal seminggu atau sebulan. Kalau buku puisi hanya laku 70 eksemplar dan yang minta gratisan 80 orang, apa tidak bolong modalnya, Pak Eko?
Soal menjual buku karya sendiri secara online saya punya pengalaman sendiri. Selain sering menerima celetukan “minta gratis”, buku saya beberapa kali dibeli orang tapi tidak dibayar. Dibeli tapi tidak dibayar artinya gratis, hanya saja narasinya “membeli”.
Dalam menjual buku sendiri secara online, saya mengikuti cara beberapa teman penulis dalam proses transaksinya. Ketika saya promosi buku di Facebook, Instagram atau Twitter lalu mendapat tanggapan ada orang yang berminat dan mau membeli, biasanya saya langsung chat via inbox untuk menanyakan alamatnya sekaligus memberi harga buku beserta ongkos kirimnya.
Lalu saya kirim buku ke alamat yang sudah diberikan itu. Saya tak pernah meminta buku saya untuk dibayar duluan atau si pembeli mentransfer uang terlebih dahulu seperti halnya transaksi online umumnya. Saya pikir ini cara menjual buku sendiri yang paling ramah dan bersahabat. Baru kemudian setelah si pembeli mengabarkan bukunya sudah sampai atau ketika saya cek online di website jasa pengiriman barang buku sudah diterima, saya hubungi kembali si pembeli dan memberikan foto nota pembayaran.
Orang yang paham biasanya langsung menanyakan nomor rekening saya. Tapi tentu ada juga pura-pura bodoh dan bertanya balik, “Lho bukannya gratis?”
Saya jawab, saya sedang jualan dan itu sudah jelas sejak saya promosi sampai saat saya inbox. Dia masih ngeyel dengan jawaban, “Si Anu juga dapat ‘kan?”—kebetulan memang ada seorang tokoh publik yang berfoto dengan buku saya dan saya posting di media sosial.
“Si Anu juga membeli,” kata saya. Tapi karena memang dasarnya mungkin bermental gratisan, dia tak menjawab lagi inbox saya dan juga tidak transfer uang.
Ada pula yang meminta dikirimi buku secara gratis dengan modus ingin mengulas atau bikin resensinya. Namun karena saya tahu itu memang cuma modus, maka meskipun buku sudah dikirim tentu ulasannya tak muncul-muncul juga. Oqe, baeqla~
Cerita ini adalah bagian dukanya menjual buku sendiri secara online. Sedangkan bagian menyenangkannya tentu ada juga, meski nggak sering. Yah, namanya juga suka-duka, maka selalu beriringan.
Misal, ketika menjual buku seringkali saya menerima uang pembayaran “yang tidak-tidak”. Beberapa dari teman yang saya kenal, beberapa dari yang sebatas saya kenal. Ketika membeli satu eksemplar buku yang harganya 40 ribu sekian rupiah beserta ongkos kirimnya, tak jarang ada yang mentransfer duit sampai dua ratus ribu rupiah.
Tentu saja saya keberatan dengan transaksi macam ini. Saya komplain ketika mereka menunjukkan bukti transfernya, namun malah dijawab, “Itu rezekimu. Terima saja.”
Wah, saya bisa apa, selain mengucapkan terima kasih? Lalu berpikir, mungkin ini gantinya buku-buku saya yang sudah kadung kena tipu gratisan.
Namun tentu ada pula yang tidak saya beratkan, karena memang ada yang tak menunjukkan bukti transfer, tapi di kemudian hari ketika saya cek buku tabungan, tiba-tiba sudah ada rekam transfer di luar ketentuan saya atas harga buku yang saya jual. Lagi-lagi saya tak bisa berbuat apa-apa karena sudah lupa siapa yang bertransaksi di hari atau tanggal sekian.
Saya pikir pengalaman menjual buku karya sendiri juga dialami oleh banyak penulis lainnya. Saya tahu, adalah hak setiap manusia untuk mendapatkan bacaan yang bermutu, hanya saja jangan lupakan juga hak penulis yang mau bersusah payah melakukan riset, belajar menulis bertahun-tahun, lalu memproses penerbitan bukunya sendiri dari nol sampai jatuh ke tangan pembaca.
Kalau kita tidak bisa menghargai buku orang secara intelektual atau pemikiran (dengan mengulasnya atau mendiskusikannya), setidaknya hargailah jerih payahnya dengan membeli bukunya—atau sekalian tidak sama sekali tanpa nyeletuk “gratis”—toh, penulis setidaknya juga butuh uang rokok atau kopi selama proses menulis.
Budaya membaca itu memang penting, tapi budaya membeli buku jauh lebih penting lagi. Sebab kalau semakin banyak orang yang membayar pakai “lah, bukannya gratis?”, mana bisa buku diproduksi? Lalu kalian mau baca apa kalau buku sudah tidak bisa lagi diproduksi? Daun?