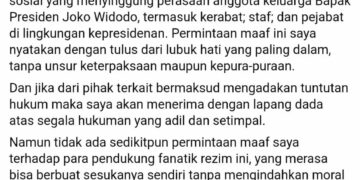MOJOK.CO – “Lafal Allah itu jangan ditulis di sembarang tempat begitu. Nggak sopan,” kata kakak saya, kemudian meminta kaos saya yang ada lafal Allah-nya untuk… “Bakar aja.”
Saat kecil dan belajar menulis aksara arab, kata pertama yang saya bisa tulis adalah lafal “Allah”. Menggunakan spidol snowman permanen saya belajar kali pertama menuliskannya di balik kertas HVS bekas revisi-revisi skripsi kakak saya.
Bukan, bukan saya mau pamer sok religius, hanya saja bagi saya saat kecil, tulisan “Allah” menggunakan aksara arab itu mudah sekali diingat. Barangkali alasannya sederhana, karena menulis tulisan Arab bagi saya yang masih Sekolah Dasar itu seperti aktivitas menggambar, maka saya lebih mudah mengingat “gambarnya” ketimbang kombinasi hurufnya. Dan “gambar” aksara Allah adalah yang paling sederhana yang saya tahu untuk ditulis saat itu.
Selain kesederhanaannya, kebetulan di sekitar lingkungan saya kata “Allah” sangat mudah ditemui. Hal ini juga saya duga menjadi stimulus secara langsung kenapa aksara ini selalu diingat saya kala anak-anak. Lah gimana? Di masjid dekat rumah ada, di ruang musala rumah juga ada, bahkan di ruang tamu ada. Hampir di setiap sudut rumah saya (kecuali kamar mandi) ada kaligrafi ini.
Selain kata “Allah”, kata “Muhammad” juga sering saya temui. Namun, saat kecil saya agak kesulitan mengingat kombinasi huruf hijaiyahnya yang sedikit rumit untuk ditulis. Jadi saya kemudian lebih memilih selalu menulis kata “Allah” saja.
Pada perkembangannya, tidak hanya di kertas atau buku-buku pelajaran saya—dengan corat-coret—coba-coba bikin tanda tangan saya menulis lafal “Allah” ini, tapi juga di tembok kamar bahkan sampai di salah satu kaos kesayangan saya. Tentu hal ini saya lakukan bukan untuk gagah-gagahan, tapi sekedar merasa suka saja menemukan mainan baru.
Seperti kalau kamu baru pertama kali bisa membaca saat anak-anak, lalu tiba-tiba semua yang ada kalimatnya selalu ingin dibaca. Nggak di koran nggak di balik bungkus mi instan. Gatal saja rasanya kalau ada sebuah tulisan yang luput belum kamu baca saat itu. Kemampuan baru yang diperoleh memang selalu ingin dijajal di mana pun tempatnya berada.
Sampai kemudian saya ditegur oleh kakak saya. Saya tidak begitu ingat kalimatnya, tapi kira-kira begini, “Hati-hati loh, Dek, nulis-nulis gitu. Apalagi nulis di kaos segala.”
Saya yang masih kecil tidak mengerti. Kenapa masalah? Ini kan nama Tuhan? Masa tidak boleh menulis nama Tuhan di mana-mana?
Lalu kakak saya memberi penjelasan, “Lafal Allah itu jangan ditulis di sembarang tempat begitu. Kan nggak sopan kalau misalnya kamu pakai kaos terus ke kamar mandi atau waktu kaosmu jatuh di bawah nggak sengaja sampai diinjak. Nggak elok itu. Masa nama Tuhan diinjak-injak?” kata kakak saya.
Saya saat itu tentu tidak begitu mengerti maksud nasihat kakak saya. Pertanyaan-pertanyaan nakal pun muncul di kepala, lah memang kenapa kalau saya masuk ke kamar mandi pakai kaos lafal Allah? Emang Allah nggak ada di kamar mandi juga? Kan Allah ada di mana-mana? Masa iya waktu di kamar mandi Allah nggak tahu kita lagi ngapain? Ya kan itu nggak mungkin banget?
Tentu pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada satu pun yang keluar dari mulut saya. Ya maklum, bisa kena gampar kakak saya kalau saya keceplosan bertanya seperti itu.
“Terus ini diapain?” tanya saya sambil menunjukkan kaos kesayangan saya yang ada nama Allah di situ.
“Dihapus lah,” kata kakak saya.
“Ya nggak bisa lah, ini kan spidol permanen gimana sih? Kowe pekok opo piye sih?” jawab saya.
“Ya sudah dibakar saja,” kata kakak saya enteng.
Mendengarnya tentu saya semakin heran. “Kakak ini gimana sih, katanya lafal Allah nggak boleh dibawa masuk ke kamar mandi, nggak boleh diinjak, ini kenapa malah boleh dibakar?” tanya saya saat itu.
Katanya kemudian, dibakar jadi pilihan karena cuma itu satu-satunya cara untuk membinasakan kaos kesayangan saya yang ada lafal “Allah”-nya. Katanya sih diniatkan untuk menjaga kesucian nama Tuhan saja, nggak lebih.
Tentu tidak cuma kaos saya yang akhirnya dibakar, tapi kertas-kertas yang saya gunakan untuk “berlatih” menulis lafal “Allah” pun dibakar semuanya.
Namanya juga anak-anak, diminta bakar-bakaran tentu saya senang bukan kepalang. Jika biasanya saya dilarang main api, eh saat itu saya malah diminta untuk “main” api. Saya bakar itu semua dengan riang gembira. Tapi tentu ada yang mengganjal, ini kan kaos kesayangan saya, masa mau dibakar begitu saja? Kan eman-eman rasanya?
Tapi demi nurut biar nggak dosa (dulu saya mikirnya gitu) ya akhirnya saya harus ikhlaskan kaos kesayangan saya itu ikut dibakar jadi abu.
Sampai masalah kemudian muncul masalah usai main bakar-bakaran itu.
“Lah ini yang di tembok kamar gimana? Dibakar juga?” tanya saya penuh harap. Wah lumayan nih bisa main bakar-bakaran di dalam rumah.
“Ya nggak perlu lah. Sini aku ajarin,” kata kakak saya.
Diambilnya spidol snowman lalu dicoret-coretlah itu tembok yang ada lafal Allah. Dicoret-coret sampai cuma terlihat blok hitam saja. Lafal “Allah” jadi tidak terlihat sama sekali.
Melihat itu saya bengong.
“Lah kenapa?” tanya kakak saya nggak merasa berdosa.
“Tahu gitu, kenapa tadi kaos saya nggak dicoret-coret aja?”
Usai saya bertanya begitu, kakak saya lalu kabur. Tawa kencang lalu terdengar dari luar kamar. Saya jengkel luar biasa dikerjai seperti itu. Ada rasa dendam yang tak bisa saya tahan. Lalu apa yang saya lakukan? Tentu saja mengadu ke otoritas tertinggi dalam keluarga saya: orang tua.
Orang tua saya lalu marah luar biasa mendengar aduan saya. Apalagi dengan beberapa tambahan-tambahan yang saya karang agar orang tua saya semakin marah ke kakak saya. Bisa ditebak kemudian, kakak saya lalu dihukum.
Bukan soal dibakarnya lafal Allah tentu saja, tapi lebih ke alasan sederhana karena harga kaos itu mahal dan benar-benar bagus. Bakar kaos orang itu mubazir meski hanya untuk dipakai bercanda.
Dan saya?
Melihat kakak saya dihukum, saya jadi menyesali perbuatan saya karena jadi tukang ngadu dan membiarkan amarah sempat menguasai diri saya. Tapi kalau diingat kembali, puas saja rasanya ketika kemarahan saya bisa terlampiaskan dengan hukuman yang diterima kakak saya.
Saat itu saya baru sadar, kalau ada yang lebih sulit dari meminta maaf: yakni memaafkan orang sebelum orang yang bersalah itu mau meminta maaf. Karena kalau sedang marah, sering kali dendam jadi jauh lebih nikmat rasanya ketimbang santapan pertama berbuka puasa.