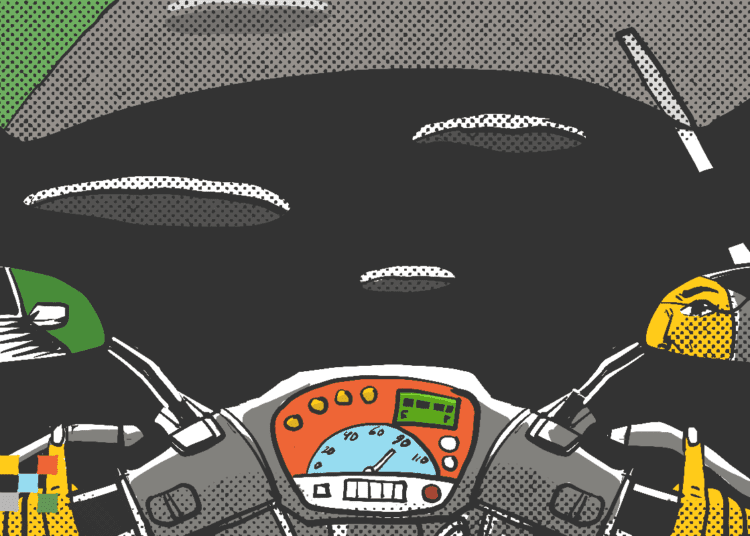Jika ada kompetisi kota mana yang paling sering bikin iri para pencari kerja di grup Facebook “Loker Se-Jabodetabek”, Karawang pasti juara bertahan. Bagaimana tidak? Di saat sobat misqueen di Jogja harus bertarung nyawa demi UMR dua koma sekian juta, buruh di Karawang bisa ongkang-ongkang kaki dengan UMK yang tembus Rp5,2 juta lebih. Angka yang fantastis, bukan?
Dari luar, Karawang tampak seperti tanah perjanjian. The Promised Land. Kota industri di mana cerobong asap mengepulkan uang, dan setiap pagi ribuan bus jemputan karyawan memadati jalanan seperti arak-arakan semut yang menggotong remah emas.
Orang luar melihat warga Karawang itu hidupnya santai, makmur, dan hedon. Lihat saja motor-motornya, minimal NMAX atau PCX. Lihat gaya outfit mbak-mbak pabriknya yang kalau pulang kerja wanginya bisa tercium dari radius satu kilometer. Sekilas, tidak ada penderitaan di kota lumbung padi yang kini jadi lumbung pabrik ini.
Tapi, izinkan saya—sebagai saksi mata yang dulu pernah merantau dan hidup di tengah hiruk-pikuk kota industri ini—untuk tertawa getir. Hahaha. Preeet.
Kalian tidak tahu saja, di balik wajah “santai” dan label “UMK Sultan” itu, warga Karawang (terutama penduduk lokal dan perantau yang tak punya ‘orang dalem’) sebenarnya sedang melakukan atraksi sirkus paling berbahaya: bertahan hidup di tengah biaya hidup yang mencekik dan sistem rekrutmen kerja yang bajingan.
Mitos UMK Sultan dan Realitas “Wani Piro”
Mari kita bedah mitos terbesarnya: gaji gede.
Benar, UMK Karawang itu tinggi. Tapi, pertanyaan kuncinya adalah: Emangnya gampang masuk pabrik di sini?
Bagi kalian fresh graduate yang polos, yang berpikir bahwa bermodal ijazah SMK nilai rata-rata 8,0 dan SKCK bersih sudah cukup untuk melamar kerja di kawasan KIIC atau Suryacipta, saya ucapkan: Selamat datang di dunia nyata, Dek.
Di Karawang, skill nomor satu bukanlah kemampuan mengoperasikan mesin bubut atau kemampuan administrasi, melainkan kemampuan negosiasi dengan “Yayasan” atau “Calo”.
Sudah menjadi rahasia umum yang baunya lebih busuk dari limbah Citarum, bahwa untuk masuk pabrik bonafide di sini, ada “uang admin” yang harus disetor. Harganya? Bervariasi. Mulai dari 5 juta sampai 10 juta rupiah. Itu pun kontraknya kadang cuma 6 bulan atau setahun.
Coba hitung pakai kalkulator beras. Kamu bayar nyogok 8 juta. Gaji 5 juta. Dua bulan pertama gajimu habis cuma buat balik modal nyogok. Bulan ketiga baru bisa napas. Bulan keenam? Kontrak habis. Terus harus nyogok lagi buat perpanjang atau pindah PT.
Siklus setan ini berputar terus. Warga Karawang yang kalian lihat nongkrong santai di warung kopi itu, sebagian besar bukan sedang menikmati hidup. Mereka sedang pusing tujuh keliling mencari pinjaman buat nyogok masuk kerja lagi. Mereka terlihat santai karena memang sudah hopeless. Mau marah, tapi lawannya sistem. Mau nangis, tapi malu sama tetangga.
Jadi, kalau ada warga lokal yang nganggur di teras rumah sambil ngerokok, jangan dituduh malas. Mereka itu korban dari sistem rekrutmen jalur “Wani Piro” yang menguasai kota ini.
Jebakan biaya hidup Karawang yang menipu
Efek samping dari label “Kota UMK Tertinggi” adalah harga barang yang ikut-ikutan naik haji.
Tukang nasi uduk, tukang kontrakan, sampai tukang parkir di Karawang punya pola pikir sederhana: “Ah, yang beli kan anak PT, duitnya banyak.”
Akibatnya, harga pecel lele di pinggir jalan Karawang kadang bisa bersaing dengan harga makanan di food court mall Jakarta. Sewa kontrakan petakan yang lembap dan minim ventilasi harganya bisa sejuta lebih. Biaya hidup di sini tidak semurah di Jawa Tengah atau Jawa Timur, Lur.
Bagi mereka yang beneran kerja di pabrik Astra atau Toyota, mungkin nggak masalah. Tapi bagaimana dengan warga lokal yang kerjanya serabutan? Bagaimana dengan buruh toko yang gajinya jauh di bawah UMK?
Mereka terjepit. Mereka dipaksa hidup dengan standar harga “kota industri” tapi dengan pendapatan “kecamatan”. Makanya, jangan heran kalau melihat gaya hidup orang sini agak timpang. Motornya baru (kredit), HP-nya iPhone (kredit), tapi makannya mie instan di kamar kos yang panasnya kayak simulasi neraka bocor. Itu bukan gaya-gayaan, itu mekanisme pertahanan diri biar nggak gila.
Teror Bank Emok
Nah, ini dia aktor antagonis utama dalam drama kehidupan warga Karawang: Bank Emok.
Buat yang belum tahu, Bank Emok adalah sebutan lokal untuk rentenir keliling atau koperasi simpan pinjam ilegal yang menyasar ibu-ibu rumah tangga. Sistemnya berkelompok, nagihnya mingguan, bunganya? Naudzubillah.
Kenapa Bank Emok subur di tanah yang katanya makmur ini? Ya karena poin pertama tadi. Ketika suami butuh duit 8 juta buat nyogok masuk kerja, lari ke mana kalau bukan ke pinjaman kilat? Bank resmi butuh agunan dan survei njelimet. Bank Emok cuma butuh KTP dan janji manis (plus teror psikis kalau telat bayar).
Di balik pintu-pintu rumah warga yang tampak tenang, sering terjadi drama mingguan saat debt collector Bank Emok datang. Ibu-ibu berkumpul, patungan nalangin anggota yang nggak bisa bayar, sambil nahan malu dilihat tetangga.
Santai? Apanya yang santai. Itu muka senyum ibu-ibu di pengajian mungkin cuma topeng buat nutupin kepanikan karena besok jadwal setoran.
Polusi dan debu adalah menu sarapan di Karawang
Kita belum bicara soal lingkungan. Karawang itu panasnya beda. Panasnya menusuk kulit, bercampur debu proyek dan asap knalpot truk kontainer yang bannya segede gaban.
Warga Karawang punya paru-paru yang terbuat dari baja. Setiap hari menghirup udara yang kualitasnya seringkali merah merona di aplikasi AirVisual. Kalau kalian lihat orang Karawang pakai masker, itu bukan cuma takut Covid, tapi takut TBC dan ISPA.
Tapi ya itu tadi, mereka tetap santai. Tetap motoran tanpa jaket, tetap ngopi di pinggir jalan yang berdebu. Bukan karena kebal, tapi karena sudah pasrah. “Mau gimana lagi, namanya juga cari duit di tempat jin buang anak yang sekarang jadi tempat bos buang limbah,” begitu kira-kira batin mereka.
Kenyataan pahit di balik Kota Padi
Dulu, Karawang dikenal sebagai Lumbung Padi Nasional. Sawahnya luas membentang. Petaninya makmur. Sekarang? Sawah-sawah itu perlahan berubah jadi beton-beton pabrik dan perumahan subsidi.
Warga aslinya, yang dulu punya tanah, kini banyak yang cuma jadi penonton. Tanah dijual, duitnya habis buat beli mobil dan daftar haji, lalu anak cucunya bingung mau kerja apa karena sawah sudah nggak ada, mau masuk pabrik nggak punya duit buat nyogok.
Ada rasa keterasingan yang samar tapi nyata. Melihat ribuan pendatang dari Jawa dan Sumatera sukses meniti karier di tanah kelahiran sendiri, sementara warga lokal masih berkutat dengan nasib yang itu-itu saja.
Epilog: santai adalah bentuk perlawanan
Jadi, kalau kalian main ke Karawang (jangan lupa bawa sunscreen SPF 100), dan melihat bapak-bapak sarungan duduk santai di pos ronda siang bolong, atau pemuda-pemuda nongkrong di warkop sampai pagi, jangan buru-buru men-cap mereka pengangguran bahagia.
Mereka sedang “santai” karena itulah satu-satunya hal gratis yang bisa mereka lakukan.
Sebenarnya, mereka sedang menertawakan nasib. Mereka sedang menghemat energi untuk pertarungan esok hari: melawan calo, menghindari Bank Emok, dan menahan gengsi di tengah kota yang memuja materi.
Orang Karawang itu kuat-kuat. Mereka bertahan hidup di atas tanah yang harganya makin tak terjangkau, di bawah langit yang makin abu-abu. Mereka santai, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena kalau mereka terlalu serius memikirkan hidup, mereka bisa gila.
Dan bagi kami, menjadi gila di kota industri adalah kemewahan yang tidak bisa kami bayar. Rumah Sakit Jiwa jauh, BPJS ngantre. Mending ngopi saja, Lur.
Penulis: Roh Widiono
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA 3 Hal di Karawang yang Membuat Pendatang seperti Saya Betah
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.