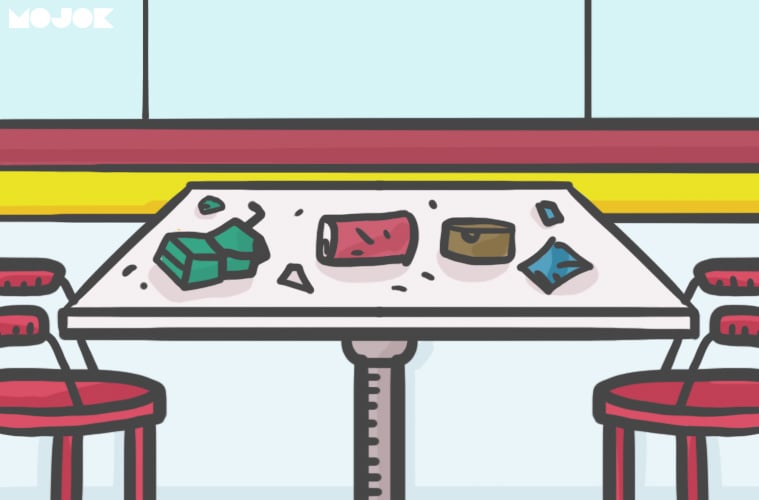Jika ada penghargaan untuk manusia dengan tingkat kesabaran setara Nabi Ayyub di era modern ini, nominasi terkuatnya bukanlah para guru honorer atau istri pejabat yang suaminya korupsi. Pemenang sejatinya adalah kami, warga rumah subsidi di pinggiran kota.
Brosur marketing selalu melukiskan perumahan subsidi sebagai “Hunian Asri, Minimalis, dan Strategis”. Foto-fotonya menampilkan keluarga kecil bahagia yang tersenyum di depan rumah tipe 30/60 dengan cat warna-warni.
Realitasnya? “Asri” berarti lokasinya di tengah sawah atau bekas rawa yang kalau hujan banjirnya semata kaki. “Minimalis” berarti saking kecilnya, kalau kita ganti baju di kamar, sikut kita bisa kepentok lemari dan dinding secara bersamaan. Dan “Strategis” biasanya berarti strategis dekat kuburan desa.
Sebagai seorang ibu rumah tangga yang tinggal di salah satu perumahan subsidi di Malang (yang katanya kota dingin tapi sekarang panasnya kayak simulasi Padang Mahsyar), izinkan saya membuka borok sekaligus memuji ketangguhan komunitas kami.
Tinggal di rumah subsidi adalah ujian mental yang tidak diajarkan di bangku kuliah jurusan Sastra sekalipun.
Baca juga: 4 Dosa yang Kerap Dilakukan oleh Pemilik Rumah Subsidi.
Tembok rumah subsidi setipis tisu dan hilangnya privasi
Mari kita bicara soal konstruksi. Rumah subsidi itu dibangun dengan prinsip ekonomi: modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Akibatnya, kualitas bangunannya seringkali bikin kita ingin menangis sambil istighfar.
Dinding pemisah antara rumah kita dan rumah tetangga itu tipisnya luar biasa. Mungkin bukan terbuat dari batako, tapi dari harapan palsu dan tepung terigu.
Efeknya? Privasi adalah barang mewah yang mustahil dimiliki.
Saya bisa mendengar dengan jelas tetangga sebelah, Bu Marni (nama samaran), sedang memarahi anaknya yang nggak mau makan sayur. Saya bisa mendengar Pak RT di sebelah kiri sedang batuk-batuk bronkitis di jam dua pagi. Bahkan, maaf cakap, suara “aktivitas malam Jumat” tetangga pun kadang bocor menembus dinding, membuat kami yang mendengarnya jadi serba salah mau ikut deg-degan atau ketawa.
Kalau tetangga bersin, kita yang bilang “Alhamdulillah”. Saking dekatnya.
Belum lagi masalah atap. Kalau ada kucing berantem di genteng, suaranya seperti ada tawuran pelajar di plafon rumah. Hidup di sini melatih kita untuk tidak kagetan dan memaklumi segala jenis kebisingan.
Renovasi rumah subsidi tiada henti: the never ending project
Istilah “Rumah Tumbuh” di perumahan subsidi itu harfiah. Rumahnya tumbuh terus, utangnya juga tumbuh terus.
Rumah subsidi bawaan developer biasanya cuma punya satu kamar mandi, satu kamar tidur, dan sisa tanah di belakang yang isinya cuma rumput liar. Maka, begitu akad kredit ditandatangani dan kunci diserahkan, dimulailah kompetisi renovasi se-komplek.
Suara gerinda keramik, suara palu memukul tembok, dan suara tukang mengaduk semen adalah backsound abadi kehidupan kami. Hari Minggu yang harusnya tenang, berubah jadi konser ketukang.
Masalahnya, renovasi di perumahan subsidi itu seringkali offside. Ada tetangga yang membangun dapur sampai memakan bahu jalan. Ada yang bikin pagar setinggi benteng Takeshi sampai menutupi akses cahaya rumah sebelahnya.
Dan yang paling epik: kanopi.
Kanopi rumah subsidi adalah simbol status. Semakin maju kanopinya (bahkan sampai menyeberangi selokan dan memayungi jalan umum), semakin tinggi kasta sosial pemiliknya. Tidak peduli mobil Damkar atau truk sampah susah lewat, yang penting mobil Agya kesayangannya tidak kepanasan.
Baca juga: Yang Perlu Dipahami sebelum Mengajukan KPR Subsidi (dan Menyesal).
Parkir mobil: pemicu Perang Dunia ketiga
Ini adalah sumber konflik horizontal paling panas. Jalan di perumahan subsidi itu lebarnya paling cuma 5-6 meter. Cukup untuk dua motor papasan, tapi ngepas banget kalau dua mobil papasan.
Ironisnya, meski rumahnya subsidi, mobil warganya banyak yang upgrade. Dari motor Beat, naik ke Agya, lalu tiba-tiba ada yang beli Innova Reborn atau Pajero Sport (entah hasil pesugihan atau trading crypto).
Masalahnya, garasinya (carport) ngga muat.
Apa solusinya? Ya parkir di jalan depan rumah. “Kan jalan umum, Mbak,” begitu alasan klasik mereka.
Akibatnya, jalanan komplek rumah subsidi berubah jadi showroom mobil bekas. Kita harus punya skill mengemudi level Michael Schumacher untuk bisa lewat tanpa menbaret bodi mobil tetangga. Kalau ada satu orang yang parkir sembarangan, grup WhatsApp warga akan langsung ramai dengan sindiran-sindiran pasif-agresif.
“Mohon kepada pemilik mobil plat N sekian-sekian, tolong dipindahkan. Mobil sampah nggak bisa masuk.”
Biasanya yang punya mobil bukannya minta maaf, malah left group. Mental baja, Bos!
Intelijen warga: CCTV berwujud manusia
Di perumahan elit, keamanannya pakai CCTV canggih dan satpam berseragam safari. Di komplek rumah subsidi, CCTV kami adalah ibu-ibu yang duduk di teras sambil nyari kutu atau beli sayur.
Daya ingat dan daya analisis mereka melebihi agen CIA.
“Eh, Mbak Fauzia kok paketnya datang terus ya tiap hari? Pasti lakinya gajinya gede.” (Padahal itu paket returan olshop).
“Itu anaknya Pak Dodi kok pulangnya malam terus? Jangan-jangan….”
Informasi menyebar lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Kalau Anda telat bayar iuran sampah, satu blok akan tahu besok paginya. Kalau Anda bertengkar sama suami, paginya tukang sayur sudah tahu kronologinya lengkap dengan analisis siapa yang salah.
Kepo adalah bentuk perhatian (katanya). Tapi bagi saya, itu adalah teror mental yang memaksa kita untuk selalu tampil “baik-baik saja” di depan publik.
Teror bunga floating rumah subsidi dan surat peringatan
Di balik segala drama sosial itu, ada satu musuh bersama yang menyatukan semua pemilik rumah subsidi: pihak bank.
Tahun-tahun pertama cicilan flat, hidup terasa indah. Cicilan sejuta, masih terjangkau gaji UMR. Tapi begitu masuk tahun ke-5 atau ke-6, saat bunga floating (mengambang) menyerang, di situlah iman diuji.
Cicilan yang tadinya sejuta, tiba-tiba naik jadi dua juta. Surat cinta dari bank mulai berdatangan. Stiker kuning bertuliskan “RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK” mulai ditempel di beberapa rumah tetangga yang tak kuat bayar.
Melihat tetangga terusir dari rumahnya sendiri adalah trauma kolektif warga di komplek rumah subsidi. Di situlah rasa solidaritas biasanya muncul. Kami yang biasanya berantem soal parkir, tiba-tiba jadi akur saling mendoakan agar rezeki lancar dan suku bunga turun (hal yang mustahil, tentu saja).
Kenapa kami bertahan?
Lantas, kenapa kami bertahan di lingkungan yang toxic, sempit, dan penuh drama ini?
Jawabannya klise tapi nyata: karena inilah satu-satunya aset yang kami punya.
Di tengah harga tanah yang gila-gilaan, bisa punya sertifikat SHM atas nama sendiri adalah kebanggaan yang tak ternilai. Biarpun tembok rumah subsidi retak rambut, biarpun air PAM-nya sering mati, biarpun tetangganya julid, ini adalah RUMAH KAMI.
Kami bertahan karena kami pejuang. Kami adalah generasi yang menolak tinggal di Pondok Mertua Indah. Dan kami adalah generasi yang berani memotong jatah jajan boba demi nyicil batako.
Jadi, jangan remehkan emak-emak dasteran yang sedang menyapu halaman perumahan subsidi. Di balik daster itu, ada manager keuangan yang hebat yang bisa mengatur gaji UMR untuk bayar cicilan, bayar listrik token, belanja sayur, dan tetap bisa beli kuota buat nonton drakor.
Warga di komplek rumah subsidi mungkin bukan orang kaya harta. Tapi soal mental? Kami lebih kaya dari penghuni apartemen mewah yang bahkan nggak kenal siapa tetangga sebelahnya.
Kami berisik, kami kepo, kami kadang norak. Tapi saat ada satu warga sakit atau meninggal, satu kampung akan turun tangan tanpa diminta.
Itulah romantika tinggal di rumah subsidi. Sempit lahannya, tapi luas (dan kadang lebay) rasa persaudaraannya.
Penulis: Fauzia Sholicha
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Rumah Subsidi Akan Berubah Jadi Penjara Jika Kalian Terjebak Bujuk Rayu Pengembang.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.