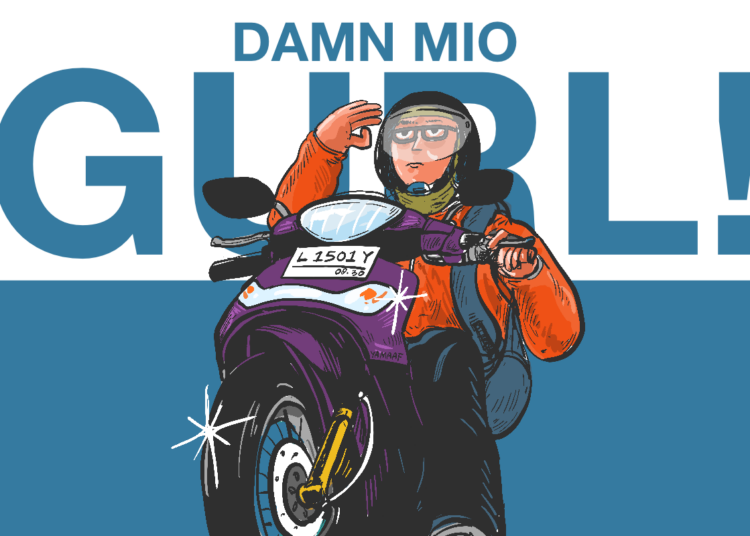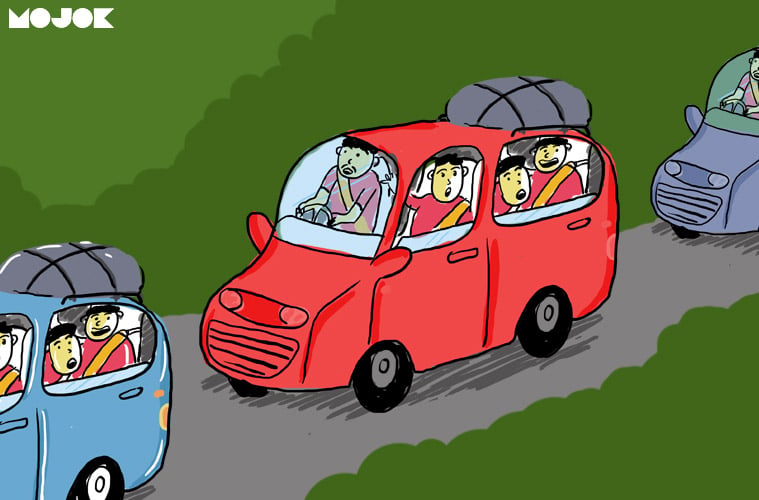Kabupaten Situbondo sering jadi bahan olok-olok kecil di jalur Pantura. Olok-oloknya begini: Situbondo hanyalah kota singgah. Sekadar mampir isi bensin dan beli minum para sopir truk. Habis itu ya, ke Banyuwangi atau ke Probolinggo. Saya saja melihatnya seperti itu, apalagi ketimbang Banyuwangi.
Tapi memang, dibandingkan Banyuwangi, Situbondo kalah jauh. Banyuwangi memiliki sederet destinasi yang sudah kelas nasional, bahkan internasional. Ijen, Baluran ( ironisnya sebagian masuk Situbondo tapi brandingnya tetap melekat ke Banyuwangi), sampai festival-festival lainnya banyak media nasional yang meliput.
Situbondo? Nyaris nggak ada narasi wisata yang benar-benar kuat. Pertanyaannya, kenapa begitu?
Situbondo, kota tanpa magnet wisata
Coba tanya ke orang luar Jawa Timur, kalau ke Situbondo enaknya ke mana, pasti banyak yang bengong. Kalaupun ada yang jawab, pasti sebut Baluran, padahal identiknya ke Banyuwangi. Atau paling banter pantai Pasir Putih. Itu pun sudah kalah pamor dari pantai di Lombok, Bali, atau Malang selatan.
Padahal Situbondo punya garis pantai panjang. Punya ekosistem mangrove yang katanya bernilai miliaran rupiah per tahun. Dan julukan kota santri. Tapi ya itu, tidak diolah jadi wisata yang layak jual. Akhirnya, yang datang ke Situbondo bukan wisatawan, tapi orang-orang yang kebetulan lewat jalur pantura menuju Bali. Atau para wali santri yang ingin menjenguk anaknya di pesantren.
Dampak ke ekonomi lokal
Coba kalau wisatanya diseriusin, ekonomi Situbondo nggak bakal jadi stagnan. Sektor utama tetap pertanian, perikanan, atau usaha kecil tradisional. Orang-orangnya tidak ada yang berkreativitas baru yang bisa mendongkrak perputaran uang. Padahal wisata itu salah satu mesin pengganda: orang datang, nginap, makan, beli oleh-oleh, naik ojek, pakai jasa lokal. Kalau wisata tidak jalan, rantai ekonomi itu nggak terbentuk.
Kalau dilihat dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Situbondo sebagian besar masih ditopang sektor primer. Tidak ada lonjakan signifikan dari sektor pariwisata. Kenapa tidak bercermin ke wilayah tetangganya, di Banyuwangi atau Jember yang PAD-nya naik gara-gara event-event wisata.
Kota sepi di malam hari
Dan efek yang paling terasa ada di wajah kotanya sendiri. Jalanan Situbondo selepas Isya bisa dibilang sepi. Jarang menemukan ruang publik yang hidup. Tidak ada alun-alun yang benar-benar jadi tarik perhatian.
Kalau mau nongkrong, anak mudanya lebih sering lari ke Bondowoso atau malah sekalian ke Banyuwangi. Bayangkan, generasi mudanya saja tidak merasa kota ini cukup memberi hiburan. Bagaimana mungkin orang luar bisa betah singgah lebih lama?
Julukan Situbondo pun hampir punah
Situbondo sering disebut kota santri. Julukan ini sebenarnya punya potensi wisata religi. Tapi sampai sekarang, tidak pernah ada usaha serius mengangkat pesantren atau sejarah ulama sebagai daya tarik wisata. Tidak ada festival skala besar, tidak ada branding kuat. Semua potensi masih jadi wacana. Kalaupun ada, itu tidak pernah sampai diseriusin benget oleh pemerintah setempatnya.
Akibatnya, identitas Situbondo nyaris kabur. Mau dijual sebagai kota wisata alam? Kalah branding dari Banyuwangi. Kota religi? Kurang promosi. Kota kuliner? Nyaris nggak ada yang dikenal luas.
Kalau masalah harapan sih tetap ada. Situbondo bisa saja bangkit. Potensi sebenarnya ada, bahan mentah tersedia. Tapi selama belum ada inovasi dan keberanian menggarap wisata secara serius, kota ini akan terus jadi kota lewat. Orang mampir sebentar, lalu tancap gas. Dan selama itu pula, ekonominya akan jalan di tempat.
Penulis: Thoha Abil Qasim
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.