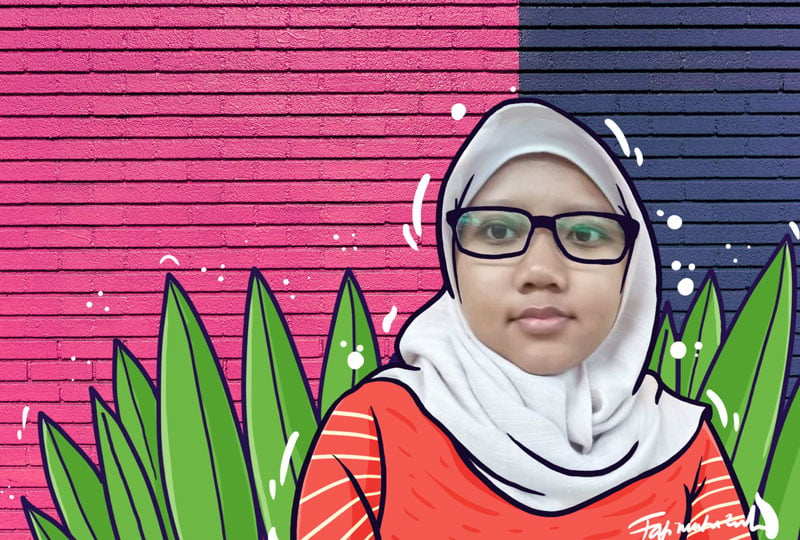Latar belakang dari dibuatnya tulisan ini, sebenarnya hanya sebagai upaya untuk penyeimbang persepsi dan wacana. Karena belakangan ini pikiran kita diisi dengan stereotip orang yang berpenampilan, berperilaku, dan berbahasa Arab atau ngarab, tidak bisa menjadi tolok ukur satu-satunya atas keimanan, kealiman, dan bagusnya perilaku. Maka, agar bisa memandang secara adil, kita juga tak bisa sembrono mengatakan bahwa yang tidak ngarab itu juga lebih beriman, lebih alim, dan lebih bagus juga perilakunya.
Bukan tanpa alasan, dulu saya pernah mengalami sesuatu yang bikin saya dihajar oleh persepsi sendiri. Ketika masih awal-awal semester kuliah, saya mencoba untuk rajin-rajin pergi ke masjid, salat jamaah, ikut ceramah, dst. Kegiatan ini, kan, pastinya dihadiri oleh banyak model orang. Ada yang ngarab, njawani, madurani, dan ada yang juga berpenampilan biasa saja. Kemudian, saya ketemu, tuh, sama yang ngarab. Lantaran persepsi awal yang terbentuk itu kalau yang ngarab ini kurang baik, maka saya sedikit memandang remeh dan memandang sinis.
Lalu, kepala saya dibenturkan oleh perilakunya yang menyapa, tersenyum, dan berperangai halus. Kan, gimana kalau sudah ketemu sama orang model gini. Akhirnya, saya pun langsung memutuskan untuk men-delete persepsi yang bagi saya kurang adil itu. Ternyata, tak semua yang ngarab itu bisa kita pandang bahwa dia tak lebih alim dari yang berpenampilan lainnya. Bahwa mau ngarab, njawani, ng-madurani, mbugis, mbatak, dan lainnya itu hanya tentang pemilihan penampilan saja. Ia tidak bisa sepenuhnya menjadi tolok ukur baik-buruknya seseorang.
Pemilihan model pakaian, intinya hampir sama dengan pemilihan makanan yang disukai. Ada yang suka pecel, suka rawon, soto ayam, soto babat, soto betawi, soto lamongan, bakso, dan lain-lain. Jadi, yang suka rawon tidak bisa mengatakan kalau rawon itulah satu-satunya makanan di bumi yang paling enak. Posisi pengakuan rawon paling enak, itu relatif dan nisbi. Begitu juga dengan yang lain.
Selain itu, penampilan seseorang tak bisa sepenuhnya menjadi representasi dari nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Semua bisa baik dan bisa juga buruk. Saya pernah belajar mata kuliah perilaku organisasi yang di dalamnya juga memuat materi yang nyrempet-nyrempet ke ranah psikologi. Ada satu fenomena yang disebut dengan disonansi. Fenomena ini terjadi saat apa yang berada di luar atau pada dimensi psikomotorik-nya tidak sesuai dengan dimensi dalam yakni afeksi dan kognisi dari orang tersebut. Dari sini bisa ditegaskan lagi, bisa jadi bahwa pemilihan berbagai model pakaian terdapat probabilitas tidak sesuai dengan apa yang berada di dalam dirinya.
Ini semua, kan, sebenarnya hanya upaya menilai seseorang. Lebih baik, agar kepala kita tak diisi dengan sesuatu yang buruk, kita pandang dengan kacamata khusnudzon saja. Kalau yang ngarab itu, mereka berupaya untuk meniru dari hal paling kecil dari dimensi kealiman, kelembutan, dan baiknya perilaku orang-orang yang benar-benar alim, lembut, dan berperilaku baik. Bisa jadi, perilaku tersebut muncul sebagai tahap awal dari perkembangan ke arah yang lebih baik. Ia seperti bunga yang butuh waktu untuk mekar, seperti biji yang butuh waktu untuk tumbuh, dan juga seperti bayi yang butuh tahap dari bergerak, merangkak, berdiri, untuk kemudian bisa berlari.
Begitu juga dengan yang berpenampilan khas dengan suku, negara, ideologi, dst. Kita khusnudzon saja dengan menganggap kalau mereka berkomitmen untuk menjaga warisan ataupun budaya dari leluhur-leluhurnya. Kalau sudah bisa gini, kan, enak. Kita jadi tak punya gumpalan-gumpalan negatif, entah itu dalam hati, pikiran, dan juga jiwa. Hidup bisa jadi lebih tenang, lebih menghargai sesama, dan lebih banyak mentolerir perilaku orang lain.
Sebenarnya, kalau kita mau bijak menyikapi apa pun, yang harus dilakukan bukan dengan menilai-nilai perilaku, sikap, pandangan, dan anggapan-anggapan dari orang lain. Melainkan dengan mampu mengkritik sikap, pandangan, dan perilaku diri sendiri. Dengan ini, tanggung jawab sebagai manusia untuk berbuat baik, atas izin-Nya bisa tercapai. Sebagai sesama manusia, kita kan, tidak ada kewajiban untuk memberi ‘rapor’. Sudah ada malaikat yang ditugaskan. Kita ada yang mencatat, mereka pun ada yang mencatat. Jadi, tanggung jawab utama yang harus dilakukan hanyalah memperbaiki sikap, pandangan, perilaku, dan amal kita sendiri terhadap orang lain.
Dengan memperbaiki sikap diri sendiri, harapannya adalah bisa menjadi seseorang yang mampu menciptakan determinasi garis resultan kedamaian bersama. Menjadi cah angon yang memiliki daya menggembalakan, memiliki kesanggupan untuk ngemong semua pihak, karakter untuk merangkul, dan memesrai siapa saja. Menjadi pemancar kasih sayang yang dibutuhkan dan diterima oleh semua warna, semua golongan, dan semua kecenderungan. Mampu membentuk persaudaraan yang tidak hanya berdasarkan kesamaan agama, kesamaan darah, suku, adat, budaya, ataupun bangsa, melainkan persaudaraan yang berdiri atas dasar cinta.
BACA JUGA Perlu Diingat: Yang Lebih Arab, Bukan Berarti Lebih Alim dan tulisan Firdaus Al Faqi lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.