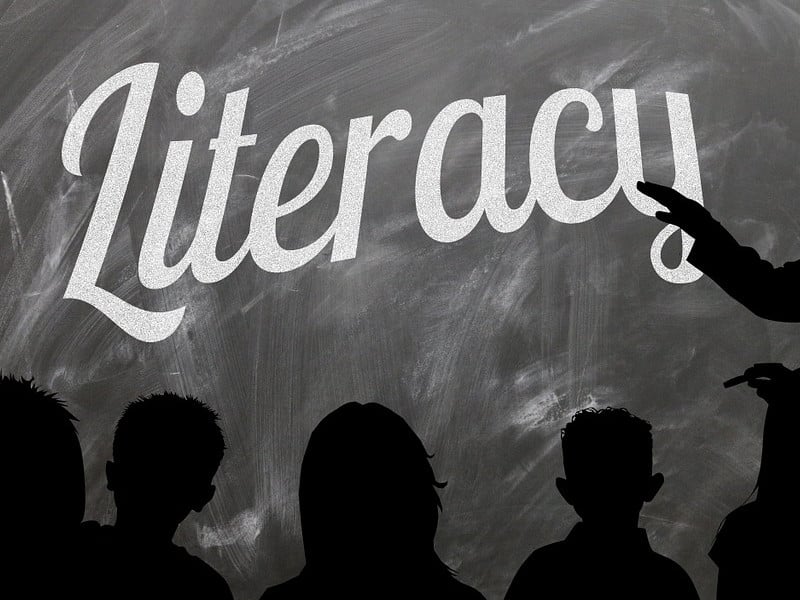Dosen saya pernah bercerita, ia berencana membuat otobiografi seorang hakim yang layak dihormati sebagai begawan hukum di Indonesia, Artidjo Alkostar. Ia menempati kamar pidana di Mahkamah Agung, beragam julukan ia dapat. Ketika sudah banyak orang muak dengan penegakan hukum di Indonesia yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, anggapan itu mesti ditunda kalau beliau yang menangani perkara.
Sekali waktu ketika dosen saya tadi dengan mobilnya berkendara di jalanan, di bawah terik cuaca Yogya dan jalanan yang dijejali kendaraan, seorang kakek melaju melewatinya dengan Honda Astrea. Penampilannya biasa saja layaknya lelaki tua pada umumnya. Tapi, mengenali wajahnya membuat dosen saya ini tak mungkin melewatkan detik-detik itu tanpa menyadari bahwa yang ia lihat adalah suatu kontradiksi.
Bukan karena Honda Astrea menjadi keunikan bagi jalanan Yogya, melainkan karena lelaki tua itu adalah hakim agung yang sedang kita bicarakan, Artidjo Alkostar.
Betapa aneh perasaan yang menyerang seorang dosen muda tatkala melihat sosok yang hendak ia telusuri kehidupannya ditemukan tanpa sengaja masih berkendara sepeda motor dengan merek lama. Lebih ironis lagi, ketika kita membandingkan Artidjo berhadapan dengan pejabat semacam lurah yang tak pernah berkendara selain mobil.
Ini bukanlah soal kemampuan atau sekadar daya beli, melainkan soal bagaimana pejabat negara menampilkan diri di muka umum. Kalau soal mobil saja, petani di daerah saya rata-rata memiliki mobil yang dibeli tanpa nyicil layaknya lurah dan camat. Dan itu cukup membuat para petani bisa mengolok-ngolok mobil plat merah yang berjejalan di hari libur, baik ke pantai maupun pesta perkawinan.
Hidup di masa kapitalisme global, mode transportasi merupakan penanda identitas. Hal itu meniscayakan adanya kesadaran kelas bagi penggunanya. Mobil memberi tanda dan status sosial bagi pemiliknya dan orang lain akan menilainya dari kendaraan apa yang ia pakai. Jangankan seorang walikota, camat saja bisa malu kalau bawahannya datang mengendarai mobil ke kantor, apalagi ketika para petani ternyata sanggup menjangkau mobil.
Seorang pejabat tentu saja tak mau dikira warga biasa. Dengan begitu mobil tidak akan lagi dilihat dari nilai gunanya sebagai alat transportasi, melainkan dari nilai identitas yang melekat padanya. Semakin seorang pejabat berhasrat memperlebar jarak dan menegaskan identitas yang berbeda dari masyarakat biasa, maka semakin tinggi pula hasrat untuk meraup pendapatan lebih dari gaji yang sanggup didapatnya. Iya kalau si pejabat buka usaha warung makan, tapi kalau korupsi, bagaimana?
Di situlah Artidjo Alkostar dengan sepeda motornya, atau dengan bajaj yang ditumpanginya berkantor ke lembaga tertinggi yudisial menolak menghamba pada nilai identitas yang memaksa pejabat negara untuk terus meningkatkan standar penilaian mengikuti tren yang berlaku di pasar.
Suatu sikap yang sebetulnya biasa-biasa saja. Namun, menjadi “mewah” karena jarang yang sanggup mempraktikannya.
Tidaklah tepat bila mengira sosok Artidjo Alkostar hanya menjelma algojo bagi para koruptor. Sebuah kesan yang seolah menyiratkan beliau hanya bermodal keberanian saja melawan kekuatan penopang di balik terdakwa kasus korupsi yang ditanganinya. Yang melahirkan putusan-putusan lebih berat bagi para terdakwa ketimbang yang diberikan pengadilan di bawah MA.
Lebih dari itu, Artidjo sesungguhnya adalah hakim progresif. Kalau ia seolah-olah begitu tertinggal dalam mengikuti tren komoditas, ia amat terdepan ketimbang hakim-hakim umumnya dalam memahami fenomena sosial.
Semisal, dalam tulisannya pada sebuah rakernas MA dengan pengadilan seluruh Indonesia, ia menerangkan bahwa dalam perkara kejahatan seksual, hubungan pelaku dengan korban menjadi pertimbangan bagi putusan hakim. Sebab, terdapat unsur eksploitasi terhadap posisi rentan korban di sana, baik secara sosial maupun ekonomi.
Kita dapat membayangkan bahwa pelaku dalam kasus perdagangan manusia yang memanfaatkan keadaan ekonomi untuk mengelabui korban, tidak saja dipersalahkan atas kejahatan perdagangan manusia, melainkan juga atas kejahatan eksploitasi terhadap kemiskinan korban.
Dengan begitu, ia ingin menegaskan bahwa keadilan harus mengedepankan kesadaran kelas, mengakui situasi sosial-ekonomi yang dihadapi oleh korban dan pelaku, serta menyadari ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Seandainya sikap ini diikuti hakim-hakim pada umumnya, kita tidak akan meributkan kasus Mbok Minah yang dituduh mencuri 3 buah kakao, ataupun kasus Baiq Nuril sebagai korban pelecehan seksual yang justru kena pidana.
Lagi-lagi, gagasan ini adalah gagasan yang biasa-biasa saja. Umar bin Khattab 15 abad yang lalu bahkan telah mempraktikannya, ia menolak menghukum budak yang mencuri karena kelaparan tak diberi makan tuannya. Alih-alih menghukum budak, Umar justru menghukum sang majikan.
Kita tak perlu heran bila kemudian Artidjo Alkostar kerap memperberat hukuman para koruptor, sebab mereka tidak dalam kondisi kelaparan. Pertimbangan atas kondisi sosial-ekonomi yang mereka miliki justru membuatnya layak mendapat hukuman berat.
Seperti saya katakan di awal, jika hukum diibaratkan pisau, di tangan Artidjo pisau itu mestinya dipegang secara terbalik. Hukum harusnya tajam ke atas dan tumpul ke bawah.
Sayangnya, beliau telah meninggalkan kita, tepat sehari sebelum hari kehakiman. Gagasan dan sikap hidupnya layak didengungkan dan menjadi pengingat bagi kita. Kita berharap kelak, akan lahir Artidjo-Artidjo baru yang menjalankan kredo, “Fiat justitia et pereat mundus” yang berarti, hendaklah keadilan binasa walau dunia harus ditegakkan.
Eh, astagfirullah… kebalik, hendaklah keadilan ditegakkan walau dunia harus binasa.
Sumber gambar: YouTube Tribunnews.com
BACA JUGA Hukum Lebih Menyenangkan Dipelajari Lewat Buku daripada Lewat Kenyataan dan tulisan Ang Rijal Amin lainnya.