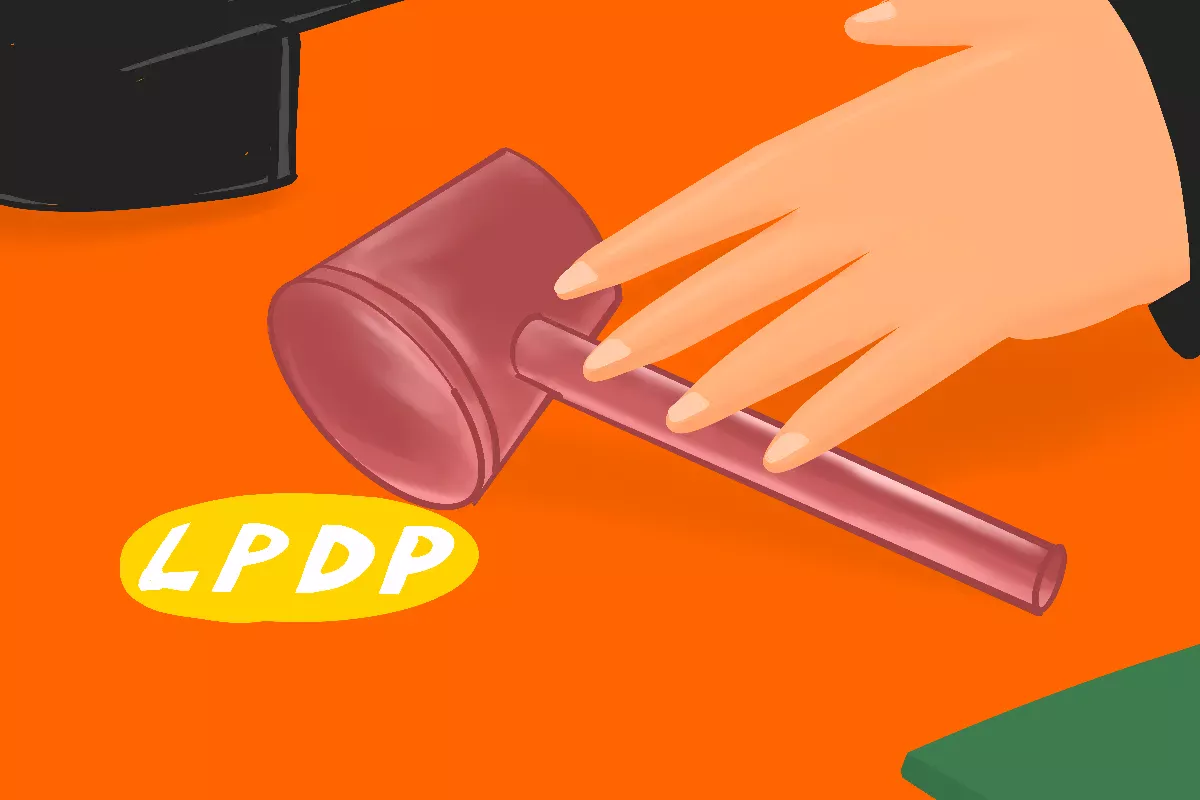Meskipun saya dosen pangan, saya tidak sedang meng-endorse produk mi instan. Pun tidak juga tulisan ini sebuah advertorial yang seolah menonjolkan glorifikasi ilmiah tanpa celah. Anggap saja saya anak desa yang kini sudah dewasa, generasi 90-an yang tumbuh dan berkembang bersama mi instan. Lain waktu barangkali akan saya bahas pula bagaimana generasi kita menua sebagai bucin alias budak micin.
Besar di desa dekat pinggiran utara daratan Jawa, saya terbiasa menghabiskan sore hari yang hujan dengan seporsi mi instan dalam cawan penuh kenangan, mangkuk cap ayam jago. Kala itu merk mi instan yang beredar di toko kelontong paling-paling Supermi dan Sarimi, itu pun hanya rasa ayam bawang. Indomie tidak terlalu populer, kalaupun ada, hanya tersedia varian Indomie goreng.
Eskalasi kemasyhuran Indomie barangkali mulai melonjak tajam di kota-kota besar dengan kampus-kampus tenar, beriringan dan beririsan dengan menjamurnya Warmindo, atau sering juga disebut Burjo. Satu-satunya jenis warung makan yang selalu ada “intel” 24 jam di dalamnya. Sungguh ngeureuyeuh! Warteg rasa-rasanya perlu belajar pada Warmindo soal strategi menguasai pasar mi instan ini.
Kini mi instan telah beredar dan terhampar merata dari kota hingga desa, produsennya pun bukan itu-itu saja. Mulai dari Indofood (Indomie, Supermi, Sarimi, Real Meat), Wings Food (Mie Sedaap, Mie Suksess), Mayora (Bakmi Mewah), ABC President (Mie ABC), Gagafood (Mie Gaga), sampai Lemonilo yang mengklaim embel-embel mi instan sehat tanpa pengawet dan MSG.
Meskipun ya menurut saya perundungan terhadap frasa “pengawet” dan “MSG” sudah keterlaluan, sih. Akan jadi membosankan kalau harus dikuliti sampai halus di sini, kapan-kapan kita bahas lagi. Ada kelindan antara keberpihakan informasi dan keilmuan yang “pasti” dengan sengkarut ideologi dalam bernegara dan berorganisasi. Kenapa? Ya karena tidak lain dan tidak bukan, tetap saja urusan cuan.
Kembali pada percaturan mi instan di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir muncul kompetitor impor dari luar negeri. Semua berubah ketika negara api menyerang. Samyang dan kawan-kawan dengan branding mi instan yang pedasnya kaya setan rame-rame di-review oleh banyak orang, mulai dari konten kreator dadakan sampai para selebgram kenamaan.
Rasa pedas yang menurut saya terlalu kepedean, masih kalah jauh dengan sambal bawang warung ayam geprek belakang kampus dengan semboyan “tentukan level pedasmu sendiri”. Sempat digoyang dengan isu haram dari potensi kandungan babi, Samyang dan kawan-kawan tetap bergeming, bertahan dari serangan lawan-lawan mi instan lokal. Mereka kini telah belajar banyak dan memahami bahwa di Indonesia yang paling penting bagi konsumen muslim adalah produk dengan sertifikat halal MUI.
Sejak itu, Indomie dan Mie Sedaap memimpin inovasi rasa mi instan yang makin unthinkable dan unbelievable. Mulai dari rasa rendang, iga penyet, korean spicy chicken, ayam geprek, seblak jeletot, white curry, salero padang, mi goreng aceh, sambal matah, dendeng balado, cabe ijo, cakalang, sate (satay flavour), masak habang, empal gentong, sambal rica-rica, sampai rasa chitato.
Satu yang jadi rasa favorit saya (dan kini entah kenapa tidak lagi ada di pasaran) rasa salted egg yang ketika itu mengikuti viralnya salted egg chicken dari KFC. Anyway, dalam teknologi flavor produsen mi instan biasanya memiliki pabrik seasoning sendiri, terpisah dari pabrik mi instan. Misalnya pabrik food seasoning division milik Indofood di Semarang.
Berkaitan dengan rasa-rasa mi instan, ada satu nama yang pernah viral di berbagai media beberapa waktu lalu. Dialah Nunuk Nuraini, Flavor Development Manager dari Indofood alumni tekpang Universitas Padjajaran yang konon telah berjasa besar menelurkan lebih dari 62 rasa Indomie. Ia seolah jadi sosok profetik yang transenden sekaligus mesias yang dikultuskan para pengabdi mi instan.
Sebagai informasi ringan, dalam industri pangan produksi bumbu bubuk melalui banyak proses pengolahan, mulai dari pemilihan bahan dari berbagai jenis rempah hingga sterilisasi yang berkaitan dengan food safety (cemaran pestisida, aflatoksin pada biji-bijian, hingga kontaminasi bakteri). Rempah nusantara yang umum digunakan sebagai bumbu bubuk di antaranya kayu manis, kunyit, jahe, dan lada.
Titik kritis yang perlu diperhatikan dalam pengolahan bumbu adalah proses pengeringan. Proses ini biasanya dikenal dengan istilah gentle drying atau proses dehidrasi. Umumnya menggunakan alat industri berteknologi pengeringan infrared atau microwave vacuum drying. Proses pengeringan dilakukan dengan sangat hati-hati agar aroma, warna, dan kandungan minyak volatil tidak menguap dan hilang percuma.
Selain itu, tahapan penepungan juga sangat diperhatikan dan bisa dibilang paling menentukan. Proses ini dilakukan menggunakan teknologi penggilingan beku dengan bantuan nitrogen untuk menurunkan suhu di bawah nol derajat celcius. Alat yang digunakan dikenal dengan nama cryomill, khusus untuk melakukan proses cryogenic grinding atau freezer milling.
Satu lagi bagian penting dalam pengolahan bumbu instan adalah pencampuran (blending dan mixing) yang disertai dengan homogenisasi hingga seluruh komposisi bumbu tercampur merata. Di sinilah peran food technologist seperti Bu Nunuk dibutuhkan, meracik proporsi yang presisi dari beragam bubuk rempah pilihan. Keseluruhan proses dalam membuat bumbu mi instan itu saja sudah menunjukkan bahwa sebenarnya mi instan sama sekali tidak instan.
Meskipun demikian, sebagai konsumen dan khususnya dosen pangan, saya merasa perlu untuk mengusulkan rasa mi instan yang lebih liar dan nakal. Misalnya rasa sambal pete yang punya aroma kuat dan khas. Mesti disempurnakan pula dengan pete asli yang dikeringkan dan bisa dijadikan topping elegan untuk campuran mie instan.
Rasa lain yang patut ditunggu mestinya memiliki identitas kepulauan kita sebagai negara maritim. Rasa dan aroma ikan asap bisa jadi pilihan pertama dalam perdebatan panjang penentuan spesifikasi bumbu bercita rasa ikan nusantara. Saya yakin bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia tidak akan segan untuk ikut mencicipinya dan bahkan mungkin mau berperan sebagai bintang iklan mi instan ikan.
Rasa lain yang tidak saya rekomendasikan, meskipun banyak dari kalian para milenial alay pasti akan mendambakan, adalah mi instan rasa boba, kopi gula aren, green tea, red velvet, hingga white chocolate. Mengapa? Karena mi instan adalah sajian berat yang lebih diharapkan memiliki karakteristik savoury, masuk dalam kategori makanan yang memiliki rasa asin, gurih (umami), dan pedas. Itu saja sudah menjelaskan mengapa sampai sekarang belum juga ada mi instan rasa gudeg atau kolak.
Akan tetapi, kita nantikan saja sejauh mana Bu Nunuk dan kawan-kawannya berani berkreasi di “dapur” pengembangan flavor produknya. Barangkali rasa yang anti-mainstream (kalau tidak mau disebut absurd) itu bisa dirilis dengan embel-embel limited edition, sehingga hanya bisa dibeli oleh para YouTuber kaya, jadi barang koleksi yang langka. Biar apa? Biar masuk MURI dong, “Mi instan termahal di dunia.” Kita mah apalah-apalah, tinggal nunggu Aa Warmindo nggodok aja.
BACA JUGA Nggak Usah Ngeyel, Mie Sedaap Lebih Enak daripada Indomie dan tulisan Adi Sutakwa lainnya.