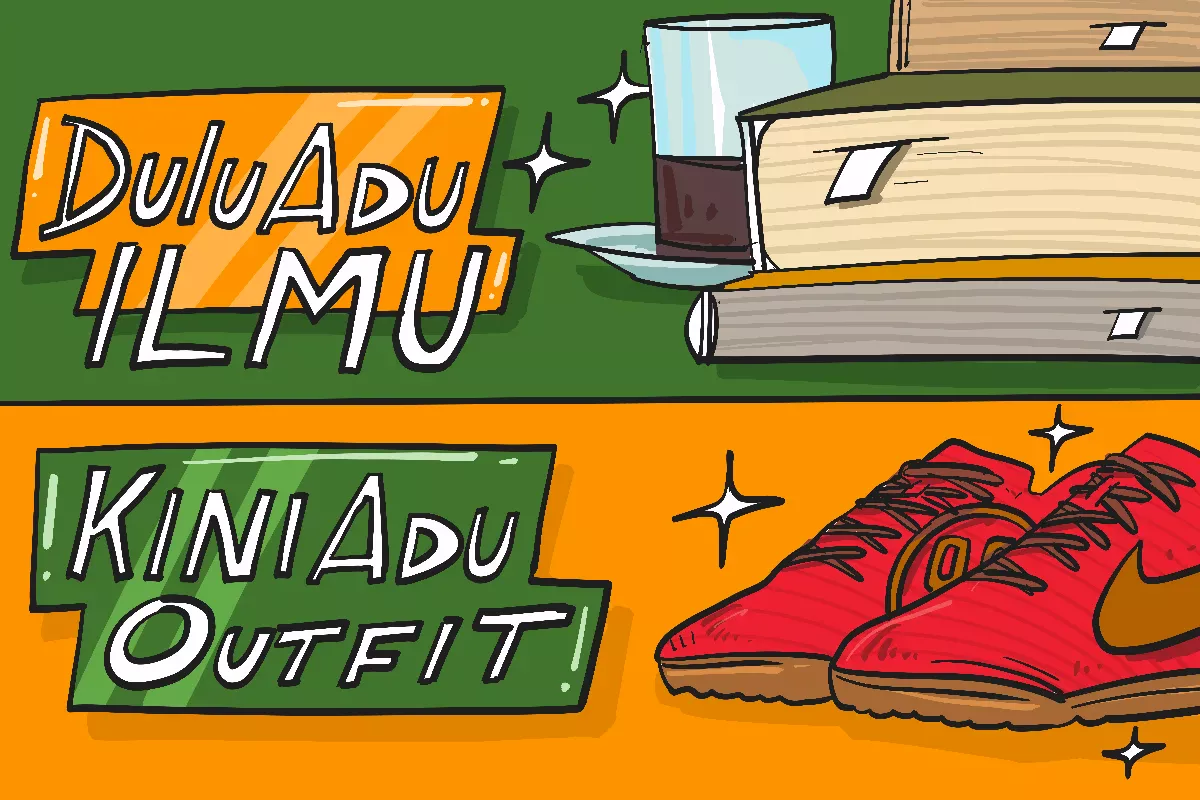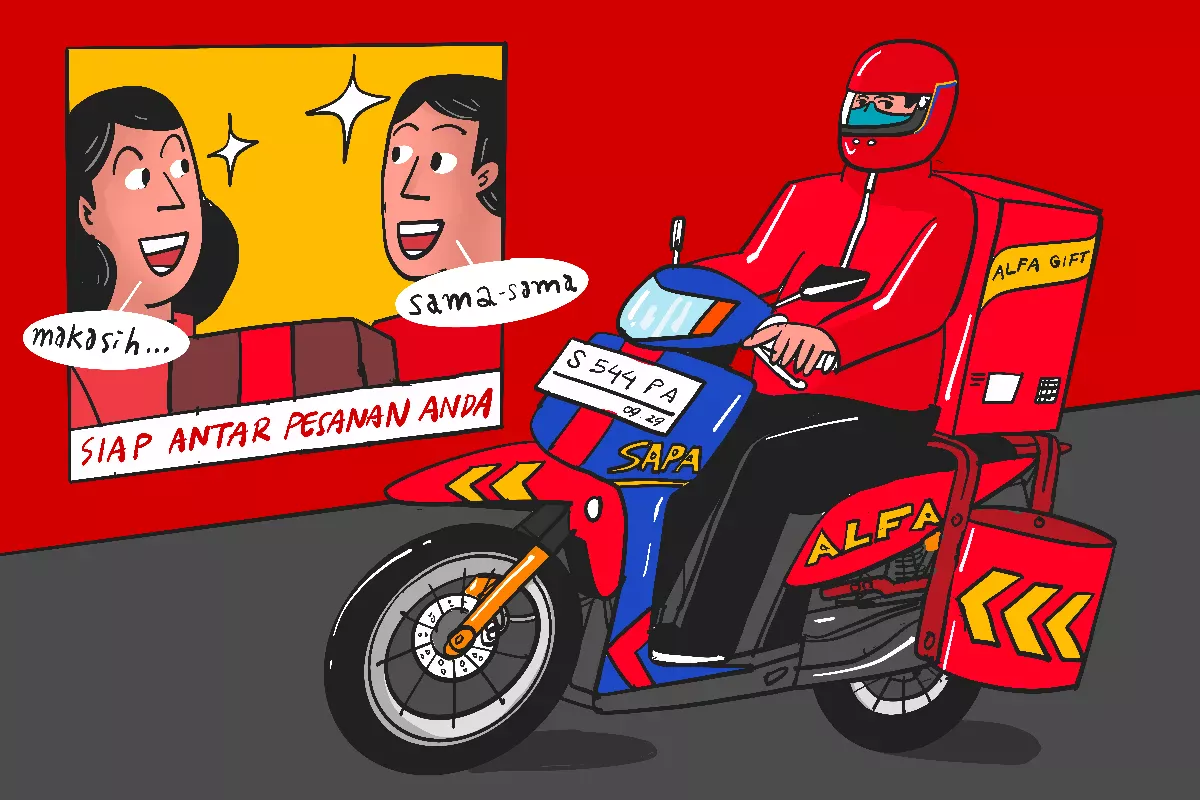Mimpi kota pensiun tidak lebih dari kampanye bisnis properti. Bukan untuk memanjakan dan memanusiakan kelompok pensiun, namun menguras kantong mereka untuk terus konsumtif
“Aku mau pensiun di Jogja,” ujar kawan saya. Sambil mengernyitkan dahi, saya hanya geleng-geleng kepala. Untuk apa pensiun di Jogja? Apakah untuk pensiun kita harus bermigrasi? Apakah kita tidak bisa pensiun di tempat tinggal saat ini? Ataukah ini hanya promosi semata?
Otak yang sudah penuh dengan urusan pekerjaan, jadi makin riuh. Konsep kota pensiun hari ini tidak masuk akal. Lebih dari itu, saya melihat ancaman. Sebuah bom waktu yang pada saatnya menjadi kekacauan. Mungkin malah sudah meledak diam-diam di balik mimpi slow living dan masa tua bahagia.
Sudah sewajarnya kita menikmati successful aging. Tapi bukan dengan migrasi dan membawa potensi bahaya ke sebuah tempat. Setiap orang berhak bahagia saat pensiun di mana saja!
Kampanye kota pensiun dan bisnis properti
Tidak perlu teori konspirasi untuk mengetahui proyek di balik kota pensiun. Sudah pasti ini urusan bisnis properti. Iming-iming menikmati masa tua di surga dunia akan berlanjut dengan tawaran properti.
Bisnis kota pensiun memang menguntungkan bagi dunia properti. Pada usia senja, orang cenderung sudah kenyang dengan nilai fungsional. Estetika dan budaya menjadi nilai yang dicari. Untuk bisnis properti, nilai ini jelas mendatangkan profit besar.
Hunian tidak lagi dinilai dari harga per meter. Tidak lagi dihitung dari biaya material dan pengerjaan. Konstruksi bangunan tidak lagi menentukan harga. Namun kecocokan dan emosional konsumen. Apabila sebuah komoditas mulai menyematkan value tambahan ini, sudah pasti harganya meroket.
Maka wajar jika konsep kota pensiun makin riuh. Setiap daerah menawarkan diri untuk menemani masa tua Anda. Terutama daerah “murah” dan asri. Sebut saja Jogja, Solo, Purwokerto, dan lain sebagainya.
Tapi apa ancaman dari kampanye kota pensiun? Maaf, tapi saya akan membuka mata Anda. Jangan menyesal ketika realitas tidak seindah mimpi yang fana.
Bom gentrifikasi dan segregasi
Anda jangan bosan menemukan kata “gentrifikasi” dalam artikel saya, karena isu ini adalah masalah nyata. Apalagi kota pensiun adalah daya tarik besar masuknya kelompok ekonomi makmur.
Karena kota pensiun cenderung suburban, maka akan kontras dengan pendatang yang masuk. Untuk bisa memutuskan tinggal di kota pensiun, maka ekonomi orang itu harus lebih tinggi dari daerah tujuan. Apalagi properti yang ada lebih mahal dari daya beli warga lokal.
Masuknya kelompok makmur akhirnya mendorong pembangunan fasilitas umum dan masuknya investasi lain. Sialnya, semua bukan untuk diakses warga lokal. Tapi untuk dinikmati kelompok makmur yang kini menguasai properti.
Selain gentrifikasi, segregasi sosial menjadi masalah yang ikut menyertai kota pensiun. Datangnya kelompok pensiun (dan makmur) tadi cenderung lebih eksklusif. Potensi gesekan budaya mungkin bisa diatasi. Tapi akan muncul pagar antara warga lokal dan pendatang ini. Baik pagar imajiner atau pagar nyata pemisah pemukiman.
Segregasi ini bisa berdampak pada ketidakstabilan sosial. Diawali dari gegar budaya, berakhir dengan hilangnya identitas lokal. Belum lagi potensi warga lokal yang makin tersudut. Bahkan demonisasi warga lokal akibat kelompok baru yang lebih dominan dalam hierarki sosial.
Seperti ini skenarionya: warga pendatang akan masuk sebagai kelompok eksklusif. Anggap saja dalam satu perumahan. Mereka punya budaya yang senada, sebagai pensiunan dengan ekonomi lebih baik dari warga lokal. Belum lagi pendidikan dan jabatan profesonal.
Kultur yang mereka bawa sebelumnya akan berbenturan dengan budaya lokal. Terutama benturan budaya kota dengan pedesaan. Maka muncul kesan, “warga lokal udik dan tidak terpelajar.” Berlanjut dengan stigma negatif lain yang akhirnya diamini bersama.
Baca halaman selanjutnya
Beban sumber daya yang ditanggung warga lokal