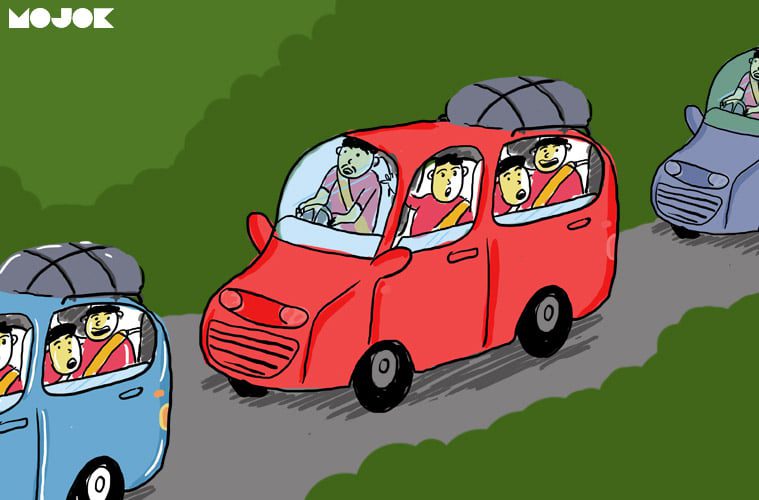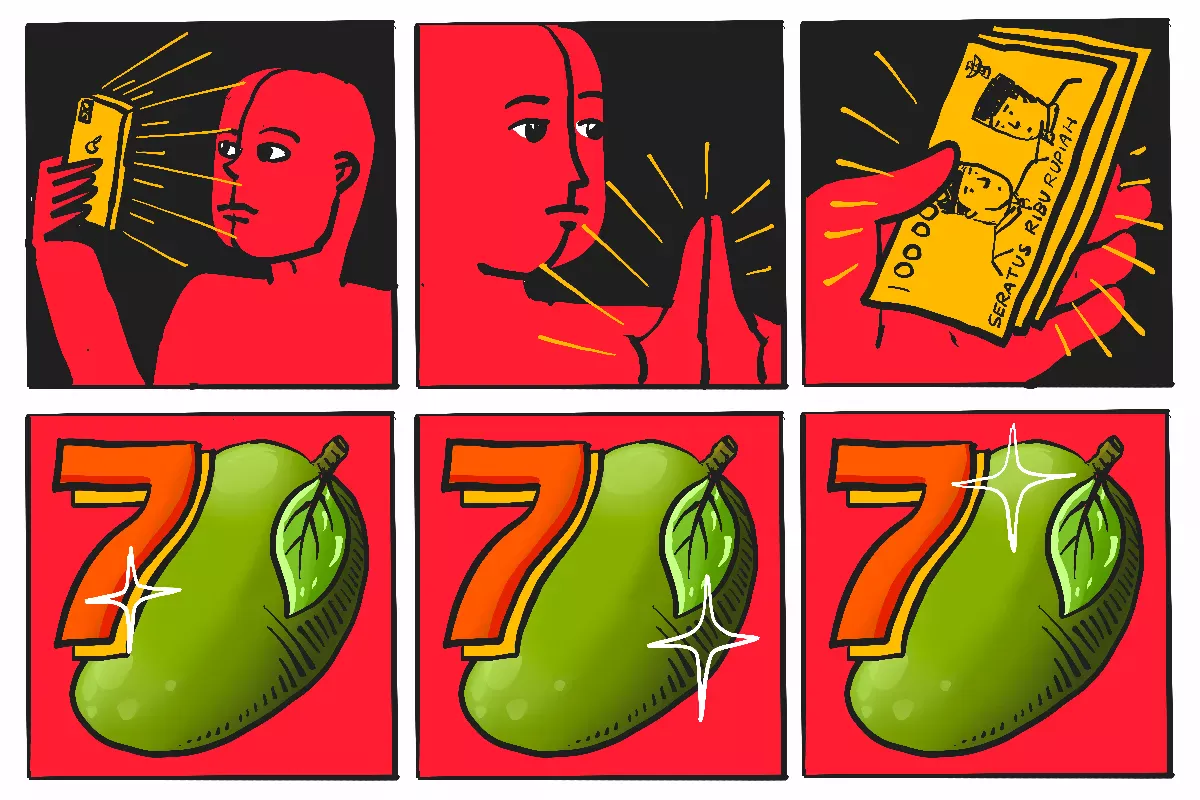Setiap ditanya asal daerah, saya sering mengalami krisis identitas ringan. Pertanyaan sesederhana, “Asalmu dari mana?” bisa membuat saya diam dua detik terlalu lama. Menjawab Boyolali rasanya setengah bohong. Tetapi menjawab Solo jelas keliru dan berpotensi menyalahi batas administratif. Akhirnya, saya sering memilih jawaban aman: Kecamatan Ngemplak, lalu bersiap menjelaskan panjang lebar.
Masalahnya, Ngemplak bukan nama yang langsung dipahami semua orang. Ia bukan kota, tapi juga sudah terlalu urban untuk disebut desa. Ia semacam wilayah abu-abu, tempat warganya terbiasa hidup di antara sawah dan beton, antara kabupaten dan kota, antara status resmi dan perasaan sehari-hari.
Keraguan identitas ini bukan tanpa sebab. Kecamatan Ngemplak kerap disebut “hampir jadi bagian dari Kota Solo”. Sebutan itu tidak pernah lahir dari keputusan resmi, melainkan dari obrolan warung kopi, grup WhatsApp warga, dan candaan setengah serius. Isu penggabungan Ngemplak ke Solo sudah beredar sejak lama, tapi selalu berhenti di level cerita. Seperti wacana diet tiap Senin: sering diomongkan, jarang dieksekusi.
Kecamatan Ngemplak lebih dekat ke pusat Solo ketimbang Boyolali
Alasan pertama yang paling sering muncul tentu soal letak geografis. Dari Ngemplak ke pusat Solo jaraknya dekat. Jalan tembus ada di mana-mana. Mobilitas warga kecamatan ini pun lebih sering mengarah ke Solo ketimbang ke pusat Boyolali. Pergi kerja ke Solo, sekolah ke Solo, belanja ke Solo. Ngemplak ini ibarat halaman belakang Solo yang tiap hari dilewati, tapi jarang diakui sebagai bagian keluarga.
Secara fungsi, Kecamatan Ngemplak memang sudah jadi kawasan penyangga. Ia menopang kebutuhan kota tanpa ikut menikmati statusnya. Warganya akrab dengan ritme urban: macet pagi hari, harga tanah naik cepat, dan lahan yang pelan-pelan kehilangan identitasnya sebagai sawah. Bedanya, ketika urusan administrasi dan pelayanan publik muncul, kami kembali diingatkan bahwa ini masih wilayah Boyolali.
Baca halaman selanjutnya: Strategis dan lengkap…